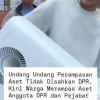Museum di Indonesia masih banyak yang berwujud sebagai "gudang artefak" yang statis, kurang interaktif, dan minim inovasi teknologi.
Mayoritas masih berkutat pada konsep konvensional: benda-benda statis dalam kotak kaca, label usang dengan deskripsi minim, dan pengalaman pengunjung yang monoton.
Padahal, studi Falk & Dierking (2016) dalam The Museum Experience Revisited menegaskan bahwa museum modern harus menawarkan experiential learning--bukan sekadar pamer benda mati.
Pengunjung generasi muda, yang kini hidup di era digital dan serba cepat, merasa museum kurang relevan dan membosankan.
Kurangnya pendekatan edukasi yang kontekstual dan pengalaman yang imersif membuat museum gagal menarik minat khalayak muda sebagai pengunjung aktif, apalagi sebagai pelaku pelestarian budaya.
Selain itu, masalah pendanaan dan manajemen yang kurang profesional turut memperparah kondisi ini. Tidak ada angka pasti alokasi anggaran khusus museum yang dipublikasikan secara terpisah dalam APBN 2025.
Namun, dari laporan dan pernyataan anggota DPR Komisi X, terdapat upaya dan perjuangan untuk mengalokasikan anggaran revitalisasi museum, khususnya di daerah seperti Nusa Tenggara Timur, dengan estimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp90-100 miliar yang diajukan secara bertahap mulai dari Rp5-20 miliar per tahun dalam APBN-P 2025.
Secara umum, anggaran untuk pemajuan kebudayaan (Dana Indonesiana), termasuk museum, biasanya masuk dalam pos anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Pada APBN 2025 dialokasikan sekitar Rp71 triliun untuk seluruh programnya, termasuk pendidikan, riset, dan kebudayaan. Namun, alokasi khusus untuk museum tidak dijabarkan secara rinci dalam dokumen publik.
Banyak museum yang tidak memiliki sumber daya memadai untuk mengembangkan koleksi, memperbarui fasilitas, atau mengadopsi teknologi baru seperti augmented reality (AR) dan virtual reality (VR) yang kini menjadi tren di museum-museum dunia.
Perbandingan dengan Perkembangan Museum di Dunia