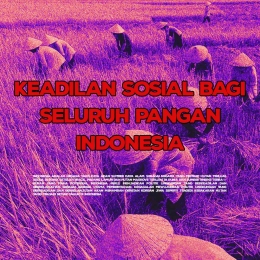Krisis Pangan
Adaptasi terhadap lingkungan dan konstidusi menjadi hal yang sangat diragukan Ketika berbagai undang-undang, dan peraturan presiden, peraturan menteri maupu peraturan daerah yang tidak responsive terhadap masalah lingkungan yang muncul. Perbandingan sebuah fenomena konstitusi Indonesia asa dan realita apabila di bandingkan dengan kebijakan yang muncul berbanding terbalik dan bertentangan dengan konstitusi. Lubang bekas tambang batu bara di Kalimantan telah menjadi lubang tambang maut yang menelan nyawa ratusan anak-anak. Penambangan timah lepas pantai di Pulau Bangka yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara PT. Timah telah merusak ekosistem bawah laut di sekitar Pulau Bangka. Berbagai fenomena HGU dan perampasan lahan kerap terjadi di Indonesia.
Istilah Politik Lingkungan sendiri adalah politik mengenai pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah harus mendesain kebijakan yang tepat di dalam menangani masalah lingkungan dan politik lingkungan menawarkan berbagai opsi dan alternatif yang dapat diambil dalam menangani pengelolaan sumber daya alam. Contoh kebijakan dalam politik lingkungan itu sendiri seperti Indonesia memiliki lahan gambut tropis terluas di dunia dan Kalimantan dan Sumatra memiliki lahan gambut terluas di Indonesia. Lahan gambut ini memiliki karakteristik unik karena sangat rentan terhadap kebakaran apabila lahan gambut menjadi kering. Lahan gambut merupakan senyawa organik yang tersusun dari dekomposisi material organik selama ratusan tahun. Lahan gambut harus dibiarkan dalam keadaan berari atau basah. Pada tahun 1995, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pertanian lahan gambut yang mengeringkan lahan gambut di Kalimantan dan Sumatera. Akademisi sudah mengingatkan Pemerintah bahwa pengeringan lahan gambut sangat berbahaya bagi lingkungan hidup. Akibatnya, lahan gambut menjadi rentan terbakar dan menjadi faktor utama kebakaran hebat di tahun 1997 dan 1998. Dalam hal ini, Pemerintah bertentangan dengan sikap dan kesepakatan akademisi terkait tata kelola gambut.
Dekomodifikasi Sistem Pangan
Dengan pengambilalihan sistem pangan oleh korporasi dalam beberapa dekade terakhir, pangan telah terintegrasi ke dalam pasar global yang menyulitkan ketika membayangkan perannya di luar dari nilai komoditas. Komodifikasi sistem pangan selalu berperan dalam mensistematiskan akumulasi modal, eksploitasi tenaga kerja, dan ekstraksi sumber daya alam. Gerakan kedaulatan pangan menyerukan hak dan penentuan nasib sendiri bagi semua orang untuk merancang dan membentuk sistem pangan mereka. Inti dari kampanye ini terletak pada de-komodifikasi. Dekomodifikasi adalah pembebasan dari ketergantungan pasar dan pemulihan hak-hak sosial kelas pekerja. Hal ini penting dan merupakan konsekuensi alami dari upaya mewujudkan kedaulatan. Untuk benar-benar mendekomodifikasi sistem pangan, pertama-tama kita harus memahami proses-proses dalam sistem dominan yang memungkinkan komodifikasinya.
Sejak awal praktik pertanian tahun 8000 SM hingga beberapa abad terakhir, petani skala kecil di seluruh dunia secara kolektif menanam tanaman pangan dan menggembalakan ternak mereka di tanah milik umum. Hal ini berubah secara dramatis pada tahun 1700-an ketika parlemen Inggris memberlakukan Enclosure Acts, yang memungkinkan kaum elit kaya untuk memprivatisasi tanah milik umum. Enclosure Movement* menyebar dengan cepat ke seluruh Inggris Raya, dan akhirnya ke seluruh Eropa. Pada abad berikutnya, doktrin gerakan ini direplikasi dan diterapkan juga pada koloni-koloni di Dunia Mayoritas**, dalam bentuk hak milik pribadi dan undang-undang. Para elit membeli hampir semua tanah milik umum, dengan kekerasan menggusur jutaan petani skala kecil dari tanah mereka.
Enclosure memfasilitasi perluasan industrialisasi di seluruh dunia dalam dua cara utama: Pertama, masyarakat yang tanahnya dirampas, diserap oleh industri dan dipaksa bekerja dengan upah minimum. Kedua, industri mengambil kendali atas sebagian besar kepemilikan umum - yang sebelumnya dikelola oleh petani dan masyarakat adat - kemudian memberi akses bagi mereka mengekstraksi sumber daya tanpa batas. Dengan melenyapkan semua nilai-nilai yang berkaitan dengan tanah, enclosure mengasingkan masyarakat tidak hanya dari tanah tetapi juga dari budaya dan sarana penghidupan mereka sendiri. Begitu tanah diprivatisasi, mereka yang tidak memiliki tanah tidak lagi memegang kendali atas alat-alat produksi dan dipaksa untuk menukar tenaga mereka dengan upah, sementara kapitalis mengklaim keuntungannya. Dengan cara ini, keuntungan dihasilkan dari komodifikasi alam dan keterasingan tenaga kerja.
Enclosure mash berlangsung dan berkembang hingga saat ini. Sejak kebangkitan rezim pangan industri di tahun 1960-an dan neoliberalisasi paksa di Dunia Mayoritas, korporasi transnasional telah mengonsolidasikan kepentingan bersama dunia untuk menciptakan enclosure secara global. Sistem pangan telah mengalami pergeseran struktural, semakin menjauh dari fungsinya sebagai jaringan kehidupan yang didedikasikan untuk memberi makan orang-orang dengan pangan sebagai komoditas yang dirancang memberikan keuntungan bagi pemilik modal. Hal terpenting dalam pergeseran ini adalah finansialisasi* sistem pangan, yang telah memungkinkan pemegang saham dan korporasi untuk mengambil kendali melalui pasar keuangan dan spekulatif. Melalui komodifikasi, nilai sosial dan ekologis manusia, pangan, dan tanah secara sistematis terkikis dan digantikan dengan nilai pasar yang kurang dihargai.
Enclosure mash berlangsung dan berkembang hingga saat ini. Sejak kebangkitan rezim pangan industri di tahun 1960-an dan neoliberalisasi paksa di Dunia Mayoritas, korporasi transnasional telah mengonsolidasikan kepentingan bersama dunia untuk menciptakan enclosure secara global. Sistem pangan telah mengalami pergeseran struktural, semakin menjauh dari fungsinya sebagai jaringan kehidupan yang didedikasikan untuk memberi makan orang-orang dengan pangan sebagai komoditas yang dirancang memberikan keuntungan bagi pemilik modal. Hal terpenting dalam pergeseran ini adalah finansialisasi* sistem pangan, yang telah memungkinkan pemegang saham dan korporasi untuk mengambil kendali melalui pasar keuangan dan spekulatif. Melalui komodifikasi, nilai sosial dan ekologis manusia, pangan, dan tanah secara sistematis terkikis dan digantikan dengan nilai pasar yang kurang dihargai. Satu-satu nya acara untuk benar benar mendekomodifikasi pangan adalah dengan mendekomodikasi sistim itu sendiri.
Dalam beberapa dekade mendatang, penting bagi kita untuk mengambil dua langkah utama: Pertama, kita harus melakukan definansialisasi sistem pangan. Sebuah studi baru-baru ini yang dilakukan ole organisasi non-profit GRAIN mengungkap bahwa krisis pangan yang kita alami saat ini terjadi sama sekali bukan karena kekurangan pangan - tapi ini adalah hasil dari ketergantungan yang lama terhadap perdagangan global dan spekulasi keuangan. Untuk membangun kembali ketahanan sistem pangan, kita harus segera melarang pelaku keuangan tertentu untuk bertransaksi dan berspekulasi di bidang pangan. Kedua, kita harus mulai mengklaim dan menumbuhkan kembali dunia milik bersama. Kita dapat mengambil inspirasi dari gerakan-gerakan seperti Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), di mana para buruh dan petani tak bertanah di Brasil mengklaim kembali tanah-tanah tidak produktif yang dimiliki oleh para pemilik tanah skala besar. Setelah tanah ini diubah menjadi milk bersama, mereka membangun pemukiman, mulai bertani, membentuk koperasi petani, dan mendirikan fasilitas seperti infrastruktur, kredit, kesehatan, dan pendidikan.
Yang terpenting, kita harus mengakui bahwa di bawah sistem pangan, ekonomi, dan politik yang dominan, hak kita untuk hidup bergantung pada apakah kita mampu membeli barang-barang yang kita butuhkan untuk bertahan hidup atau tidak. Dan untuk membeli barang-barang itu, kita menjual diri kita sendiri - waktu dan tenaga kita. Kita bukan hanya konsumen, kita adalah komoditas - nilai kita diukur dengan apa yang dapat kita tawarkan ke pasar. Kedaulatan, otonomi, dan hak pilihan telah diambil dari diri kita.
Pangan Adalah Politik
Makanan tidak muncul dalam ruang hampa makanan mewujudkan semua cara kita berhubungan dengan sumber daya, tanah, dan satu sama lain. Seringkali, narasi sistem pangan berkutat tentang tanah, tanpa menyadari bahwa petani dan masyarakat adat di seluruh dunia sering ditindas, ditangkap, dan dibunuh oleh perusahaan dan pemerintah hanya karena mereka menegaskan hak dasar atas tanah, dan hak mereka untuk menanam pangan untuk keluarga mereka, subsistensi.
Mereka digugat oleh raksasa agribisnis yang mematenkan varietas benih lokal yang telah dibudidayakan oleh masyarakat selama ribuan tahun. Mereka didorong ke dalam siklus utang oleh perusahaan yang membuat petani bergantung pada input bersubsidi, kemudian menaikkan harganya. Masalah-masalah ini tidak akan diselesaikan dengan beralih ke model pertanian baru; masalah ini akan diselesaikan dengan menegakkan hak asasi manusia dan mendistribusikan kembali kekuasaan kepada petani dan masyarakat.
Ketahanan Pangan Tidak Cukup
Wacana seputar ketahanan pangan muncul di tengah kebijakan neoliberal berupa program penyesuaian struktural, surplus dumping, dan industrialisasi. Ketahanan pangan memperlakukan kelaparan sebagai masalah apolitis dan upaya untuk memecahkan masalah dalam sistem pangan industri. Akibatnya, pendeketan yang dilakukan cenderung dipimpin oleh lembaga yang sama yang bertanggung jawab dalam memiskinkan masyarakat.
Kedaulatan pangan secara langsung fokus pada kekuasaan, mengangkat hak masyarakat untuk membentuk sistem pangan mereka sendiri - apa yang harus ditanam, bagaimana menanam, di mana menjualnya, dan berapa harganya. Sistem ini merayakan dan melestarikan pengetahuan adat dan lokal, praktik penggunaan lahan, dan mengamankan lebih dari sekadar makanan. Tidak ada ketahanan pangan yang nyata tapa kedaulatan pangan.
Dampak Krisis Pangan Bagi Indonesia
Tragedi yang terjadi pada tahun 1997 merupakan awal dari perubahan pemerintahan di Indonesia yang sekian lama di belenggu oleh kepemimpinan Soeharto. Disisi lain perubahan yang di nanti oleh masyarakat ini tidak sesuai keinginan masyarakat itu sendiri. Betapa tidak, beberapa harga kebutuhan bahan pokok mulai tidak stabil termasuk harga 9 bahan pokok melonjak naik. Kenaikan harga ini kemudian memicu ketidak stabilan politik di Indonesia yang akhirnya mengeluarkan berbagai kebijakan oleh pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah termasuk pengadaan impor gula, daging, beras, dan beberapa pangan lainnya dirasa kurang menggembirakan bagi masyarakat Indonesia hingga saat ini. Kebijakan pemerintah akan impor beras sebagai kebijakan pangan untuk mengatasi krisis pangan, dirasa merugikan bagi Indonesia secara terusmenerus. Hal ini didasari pada daya saing produk pangan Indonesia dirasa masih kalah jauh di banding Negara-negara Malaysia, Thailand, dan Filipina. Jika terus menerus terjadi impor beras, Indonesia nantinya akan mengalami ketergantungan terhadap Negara-negara lain, akibatnya sektor pertanian kita semakin terpuruk.1837 Pada tahun 2007-2008, harga pangan di pasar internasional kembali melonjak. Hal ini menjadi perhatian bagi Negara-negara di dunia khususnya Negara-negara berkembang untuk memberi perhatian lebih pada aspek ketersediaan pangan. Menipisnya ketersediaan pangan atau terjadinya krisis pangan akan mempengaruhi roda perekonomian Indonesia.
Selain kelaparan, dampak lain dari krisis pangan yang terjadi di Indonesia adalah ketergantungan akan impor. Saat ini Indonesia termasuk pengimpor beras terbesar dengan jumlah 2,5 juta ton beras per tahun. Selain beras juga mengimpor 2 juta ton gula dan 1,2 juta ton kedelai. Jika ini tidak secepatnya di antisipasi oleh pemerintah, maka tidak mustahil Indonesia akan mengalami seperti yang terjadi di Negara Haiti yang menjadi salah satu negara krisis pangan dengan penghasil beras produksi 170.000ton beras per tahun masih mengalami krisis pangan. Sementara Indonesia diprediksi akan mengalami krisis pangan tersebut pada tahun 2017 di 150 kabupaten/kota dari 480 kabupaten/kota di Indonesia melihat populasi penduduk yang menjadi 237 juta jiwa per 2010 serta melihat peristiwa yang terjadi di indonesia mengenai kelangkaan kedelai pada awal 2008, serta impor beras dan gula begitu juga dengan komoditi pangan lainnya.
Upaya Yang Harus Dilakukan Pemerintah Dalam Menghadapi Krisis Pangan
Aktor yang terlibat dalam ketahanan pangan setelah kerjasama antar berbagai aktor yag telah terjalin, langkah selanjutnya yang harus ditempuh pemerintah Indonesia dalam upaya mempertahankan ketahanan pangan adalah Negara dalam hal ini pemerintah, harus memperhatikan produksi dalam negeri. Bukan hanya produksi dari sektor pertanian, tetapi juga harus memperhatikan sektor perkebunan dan peternakan. Perhatian pemerintah terhadap ketiga sektor tersebut harus ditingkatkan guna menjaga ketersediaan kebutuhan pangan dalam negeri.
Dalam menghadapi krisis sumber energi dan pangan, Indonesia harus menjadi basis produksi pangan khsususnya di kawasan ASEAN. Kestabilan dan keterjangkauan harga terhadap pangan oleh masyarakat Indonesia harus diperhatikan oleh pemerintah diberikan nya subsidi terhadap bahan dasar pangan. Perluasan wilayah atau tanah garapan khususnya bidang pertanian yang tadinya semakin terbatas menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk menunjang peningkatan produksi pangan.
Keterlibatan UMKM harus dimaksimalkan. Menurut Rondinelli, Nellis, dan Cheema (1983), desentralisasi adalah sebuah strategi pembangunan ekonomi yang lebih efisien dan efektif, sebuah mitigasi terhadap kegagalan rencana pembangunan nasional, sebuah upaya komunitas lokal untuk memperoleh informasi yang lebih detail terkait sumber daya alam di sebuah daerah, sebuah strategi penciptaan kebijakan pembangunan daerah yang lebih responsif, sebuah kebijakan untuk mendorong keterlibatan komunitas. Desentralisasi memberikan manfaat yang lebih besar bagi komunitas lokal. Jarak kekuasaan antara komunitas lokal dengan ibukota diatasi dengan konstruksi pemerintah daerah. Ketika pemerintah pusat menyusun kebijakan ekonomi berbasis pertanian, pemerintah daerah dapat mendorong kebijakan ekonomi berbasis pariwisata atau perikanan karena lebih sesuai dengan karakteristik komunitas lokal.
Bibliography
Adity, K. G. (2011). Studi Pengaruh RSPO terhadap Kebijakan Pemerintah. Transnasionalisme Kelapa Sawit.
Akib, M. (2013). Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah. Politik Hukum Lingkungan, Jakarta.
Angelika, Y. (2015). Jurnal Online Mahasiswa. Kebijakan Pemerintah Indonesia Pasca Keluar dari Rountable Sustainable Palm Oi, 1-11.
Antara. (2019). Retrieved from Kuasa lebih "raja kecil" otonomi daerah: https://papua.antaranews.com/berita/498716/kuasalebih-raja-kecil-otonomi-daerah.
Bram. (2012). Kejahatan Korporasi dalam Pencemaran Lintas Batas Negara. Studi Pencemaran Kabut Asap Kebakaran Hutan di Indonesia, 15-12.
Budi, W. (2010). Melawan Gurita Neoliberalisme. Jakarta: Erlangga.
Djojohadikusumo. (1976). LP3ES. Indonesia dalam perkembangan Dunia.
EBTKE. (6, Maret 2019). Direktorat Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi. Retrieved from esdm: http://ebtke.esdm.go.id
Grain. (2022). From Food Crisis to Food Crisis.
Indonesia, K. L. (2022). Isu-isu Khusus Ketahanan Pangan. Jakarta: BPS.
Kompas. (2018, Oktober 7). Sumber Daya Alam: Pertimbangan. Retrieved from Sumber Daya Alam: Pertimbangan.
Krisis Pangan dan Bahaya Kelaparan Ancam Dunia. (2011). Humas UGM.
Kujay A, L. (2021). The Society for International Development. From Food As Commodity To Food As Liberation, 1-13.
Oktavio, N. (2011). Krisis Pangan dan Bahaya Kelaparan Ancam Dunia. Masalah Yang Membelit Pembangunan dan Pertanian di Indonesia.
Saleem. (2016). Environmental Diplomacy. The SAGE Handbook of Diplomacy by Costas Constantinou, Pauline Kerr and Paul Sharp, 601616.
Statistik, B. P. (2011-2013). BPS. Jakarta: Badan Pusat Statistik.