Di hadapan Sidang Majelis Umum PBB tahun ini, dunia kembali menyaksikan bagaimana panggung diplomasi global sering menjadi ruang hampa moral. Konflik bersenjata, tekanan ekonomi, dan aliansi geopolitik kerap membuat isu kemanusiaan kehilangan makna ketika memasuki panggung politik internasional. Namun di tengah kehati-hatian diplomatik yang dingin itu, sebuah suara perempuan justru muncul sebagai penanda bahwa keberanian moral belum sepenuhnya mati. Presiden Slovenia, Nataa Pirc Musar, berdiri di podium PBB dan mengucapkan sebuah kalimat yang sederhana namun mengguncang tatanan politik yang hipokrit: "Silence in the face of injustice is complicity." diam terhadap ketidakadilan adalah bentuk keterlibatan di dalamnya. Pernyataan itu bukan hanya kritik terhadap agresi Israel di Gaza, tetapi juga sebuah tantangan moral terhadap negara-negara dunia yang memilih diam, ragu, atau berpura-pura netral atas genosida yang terus berlangsung terhadap rakyat Palestina.
Di saat banyak pemimpin negara memilih bahasa retoris yang aman, Musar menyebut realitas di Gaza sebagaimana adanya: kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh negara yang didukung kekuatan besar dunia. Pidatonya menjunjung martabat kemanusiaan, bukan kepentingan diplomatik. Ia tidak bermain aman. Ia tidak bersembunyi di balik istilah "konflik" yang kabur. Ia menyebut kejahatan perang sebagai kejahatan, menyebut penindasan sebagai penindasan, tanpa takut mengganggu kenyamanan politik negara-negara kuat yang menjadi pelindung Israel. Inilah yang membuat kehadirannya di forum internasional terasa penting: ia menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan sekadar mengelola kekuasaan, tetapi juga soal keberanian moral untuk menyatakan kebenaran pada saat dunia memilih bungkam.
Keberanian Presiden Slovenia ini kontras dengan mayoritas pemimpin dunia lain yang berbicara di UNGA. Kritik terhadap Israel sering dilemahkan dengan kalimat diplomatik yang dikemas manis: menyerukan "de-eskalasi," "solusi damai," atau "dialog konstruktif," padahal dunia tidak sedang menghadapi konflik dua pihak yang seimbang, tetapi sebuah penindasan kolonial yang terjadi secara sistematis. Di tengah pengepungan brutal, penghancuran rumah sakit, pemutusan akses pangan dan air, serta pembantaian terhadap perempuan dan anak-anak Palestina, masih banyak negara yang menggunakan bahasa politik yang secara moral tidak lagi relevan. Musar menunjukkan bahwa keberanian untuk berpihak adalah syarat dasar kemanusiaan.
Pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di forum yang sama memang menyinggung Palestina dan menegaskan posisi Indonesia yang mendukung perdamaian. Ia berkata, "Indonesia will always stand with justice and humanity, and with the rights of all people, including the Palestinians." Kalimat itu terdengar baik, rapi, dan sopan. Namun berbeda dengan Musar, Prabowo tidak menyebut pelaku kekerasan. Tidak ada kata "Israel" dalam kritiknya. Tidak ada seruan akuntabilitas. Tidak ada penyebutan kejahatan perang. Tidak ada kecaman terhadap blokade kemanusiaan. Dengan kata lain, posisi Indonesia dalam pidato itu jelas, tetapi tidak tegas. Ia bermoral, tetapi tidak berani. Ini bukan soal retorika perang; ini soal memanggil penjahat perang dengan namanya.
Inilah perbedaan antara pidato yang hanya aman secara diplomatik dengan pidato yang berani secara moral. Keberanian politik tidak diukur dari jumlah kata "perdamaian" dalam sebuah pidato, tetapi dari keberanian untuk menyebut kejahatan kemanusiaan sebagai kejahatan. Dunia tidak kekurangan seruan gencatan senjata; yang kurang adalah tuntutan pertanggungjawaban. Jika bahkan para pemimpin dunia tidak berani berbicara jujur, lalu siapa lagi yang akan menuntut keadilan bagi anak-anak Gaza yang dibantai dengan dalih "pertahanan diri"?
Kehadiran Musar di podium PBB membawa refleksi penting: mungkin dunia memang membutuhkan lebih banyak pemimpin perempuan di panggung global, bukan karena perempuan lebih "lembut," tetapi karena mereka membawa politik yang berani dan tidak tenggelam dalam kalkulasi kekuasaan. Ketika pria sering memimpin melalui logika militeristis dan kompromi geopolitik, perempuan seperti Musar membuktikan bahwa politik juga dapat digerakkan oleh nurani dan keberanian moral. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak pemimpin yang ahli bicara, tetapi pemimpin yang mampu mengambil posisi ketika kemanusiaan diinjak-injak.
Gaza bukan hanya soal konflik politik. Gaza adalah soal martabat manusia. Ini bukan sekadar persoalan wilayah. Ini persoalan penindasan yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan terus ditutupi oleh narasi yang direkayasa. Ketika rumah sakit dihancurkan, ketika bantuan kemanusiaan ditolak masuk, ketika jurnalis ditembak mati untuk membungkam kebenaran, apakah dunia masih mau menyebut ini sebagai "ketegangan regional"? Atau saatnya kita mengakui secara jujur: ini adalah kejahatan yang disengaja terhadap satu bangsa---genosida dalam terang benderang. Pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat siapa yang bersikap netral, tetapi siapa yang memilih berpihak pada yang tertindas. Seperti yang dikatakan Musar, "Justice is not a matter of opinion; it is a responsibility." Dan hari ini, Gaza memanggil bukan hanya belas kasihan kita, tetapi keberanian politik kita. Palestina tidak butuh simpati; Palestina butuh keadilan.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

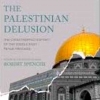

![[teenlit] Bumi yang Hijau Jiwa Gen Z](https://assets-a2.kompasiana.com/items/album/2025/09/15/file11a04266-dd2f-4fdb-a332-fa005ad7ab3e-68c82a0a34777c559a4c8a92.png?t=t&v=100&x=100&info=meta_related)



