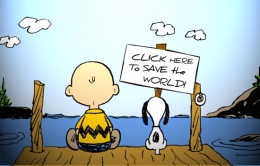Penelitian lain yang dilakukan oleh Yu-Hao Lee & Gary Hsieh dari Michigan State Universitymenemukan hasil yang hampir sama namun memiliki sedikit perbedaan dengan penelitian yang dibahas sebelumnya. Penelitian ini mengangkat peristiwa penembakan yang terjadi di Colorado, Amerika serikat pada tahun 2012, mereka mendesain sebuah eksperimen online yang mengundang partisipan untuk menandatangai sebuah petisi online untuk melarang penggunaan senapan atau memberi dukungan pembuatan UU yang mengatur penggunaan senjata tembak sesuai sikap mereka dalam menanggapi isu tersebut. Kemudian peneliti bertanya apakah partisipan mau berdonasi sebagai kompensasi untuk organisasi yang memperjuangkan hak-hak bersenjata dan pengontrol beredarnya senjata (congruent civic action) atau untuk organisasi pendidikan (incongruent civic action). Peneliti menemukan bahwa ketika tindakan yang lebih nyata tersebut tidak berkaitan dengan isu sebelumnya, partisipan yang tidak menandatangani petisi mendonasikan uangnya secara signifikan daripada kelompok kontrol, mungkin karena adanya efek moral pembersih (moral cleansing effect). Namun, ketika aksi lanjutan tersebut terkait dengan isu sebelumnya, menandatangani petisi memang meningkatkan kemungkinan mereka berdonasi namun bukan secara jumlah. Mereka juga mencari apakah menandatangani petisi akan berdampak pada niat untuk berpartisipasi pada aksi memperjuangkan kepentingan secara tradisional (seperti kampanye,dll). Hasilnya menunjukkan bahwa berpartisipasi dalam petisi hanya meningkatkan niat untuk berpartisipasi dalam aksi yang sama saja (Lee & Hsieh, 2013).
Sementara pendukung aktivisme online memiliki kepercayaan yang lain, mereka berpendapat bahwa media sosial bisa digunakan untuk menjangkau banyak orang dengan meningkatkan kesadaran maupun pengetahuan mereka dan membuka mata dunia. Aksi yang sederhana dapat mengajak oranglain yang mungkin tidak pernah terlibat dalam aksi-aksi tradisional mengenai perjuangan untuk kepentingan umum. Banyak contoh dimana slacktivismbaik secara langsung maupun tidak langsung menguntungkan, dari meningkatkan milyaran kontribusi penggalangan dana (contohnya penggalangan donasi setelah terjadinya gempa bumi dan bencana lainnya) hingga meningkatkan kesadaran (contohnya pada aksi KONY 2012). (Lee & Hsieh, 2013).
Dalam hal ini kita memang harus bijak menyikapinya, disatu sisislacktivism merupakan suatu terobosan aktivisme baru karena dapat menjangkau banyak orang didunia sehingga kemungkinan untuk membuka wawasan orang lain semakin besar. Namun tindakan ini memang tidak bisa dikatakan sepenuhnya positif karena dampak kedepan yang mungkin ditimbulkannya yakni adanya kemungkinan seseorang bersikap lebih apatis dan lebih memilih untuk sekedar memberi like,membagikan post, dan beberapa tindakan serupa lainnya. Seolah kita dihadapkan dalam sebuah dilema karena slacktivismsendiri merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari (mengingat ini timbul karena kemajuan teknologi), lalu sikap apa yang seharusnya diambil tanpa melupakan prinsip-prinsip kemanusiaan kita dalam (hal ini adalah nilai dan prinsip menolong sesama)?
Pertama kita perlu mengetahui poin apa saja yang perlu diperhatikan, karena sebenarnya yang dipermasalahkan bukan tindakan memberi like,membagikan postingan, mewarnai foto profile dan tindakan sejenisnya. Namun yang dikritik adalah tindakan setelah itu, adakah aksi nyata yang dilakukannya atau tidak, atau mungkin aksinya tersebut hanya terhenti begitu saja setelah dia memperoleh kepuasan diri. Bagaimana jika banyak orang yang berpikir bahwa aksi slacktivist yang dilakukannya memiliki pengaruh yang besar dan telah cukup untuk membuat perubahan meski tanpa melakukan tindakan apapun lebih dari itu? Dengan memberi like, membagikan post dan menunjukkan sebuah dukungan akan ada seseorang yang berpikir bahwa “cukuplah saya membantu sampai disini karena saya punya hambatan yang membuat saya berbuat lebih” kemudian muncullah efek kepuasan sesaat pada dirinya (karena dirinya merasa telah berbuat sesuatu) seolah dia telah melakukan hal besar, sementara itu melalui aksi slacktivistnya tersebut muncul kepercayaan bahwa akan ada orang lain yang lebih mampu melakukan aksi nyata seperti memberikan donasi, dst. Berusaha ikut dan aktif dalam gerakan menuju perubahan tentu sangat diperbolehkan (apalagi perubahan kearah yang lebih baik), namun janganlah lupa bahwa suatu tindakan tidaklah berarti jika tidak diwujudkan dalam kehidupan nyata.
Dalam menyikapinya ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, diantaranya perlunya mengubah pola pikir “lebih baik saya bertindak seperti ini daripada tidak sama sekali”, jika kita dapat bertindak lebih nyata mengapa kita tidak memilihnya. Tidak jarang beberapa kampanye digital mengajak masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara langsung dengan cara menyumbangkan uangnya / donasi melalui rekening ataupun mengirimkan donasi ke alamat tertentu, bahkan ada banyak gerakan seperti salah satunya adalah WWF Indonesia / Youcan yang sering membuat program untuk mengajak masyarakat agar bisa menjadi sukarelawan/volunteer.
Lalu janganlah mengatasnamakan kemanusiaan demi kepuasan diri dan popularitas hanya karena dukungan yang ditunjukkannya tersebut akan dilihat oleh followerdan teman didunia maya. Karena prinsip menolong seharusnya didasarkan atas perasaan empati yang muncul dari dalam diri seseorang, jika tidak didasarkan murni atas perasaan empati dan rasa peduli maka yang terjadi adalah tindakan yang terkesan setengah-setengah (seperti yang ditunjukkan dalam penelitian University State of Michiganyang dibahas sebelumnya).
Kemudian kita juga harus menyadari bahwa slacktivism tidak sepenuhnya membawa manfaat jika tidak benar-benar diwujudkan di dunia nyata. Tidak jarang juga ada beberapa oknum yang memanfaatkan fenomena ini untuk meraup keuntungan dan mendapat royalty sebanyak-banyaknya dari pendapatan like,jumlah share,pengikut, dst. Yang perlu kita dilakukan adalah menyaring informasi itu sendiri mana yang benar dan mana yang tidak. Tentu sudah tidak asing untuk kita melihat sebuah postingan yang berisi suatu gambar dramatis dibubuhi tulisan ancaman sebuah doa tidak baik yang akan terjadi jika kita tidak menulis “amin”, memberi like atau membagikannya, ini adalah salah satu contoh oknum yang memanfaatkan isu-isu kemanusiaan dan fenomena slacktivismsebagai kepentingan bisnisnya.
Slacktivism adalah salah satu fenomena yang muncul karena kemajuan teknologi sehingga dapat dikatakan fenomena ini memang sulit untuk dihindari atau dicegah agar tidak terjadi, mengingat fakta bahwa teknologi adalah bagian dari sendi kehidupan masyarakat di era ini. Selain itu meski berdasarkan banyak penelitian menunjukkan adanya kecenderungan negatif yang muncul dari para pelaku slacktivismnamun disisi lain tidak dapat dipungkiri slacktivismtelah membawa angin baru untuk membawa kehidupan menuju sebuah kemajuan yang positif karena kelebihannya yang dapat menjangkau banyak orang di berbagai tempat. Namun jangan melupakan bahwa suatu perubahan tidak akan terjadi jika tidak diikuti oleh tindakan yang lebih nyata.
Karena sama-sama memiliki plus dan minus ini kita menjadi harus lebih bijak dalam menyikapinya, adapun hal-hal yang dapat kita lakukan diantaranya adalah mengubah pola pikir “lebih baik saya bertindak seperti ini daripada tidak sama sekali”, tidak mengatasnamakan kemanusiaan demi kepuasan diri dan popularitas, serta menyadari sepenuhnya bahwa slacktivismtidak sepenuhnya membawa manfaat jika tidak benar-benar diwujudkan di dunia nyata. Dengan menerapkan hal-hal tersebut sisi kemanusiaan untuk menolong orang lain yang sejatinya menjadi tendensi makhluk sosial biasnya dapat dikurangi. Janganlah kita biarkan media sosial mengubah generasi ini menjadi generasi yang dipenuhi dengan delusi akan perubahan yang lebih baik, padahal aksi yang dilakukan tidak sepenuhnya mencerminkan usaha menuju kearah sana. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip menolong sesama memang tidak dapat terbantahkan jika semakin kemari semakin mengalami degradasi, terbiaskan oleh berbagai kepentingan yang mengikuti ego manusia. Manusia telah dikarunia akal/kognisi untuk berpikir dan perasaan/afeksi untuk merasa, ini juga yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Tentunya kita dapat menggunakan keduanya ketika kita melihat ada orang lain / makhluk ciptaan lain yang sedang membutuhkan, dan seharusnya sisi kemanusiaan kita akan tergelitik hingga sampai pada titik “membantu mereka” tanpa dibubuhi oleh alasan lain yang tidak dapat dibenarkan.
Simpati hanya akan menjadi simpati dan tentunya tidak dapat mengubah keadaan yang terjadi, karena simpati hanyalah sebuah perasaan/afeksi yang dirasakan seseorang, namun semua akan dapat berubah ketika simpati itu diwujudkan dalam tindakan nyata yang kita kenal dengan sebagai empati. Bayangkan melalui slacktivismyang di ikuti kesadaran untuk berpartisipasi lebih nyata, seberapa banyak perubahan yang telah/dapat dicapai dan seberapa banyak orang yang telah/dapat ditolong setiap harinya? Hanya karena “aksi kecil” dimana semua orang mau mengulurkan tangannnya secara nyata tanpa memikirkan kerugian yang harus ditanggungnya.
Daftar Pustaka
Kristofferson, K., White, K., & Peloza, J. (2013). The Nature of Slacktivism: How the Social Observability of an Initial Act of Token Support Affects Subsequent Prosocial Action. Journal of Consumer Research Vol. 40 , 1149-1166.