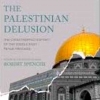Penulisan sejarah sejatinya tidak pernah lepas dari subjektivitas dan kepentingan. Sejarah yang seharusnya netral dan objektif sering kali ditulis dan dimanipulasi karena kepentingan legitimasi penguasa. Kita tidak lagi bisa memandang sejarah hanya sebagai catatan masa lalu, di dalamnya terdapat arena perebutan makna, kepentingan, identitas, dan legitimasi. Maka dari itu setiap upaya penulisan ulang sejarah akan selalu menimbulkan polemik.
Tahun 2025 ini pemerintah Indonesia memulai sebuah proyek besar yang cukup ambisius. Kementerian Kebudayaan menggagas proyek penulisan ulang Sejarah Nasional Indonesia yang ditargetkan rampung pada 17 Agustus 2025 kemarin. Proyek ini melibatkan lebih dari seratus sejarawan, penulis, dan editor. Alasan resminya adalah untuk memperbarui narasi sejarah dengan temuan-temuan baru, menghadirkan historiografi yang lebih lengkap, dan memperbaiki kekeliruan. Namun, sebuah pertanyaan muncul, apakah benar ini adalah upaya pembaruan ilmu atau sekedar melanggengkan narasi negara?
Jika melihat ke belakang, di Indonesia sendiri sejarah kerap menjadi alat legitimasi dan instrumen politik. Misalnya sejarah versi Orde Lama yang banyak menampilkan heroisme revolusi dan peran Soekarno dalam upaya persatuan bangsa. Selanjutnya, versi Orde Baru pasca peristiwa 1965, sejarah ditekankan pada versi tunggal yang menempatkan PKI sebagai dalang dan militer sebagai penyelamat bangsa. Dari sini sebenarnya ada pola yang dapat kita tarik, siapa yang berkuasa maka dialah yang mampu menentukan kemana arah sejarah akan ditulis. Maka dari itu penulisan ulang sejarah 2025 ini memunculkan setitik kewaspadaan. Apakah proyek ini sungguh akan menghadirkan narasi yang lebih jujur atau memperkuat belenggu negara atas memori kolektif yang berujung pada pemutihan sejarah?
Proyek ini merupakan salah satu langkah besar dalam historiografi pasca reformasi. Lingkupnya lebih luas bahkan hingga periode kontemporer termasuk masa pemerintahan SBY dan Jokowi. Pemerintah juga menjanjikan uji publik dengan konsultasi di berbagai daerah. Seperti yang disebutkan tadi, tujuannya adalah untuk merevisi, menambahkan, sekaligus meluruskan.
Namun, meski dikemas dalam kata "meluruskan" atau "menambahkan", proyek ini tetap menimbulkan kritik yang cukup tajam. Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) turut mengkritik proyek ini. Mereka khawatir proyek penulisan ulang ini justru akan melahirkan narasi tunggal yang berpotensi menolak narasi kritis. Padahal sejarah tidak bisa hanya ditampilkan dari satu perspektif saja. Timbul kekhawatiran proyek ini akan terlalu menonjolkan sisi positif sejarah Indonesia dan mengaburkan konflik politik, tragedi, dan pelanggaran HAM.
Polemik ini memperlihatkan bahwa Indonesia masih sulit melepaskan sejarah dari cengkeraman negara. Publik pun masih belum mengetahui siapa saja penulisnya, apakah kelompok minoritas akan terwakili, dan sejauh mana suara korban akan dilibatkan. Ketika pemerintah mengambil alih penulisan ulang sejarah, tentu akan muncul pertanyaan adakah kepentingan atau agenda politik dibaliknya? Bagaimana peristiwa kontroversial seperti tragedi 1965, Timor Timur, atau reformasi 1998 akan ditulis? Apakah korban kekerasan negara akan diberi ruang atau justru dihapus dari lintasan sejarah bangsa?
Hal ini menimbulkan dilema besar. Kita memang membutuhkan pembaruan sejarah agar sesuai dengan temuan terbaru, namun di sisi lain pembaruan itu juga dapat beresiko jika dilakukan sepenuhnya oleh negara. Kata "pelurusan" itu sendiri sebenarnya sudah cukup problematis. Meluruskan apa dan bagi siapa? Apakah nantinya akan memberikan ruang bagi kebebasan bersuara dan berpendapatatau justru mempersempit sejarah dengan mengesahkan satu versi saja? Pemerintah khususnya kementerian kebudayaan memberikan transparansi yang lebih detail terkait urgensi penulisan sejarah ulang ini.
Sejarah adalah milik publik. Maka seharusnya publik juga mengetahui siapa saja penulis yang terlibat, bagaimana seleksi narasi dilakukan, dan apakah arsip-arsip yang digunakan terbuka untuk diverifikasi. Minimnya transparansi ini yang membuat publik semakin khawatir. Sejarah akan terus berada dalam belenggu negara jika publik tidak dilibatkan dalam upaya rekonstruksinya. Kekhawatiran ini valid karena jika dilihat dari pengalaman panjang bangsa Indonesia di mana sejarah ditulis berdasarkan kepentingan rezim.
Jika pemerintah benar-benar ingin menyajikan sejarah yang jujur dan inklusif, setidaknya ada beberapa cara yang dapat ditempuh. Melibatkan korban dan keluarga korban adalah salah satu jalan yang dapat ditempuh. Sejarah tidak dapat ditulis dengan perspektif elit dan negara saja. Harus ada pula keterbukaan arsip dan transparansi proses sehingga publik juga dapat menilai narasi yang ditulis ulang. Selain itu, tidak boleh ada narasi tunggal yang disebut sebagai "sejarah resmi". Hal ini memicu penulisan sejarah dari perspektif lain dianggap tidak resmi dan tidak diakui. Sekalipun narasi oposisi itu membuka sisi kelam negara.
Proyek penulisan ulang sejarah nasional 2025 ini dapat menjadi momentum emas untuk mengembangkan historiografi Indonesia. Namun, jika dilakukan secara tergesa-gesa, tertutup, dan dalam kendali negara, yang muncul hanyalah narasi resmi baru yang memutihkan masa lalu. Sejarah bukan hanya jendela masa lalu, sejarah adalah cara berpikir dan memahami manusia itu sendiri, serta menata masa depan. Jika pemerintah gagal dalam proyek penulisan ini, maka yang terjadi hanyalah pola pengulangan yang sama. Sejarah akan kembali dalam belenggu penguasa.
KOMPASTV, (2025, Mei 28). [FULL] Blak-Blakan! Polemik Penulisan Ulang Sejarah Nasional: Pengaburan Masa Lalu 'by Order'? [Video]. Youtube, https://youtu.be/VrFcauItzsA?si=gCwIdHE8ZptY0FIR