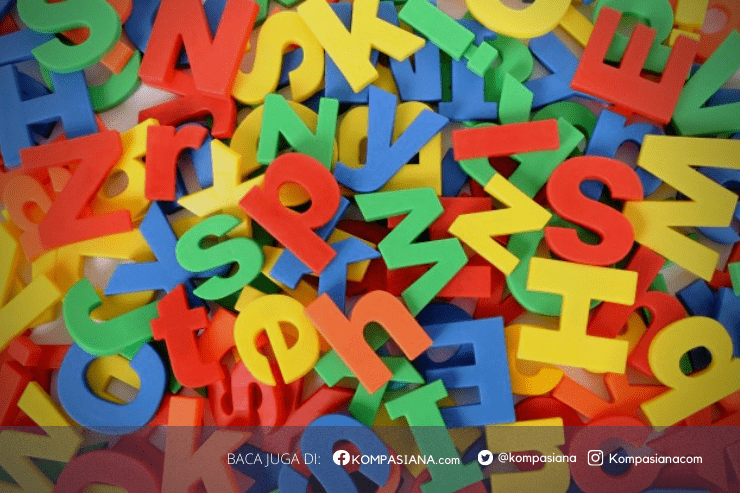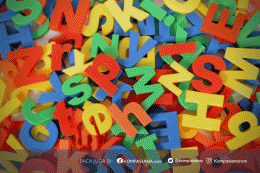“Mengapa saat ini rasa cinta dan kebanggaan masyarakat kita akan bahasa Indonesia semakin luntur?” demikian salah satu ungkapan mahasiswa asal NTT, saat mengikuti perkuliahan. Selanjutnya dia menjelaskan betapa pentingnya peranan bahasa Indonesia bagi masyarakat Indonesia Timur. Apalagi di daerahnya ada beberapa bahasa daerah. Antarwarga suatu daerah harus menggunakan bahasa Indonesia bila harus berkomunikasi dengan warga daerah lainnya. Dalam hal ini bahasa Indonesia berperanan penting menjadi bahasa perhubungan antarmasyarakat yang berbeda etnis dan budayanya.
Ungkapan mahasiswa tersebut sangat beralasan. Rasa cinta dan bangga akan bahasa Indonesia kita tampaknya saat ini menurun dibandingkan saat Orde Baru. Meskipun hal ini belum ada kajian atau penelitian tentang hal tersebut, sebagai pengajar bidang studi Bahasa Indonesia, kami sangat merasakannya.
Pada masa Orde Baru dengan Pemerintahan Soeharto yang dianggap otoriter, mobilisasi umum merupakan sarana yang sangat efektif dalam mengimplementasikan program. Hal ini juga terjadi saat pembinaan bahasa Indonesia. Berbagai penataran dan pelatihan tentang bahasa Indonesia berjalan lebih efektif. Campur tangan kekuasaan ini pun dapat digunakan saat sosialisasi penggunaan bahasa yang baik dan benar. Misalnya, pernah berkali-kali pemerintah daerah terpaksa harus memperingatkan bahkan menurunkan paksa pada spanduk, iklan, atau papan nama yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Saat itu, Soeharto adalah figure pemimpin yang dapat dijadikan panutan karena “dianggap” sangat cinta dan bangga akan bahasa Indonesia (meskipun banyak kritik pada idioleknya yang tidak bisa hilang yaitu : semangkin, pendidi’an, dan akhiran ‘-ken’). Meskipun bisa berbahasa Inggris (karena pernah bertahun-tahun mengikuti pendidikan militer di luar negeri), Soeharto tetap menggunakan bahasa Indonesia saat menerima tamu dari negara asing dan bahkan berpidato di berbagai forum penting di luar negeri. Karena itulah sangat terasa bahasa Indonesia menjadi kebanggaan kita bersama.
Sejalan dengan runtuhnya rezim Soeharto, gerakan reformasi terjadi dalam setiap aspek kehidupan. Eforia perubahan dan kebebasan tampaknya lebih menonjol setelah terkungkung oleh ketatnya pemerintahan otoriter. Kini, orang bisa leluasa untuk melakukan apa saja, termasuk juga berbahasa. Aturan bahasa Indonesia yang dianggap sebagai ‘bahasa kekuasaan yang membelenggu’ pun dilepaskan. Bahkan kebaikan Soeharto habis sama sekali dan yang tampak hanya keburukannya saja.
Namun demikian, apa yang terjadi sesudahnya? Penggantinya malah tidak mampu menjadi kiblat panutan dalam berbahasa Indonesia. Justru yang muncul adalah pamer karena merasa lihay dalam berbahasa asing. Masyarakat pun semakin tidak perduli dengan perlunya berbahasa Indonesia. Dimana-mana muncul wacana menggeser peran bahasa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kita pun semakin miris dengan menjamurnya sekolah internasional (SBI/RSBI) hingga ke pelosok kabupaten dan kecamatan. Keberadaan mereka seolah berlomba-lomba bersaing menjadi yang terbaik di daerah masing-masing. Mereka berupaya mengganti bahasa Indonesia dengan bahasa asing lainnya sebagai bahasa pengantar di sekolah untuk semua mata pelajaran. Bahkan, (ada yang) untuk mengajarkan bahasa Indonesia pun para guru menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantarnya. Apakah para guru dan generasi penerus ini sudah menganggap eksistensi bahasa, bangsa, bahkan negara ini sudah tidak penting lagi?
Empat Pilar Bangsa
Beberapa tahun terakhir, kita dihadapkan pada wacana untuk menegakkan empat pilar bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Binneka Tunggal Ika, dan Proklamasi 17 Agustus 1945. Rupanya para petinggi negara ini sudah sadar perlunya menegakkan eksistensi bangsa dan negara ini di masa depan. Tantangan serius berupa disintegrasi dan globalisasi dapat merobohkan empat pilar kebangsaan ini. Berbagai konflik sara sering mencuat menunjukkan goyahnya pilar Binneka Tunggal Ika. Banyak pula yang semakin alergi dengan istilah yang bernama Pancasila, apalagi mengamalkannya. Undang-Undang Dasar 1945 pun dikoyak-koyak pasalnya disesuaikan dengan kepentingan sesaat. Akhirnya globalisasi menggerus kecintaan dan kebanggaan kita akan eksistensi Negara yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.
Fenomena di atas menunjukkan perlunya merekonstruksi nasionalisme kita, termasuk juga dalam berbahasa Indonesia. Kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara indoktrinasi model Orde Baru karena bukan masanya. Yang memungkinkan adalah melalui penanaman kesadaran mendalam tentang hakikat cinta dan kebanggaan akan bangsa, bahasa, dan negara kita. Saluran informasi melalui media hendaknya tidak jemu-jemu memberikan iklan layanan masyarakat tentang topik ini. Jangan lupa, siapkan generasi mendatang yaitu anak-anak didik yang siap menegakkan empat pilar bangsa ini. Termasuk di dalamnya, kembali mencintai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai salah satu wujud nasionalisme. (Sartono-Guru Bahasa Indonesia, Sidoarjo)
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI