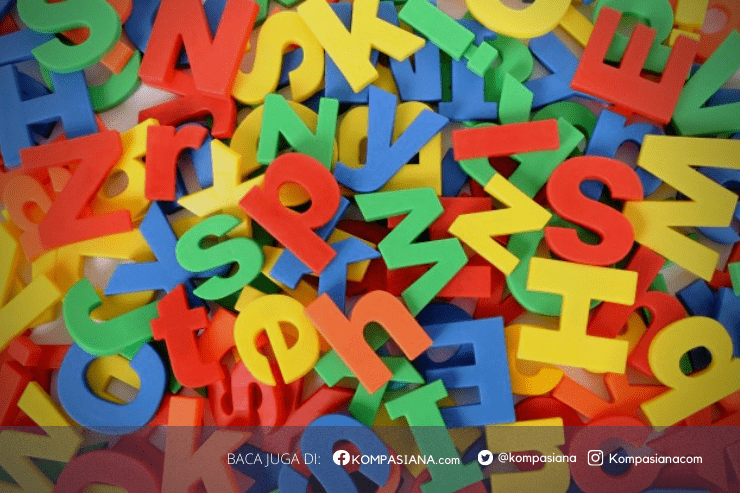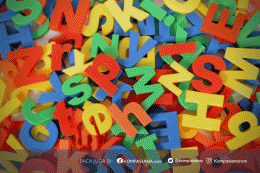“Bahasa Indonesia terlupakan dari salah satu pilar bangsa kita. Padahal peranan bahasa Indonesia tidak kalah pentingnya dari keempat pilar bangsa lainnya. Justru bahasa Indonesia lebih tepat sebagai soko guru dari 4 pilar bangsa kita.”
Hal ini sebagaimana J. Vendreyes, seorang sosiolog Perancis, pernah mengungkapkan bahwa bahasa yang sama akan mendorong para penuturnya memiliki kesamaan cara pandang. Kesamaan cara pandang akan mendorong mereka untuk bersatu.
Sejarah mencatat betapa besar peranan bahasa Indonesia dalam mempersatukan bangsa ini sekaligus meningkatkan nasionalisme. Sejak abad ke-7 bahasa Indonesia yang saat itu masih berupa cikal bakalnya yaitu bahasa Melayu Kuno (Kwun Lun) telah menunjukkan peranannya. Bahasa ini telah digunakan sebagai bahasa perhubungan antaranggota masyarakat dan agama. Hal ini tertuang dalam beberapa prasasti, yaitu : Kedudukan Bukit, Talang Tuwo, Kota Kapur, dan Genting Kra (Malaysia).
Di era pertengahan, bahasa Melayu berkembang sebagai bahasa perhubungan (‘lingua franca’) antaranggota masyarakat, di kalangan pemerintahan, bahkan berkomunikasi dengan bangsa lain yang berpentingan dengan etnis Melayu di Kepulauan Riau, Semenanjung Malaka, dan sekitarnya. Bukti-buktinya tersurat jelas pada karya-karya sastra Melayu, antara lain : “Sejarah Melayu”, “Hikayat Raja-raja Pasai”, “Hikayat Hang Tuah”, dan sebagainya.
Perkembangannya semakin pesat ke berbagai wilayah Indonesia, terbukti adanya bahasa Melayu rendah di berbagai wilayah di Indonesia. Peranannya menjadi sangat penting pada masa pergerakan pemuda. Puncaknya pada Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928 di Jakarta. Bahasa tersebut dinobatkan sebagai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
Sebagaimana pernyataan J. Vendreyes di atas, bahasa yang sama mendorong penuturnya untuk bersatu. Oleh Pemerintah Kolonial Belanda, peristiwa ini dianggap sebagai ancaman serius. Persatuan berbagai suku bangsa akan menjadi kekuatan yang sangat sulit untuk dilumpuhkan. Karena itulah, pada tahun 1932 Pemerintah Kolonial Belanda mengadakan kursus bahasa Belanda secara besar-besaran. Tujuannya untuk ‘menggembosi’ perkembangan bahasa Indonesia. Mereka yang lulus dari kursus singkat ini akan langsung diangkat sebagai pegawai rendahan atau sebagai juru tulis. Ternyata strategi ini sangat efektif. Akhirnya bahasa Indonesia terpuruk dan hanya dipakai oleh sekolah-sekolah nasionalis dan kalangan pemuda pergerakan.
Kedatangan penjajahan Jepang membawa angin segar bagi perkembangan bahasa Indonesia. Dalam Maklumat Bangkalan (Maret 1942) dinyatakan bahwa semua nama jalan, bangunan-bangunan, dan sebagainya harus diubah menjadi bahasa Indonesia atau bahasa Jepang. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa komunikasi dalam pemerintahan. Peraturan tersebut memberikan konsekwensi tegas bagi siapa yang melanggarnya. Karena itu bahasa Indonesia berkembang sangat pesat tanpa halangan yang berarti lagi karena sangat penting peranannya.
Kedudukan bahasa Indonesia semakin penting dengan dikukuhkannya menjadi bahasa Negara sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 36, “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”. Sejak saat itu bahasa Indonesia terus berkembang dan berbenah.
Bahasa Menunjukkan Bangsa
Kita sering mendengar pomeo tersebut yang artinya dari bahasa yang digunakan oleh seseorang menunjukkan etnisitasnya dari suku apa, kebangsaannya dari bangsa atau negara mana, bahkan nasionalisme mana yang dianutnya. Bila dia berkulit sawo matang seperti kita, tinggal di sekitar kita, namun tidak bangga menggunaka bahasa Indonesia alias selalu menggunakan bahasa asing, maka dapat dipertanyakan nasionalismenya atau bahkan mungkin dia seorang yang masa bodoh dan “komprador” (suka menggadaikan bangsa).
Akhir-akhir ini berkembang wacana empat pilar bangsa yang meliputi Pancasila, UUD 1945, Binneka Tunggal Ika, dan Proklamasi 17 Agustus 1945. Berbagai penataran dan seminar pembinaan mental diadakan mulai dari berbagai lembaga tinggi negara, lembaga pemerintahan, hingga kalangan mahasiswa dan pelajar. Tidak tanggung-tanggung wacana ini didukung penuh oleh Ketua MPR Bapak Taufiq Kiemas.
Para petinggi negara ini rupanya telah mulai menginsyafi pentingnya menegakkan empat pilar bangsa tersebut. Disintegrasi dan ketidakpedulian terhadap penjanjian agung falsafat negara merupakan ancaman terhadap pilar Binneka Tunggal Ika dan Pancasila. Sementara itu UUD 1945 semakin terkoyak-koyak oleh pasal-pasal kepentingan. Semua hal tersebut akhirnya mengancam tegaknya negara yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.
Setelah runtuhnya rezim Orde Baru, tantangan primordialisme semakin kuat sejalan diberlakukannya otonomi daerah. Di samping itu, globalisasi tidak kalah serunya menggerus nasionalisme kita. Banyak kalangan menilai keempat pilar kebangsaan kita ini sudah hampir roboh semua. Hal ini dikhawatirkan juga mengancam eksistensi negara ini.
Ternyata tantangan di atas juga terjadi pada bahasa kita. Bahasa Indonesia mengalami polusi interferensi dimana-mana. Banyak yang merasa tidak keren jika nama kegiatannya tidak berbahasa asing. Demikian pula berbagai gedung, bangunan, perumahan, pertokoan harus berbahasa asing untuk menaikkan pamornya. Mungkin mereka khawatir dianggap ketinggalan jaman dan tidak laku bila menggunakan bahasa Indonesia.
Karena kebahasaan erat sekali dengan kebangsaan alias nasionalisme, maka pembinaan mental yang terkait akan bahasa Indonesia sangat urgen untuk dilakukan. Pembinaannya perlu diarahkan pada kebanggan dan kecintaan akan bahasa Indonesia serta ketaatan menggunakan kaidah yang baik dan benar. (Sartono, Guru Bahasa Indonesia)
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI