Indonesia baru saja meluncurkan Danantara pada awal pekan lalu, sebuah Sovereign Wealth Fund (SWF) yang digadang-gadang akan menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Dengan total aset senilai USD 900 miliar atau sekitar Rp 15.000 triliun, Danantara diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan dan kesejahteraan nasional.
Namun demikian, di balik optimisme itu, ada pula kekhawatiran mengenai potensi risiko yang menyertainya.
SWF sering disebut dana abadi bagi sebuah negara. Dana itu bersumber dari kelebihan uang (excess) yang kemudian diputar atau diinvestasikan, sehingga menghasilkan laba terus-menerus tanpa menggerus modal awalnya.
Laba tersebut kemudian digunakan untuk membangun proyek-proyek negara yang tidak mungkin dilakukan perusahaan swasta karena punya orientasi kemaslahatan jangka panjang (bukan profit jangka pendek).
Perbedaan utama satu SWF dari SWF lain adalah dari mana modal awalnya dan bagaimana dana itu diinvestasikan. Sebagian besar (70%) SWF di dunia memperoleh modal awal dari penjualan sumber daya alam non-terbarukan (industri ekstraktif).
Model ini misalnya dimanfaatkan secara cerdik oleh Norwegia. Negeri itu menyisihkan hasil penjualan minyak dan gas untuk menjadi modal awal The Government Pension Fund Global (GPFG), salah satu SWF terbesar dan paling menguntungkan di dunia. SWF milik Norwegia itu memanfaatkan dana hasil penjualan minyak itu untuk berinvestasi dalam beragam perusahaan/proyek yang menguntungkan, terutama di luar negeri.
Dengan cara itu, Norwegia memperluas dan menganekaragamkan sumber-sumber pemasukan negara sehingga tak hanya tergantung dari minyak. Norwegia sadar bahwa disamping minyak akan habis, harganya juga berfluktuasi yang bisa mengganggu penyelenggaraan ekonomi negara.
The Alaska Permanent Fund (APFC), SWF milik Negara Bagian Alaska di Amerika Serikat, juga menerapkan konsep serupa Norwegia. Alaska kaya akan minyak dan gas.
Negara-negara petro-dollar di Timur Tengah juga mengambil jalan yang sama: memakai surplus penjualan minyak untuk memodali SWF seperti Mubadala (Uni Emirat Arab), The Public Investment Fund (Saudi Arabia), Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), dan Qatar Investment Authority (QIA). SWF ini dikenal memiliki portofolio investasi global yang luas dan beragam, mencakup properti, teknologi, hingga industri strategis.
Sementara itu, Temasek Holdings milik Singapura dan Khazanah Nasional Berhad (KNB) milik Malaysia mengadopsi model berbeda. Dana awal mereka sebagian besar berasal dari penyertaan modal negara dan aset perusahaan pelat merah. Mereka berfokus pada investasi strategis di sektor domestik maupun internasional, dengan tujuan memperkuat posisi ekonomi negara masing-masing.
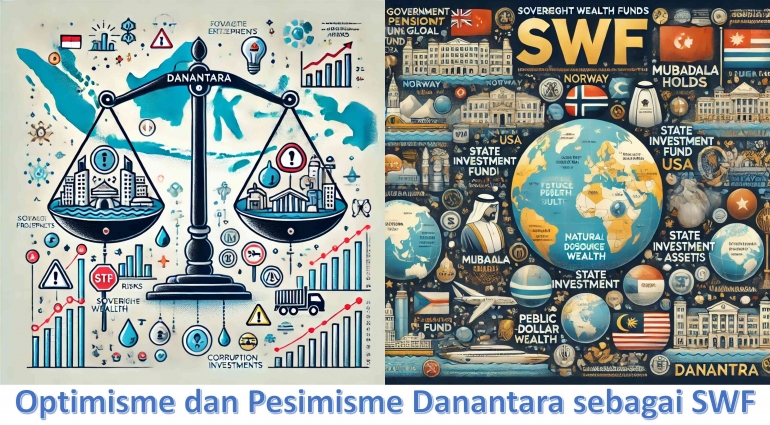
Namun, pelajaran berharga juga bisa diambil dari perbedaan nasib dua SWF Malaysia: Khazanah Nasional Berhad (KNB) dan 1Malaysia Development Berhad (1MDB). KNB berhasil meningkatkan nilai asetnya secara konsisten berkat pengelolaan yang profesional, transparansi, dan akuntabilitas yang kuat.
Sebaliknya, 1MDB terjerat dalam skandal korupsi besar dan gagal bayar akibat lemahnya pengawasan dan tata kelola yang buruk. Perbedaan mendasar ini menunjukkan betapa pentingnya komitmen terhadap prinsip-prinsip good governance dalam menentukan keberhasilan sebuah SWF.
Danantara, di sisi lain, menggunakan pendekatan yang lebih berani dan berbeda. Dengan mengumpulkan seluruh aset BUMN di bawah satu atap superholding, Danantara diharapkan memiliki daya ungkit besar untuk mendapatkan pendanaan dan investasi.
Namun demikian, konsentrasi kekayaan nasional dalam satu entitas ini juga menimbulkan kekhawatiran: bagaimana jika pengelolaannya kurang transparan atau keputusan investasi yang diambil kurang tepat?
Optimisme atas Danantara terletak pada potensi efisiensi dan percepatan pembangunan. Dengan pengelolaan terpusat, keputusan bisa diambil lebih cepat dan sigap, serta aset negara bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk proyek-proyek strategis.
Selain itu, Danantara berpotensi mendatangkan investasi asing dalam jumlah besar, yang dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan proyek nasional lainnya. Namun, pesimisme juga tak bisa diabaikan. Konsentrasi aset yang terlalu besar dalam satu lembaga menimbulkan risiko tinggi.
Jika terjadi salah kelola atau investasi yang gagal, dampaknya bisa sangat luas bagi perekonomian nasional. Selain itu, kurangnya transparansi dan pengawasan bisa membuka celah bagi praktik korupsi dan nepotisme. Kasus 1MDB menjadi pengingat nyata betapa pentingnya tata kelola yang baik untuk menghindari risiko besar tersebut.
Kita bisa belajar dari Norwegia dan Alaska dalam memanfaatkan kelebihan pendapatan sumber daya alam untuk investasi jangka panjang yang berkelanjutan. Di sisi lain, Temasek dan Khazanah menunjukkan bahwa pengelolaan aset negara yang terfokus dan profesional juga bisa menghasilkan keuntungan besar.
Danantara adalah langkah besar dan ambisius. Untuk menjadi sukses, ia harus mampu menyeimbangkan antara keberanian berinvestasi dan kehati-hatian dalam pengelolaan aset. Dengan pengawasan yang ketat, transparansi, dan akuntabilitas, bukan tidak mungkin Danantara akan menjadi salah satu SWF paling berpengaruh di dunia.
Akan tetapi, sebaliknya, tanpa komitmen kuat terhadap good governance, Danantara berisiko terjebak dalam skenario yang merugikan.
Oleh karena itu, keberhasilan Danantara sangat bergantung pada sejauh mana prinsip-prinsip pengelolaan yang baik dapat diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan.

Dengan begitu, optimisme yang menyertainya bisa benar-benar terwujud, bukan sekadar harapan kosong.
Penulis: Merza Gamal (Pemerhati Sosial Ekonomi Syariah)
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI









