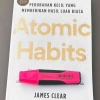Menjadi santri bukan sekadar belajar kitab dan menghafal nasihat guru. Menjadi santri berarti belajar bagaimana menata hati dalam menerima ilmu. Sebab tanggung jawab seorang terpelajar bukan hanya memahami isi pelajaran, tapi juga menjaga adab di setiap langkahnya.
Bagi kami, menghormati guru bukan kewajiban karena takut, melainkan karena sadar: ilmu tidak akan pernah sampai tanpa adab. Kami menyapa, menunduk, memberi salam, dan tersenyum bukan karena terpaksa, tapi karena itu wujud cinta dan hormat. Itu cara kami mengingat bahwa setiap pengetahuan yang diberikan guru bukan sekadar informasi, melainkan warisan ruhani yang disampaikan dengan ikhlas.
Di luar sana, banyak yang membicarakan pesantren sebagai ladang feodalisme. Mungkin memang ada yang seperti itu, tapi tidak adil jika semua dipukul rata. Setiap pesantren punya kultur yang tumbuh dari tanah sosialnya sendiri. Yang membuatnya hidup bukan sistemnya, tapi manusianya. Feodalisme bukan bawaan pesantren, melainkan cara sebagian orang memaknai relasi kuasa dalam bingkai penghormatan.
Sebagai santri, aku tidak merasa tertekan oleh adab. Justru adab itulah yang menjaga kami agar tetap rendah hati di tengah derasnya arus pengetahuan. Guru bagi kami bukan penguasa, tapi pembimbing. Dan dalam setiap ucapan salam serta senyum, kami berusaha merawat hubungan itu---agar ilmu yang diterima tidak sekadar menambah tahu, tapi juga menumbuhkan jiwa.
Adab bukan penghalang kebebasan berpikir, tapi pagar agar akal tidak tersesat dalam kesombongan. Di sanalah letak kehormatan seorang santri: berpikir kritis tanpa kehilangan hormat, berani bersuara tanpa melupakan tata krama, dan terus belajar tanpa merasa paling tahu.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI