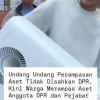Coba bayangkan ini pagi-pagi buta, seorang anak di pelosok Halmahera menyusuri jalan setapak berlumpur. Ia tidak memegang gawai canggih atau membawa bekal lengkap, hanya selembar buku tulis lusuh yang basah karena embun. Ia berjalan kaki lima kilometer hanya untuk duduk di bangku sekolah yang atapnya bocor dan papan tulisnya sudah tak layak pakai. Di saat yang sama, anak di kota besar menyalakan laptop, membuka platform pembelajaran digital, dan ikut kelas interaktif dari rumah.
Dua potret ini bukan perbandingan imajinatif ini adalah potret nyata dari ketimpangan pendidikan di Indonesia. Ketika sebagian anak-anak di negeri ini sudah bicara tentang coding dan AI, masih banyak yang bahkan belum bisa membaca lancar saat duduk di kelas tiga SD. Dan ironisnya, itu bukan karena mereka malas, tapi karena sistemnya yang tidak pernah berpihak pada mereka.
Masalah Pendidikan di Daerah Tertinggal Bukan Sekadar Infrastruktur
Kamu mungkin berpikir, "Masalah utama pendidikan di daerah tertinggal pasti karena minimnya bangunan sekolah dan fasilitas dasar." Meskipun itu ada benarnya, kenyataannya jauh lebih kompleks. Infrastruktur memang jadi masalah awal, tapi akar permasalahannya jauh lebih dalam dari sekadar dinding dan meja belajar.
Pendidikan adalah ekosistem. Kalau kamu hanya memperbaiki bangunan tapi membiarkan kurikulumnya tetap kaku, guru tidak terlatih, atau metode pengajarannya tidak relevan dengan konteks lokal, maka hasilnya tetap akan timpang. Misalnya, guru yang ditempatkan di wilayah terpencil kadang tidak mendapatkan pelatihan pedagogis yang adaptif terhadap budaya lokal. Bayangkan mengajarkan kurikulum nasional dengan konteks urban kepada anak-anak di pedalaman Papua yang tidak hidup dalam kerangka sosial yang sama. Itu bukan mengajar itu memaksakan.
Lebih parah lagi, banyak guru kontrak di daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan) hanya bertahan beberapa bulan. Tak sedikit yang akhirnya kembali ke kota karena tekanan hidup di pelosok tak sebanding dengan honor yang diterima. Dalam kondisi seperti ini, pendidikan di sana bukan hanya tertinggal, tapi nyaris dilupakan.
Pemerataan Pendidikan Masih Jadi Retorika Formalitas
Salah satu jargon yang sering kamu dengar dari pejabat pemerintah adalah "pemerataan pendidikan". Tapi coba renungkan, apa benar itu sudah terjadi? Atau jangan-jangan kita sedang menutupi jurang ketimpangan dengan kata-kata indah?
Dalam laporan World Bank tahun 2023, Indonesia menempati posisi bawah dalam hal Learning Poverty, yakni proporsi anak usia 10 tahun yang tidak bisa memahami bacaan dasar. Di beberapa provinsi timur Indonesia, angka ini mencapai lebih dari 50%. Artinya, lebih dari setengah anak-anak di sana tidak bisa memahami teks sederhana meski sudah duduk di bangku sekolah dasar. Itu bukan hanya angka, itu alarm keras.
Ironisnya, alokasi anggaran pendidikan nasional sebesar 20% dari APBN sering kali tidak menyentuh daerah-daerah yang benar-benar butuh. Dana BOS, misalnya, lebih banyak dimanfaatkan oleh sekolah di kota karena proses administrasi dan pelaporannya yang lebih tertata. Sementara sekolah di pelosok sering kebingungan mengakses bantuan karena keterbatasan SDM dan keterampilan digital. Dalam sistem seperti ini, yang tertinggal akan semakin tertinggal.