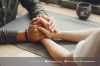Seseorang yang telah menikah dengan seseorang yang tidak memiliki hubungan pernikahan dengannya dikenal sebagai perselingkuhan. Kegiatan berselingkuh adalah hal yang tidak lazim dan menyimpang dari norma masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat akan sangat tertarik untuk berbicara tentang perselingkuhan saat berkumpul. Menurut CNN Indonesia (2022), ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap cerita perselingkuhan mencapai 60,29% dari 209 orang yang disurvei. Dengan demikian, peristiwa perselingkuhan dapat dianggap sebagai pemberitaan karena memenuhi syarat berita human interest dan konflik. Namun, sepanjang cerita, pelaku perempuan selalu digambarkan sebagai pihak yang bersalah dan bertanggung jawab atas perselingkuhan. Ini dapat dilihat dari pemilihan kata yang digunakan dan jumlah informasi yang tidak seimbang yang diberikan kepada pelaku laki-laki dan perempuan.
Bias gender yang kuat seringkali mendominasi diskusi tentang perselingkuhan di masyarakat dan budaya Indonesia. Perempuan sering dikaitkan dengan kesalahan moral menurut cerita yang diputar di media, diskusi publik, dan percakapan sehari-hari, seolah-olah mereka adalah faktor utama atau pihak yang melenceng dalam hubungan. Pola pikir ini secara tidak langsung memperkuat struktur patriarki yang telah lama tertanam dalam kebiasaan dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: mengapa wanita selalu dianggap bersalah dalam perselingkuhan? Indonesia memiliki norma yang ketat tentang peran gender karena keragaman budaya dan nilainya yang luas. Di satu sisi, perempuan sering dianggap sebagai penjaga kesucian dan moralitas keluarga, sebuah posisi yang sangat diharapkan dan menuntut. Laki-laki, di sisi lain, cenderung memiliki kebebasan yang lebih besar dalam mengekspresikan keinginan dan perilaku mereka, bahkan ketika perilaku tersebut tidak sesuai dengan standar. Karena ketidaksamaan ini, ketika terjadi pelanggaran dalam hubungan, perempuan dengan cepat dianggap sebagai pihak yang bermasalah, sementara peran laki-laki sering diabaikan atau diabaikan.
Media massa juga sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik. Dalam kasus perselingkuhan, pemberitaan sering mengambil unsur sensasional dan berfokus pada cerita "kesalahan perempuan". Dalam pemberitaan seperti ini, perempuan tidak jarang digambarkan sebagai orang yang lemah, naif, atau rentan, yang pada gilirannya memperkuat stereotip negatif yang sudah ada tentang mereka. Narasi ini membuat membebaskan diri dari stigma menjadi lebih sulit bagi perempuan. Itu juga mengaburkan kompleksitas kasus perselingkuhan, yang sebenarnya disebabkan oleh interaksi dinamis antara berbagai faktor pribadi, sosial, dan struktural. Narasi yang menyatakan bahwa "perempuan selalu bersalah" dalam masalah perselingkuhan mencerminkan dominasi struktur patriarki dalam masyarakat Indonesia. Dalam sistem ini, perempuan dianggap sebagai pelindung moral keluarga dan komunitas. Ketika perselingkuhan terjadi, tekanan sosial lebih banyak ditujukan kepada perempuan, baik sebagai istri yang dianggap "gagal menjaga suami" maupun sebagai orang ketiga yang dianggap "penghancur rumah tangga orang lain. " Ini bukan sekadar isu sosial, tetapi mencerminkan relasi kekuasaan yang berakar dalam sejarah dan budaya.
Bourdieu mengemukakan istilah "habitus" sebagai pola pikir dan perilaku yang terbentuk oleh struktur sosial. Dalam konteks ini, habitus masyarakat Indonesia sering kali menginternalisasi pandangan bahwa perempuan seharusnya pasif, setia, dan bertanggung jawab atas kestabilan keluarga. Ketika ada penyimpangan dari norma ini, perempuan mendapatkan sanksi sosial yang lebih berat. Ini mengindikasikan bahwa institusi keluarga tidak bersifat netral gender, melainkan berfungsi untuk memperkuat ketidakadilan relasi. Di sisi lain, teori sosialisasi gender menjelaskan bagaimana anak-anak diperkenalkan kepada peran dan harapan berdasarkan jenis kelamin sejak kecil. Laki-laki diberi kesempatan untuk mengeksplorasi, sedangkan perempuan diajarkan tentang kesetiaan dan pengorbanan. Saat perempuan menyimpang dari norma dalam konteks hubungan, meskipun laki-laki juga terlibat, masyarakat cenderung menilai perempuan dengan standar moral yang jauh lebih ketat. Kisah perselingkuhan kemudian menjadi sarana untuk memperkuat stereotip ini.
Media, sebagai agen sosialisasi yang kedua, juga berkontribusi pada reproduksi bias gender. Representasi perempuan dalam sinetron atau berita infotainment sering kali menekankan karakter negatif saat terlibat dalam skandal perselingkuhan. Istilah seperti "pelakor" sering dipakai hanya untuk perempuan, tanpa mempertimbangkan dinamika hubungan dan alasan konflik. Pandangan ini menegaskan bahwa media bukan hanya mencerminkan realitas, tetapi juga membentuk realitas sosial yang bias. Teori labeling dari Howard Becker menjelaskan bagaimana identitas seseorang terbentuk berdasarkan label sosial yang diberikan oleh masyarakat. Dalam kasus perselingkuhan, perempuan yang terlibat lebih dulu mendapatkan stigma negatif dibandingkan laki-laki. Label seperti "penggoda" atau "perusak rumah tangga" dapat mengakibatkan konsekuensi sosial seperti pengucilan, kekerasan simbolik, hingga hilangnya kesempatan kerja atau pendidikan. Sementara itu, laki-laki sering dianggap sebagai "korban godaan," yang memperkuat ketidakadilan dalam tanggung jawab sosial.
Ketidakadilan ini juga dapat berpengaruh terhadap akses perempuan terhadap keadilan hukum dan pemulihan psikososial. Dalam kasus perceraian karena perselingkuhan, perempuan sering kali menghadapi beban ganda: membuktikan kesalahan pasangan sekaligus menjaga martabat diri di hadapan publik yang memberikan stigma. Proses hukum yang berbelit dan kecenderungan bias dalam institusi memperkuat posisi subordinat perempuan dalam konflik keluarga. Ini menunjukkan bahwa masalah ini bersifat struktural, bukan sekadar masalah individu. Dengan demikian, analisis sosiologis terhadap narasi "perempuan selalu bersalah" menunjukkan bahwa bias gender dalam kasus perselingkuhan adalah hasil dari konstruksi sosial, internalisasi norma patriarki, dan peran media dalam membentuk pandangan publik. Diperlukan pendekatan kritis dalam bidang pendidikan, regulasi media, serta reformasi hukum untuk mengurangi bias dan mendorong kesetaraan gender dalam memahami, menilai, dan menangani kasus-kasus hubungan interpersonal seperti perselingkuhan.
Narasi tentang perselingkuhan di Indonesia yang sering menyalahkan "perempuan" menunjukkan pentingnya adanya pendidikan kritis gender dalam pembelajaran. Saat ini, topik mengenai hubungan kekuasaan, konstruksi sosial gender, dan pemahaman terhadap bias media masih kurang diperhatikan dalam kurikulum resmi. Hal ini menyebabkan siswa tumbuh dengan pemikiran patriarkal tanpa mendapatkan kesempatan untuk mendiskusikan isu keadilan relasional serta kompleksitas motivasi individu. Kelas seharusnya menjadi tempat refleksi di mana isu-isu media seputar perselingkuhan dianalisis sebagai fenomena sosial, bukan hanya sekedar gossip. Dengan memberikan siswa keterampilan dalam literasi media dan berpikir kritis, pendidik dapat mendorong pemahaman bahwa istilah seperti "pelakor" bukanlah gambaran yang objektif, melainkan hasil stereotip gender yang merugikan perempuan. Lebih lanjut, penggabungan modul interdisipliner---seperti sosiologi gender, psikologi, dan etika---dapat mendukung pemahaman menyeluruh. Penilaian kurikulum dan materi ajar perlu melibatkan perspektif perempuan, ahli gender, dan praktisi sosial supaya materi yang diajarkan benar-benar mencerminkan beragam pengalaman.
Selanjutnya, perubahan dalam pendidikan harus melibatkan pelatihan guru yang peka terhadap gender dan penciptaan komunitas belajar. Guru memiliki peran penting sebagai penggerak perubahan dalam lingkungan sekolah yang bersih dari stereotip dan stigma. Melalui lokakarya, seminar, dan pelatihan, pendidik dapat mempelajari cara mengelola diskusi, analisis media, serta strategi untuk memberdayakan siswa dengan pendekatan partisipatif. Selain itu, kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil serta lembaga feminis akan memperkaya materi ajar dan meningkatkan relevansi pembelajaran. Di tingkat sekolah, kelompok diskusi gender dan literasi media bisa dibentuk untuk mendorong dialog antar siswa dari berbagai angkatan dan disiplin ilmu. Keterlibatan aktif siswa dalam kampanye kesetaraan gender---melalui teater, karya seni, serta media digital---akan membekali mereka menjadi agen perubahan. Di samping itu, pengumpulan masukan dari siswa dan pihak terkait akan membantu mengevaluasi dampak dari intervensi dan menyesuaikan metode pembelajaran.
Dalam menghadapi bias gender yang terkandung dalam narasi "Perempuan Selalu Salah?" terutama dalam konteks perselingkuhan di Indonesia, dibutuhkan strategi multilevel yang mencakup intervensi budaya, pendidikan, kebijakan, dan praktik media. Pertama, pendekatan kultural harus fokus pada dekonstruksi nilai patriarkal melalui penguatan pendidikan kesetaraan gender di seluruh jenjang pendidikan. Kurikulum harus menyertakan pembelajaran tentang konstruksi sosial gender, relasi kuasa, serta dampak psikososial dari stereotip dan stigma. Materi seperti ini tidak semata dipahami secara teoritis, tetapi ditanamkan melalui metode pedagogi reflektif dan partisipatif yang memberi ruang bagi siswa untuk mempertanyakan norma yang telah mapan. Selain itu, pelatihan sensitif gender bagi pendidik dan penyusunan modul pembelajaran yang menyisipkan studi kasus nyata dari kehidupan sehari-hari (misalnya narasi viral tentang perselingkuhan dan pemberitaan yang bias) akan memperkuat pemahaman kritis siswa. Di luar sekolah, pendidikan informal melalui komunitas, diskusi publik, dan konten digital kreatif bisa menjadi senjata ampuh melawan reproduksi narasi timpang tersebut. Misalnya, kampanye media sosial dan karya seni visual yang mengangkat perspektif perempuan secara empatik dapat menciptakan kesadaran baru di ruang publik yang selama ini didominasi oleh narasi misoginis. Pelibatan tokoh agama, budayawan, dan influencer yang progresif juga penting untuk menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas dan heterogen.
Lebih jauh, reformasi struktural juga mutlak dibutuhkan agar perubahan tidak berhenti pada ranah wacana, melainkan berdampak langsung pada sistem sosial yang eksis. Dalam ranah hukum, perlu ada revisi dan penguatan instrumen hukum yang menjamin keadilan berbasis gender, termasuk dalam perkara perselingkuhan dan perceraian. Prosedur pembuktian harus bebas dari bias moralistik terhadap perempuan, dan akses terhadap bantuan hukum harus tersedia tanpa diskriminasi status sosial. Sementara itu, media massa harus diatur melalui kode etik peliputan yang adil gender. Dewan Pers dan lembaga penyiaran sebaiknya menyusun standar pelaporan yang tidak menyudutkan pihak tertentu berdasarkan gender dan mendorong jurnalisme empatik yang memahami konteks sosial pelaku maupun korban. Institusi media juga perlu melakukan pelatihan rutin untuk jurnalis dalam mengenali dan menghindari bahasa serta framing yang seksis. Di sisi lain, lembaga-lembaga keagamaan dan adat perlu diajak berdialog untuk membongkar tafsir-tafsir normatif yang memojokkan perempuan, tanpa menegasikan nilai-nilai spiritual yang konstruktif. Gerakan perempuan, baik yang berbasis akademik maupun akar rumput, harus diperkuat melalui pendanaan, jejaring solidaritas, dan akses ke ruang kebijakan publik. Penutupan ini tidak dimaksudkan sebagai akhir, melainkan sebagai undangan terbuka untuk menggerakkan seluruh lapisan masyarakat dalam membentuk ulang narasi yang lebih adil dan setara. Menghapus keyakinan lama bahwa perempuan "selalu salah" bukan hanya tugas individu, tetapi proyek kolektif bangsa yang ingin maju secara etis, intelektual, dan manusiawi. Tanpa komitmen menyeluruh, bias dalam narasi perselingkuhan akan terus direproduksi dan melegitimasi ketidakadilan gender yang lebih luas.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI