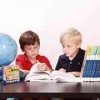Dalam konteks pendidikan, tenaga didik (guru) merupakan actor yang memainkan peran sentral didalamnya. Dia bisa mengubah manusia yang tadinya tidak tahu menjadi tahu dan bahkan ditangan dialah Indonesia dan dunia dipegang, dia bak matahari yang siap menyinari dan membakar kebodohan-kebodohan yang ada. Akan tetapi, melihat konteks kekinian tenaga didik (guru) yang diharapkan menjadi motor perubahan bangsa dan negara sangat jauh dari apa yang dicita-citakan para tenaga didik yang dipercaya bisa memberantas kebodohan kini menjelma menjadi mesin pembodoh itu sendiri, banyak kasus ketika jam KBM (kegiatan belajar mengajar) mereka malah asik berbelanja di mall-mall, sefie sana-sini, foyafoya kesana kemari.
Hal ini kemudian mendukung terciptanya negara gagal (failed country), selain itu dalam metode pembelajaranya pun sangat minim inovasi dan malah menjadi sebuah tenaga didik yang bisa disamakan dengan 'Gaya Bank' dalam metode dan pembelajaranya. Berbicara tentang tenaga didik teringat akan pemikir brazil bernama Paulo Freire ia berasal dari kalangan wong cilik semasa hidupnya ia mengkritik habis metode dan cara ajar di brazil dahulu, pemikirannya mengenai pendidikan menjadi sangat ampuh dalam memperbaiki paradigma masyarakat dalam memahami seperti apa essensi pendidikan yang sebenarnya apalagi bagi kaum - kaum wong cilik.
Pengalaman yang dialaminya di tempat kelahirannya di Brazil telah menunjukkan realitas seperti itu, menurutnya pendidikan yang diterapkan oleh negara justru telah menjadi alat penindas bagi masyarakat miskin dan sangat jauh membuat masyarakat teralienasi (terasingkan) pada realitas dirinya, dimana pendidikan yang seharusnya menjadi alat untuk mencerahkan pemikiran masyarakat malah berbalik fungsi menjadi alat untuk menghegemoni pemikiran masyarakat agar menjadi tunduk dan patuh terhadap pemerintah walaupun kondisi pemerintah pada saat itu sangat jauh dari harapan dan berkat dobrakannya kini wajah pendidikan di brazil menjadi banyak rujukan diberbagai belahan dunia. (A.B. Susanto, 2008: 84)
Pemikiran Freire tentang pendidikan lebih menyerupai petunjuk (guidance) normatif ikhwal kependidikan. Yaitu, berupa bimbingan menjadi guru yang benar dan murid yang benar dalam arti tahu posisi dan tanggung jawabnya, cara-cara membaca atau belajar yang produktif, menyikapi lingkungan sosio-kultural dan sosio-politik secara kritis dan berusaha bermain cantik dalam lingkungan dan sistem di mana dia harus tetap melakukan perubahan.
Substansi pemikiran Freire tentang pendidikan terletak pada pandangannya tentang manusia, tentang dunianya yang kemudian ditransformasikan ke dalam dunia pendidikan yang menghasilkan model pendidikan alternatif yang ditawarkannya, yaitu model pendidikan yang membelenggu ke model yang membebaskan. Eksistensi dan peran besarnya dalam dunia pendidikan sebagai salah satu kontributor teori-teori pendidikan menempatkan dirinya dalam deretan orang-orang yang revolusioner-radikal. Sifat optimismenya sebagai pendidik, meski dalam pemenjaraan dan pembuangan, kontroversialnya kepribadian dan revolusionernya dalam metode pendidikan, telah menjadikannya sebagai seorang pemimpin perjuangan kaum tertindas di dunia ketiga. (Listiyono, 2003: 126)
Pendidikan kaum tertindasnya Paulo Freire berupa pendidikan yang membebaskan dan pendidikan yang mampu memanusiakan manusia. Dilatar belakangi karena adanya fitrah seorang manusia yang selalu menjadi objek (penderita) bukan subjek (pelaku) pendidikan. Bagi Freire penindasan dalam bentuk apapun itu namanya, merupakan sesuatu yang tidak manusiawi (dehumanisasi).
PENDIDIK ALA "BANK" VS PENDIDIK HADAP MASALAH
Hal inilah sebenarnya menjadi titik tolak dari pemikirannya tentang pendidikan. Dewasa ini pendidikan yang ada sangat mengekang dan menindas masyarakat, yang menyebabkan adanya situasi yang menyebabkan pemikiran peserta didik menjadi dangkal dan jangan heran bilamana mereka menjadi manusia sumbu pendek, pendidikan seperti itulah yang disebut Freire dengan sebutan Pendidikan Gaya "Bank" (banking education). Metafor banking berasumsi bahwa ilmu pengetahuan adalah semacam barang, seperti uang yang bisa ditransfer dari satu orang kepada orang lain. Pendidikan banking berarti ilmu pengetahuan ditransfer dari pendidik kepada peserta didik.
Secara aplikatif, pendidikan gaya bank ini menjadikan peserta didik sebagai 'objek' dari proses pendidikan dan menganggap bahwa peserta didik sebagai wadah kosong yang harus diisi dengan pemahaman - pemahaman serta pengetahuan - pengetahuan yang telah ditentukan oleh pendidik, sistem pendidikan beserta kurikulumnya, yang artinya, peserta didik dalam hal ini memposisikan peserta didik sebagai orang yang tidak tahu apa - apa dan harus diisi pengetahuan oleh pendidik supaya bisa tahu dalil-dalil tentang pendidikan yang harus dihapal tanpa diberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fungsi teori tersebut secara implementatif dalam realitas kehidupan mereka. Ilmu yang mereka pahami hanyalah sebatas teori - teori yang secara real sangat tidak mereka pahami dalam keseharian mereka (Fauzan, 2013)
Padahal semestinya, yang namanya ilmu pengetahuan adalah upaya untuk mengenali kehidupan dan dikembangkan sebagai upaya untuk menunjang nalar seseoarang dalam memahami realitas dirinya dan lingkungannya. Dalam sistem pendidikan ini, kreatifitas peserta didik dalam mengembangkan minat dan potensi keilmuannya sangat terpasung oleh sistem yang sangat kaku tersebut. Konsekuensinya, pelajar diintegrasikan kedalam dunia penindas- suatu dunia yang didasarkan pada dehumanisasi kaum tertindas. Sebaliknya Freire membandingkan dengan sistem pendidikan hadap masalah yang ditawarkannya sebagai tandingan (counter) terhadap sistem pendidikan 'gaya bank'.
Dalam sistem yang ditawarkannya tersebut, Freire menyebutkan bahwa dalam sistem pendidikan hadap masalah, berjalannya pendidikan dilakukan dengan bentuk dialogis dua arah. (Utomo, 200: 51) dimana pendidik dan peserta didik memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat dan gagasannya (tidak ada yang superior dan imperior) mengenai suatu teori keilmuan yang kemudian teori tersebut langsung dibahas sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang terjadi, yang konteksnya kali ini adalah teori - teori yang digunakan hanyalah dijadikan sebagai pisau analisis dalam menjawab setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam pendidikan sistem hadap masalah ini juga pendidik bukanlah orang yang posisinya sebagai orang yang paling paham dan paling berkuasa dalam mengisi "kepala - kepala" anak didiknya. Dalam sistem ini, pendidik hanyalah fasilitator dalam mewadahi dialog pendidikan yang dilakukan oleh beberapa peserta didik dan tentu saja pendidik juga sekaligus akan belajar melalui dialog tersebut.
Pendidik juga bertugas dalam membuat suatu wacana mengenai permasalahan tertentu dan teori - teori yang dapat dijadikan dasar analisis yang selanjutnya akan dibahas oleh peserta didik sendiri dengan pandangannya masing -masing, melalui dialog itulah kemudian akan didapatkan suatu kesimpulan yang akhirnya dapat dipahami dengan mudah oleh seluruh peserta didik. Secara singkat, Freire membagi bentuk kesadaran manusia dalam 3 jenis kesadaran: kesadaran magis, kesadaran naif dan kesadaran kritis. Kesadaran magis adalah kesadaran peserta didik (masyarakat) yang tidak mampu melihat kaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya.
Bersifat fatalistis dan selalu hidup dalam ketergantungan terhadap orang lain maupun sistem walaupun ia sebenarnya tahu bahwa dirinya dalam kondisi yang tertindas. Yang kedua yakni kesadaran naif adalah yang lebih melihat aspek manusia sebagai akar penyebab masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Bentuk ekspresi yang dilakukan selalu diselumuti emosional, banyak berpolemik dan berdebat tetapi tidak dengan berdialog.
Sedangkan kesadaran yang ketiga dan yang paling terpenting adalah kesadaran kritis yang lebih melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. kesadaran yang ditandai dengan adanya pemahaman yang mendalam mengenai kondisi - kondisi kekinian, ada kemauan untuk mencari solusi terhadap setiap permasalahan yang terjadi secara kritis, dan selalu berusaha dalam mendalami sebab dan akibat dari setiap permasalahan melalui dialog yang bersifat kritis dan mengakar.
Telaah Pemikiran Freire: Tingkat Kesadaran Orang Indonesia
Tergelincirnya sistem pendidikan dari cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat kemerdekaan bukanlah fenomena baru. Kritik bertubi-tubi terhadap perjalanan pendidikan di Indonesia juga tak kunjung melahirkan reformasi pendidikan, justru yang terlahir adalah proses involusi. Terjadi perubahan, hanya bersifat administratif bukan substantif dalam pendidikan. Kehebohan pendidikan kita, tak pernah berbeda sepanjang tahun. Soal mekanisme rekrutmen siswa, Ujian Nasional, seragam sekolah, buku pelajaran dan sebagainya.
Perbincangan penting soal substansi pendidikan, arah dan tujuan, dasar filosofis seolah tak pernah penting dibicarakan. Tidak heran jika situasi tersebut mengakibatkan proses pendidikan kita bersifat meliorisme. Tambal sulam. Setiap ganti menteri, selalu ganti kebijakan. Kehadiran menteri baru selalu menghadirkan kehebohan baru dalam dunia pendidikan kita.
Berbicara mengenai kesadaran jika ditarik dalam konteks sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia hanya mampu memberikan atau mampu mengantarkan pada tahap kesadaran naival conscientizacao (kesadaran naif), seperti yang sudah disinggung tadi bahwa kesadaran naif dalam diri manusia baru sebatas mengerti namun kurang bisa menganalisa persoalan-persoalan sosial yang berkaitan dengan unsur-unsur yang mendukung suatu problem sosial.
Ia baru mengerti bahwa dirinya itu tertindas, terbelakang dan itu tidak lazim Hanya saja kurang mampu untuk memetakan secara sistematis persoalan-persoalan yang mendukung suatu problem sosial itu. Apalagi mengajukan suatu tawaran solusi dari problem sosial. Berikut akan dipaparkan secara kritis tingkatan-tingkatan kesadaran masyarakat Indonesia:
Pertama, kesadaran magis. Dalam hal ini merupakan kesadaran paling rendah yang dimiliki oleh manusia. Faktanya, orang dengan kesadaran ini melihat kehidupan mereka sebagai sesuatu yang tidak terelakkan, natural dan sulit diubah. Mereka cenderung mengaitkan kehidupannya dengan takdir, mitos dan kekuatan superior yang tidak terbukti secara empiris maupun ilmiah. Sehingga orang dengan kesadaran ini, menganggap kemiskinan dan penindasan sebagai takdir yang tidak terelakkan, sama seperti apa yang sudah di definisikan sebelumnya, orang dengan tipe seperti ini cenderung dogmatik terhadap yang akan dikatakan kepadanya.
Mayoritas masyarakat Indonesia berada pada tingkat kesadaran magis dan lebih sering kita jumpai pada mereka yang lemah dan tertindas oleh kekuasaan. Mereka yang tak punya. Mereka terbelenggu oleh permasalahan yang begitu kompleks yang membuat mereka pada akhirnya pasrah dan menerima apa adanya dalam hidup ini, tanpa adanya usaha, perlawanan ataupun tindakan-tindakan. Mereka yang miskin akan tetap miskin bahkan makin miskin lagi. Fakta seperti ini banyak kita jumpai di Indonesia. Contoh: berpikir bahwa sakit dan sembuh merupakan kehendak Tuhan tanpa harus ada usaha penyembuhan itu sendiri serta menganggap bahwa bodoh adalah takdir Tuhan.
Kedua, kesadaran naif. Paulo Freire menyebutnya sebagai kesadaran semi-intransitif, karena orang pada tingkat kesadaran ini telah bisa menjadi subjek yang mampu berdialog dengan yang lain, tapi belum sampai pada tahap memahami realitas dalam true act of knowing. Kaum Liberal, mengakui bahwa memang ada masalah di masyarakat Namun bagi mereka pendidikan sama sekali steril dari persoalan politik dan ekonomi masyarakat.
Tugas pendidikan cuma menyiapkan murid untuk masuk dalam sistem yang ada. Sistem diibaratkan sebuah tubuh manusia yang senantiasa berjalan harmonis dan penuh keteraturan (functionalism structural). Kalaupun terjadi distorsi maka yang perlu diperbaiki adalah individu yang menjadi bagian dari sistem dan bukan sistem.
Pendidikan dalam perspektif liberal menjadi sarana untuk mensosialisasikan dan mereproduksi nilai-nilai tata susila keyakinan dan nilai-nilai dasar agar stabil dan berfungsi secara baik di masyarakat. Mereka mampu memahami masalah yang mereka alami, namun mereka cenderung menyepelekan dan tidak mengujinya secara cermat. Sehingga mereka sangat rentan dimanipulasi oleh elit politik lewat propaganda, slogan ataupun mitos. Masyarakat Indonesia saat ini sudah banyak yang memiliki kesadaran seperti itu. Bisa memahami permasalahan yang sedang mereka alami namun terlihat tidak peduli.
Dapat dilihat ilustrasi problem saat ini, contoh: kasus money politic. Dalam euforia pemilihan umum banyak praktik politik kotor yang mengelilingi tubuh struktur sosial masyarakat kita. Pihak calon kandidat pemimpin bersama tim suksesnya melakukan beragam cara untuk memenangkan percaturan pemilihan umum, termasuk dalam hal ini adalah praktik money politic. Disisi lain, pihak sebagai penentu siapa pemenang dalam percaturan pemilihan umum yakni masyarakat tentunya telah paham bahwa praktik politik musiman tersebut akan kembali hadir.
Kampanye dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang larangan untuk melakukan serta menerima money politic dalam serangkaian pemilihan umum sekiranya sudah cukup untuk menyadarkan calon kandidat bersama tim sukses dan masyarakat. Namun, pendidikan model gaya bank benar-benar telah merusak seruan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab, praktik money politic tetap saja bergulir disetiap hajatan pemilihan umum. Baik calon kandidat bersama tim sukses dan masyarakat samasama tetap memberikan pemakluman atas praktik politik kotor tersebut. Meskipun diantara mereka sebenarnya tahu bahwa praktik politik yang demikian tidak baik bagi keberlanjutan pendidikan politik kedepannya.
Ketiga, kesadaran yang paling tinggi dalam arkeologi kesadaran manusia menurut Paulo Freire adalah kesadaran kritis. Manusia dalam kesadaran ini mampu berpikir dan bertindak sebagai subjek serta mampu memahami realitas keberadaannya secara menyeluruh, mampu memahami pemahaman yang kurang baik dalam teks dan realitas. Masyarakat dengan tingkat kesadaran kritis masih sedikit ditemui saat ini. Mungkin karena masyarakat sudah terbiasa di-nina bobo-kan.
Sehingga susah untuk berpikir kritis. Akibatnya sulit untuk mencapai keadilan. Karena jumlah mereka yang berpikir kritis ini masih sedikit. Kalah dengan suara mereka yang memiliki kekuasaan.Bagi Freire, pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang menumbuhkan kesadaran kritis. (Mu'arif. 2005:16) Walaupun hal tersebut tidak akan langsung terjadi secara cepat dan instan, akan tetapi semuanya butuh proses yang bertahap sehingga akan mencapai pada kesadaran tersebut.Banyak pelajaran berharga yang dapat kita tarik dalam pemikiran Freire mengenai pendidikan apalagi jika kita kaitkan kedalam realitas pendidikan dinegeri kita pada saat ini.
Seperti apa kondisi pendidikan kita? apakah benar sistem pendidikan kita membuat kita menjadi orang - orang yang cerdas dan menghasilkan orang - orang yang dapat memberikan solusi terhadap setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari - hari. Lalu apakah pendidikan yang kita rasakan hari ini merupakan suatu upaya untuk membebaskan masyarakat dalam belenggu penindasan? sadari lah bahwa pendidikan yang kita rasakan ini masih jauh dari harapan.
Pendidikan hanya berorientasikan nilai dan hanya diukur dari segi angka semata. Jika kita katakan bahwa pendidikan hari ini memihak kepada siapa, idealnya dalam aturan perundang - undangan di negeri ini adalah untuk semua rakyat Indonesia baik yang mampu maupun tidak mampu. Namun kenyataannya, pendidikan masih menjadi akses yang sangat sulit dijangkau oleh rakyat miskin dan hanya yang memiliki uang yang banyaklah yang dapat menikmati pendidikan. Belum lagi permasalahan fasilitas pendidikan yang sangat memprihatinkan dan tidak merata kondisinya.
PAULO FREIRE DAN FILSAFAT TUTWURI
Agak berbeda dengan filsuf sekalibernya, Freire tidak terutama menggugat sistem persekolahan. Melainkan lebih memberi sosok jelas bagi program pendidikan yang menjawab masalah (La Belle, 1976). Dalam berbagai bukunya, Freire mengungkapkan sistem pendidikannya yang sungguh-sungguh berasas filsafat Tutwuri Handayani.
Freire menggariskan perlunya para pendidik bersikap tanpa pamrih , dalam artian tidak memaksakan latarbelakang kebudayaan atau pandangan dunia dari kelas sosialnya sendiri. Kata-kata kunci atau tema-tema pendidikan perlu digali dari dunia tematis wong cilik atau terdidik sendiri sehingga kata-kata yang mereka ucapkan adalah kata-kata sejati, bukan mantra-mantra dari luar yang sekadar harus dilafalkan.Pendidikan ialah problem posting education, bukan sekadar pendidikan gaya 'Bank', dimana pendidik menyuapkan pemecah masalah kepada teridik (problem solving) malah dalam makalahnya, Freire dengan Bahasa profetis mengatakan bahwa para pendidik mesti mati (meninggalkan prasangka dan pamrih elitisnya) untuk mengalami "paskah" yaitu "dibangkitkan bersama dengan" para peserta didik.
Pendidikan tidak boleh jatuh menjadi "bimbingan dan pengarahan" (atau "eksistensi" dalam istilah Freire), karena hal itu hanya akan mengingkari situasi genealogis sejati. Pengetahuan sejati tumbuh dari dialog antarsubjek (model hubungan antarmanusia menurut Marcel atau Buber), bukan antara subjek dengan objek (model hubungan antarmanusia menurut Sartre).
Dari pihak guru, pendidik atau katakanlah pemimpin masyarakat, diharapkan adanya sikap tutwuri handayani sebagai salah satu sikap yang mutlak perlu.Teori dan metode pendidikan Freire sebenarnya juga sarat dengan nilai-nilai religius, kemanusiaan, percaya diri sebagai suatu bangsa, kerakyatan, dan keadilan sosial.
Meskipun tak perlu diingkari, bahwa aspek tertentu dari sosialisme ilmiah memang merupakan salah satu inspirasi bagi teori dan metode pendidikan Freire, tetapi bukannya tanpa perbedaan yang tajam pula. Freire tegas menolak tidak hanya "sektarianisme kanan", melainkan juga kiri" karena kedua duanya berpretensi "mengurung sejarah". Sektarianisme kanan karena pamrih-pamrihnya menganggap bahwa dimensi historis paling penting ialah masa kini dan karena itu sektarianisme kanan cenderung mempertahankan status quo. Sektarianisme kiri cenderung menganggap bahwa dimensi historis paling penting ialah masa depan dan karena itu punya obsesi untuk menjungkir balikkan segala nilai.
Kedua-duanya manipulatif dan hanya menimbulkan penderitaan di kalangan wong cilik. Akan tetapi, sikap tutwuri handayani merupakan salah satu unsur yang diwujudkan dalam metode pendidikan Freire. Dengan terbata-bata, Freire sendiri mengejarnya dengan kata-kata metaforis semisal "mati", "paskah", "bangkit", "metanola" dan lain-lain.
Lapisan menengah rupa-rupanya lebih sibuk dengan mobilitasnya sendiri daripada sungguh-sungguh prihatin dengan nasib bangsa sebagai suatu keseluruhan.Salah satu pertanyaan Pak Abdurrahman Wahid dalam kata pengantar yang ditulisnya bagi buku Freire yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia ialah, mengapa para pemimpin nasional kita yang nota bene banya eks guru, "segera larut kedalam pola kehidupan sebagai elite negeri? (Freire,1984a)
Dalam memetik sumbangan Freire dan menanggapinya, justru pada titik inilah sebaiknya kita termengu: metode apakah yang bisa membuat para pendidik dan pemimpin tetap bersikap dialogis, tidak mendikte, tidak mendiskreditkan, tidak asal memberi 'cap' dan tetap tutwuri handayani?Dari pemikiran ini seharusnya kita mulai bercermin terhadap sistem pendidikan yang terjadi pada saat ini, apakah mencerdaskan? berpihak kepada orang - orang yg lemah? dan mampukah menghasilkan para intelektual - intelektual yang nantinya akan membangun negara?
REFERENSI
Freire, Paulo. 2000. Pendidikan Kaum Tertindas, Terj. Utomo Dananjaya, dkk. Jakarta: Pustaka LP3ES.
Santoso,Listiyono dkk. 2003. Epistemologi Kiri. Yogyakarta: Ar-Ruzz.
Media.Mu'arif. 2005. Wacana Pendidikan Kritis. Yogyakarta: IRCiSoD.