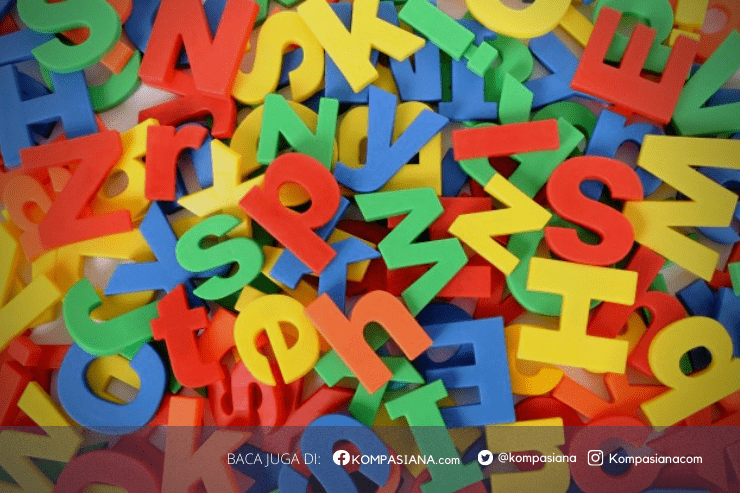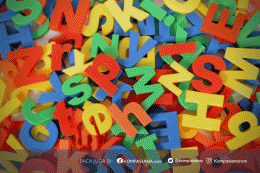Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “rantau” cukup banyak. Rantau memiliki pengertian pantai di sepanjang teluk (sungai); pesisir, daerah (negeri) di luar daerah (negeri) asalnya sendiri atau daerah (negeri) di luar kampung halaman; negeri asing. Sedangkan kata kerjanya, merantau, memiliki berbagai pengertian juga, seperti berlayar (mencari penghidupan) di sepanjang rantau (dari satu sungai ke sungai lain dan sebagainya), pergi ke pantai atau pesisir, pergi ke negeri lain (untuk mencari penghidupan, ilmu, dan sebagainya).
Masih berkembangnya anggapan bahwa tinggal di kota atau berkuliah di perguruan tinggi negeri, yang notabene kebanyakan berada di Pulau Jawa, membuat arus perantauan masih tetap deras hingga saat ini. Saya sendiri pernah dua kali merantau: pertama, pindah dari Yogyakarta mengikuti Bapak yang bekerja di Pulau Batam dan, yang kedua, ketika saya melanjutkan pendidikan di salah satu universitas negeri di Depok.
Hal menarik yang dapat ditemui dalam pengalaman saya merantau ialah kebingungan penggunaan bahasa, terutama dalam percakapan sehari-hari. Bagaimana tidak, di satu tempat saya diharuskan mengerti kromo inggil, di tempat lain saya harus luwes ber-gue-elo.
Meskipun saya orang Jawa asli, saya sudah tidak fasih lagi berbicara Jawa lisan, sehingga ketika saya pulang kampung, jujur, saya agak malas untuk memulai pembicaraan apabila sedang tidak ditanya, terutama pada orang-orang tua. Kalaupun terpaksa, saya akan menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Jawa terpatah-patah. Meski begitu, adat istiadat menyiratkan bahwa kuranglah sopan berbicara Bahasa Indonesia selagi kita dapat menggunakan Bahasa Jawa. Saya pernah mencuri-dengar cerita dari keluarga saya mengenai tetangga kami di Yogya yang bercakap dengan Bahasa Indonesia pada orang tuanya. Tetangga saya tersebut pernah merantau juga ke Batam. Dalam pandangan orang sekampung, tetangga saya tersebut tidak sopan karena tidak menggunakan Bahasa Jawa. Nah, loh!
Di Batam, sesama kawan, kami akan menggunakan "aku" sebagai kata panggil diri sendiri dan "ko", yang berasal dari kata kau, untuk menunjuk lawan bicara. Ketika berkuliah, penggunaan "aku-ko" tidaklah lazim di antara kami, sedangkan "aku-kamu" (yang masih banyak dipakai oleh kawan-kawan dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur) luas dianggap sebagai ucapan yang hanya dipakai oleh orang-orang yang sedang mempunyai hubungan khusus (baca: berpacaran). Alih-alih, kami menggunakan "gue-lo". Keterbatasan teman sesama anak daerah yang menggunakan "aku-ko" membuat beberapa teman saya malah ketularan menggunakan "gue-lo" ketika bertemu dengan teman seperantauan. Hmm, secara pribadi, saya "mengecam" praktik semacam ini. Jadilah kami semua ini, yang berasal dari seluruh penjuru Indonesia, menggunakan "gue-lo" dalam memperluas pergaulan kami. Nah, loh lagi!
Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan disebutkan " Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa." Selain itu, Bahasa Indonesia juga "berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah." Nah, semestinya kebingungan bahasa bukan menjadi suatu masalah lagi. Sudah ada Bahasa Indonesia yang seharusnya cukup baiklah bagi semua orang untuk menggunakannya. Memang inilah yang menjadi dilema penggalakan Bahasa Indonesia. Di satu sisi, penggunaan bahasa daerah dan dialek setempat lebih penting dibanding Bahasa Indonesia itu sendiri.
Memang, kemudian akan muncul argumen bahwa penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar tidaklah mutlak diperlukan dalam ragam percakapan. Namun, bila dilihat baik-baik, kebiasaan mengabaikan Bahasa Indonesia seringkali menimbulkan masalah, mulai dari yang sepele hingga konflik antarsuku, dan ini dimulai dari kebiasaan bercakap-cakap sehari-hari.
Sebagai contoh, bila kita berbicara menggunakan Bahasa Indonesia sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), kita akan dianggap kaku dan mungkin akan ditertawakan, diolok, ataupun dicela, seperti kasus yang saya temui di kampung saya di Yogya. Contoh nyata juga, ada teman saya yang selalu menyebut dirinya sendiri dengan "saya". Bukannya dianggap sopan, ia malah dianggap menggelikan. Untunglah, dia sendiri tidak ambil hati serta pada dasarnya orangnya memang sopan dan baik hati. Namun, dalam forum resmi, semisal presentasi di depan kelas atau sidang skripsi, sering ditemui penggunaan Bahasa Indonesia yang tidak pada tempatnya. Kebanyakan bersumber dari kurangnya kebiasaan penggunaan Bahasa Indonesia yang benar pada percakapan sehari-hari.
Saya ingin menceritakan kembali suatu kisah lucu yang tak perlu diambil hati:
Suatu hari, di sebuah perkampungan yang dihuni oleh orang Melayu, orang Jawa, dan orang-orang dari suku lainnya di Indonesia, seekor babi hutan tiba-tibamenerobos masuk perkampungan. Orang Jawa yang melihatnya serta-merta berteriak, "Babi mlayu, babi mlayu!", yang maksudnya "Babi lari, babi lari!"
Namun, orang Melayu yang mendengarnya salah paham, dan, dengan beringas, hendak menghajar orang Jawa tersebut. "Heh, ape maksud awak cakap kami ni babi, hah?"