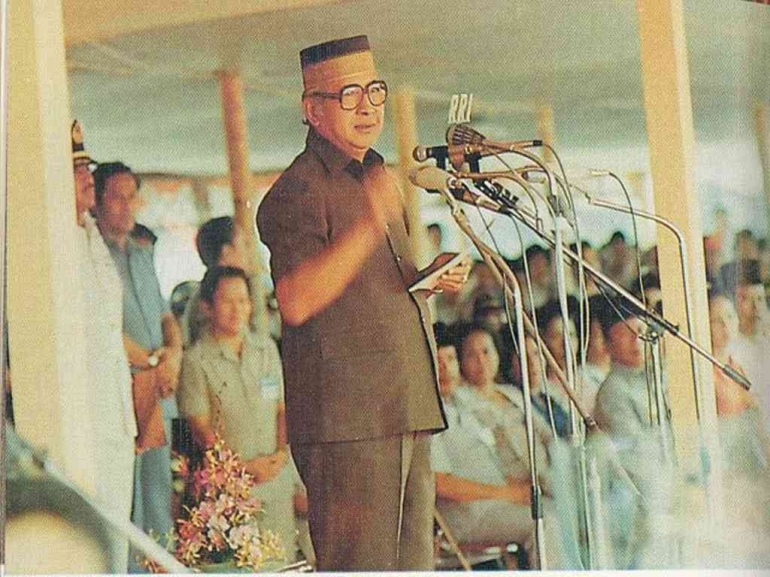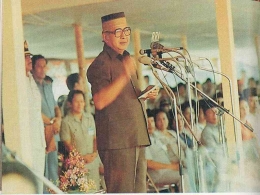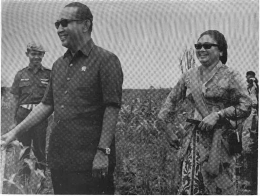Di sebuah ruang kelas sekolah dasar Inpres, seorang guru perempuan setengah baya sedang menerangkan Presiden Suharto sebagai “Bapak Pembangunan” karena di bawah kepemimpinannya Republik Indonesia banyak melakukan pembangunan infrastruktur, seperti jalan aspal, waduk irigasi, sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan yang lain.
Selain itu Pak Harto, begitu para guru biasa menyebutkan namanya, juga membawa Indonesia swasembada pangan sehingga mendapat penghargaan dari FAO, sesuatu yang dikatakan cukup membanggakan.
Ujung dari penjelasan Bu Guru adalah bahwa para murid harus mengetahui jasa-jasa Bapak Pembangunan dan harus menghormatinya sebagai pemimpin yang telah membawa Indonesia ke era kemajuan dan kesejahteraan.
Pengantar
Cerita di atas saya pungut dari ingatan masa lalu ketika duduk di sekolah dasar di salah satu dusun di Lamongan. Saya sengaja memungutnya untuk menggambarkan kuatnya pengaruh Presiden Suharto dalam kehidupan masyarakat Indonesia di masa Orde Baru (selanjutnya disingkat Orba).
Salah satu institusi dan aparatus yang digerakkan adalah sekolah dan para guru. Para guru adalah subjek yang memengaruhi pola pikir anak-anak sebagai generasi penerus. Apa yang ada dalam benak saya dan kawan-kawan sebaya waktu itu adalah Pak Harto sebagai figur pemimpin sempurna yang berjasa besar kepada Republik ini.
Kesempurnaannya semakin lengkap ketika dalam dunia imajiner kami sering disuguhi film hitam putih berjudul Janur Kuning di TVRI yang membicarakan peran penting Suharto dalam melawan penjajah Belanda.
Belum lagi setiap malam 1 Oktober kami selalu disuguhi film horor yang mencekam, Pengkhianatan G 30 S/PKI, yang menggambarkan kekejaman PKI karena ikut melakukan kudeta serta membunuh para jendral penting angkatan darat. Lagi-lagi, Suharto diposisikan sebagai penyelamat karena tindakan taktisnya dalam mengendalikan situasi politik dan keamanan di dalam negeri.
Para guru kami tidak pernah menceritakan adanya genosida terhadap para anggota atau mereka yang dituduh PKI yang secara sistematis mampu menciptakan teror untuk warga negara.

Bagi generasi yang lahir di era 70-an atau 80-an, ingatan tentang Suharto adalah “senyum manis” seorang purnawirawan jendral yang mengabdikan dan mendedikasikan pikiran dan hatinya untuk kejayaan Republik ini. Ingatan seperti ini merupakan bentukan historis yang terlahir dari “mekanisme-mekanisme kultural” penuh rekayasa yang dilakukan secara massif, terstruktur, dan terukur.
Berbeda dengan mekanisme opresif-militeristik yang mengedepankan komando dan penerimaan perintah dari atasan kepada bawaan, mekanisme kultural menyentuh aspek imajinasi, nalar, dan batin manusia, sehingga mereka merasa tidak tengah berada dalam pengaruh kekuasaan tertentu.
Mekanisme kultural itulah yang lebih dari 30 tahun berlangsung di Indonesia dan mampu memengaruhi pola pikir masyarakat, khususnya mereka yang pernah merasakan “kejayaan hidup” di masa-masa Suharto berkuasa.
Bagi warga yang sudah meyakini keunggulan Orba, sekecil apapun masalah yang mereka hadapi di masa-masa pasca Reformasi akan dibandingkan dengan masa-masa Suharto; seolah-olah di masa Sang Jendral Besar tidak ada masalah serius.
Singkatnya, kepemimpinan Suharto di masa Orba digambarkan sebagai contoh sempurna dari bagaimana seorang presiden seharusnya memimpin Indonesia dengan beragam potensi dan permasalahannya.
Tidak mengherankan kalau beberapa tahun terakhir mulai dihembuskan mulai berkembang kerinduan terhadap kepemimpinan gaya Suharto yang tegas tetapi (dikampanyekan) bisa menjamin kesejahteraan rakyat. Kerinduan tersebut diwujudkan dalam tulisan di bak truk hingga meme bergambar Suharto dengan tulisan “Isek Enak Jamanku Toh?” di media sosial.
Apa yang mengerikan dari penyebaran wacana kejayaan Orba tersebut adalah adanya usaha untuk menghilangkan bermacam tindakan otoriter-koruptif yang merugikan manusia-manusia Indonesia selama puluhan tahun.
Melihat fakta tersebut, tulisan ini akan menghadirkan pembacaan refleksif-personal terhadap peristiwa-peristiwa yang saya alami di masa anak-anak hingga mahasiswa.
Untuk menjabarkan ragam peristiwa yang merupakan dampak dari mekanisme kultural rezim Orba, saya akan menggunakan kerangka teoretis wacana Foucauldian (Foucault, 1981, 1984, 1998, 20013) dan hegemoni Gramscian (Gramsci, 1981; Boggs, 1984; Boothman, 2008; Howson, 2008; Fontana, 2008) dengan alur berikut.
Semua wacana terkait kepemimpinan dan kebaikan Suharto serta wacana kebangsaan dan kebudayaan nasional merupakan “formasi diskursif” yang membentuk “rezim kebenaran” yang memengaruhi pola pikir dan tindakan masyarakat Indonesia, khususnya dalam memosisikannya sebagai figur pemimpin ideal.
Penyebaran wacana-wacana tersebut memunculkan pengetahuan yang membaikkan rezim dan meniadakan wacana-wacana terkait pelanggaran HAM ataupun praktik korupsi yang melibatkan keluarga dan kroni-kroninya di kalangan pengusaha.
Wacana-wacana tersebut disebarluaskan melalui aparatus yang menjadikan masyarakat luas tidak mendapatkan informasi terkait keburukan rezim dan hanya mendapatkan informasi tentang kebaikannya. Pada titik itulah, konsensus akan dibentuk dan rakyat pun bisa memberikan kesepakatan dukungan politik untuk rezim Suharto.
Saya tidak mengatakan bahwa mekanisme kultural tersebut tanpa melibatkan tindakan opresif. Perlu dicatat tindakan opresif negara tetap dihadirkan melalui beberapa peristiwa berdarah, pencekalan, dan lain-lain, demi untuk memberikan efek jera ke rakyat.
Analisis Foucauldian juga membantu untuk menelaah perkembangan diskursif saat ini di mana beberapa politisi mewacanakan untuk mengusung kejayaan Orba. Tujuan utama tulisan ini adalah memberikan penjelasan tentang bagaimana beroperasinya kekuasaan yang dibangun dengan fondasi moralitas dan budaya ternyata menutupi tumpukan keburukan dan kebiadaban yang sebenar-benarnya.
Dengan demikian, ketika ada pihak-pihak tertentu yang ingin “mengembalikan kejayaan Orba” ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita bisa dengan cepat membaca formasi wacana dan praksis yang mereka mainkan, sehingga bisa melakukan antisipasi untuk melawan kebangkitan kembali formula rezim yang sama.
Pembangunan dan Pembangunanisme
Indonesia di bawah rezim Suharto, setelah menurunkan Sukarno dengan jalan yang seolah-olah konstitusional, adalah negara yang digerakkan dengan kebijakan “pintu terbuka”. Negara membuka selebar-lebarnya kesempatan investasi, baik oleh pengusaha transnasional ataupun nasional.

Pemerintah menggerakkan investasi demi melakukan pembangunan infrastruktur dan eksploitasi sumberdaya alam, khususnya mineral. Apakah ini berarti bahwa kebijakan terkait investasi asing di Indonesia tidak ada selama kepemimpinan Sukarno? Tidak demikian.
Pada kepemimpinan Sukarno juga sudah ada kebijakan yang dibuat untuk mengatur investasi asing, tetapi kondisi pemerintahan yang sering berganti kabinet serta tentangan dari kalangan komunis menjadikan kebijakan itu tidak bisa berjalan (Historia).
Pasca tragedi berdarah 1965, beberapa ekonom Universitas Indonesia seperti Widjojo Nitisastro, Emil Salim, Ali Wardhana, Subroto, dan Muhammad Sadli diminta membantu Suharto untuk mendesain kebijakan pemulihan ekonomi. Salah satu produk yang mereka hasilkan adalah Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA) No 1 Tahun 1967.
Berbekal UU inilah, Suharto menandatangani “kontrak karya” antara pemerintah RI dan Freeport Sulphur Incorporated AS untuk mengeksploitasi emas dan tembaga di Irian Jaya (sekarang Papua). Kontrak karya itu sekaligus menjadi penanda masuknya pemodal asing dalam kehidupan ekonomi dan politik Indonesia.
Semangat utama dari UU PMA 1967 adalah liberalisasi ekonomi yang diasumsikan bisa berdampak baik kepada proses pembangunan Indonesia. Karakteristik utama liberalisasi ekonomi adalah memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada swasta internasional dan nasional untuk berinvestasi dalam sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.
Meskipun demikian, negara tidak membebaskan sepenuhnya proses ekonomi tersebut. Mereka tetap mengontrol melalui peraturan-peraturan yang selalu dikatakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Inilah yang menjadikan sistem ekonomi Indonesia menjadi liberal tetapi tetap diarahkan oleh rezim.

Politik pintu terbuka yang dijalankan rezim Suharto dari pusat hingga daerah merupakan upaya untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang. Untuk mengerangkai arah pembangunan, pemerintah membutat REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun).
Adapun jiwa dari proses pembangunan adalah Trilogi Pembangunan yang terdiri atas: (1) stabilitas nasional, (2) pertumbuhan ekonomi, dan (3) pemerataan hasil-hasil pembangunan.
Sangat jelas bahwa rezim negara Orba bertujuan mempercepat pertumbuhan dan kemajuan ekonomi, baik dalam lingkup kota-kota besar maupun daerah-daerah terpencil karena diidealisasi akan menurunkan angka kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat serta permasalahan sosial lainnya.
Bukan hanya aspek industri dan infrastruktur yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan ekonomi nasional, tetapi juga sektor pertanian dengan program Revolusi Hijau di mana sektor pertanian diperkuat melalui penggunaan bahan-bahan kimia dan mesin serta pembangunan sarana-sarana irigasi.
Sementara, industri budaya pop berkembang pesat. Hal itu bisa dilihat pertumbuhan industri musik dan film di tanah air yang mengalami perkembangan pesat. Bermacam genre dan musik berkembang dan menyasar warga negara dari kota hingga dusun. Untuk mendukung semua target pembangunan tersebut dibutuhkan “stabilitas nasional” berupa ketertiban, keamanan, dan integrasi sosial.
Kata pembangunan, stabilitas, keamanan dan ketertiban, pertumbuhan ekonomi, swasembada pangan, dan kesejahteraan menjadi wacana publik yang disebarluaskan melalui saluran media, baik yang dikelola badan pemerintah seperti RRI dan TVRI maupun swasta seperti koran-koran nasional.
Wacana tersebut disebarkan melalui berita yang bertujuan mengonstruksi keberhasilan rezim Suharto dalam membangun negeri. Tidak jarang TVRI menyiarkan “laporan khusus” berisi kunjungan Suharto ke daerah untuk panen padi bersama aparat dan masyarakat.
Di ruang kelas, saya dan kawan-kawan harus menghafalkan definisi “pembangunan”, “bapak pembangunan”, REPELITA, dan PELITA agar bisa mendapatkan nilai baik dalam pelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial).
Sementara, bapak dan ibu saya sering diundang dalam pertemuan-pertemuan di balai desa untuk membahas program pertanian dan kesejahteraan keluarga.
Mobilisasi wacana-wacana tentang segala bentuk keberhasilan pembangunan dan kewajiban warga negara untuk mendukung semua program negara dalam media dan ruang kelas terbukti mampu membentuk wacana utama tentang “pembangunanisme” (developmentalism) dalam benak pelajar dan rakyat.
Menjadi wajar ketika banyak di warga negara, dari anak-anak hingga dewasa, mengidolakan Suharto karena pikiran dan imajinasi mereka dipenuhi oleh wacana keberhasilan pembangunan.
Bagi saya dan kawan-kawan sebaya, Pak Harto telah menjelma semacam tokoh idola yang dibentuk oleh bangunan naratif dan diskursif pembangunanisme di ruang kelas dan TVRI, sejak saya duduk di bangku SD hingga SMP. Saya akui, pada waktu itu, tidak ada sosok pemimpin lain yang bisa mengalahkan pesonanya.

Apa yang tidak kami ketahui pada waktu itu adalah kelemahan dan kesalahan seorang Suharto. Apakah Suharto tidak punya kelemahan dan kesalahan? Tentu saja punya.
Masalahnya, kelehaman dan kesalahan itu tidak pernah boleh dipublikasikan oleh media dan dijelaskan oleh para guru di ruang kelas. Seingat saya, dari SD hingga SMP, tak satupun guru yang berani menerangkan kelemahan dan kesalahan Pak Harto sebagai superhero.
Kesempurnaan seorang Suharto menjadi semakin lengkap bagi warga di wilayah Lamongan ketika pemerintah membangun sebuah waduk yang mampu mengairi hektaran tanah pertanian di beberapa kecamatan. Saya dan kawan-kawan sempat menyaksikan bagaimana traktor, backhoe, truk, dan alat-alat berat lainnya serta para pekerja mengerjakan proyek prestisius tersebut.
Ada rasa kagum yang membuncah melihat proses pengerjaan waduk tersebut. Meskipun waktu itu terdapat warga dari beberapa desa harus diminta pindah ke kawasan baru (bedhol desa), membangun desa baru di kawasan hutan, kami tidak pernah menganggapnya masalah karena semua dilakukan demi pembangunan.
Apalagi para guru kami juga mengatakan bahwa pembangunan waduk memang membutuhkan lahan, sehingga perpindahan warga tersebut merupakan keharusan. Pada waktu itu, saya dan kawan-kawan juga tidak pernah mendengar ungkapan “pelanggaran hak asasi manusia.”

Bagi warga, kehadiran waduk tersebut membentangkan harapan akan kehidupan yang lebih baik karena mereka akan bisa mengerjakan sawah meskipun di musim kemarau. Praktik pertanian tadah hujan yang selaman puluhan tahun menjadi tambatan hidup warga memang kurang memberikan keuntungan secara ekonomis.
Maka, peresmian waduk yang diberi nama Waduk Gondang Lor (sesuai dengan nama desa tempatnya berada) pada tahun 1987 menjadi momen istimewa bagi warga Lamongan karena harapan untuk berpenghidupan yang lebih baik akan segera terwujud. Apalagi sebelum peresmian tersebut, jalan raya dari Lamongan menuju Waduk Gondang Lor diaspal.
Desa-desa di sekitar waduk dialiri listrik yang selama bertahun-tahun belum dirasakan warga. Masuknya listrik tentu membawa ruang kultural desa lebih berwarna karena warga bisa menikmati televisi setiap hari.
Gambaran akan kebahagiaan tersebut menyatu dengan kebanggaan ketika mengetahui bahwa Presiden Suharto didampingi Ibu Tien Suharto dan jajaran menteri serta pejabat daerah akan datang langsung meresmikan setelah meresemikan terlebih dahulu jalan toll Surabaya.
Sekolah-sekolah di Kecamatan Sugio Lamongan diliburkan untuk menyambut kedatangan Pak Harto. Saya masih kelas 3 SD ketika diajak orang tua dan tetangga untuk berjalan kaki beberapa kilometer, menyusuri pematang sawah menuju lokasi peresmian, di pinggir waduk.

Ketika Pak Harto dan rombongan turun dari helikopter, ribuan warga yang sudah menunggu sontak memanggil nama Pak Harto dan Bu Tien. Saya pun ikut berdesakan agar bisa melihat wajah Bapak Pembangunan. Meskipun tidak bisa berjabat tangan, warga sudah merasa puas dan bahagia karena bisa melihat secara langsung pemimpin bangsa yang biasanya hanya bisa dilihat dari TVRI.
Gambaran di atas menegaskan betapa pembangunanisme yang menggeliat di era 1980an tidak hanya menjadi wacana di ruang kelas dan media, tetapi juga dipraktikkan dalam bentuk infrastruktur, meskipun tidak semua warga Indonesia bisa merasakannya.
Dampak langsung dari proyek-proyek pembangunan di segala bidang yang dilakukan rezim Suharto adalah berkembangnya modernisme; menguat dalam kehidupan warga kota, berkembang dalam kehidupan warga desa.
Setiawan (2011: 130-131) memaparkan bahwa pengaruh nyata pembangunanisme bagi masyarakat desa memasukkan mereka ke dalam jejaring modernitas. Bagaimanapun juga, TVRI, percepatan industri, Revolusi Hijau, pengaspalan jalan, listrik, dan “Keluarga Budi”, berhasil menggerakkan masyarakat menuju modernitas.
Pilihan ekonomi-politik pembangunanisme dengan mengedepankan percepatan pertumbuhan ekonomi, percepatan industri dan pertanian, serta stabilitas keamanan dan integrasi, menyebabkan pergeseran atau perubahan orientasi dan praktik sosiokultural desa. TVRI menjadi situs yang memudahkan masyarkat desa bersentuhan dengan pembangunan dan modernitas dalam arahan rezim negara.
Percepatan industri di kota membutuhkan perluasan pasar sampai ke tingkat desa. Revolusi Hijau menjadi senjata andalan untuk bisa mempercepat laju perkembangan masyarakat desa dengan sistem pertanian modern.
Pengaspalan jalan mempertinggi mobilitas masyarakat desa ke kota, sehingga mempermudah mereka untuk mendapatkan benda-benda modern dari kota kabupaten atau kecamatan. Kesempatan memperoleh pendidikan, paling tidak sampai ke tingkat dasar dan menengah/SMP-SMA, menjadikan pikiran-pikiran modern bersemi dalam pikiran generasi muda desa.
Harus diakui salah satu keberhasilan penting rezim Suharto adalah menghadirkan modernisme ke dalam kehidupan masyarakat desa sebagai dampak langsung pembangunanisme. Bermacam pernik benda dan beragam orientasi menjadi modern mulai berkembang dalam benak warga desa.
Ragam tayangan TVRI, pelajaran di sekolah, hingga berita dan bentuk nyata pembangunan menjadi rujukan warga untuk merasakan diri-modern. Perhatian perlu diberikan pada kontribusi penting TVRI yang mampu mengarahkan, mengendalikan, dan membatasi pesan pembangunan menuju modernitas sebagai kebutuhan kolektif menuju kemajuan bernegara dan berbangsa.
Bahkan, sebagian besar masyarakat desa tidak merisaukan ideologi kapitalisme yang diadopsi dalam pembangunanisme oleh para ekonom dan teknokrat serta pengaruh-pengaruh buruknya. Masyarakat diberi informasi-informasi tentang pembangunan di bawah kepemimpinan Soeharto yang akan menciptakan kehidupan yang lebih baik (Setiawan, 2011: 120).

Paparan-paparan di atas menunjukkan kelihaian rezim penguasa dalam memainkan dan membentuk formasi diskursif, mengikuti pemikiran Foucauldian, tentang subjek ke-Suharto-an dan beragam keberhasilan pembangunan.
Konstruksi peran penting Suharto dan seluruh pejabat dan aparat di bawahnya dalam mewujudkan beragam program pembangunan dari kota hingga desa, meskipun tidak semua, merupakan kekuatan diskursif-strategis untuk meyakinkan warga negara bahwa rezim ini berbeda dengan rezim Sukarno.
Menawarkan bermacam praktik dan orientasi kultural modern menjadikan warga berpikir bahwa kepemimpinan Suharto bisa menghadirkan perubahan signifikan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya oleh rakyat Indonesia.
Kesadaran menginkorporasi bermacam permasalahan ekonomi dan sosial yang dihadapi rakyat untuk kemudian mengartikulasikannya dalam program-program pembangunan yang melibatkan investor nasional dan internasional memperkuat penerimaan masyarakat terhadap rezim Orba.
Mayoritas masyarakat memosisikan Suharto benar-benar sebagai pemimpin yang layak memimpin Republik ini karena dirasa mampu memberikan banyak perubahan ke arah modern.
Pada level itulah, rezim Suharto berhasil mendapatkan konsensus dari mayoritas masyarakat, pengusaha, intelektual, birokrasi, dan agamawan untuk menjalankan kepemimpinan demi menuju Indonesia adil dan makmur.
Dengan demikian, rezim Orba mendapatkan kekuasaan hegemoniknya karena mendapatkan konsensus mayoritas publik yang merasakan dampak positif pembangunan bagi kehidupan mereka.
Fakta dan Tragedi yang Disenyapkan
Sebuah kekuasaan hegemonik akan terus memperbaiki strategi dan praksisnya di tengah-tengah beragam orientasi dan permasalahan yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Selain mengartikulasikan hal-hal yang diinginkan publik, rezim juga perlu memetakan dan memutuskan wacana-wacana apa yang sekiranya bisa mengancam keberlangsungan dan kemapanan kekuasaan.
Membersihkan ruang bernegara dan berbangsa dari bermacam narasi negatif tentang rezim Orba merupakan mekanisme kultural yang juga diterapkan penguasa. Tujuannya adalah tidak membiarkan munculnya gugatan-gugatan oleh warga negara terhadap kepemimpinan Pak Harto.

Karena ketika banyak pertanyaan dibiarkan berkembang dalam benak masyarakat terkait permasalahan tertentu bisa menjadi titik lemah dari sebuah pemerintahan. Dalam kondisi demikian resistensi bisa dengan mudah dimobilisasi dan digerakkan individu atau komunitas yang ingin menumbangkan rezim.
Sebagai saya paparkan secara singkat dalam pembahasan sebelumnya bahwa keberbasilan pembangunan dan beragam wacana pembangunanisme berhasil ‘membius’ masyarakat. Hal itu tidak berarti tidak ada masalah serius yang melibatkan rezim Suharto.
Sebaliknya, dari data-data yang mulai terbuka pasca Reformasi 1998, kita disuguhi "fakta-fakta negatif" yang sengaja disenyapkan demi menjaga stabilitas keamaan dan integrasi nasional. Karena kehadiran narasi-narasi tersebut bisa memroduksi wacana-wacana tandingan dan, bahkan, perlawanan yang bisa membahayakan kekuasaan.
Maka dari itu, mereka tidak dibiarkan berkembang di media massa, film, lagu, televisi, ataupun omongan publik. Aparat sensor dan aparat keamanan siap meniadakan semua narasi dan wacana negatif yang dianggap merongrong rezim.
Adapun beberapa permasalahan serius yang ditiadakan dalam narasi resmi Orba adalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta pelanggaran HAM berat. Saya dan kawan-kawan tidak pernah mendengar narasi tersebut dari SD hingga SMP, baik dari bapak dan ibu guru ataupun dari TVRI.
Temuan-temuan penting pasca lengsernya Suharto, 1998, dengan terang-benderang menunjukkan betapa korupnya penguasa ini bersama keluarga dan kroni-kroninya. Berdasarkan temuan Transparancy International 2004, dana yang terkumpul dari total perkiraan korupsi Suharto adalah 15-25 miliar dolar AS, sehingga ia dijuluki “diktator terkorup di dunia” (Republika).
Usman Hamid, Direktur Amnesti Internasional Indonesia, menamai praktik korupsi Suharto sebagai grand corruption karena dilakukan secara sistemik, terstruktur, dan rapi; melibatkan aparat negara dan dibungkus dengan peraturan yang legal. Korupsi sistemik dilakukan melalui peraturan undang-undang dan keputusan presiden tentang tata niaga; “korupsi yang diselimuti aturan”.
Implikasi mengerikan dari praktik tersebut adalah “regenerasi” atau “pengembangbiakan” korupsi di semua ranah pemerintahan; eksekutif, yudikatif, legislatif, hingga aparat keamanan. Akibatnya, tidak ada kekuatan dalam pemerintahan yang berani mengungkap praktik korupsi berbalut aturan tersebut.
Salah satu modus yang dilakukan Suharto adalah membuat peraturan pemerintah yang memungkinkan uang negara masuk ke yayasan-yayasan yang ia dirikan bersama keluarga dan kroninya.
Menurut Erwin Natosmal Oemar, aktivis Indonesian Legal Roundtable (ILR), genelogi korupsi Soeharto diawali pada 1976 dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1976 tentang penetapan penggunaan sisa laba bersih bank-bank milik pemerintah. Setiap tahun sebesar lima persen keuntungan bank harus disumbangkan ke yayasannya (Merdeka).
Bahkan realisasinya 50 persen dari keuntungan sisa laba bersih bank dikirim dan disalurkan ke yayayan tertentu.[6] Beberapa yayasan yang didirikan Suharto antara lain: Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bhakti Sosial, Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora.
Selain dana dari bank BUMN, sumber dana bagi yayasan tersebut juga di dapat dari penggunaan dana reboisasi Departemen Kehutanan dan pos bantuan presiden. Modus tersebut menarik karena yayasan-yayasan tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan sosial untuk warga negara yang membutuhkan.
Para mahasiswa yang kurang mampu, misalnya, mendapatkan beasiswa Supersemar. Sementara, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila membantu pembiayaan untuk pendirian masjid di wilayah Indonesia. Kegiatan-kegiatan seperti itulah yang menjadikan nama Suharto dan kroni-kroninya selalu baik di masyarakat.
Anak-anak Suharto juga menikmati berbagai macam fasilitas bisnis yang menggurita; dari pertanian, perikanan, pertambangan, kehutanan, hingga industri berat. Gurita bisnis keluarga Cendana, begitu biasa dipanggil, sudah menjadi rahasia umum, tetapi tidak banya pihak yang berani membongkarnya.
Para intelektual dan wartawan pun berpikir seribu kali ketika hendak meneliti dan memberitakan aspek nepotisme karena ancaman penjara bahkan nyawa menjadi taruhannya. Kemudahan fasilitas yang diberikan Suharto menjadikan anak-anaknya dengan mudah membuat bermacam usaha komersil.
Siti Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut) membangun kerajaan bisnis dengan bendera PT. Citra Lamtoro Gung Persada. Di masa jayanya, perusahaan ini menyapu semua bidang bisnis, mulai konstruksi,perdagangan, pertanian, sampai kerajinan tangan.
Putra bungsunya, Hutomo Mandala Putra (Tommy) mendirikan PT. Humpuss yang juga bergerak di berbagai bdang usaha, seperti properti dan konstruksi, pengeboran minyak dan gas, transportasi, produksi minyak tanah dan solar, kilang minyak, dan eksplorasi minyak tanah. Sigit Harjojudanto, putra kedua Suharto, juga memiliki saham di PT. Humpuss (Tirto).
Putra ketiga Suharto, Bambang Triatmojo, mendirikan PT. Bimantara yang bergera di industri media. RCTI, televisi swasta pertama di Indonesia, merupakan bagian dari Bimantara, sebelum akhirnya diakuisisi oleh Harrry Tanoe.
Kehadiran RCTI ini yang membawa masyarakat Indonesia ke dalam budaya modern yang relatif terbuka karena berorientasi komersil. Siti Hediati Hariyadi memiliki PT. Abitama, sedangkan Siti Hutami Endang Adiningsih mengembangkan usaha pertanian di PT. Manggala Krida Yudha. Taman buah Mekarsari adalah salah satu usaha PT. Manggala Krida Yudha.
Pada masa itu, mayoritas aparat pemerintah tidak ada yang mempersoalkan penyelewengan keuangan dan kebijakan yang dilakukan Suharto. Mayoritas tidak ada pula yang berani menolak kebijakan Suharto dan keinginan keluarga Cendana dan kroni-kroninya, meksipun aktivitas bisnis mereka merugikan rakyat kebanyakan (Detik).
Salah satu kasus yang sangat merugikan petani adalah Keppres No 20/1992 tentang tata niaga cengkeh. Dalam Keppres tersebut diatur agar petani harus menjual cengkeh ke Koperasi Unit Desa (KUD) untuk kemudian dijual ke BPPC. Adapun yang bermain dalam keputusan ini adalah Tommy Suharto.
Pemerintah saat itu menetapkan harga cengkeh dengan Inpres No 1/1992 sebesar Rp 7.900 dan Rp 6 ribu untuk setiap kilogramnya. Pemerintah kemudian mengubah harga cengkeh berdasarkan Inpres 4\/1996 sebesar Rp 8 ribu setiap kg. Kebijakan ini sangat merugikan petani karena mereka tidak bisa bernegosiasi untuk memasarkan hasil panen mereka untuk mendapatkan hasi maksimal
Rezim Suharto sangat lihai dalam mengelola isu-isu yang dikategorikan bisa mendegradasi kepercayaan publik. Seingat saya, dari SD hingga SMP, saya tidak pernah mendengar dan membaca istilah korupsi, kolusi, ataupun nepotisme. Ini merupakan mekanisme kultural untuk menghindari penciuman publik terhadap ketidakberesan yang dilakukan penguasa.
Apa yang saya baca dari koran adalah istilah “kesalahan prosedur”, “kesalahan administrasi”, “kesalahan penghitungan”, dan “penyalahgunaan wewenang”. Wacana-wacana tersebut merupakan bentuk penghalusan bahasa terhadap ketidakberesan dalam hal KKN yang dilakukan rezim Orba.
Sanksi hukumnya juga tidak sedahsyat sekarang. Hal yang sangat umum adalah mutasi jabatan untuk para pejabat yang ketahuan melakukan tindakan-tindakan indispliner serta terindikasi merugikan keuangan negara. Istilah dan wacana KKN, meskipun benar-benar terjadi, tidak diperkenankan menjadi populer di ruang publik.
Mereka diposisikan sebagai liyan yang harus dikendalikan dan dimarjinalisasikan dan kalau perlu disingkirkan karena bisa menganggu integritas nasional dan stabilitas politik yang sekaligus mengganggu kekuasaan rezim Suharto.
Apa yang juga tidak dimunculkan dalam ruang pendidikan, media massa, dan industri budaya di masa rezim Orba berkuasa adalah kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang melibatkan rezim Suharto. Para guru tercinta tidak pernah bercerita bahwa Suharto pernah terlibat dalam tindakan pelanggaran HAM berskala besar.
Karena mereka juga sudah dikondisikan agar tidak pernah menyampaikan persoalan itu. Samahalnya mereka tidak diperkenankan berbicara tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Padahal kalau mau menelusuri dari berita-berita kontemporer, dengan mudah kita akan temukan deretan “dosa besar” Suharto.
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), pada tahun 2016, di tengah-tengah usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Suharto, mengidentifikasi 10 dosa besar si diktator (Kompas).
Pertama, kasus Pulau Buru 1965-1966 dalam tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan di mana sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB) melalui keputusan Presiden Nomor 179/KOTI/65, Suharto diduga telah menyebabkan ribuan orang menjadi korban pembunuhan, penangkapan, penahanan massal dan pembuangan ke Pulau Buru.
Ini belum kasus genosida 65 di mana banyak anggota, simpatisan, keluarga, dan warga yang dituduh PKI dibunuh tanpa pengadilan dan tanpa pemakaman yang layak.
Kedua, penembakan misterius 1981-1985, yakni semacam ‘hukuman mati’ tanpa proses pengadilan terhadap residivis, bromocorah, gali, dan preman tanpa melalui pengadilan dengan tujuan menciptakan keamanan dan ketertiban untuk pembangunan nasional. Menurut Kontras, Suharto patut diduga membuat kebijakan petrus karena dalam pidato rutin kenegaraan pada Agustus 1981.
Ia mengungkapkan bahwa pelaku kejahatan harus dihukum dengan cara yang sama saat ia memperlakukan korbannya. Operasi tersebut merupakan terapi kejut agar para kriminal tidak melakukan kejahatan. Dalam catatan Amnesty Internasional korban jiwa karena kebijakan tersebut mencapai kurang lebih 5 ribu orang, tersebar di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bandung.
Ketiga, tragedi Tanjung Priok 1984 di mana Suharto memanfaatkan KOPKAMTIB untuk mendukung dan melindungi kebijakan politiknya. Suharto selaku panglima tertinggi ABRI mengeluarkan sikap, pernyataan, dan kebijakan yang bersifat represif untuk menghancurkan perlawanan masyarakat terhadap kebijakan asas tunggal Pancasila.
Suharto sebagai presiden dan penanggung jawab seluruh kegiatan KOPKAMTIB disebut mewajibkan ABRI mengambil tindakan represif untuk menghadapi kelompok-kelompok Islam yang dianggap sebagai golongan ekstrem yang harus dicegah dan ditumpas seperti penanganan G 30 S. Akibatnya, dalam Peristiwa Tanjung Priok 1984, sekitar lebih 24 orang meninggal, 36 terluka berat, 19 luka ringan.
Keempat, peristiwa Talangsari 1987 di mana aparat keamanan mengambil tindakan represif terhadap kelompok-kelompok Islam yang dianggap ekstrem; menyebabkan 130 orang meninggal, 77 orang mengalami pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, 53 orang terampas kemerdekaanya, 45 orang mengalami penyiksaan, dan 229 orang mengalami penganiayaan.
Kelima, Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh (1989-1998) berupa operasi militer yang menyebabkan penderitaan dan penindasan berkepanjangan bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak.
Investigasi Komnas HAM menegaskan bahwa selama 10 tahun DOM, sedikitnya 781 orang meninggal, 163 orang hilang, 368 orang mengalami penyiksaan/penganiayaan dan 102 perempuan mengalami pemerkosaan.

Keenam, DOM Papua (1963-2003) bertujuan untuk mematahkan perlawanan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Operasi ini mengakibatkan terjadinya beberapa peristiwa yang sangat kejam.
Beberapa peristiwa tersebuat adalah: (1) tragedi Teminabun 1966-1967, 500 orang ditahan dan kemudian dinyatakan hilang; (b) tragedi Kebar 1965, 23 orang terbunuh; (c) tragedi Manokwari 1965, 64 orang dieksekusi mati; (d) Tragedi Enatorali 1969-1970, 634 orang terbunuh; dan (e) tragedi Jayawijaya dan Wamena Barat, kurun waktu 1970-1985, terjadi pembantaian di 17 desa.
Ketujuh, peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli) yang dilatarbelakangi pandangan Soeharto bahwa Megawati merupakan ancaman terhadap kemapanan rezim Orde Baru. Aksi yang melibatkan aparat menyebabkan 11 orang meninggal, 149 luka-luka, 23 orang hilang, 124 orang ditahan.
Kedelapan, penculikan dan penghilangan secara paksa 1997–1998 yang tidak bisa dilepaskan dari konteks politik peristiwa 27 Juli, yakni menjelang Pemilihan Umum 1997 dan Sidang Umum MPR 1998 di mana wacana pergantian kekuasaan semakin menguat. Setidaknya 23 aktivis dan masyarakat yang dianggap akan melakukan subversi menjadi korban penculikan dan penghilangan paksa.
Kopassus disebut menjadi eksekutor lapangan, dengan nama operasi Tim Mawar. Sebanyak 9 orang dikembalikan, 1 orang meninggal dunia dan 13 orang masih hilang.
Kesembilan, peristiwa Trisakti 12 Mei 1998 di mana aktivis dan mahasiswa pro demokrasi mendorong reformasi total dan turunnya Soeharto dari jabatannya karena krisis ekonomi dan maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Tindakan represif ABRI menyebabkan 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal. Kesepuluh, kerusuhan 13–15 Mei 1998 terjadi dalam peristiwa Trisakti. Dalam peristiwa ini terjadi pembunuhan, penganiayaan, perusakan, pembakaran, penjarahan, penghilangan paksa, perkosaan, serta penyerangan terhadap etnis tertentu.
Tentu saja masih banyak kasus penindasan rezim negara kepada masyarakat yang tidak diberitakan oleh media, khususnya yang berlangsung pada era pasca 65 hingga 1990-an. Adapun kasus-kasus yang terjadi pada pertengahan 1990-an hingga menjelang Reformasi 1998 mulai banyak diberitakan media massa.
Menjadi wajar kalau masih banyak warga negara yang menyenangi pemerintahan Suharto karena mereka tidak banyak mendapatkan informasi. Para mahasiswa, aktivis, dan intelektual kampuslah yang sedikit banyak mendapatkan akses informasi terkait kebobrokan rezim. Tidak heran kalau gerakan Reformasi berasal dari para mahasiswa, aktivis pro-demokrasi, dan intelektual terlibat.
Kasus-kasus di atas mengklarifikasi betapa di balik keberhasilan pembangunan dengan segala macam kampanyenya, rezim Orba sangat berbahaya karena selama lebih dari 30 tahun mereka tidak hanya melakukan KKN secara berjamaah dan regenerasinya bisa kita rasakan sampai sekarang, tetapi juga memberangus secara keji individu dan kelompok yang dianggap berbahaya bagi kekuasaan.
Nyawa manusia menjadi begitu murah dibandingkan kemapanan kekuasaan rezim. Harus diakui, Suharto berhasil menjalankan pembangunan dalam banyak bidang.
Meskipun demikian, kebiadaban yang dijalankan jelas-jelas tidak bisa diterima karena kemampuan rezim Suharto memainkan wacana pembangunanisme yang menutupi semua kejahatan sistemik negara memang bukan jaminan untuk menyelamatkan kekuasaannya.
Namun, kemampuan strategis itu terbukti mampu menghindari perlawanan dalam skala besar terhadap kejahatan dan kebiadaban yang dilakukan negara terhadap warganya.
Mengatasi Ketakutan-ketakutan: Kampanye Budaya Bangsa
Penggiatan pembangunan di segala bidang kehidupan, tidak hanya memperkuat nilai dan aspek kapitalisme di tengah-tengah masyarakat, tetapi mulai juga menghadirkan wacana-wacana lain yang berbeda dari wacana resmi negara.
Hasrat untuk menikmati kebebasan dan gaya hidup berorientasi Barat menjadi begitu kuat di tengah-tengah masyarakat sebagai akibat semakin populernya gaya hidup modern. Selain itu, pendidikan berorientasi Barat, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, mengantarkan aspek-aspek kemajuan berpikir berbasis rasionalitas, kebebasan, dan nalar kritis.
Menguatnya kebebasan berpikir dan berintak ala Barat inilah yang menjadikan rezim penguasa mengalami ketakutan dan kecemasan. Di tambah lagi semakin biasanya inteletual dan mahasiswa dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sebenarnya, bukan pseudo-democracy yang dijalankan rezim Suharto.
Menghadapi kondisi tersebut, rezim Suharto melakukan mekanisme-mekanisme kultural agar kehendak akan kebebasan dan demokrasi yang sebenarnya tidak terlalu berdampak kepada keberlangsungan kekuasaan mereka.
Mendeskripsikan budaya nasional sesuai dengan kehendak rezim negara merupakan salah satu mekanisme diskursif yang dibuat negara. Rezim Orde Baru memiliki arah dalam kebijakan pengembangan budaya nasional, sebagaimana dituangkan dalam REPELITA.
Pencantuman “kebudayaan nasional” sebagai bagian dari kebijakan pembangunan baru dimulai pada REPELITA II (1974-1979) dan dilanjutkan pada REPELITA sesudahnya. Wacana pengembangan budaya nasional merupakan rambu-rambu bagi setiap warga negara. Secara umum, kebudayaan nasional menurut cara pandang negara bisa dikerangkai dalam beberapa wacana berikut (Bappenas).
Pertama, budaya bangsa pada hakekatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan kultural sekaligus menjadi landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya.
Kedua, budaya Indonesia yang mencerminkan nilai luhur bangsa, harus dibina dan dikembangkan guna memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, kepribadian bangsa, rasa harga diri dan kebanggaan nasional, kesetiakawanan nasional, dan jiwa kesatuan dan persatuan nasional.
Ketiga, tumbuhnya budaya nasional yang berkepribadian dan berkesadaran nasional dapat mencegah berkembangnya nilai-nilai kultural yang bersifat feodal dan kedaerahan yang sempit, sekaligus untuk menanggulangi pengaruh “budaya asing” yang negatif.
Apa yang kemudian diwacanakan oleh rezim negara adalah konsep “integrasi” yang menyatukan bermacam budaya daerah yang eksis di tanah air dalam sebuah bingkai besar bernama budaya nasional; sebuah semangat yang didasari kepentingan stabilitas politik pasca tragedi 1965.
Ketakutan akan munculnya wacana-wacana Barat berupa kebebasan berpikir dan bertindak serta berkembangnya demokrasi yang sebenarnya dianggap membahayakan pembangunan karena bisa mendorong gerakan perlawanan, mendorong rezim untuk memosisikan budaya nasional sebagai cerminan nilai-nilai luhur bangsa.
Pada dasarnya, konsep ini tidak jauh berbeda dengan konsep yang dikembangkan rezim Soekarno, tetapi memiliki kepentingan politik yang berbeda. Pada masa Soekarno konsep kepribadian bangsa digunakan untuk mengembangkan nasionalisme dan menyelesaikan proyek “revolusi yang belum selesai.”
Sementara, pada masa Soeharto lebih diarahkan pada usaha untuk mendukung keberhasilan pembangunan. Maka, budaya nasional yang bisa mendukung penghayatan dan pengamalan Pancasila serta menghadirkan nilai-nilai positif merupakan rambu-rambu normatif kebijakan negara dalam hal budaya dan ekspresi kultural yang diproduksi oleh aktor-aktor kultural.
Konsekuensinya, segala penyimpangan dari kepribadian bangsa dalam ekspresi kultural akan mendapatkan sanksi yang tegas, baik berupa gunting sensor film maupun pencekalan pertunjukan seni.
Penekanan wacana budaya nasional sebagai kepribadian bangsa dan kesadaran nasional dalam idealisasi negara memiliki dua fungsi strategis, yakni “mencegah berkembangnya nilai-nilai sosio-kultural kedaerahaan yang berpotensi menyemaikan politik identitas” dan “menganggulangi pengaruh budaya asing yang negatif.”
Penekanan tersebut merupakan bentuk kontrol rezim negara terhadap tumbuhnya gerakan di tingkat lokal yang akan menghambat program investasi transnasional ataupun nasional di wilayah-wilayah daerah, baik dalam aspek pertambangan, perkebunan, dan lain-lain.
Sementara, budaya asing (modernitas yang mengutamakan kebebasan individual) juga dibaca sebagai nilai dan praktik yang membahayakan bangunan kepribadian bangsa. Meskipun demikian, untuk aspek-aspek kemajuan seperti pendidikan dan investasi ekonomi diposisikan sebagai sesuatu yang baik sehingga masyarakat perlu dipersiapkan agar bisa menyerapnya.
Untuk menjelaskan pentingnya modernitas yang baik untuk negara dan bangsa, rezim menggunakan istilah “budaya luar” yang terkesan netral, bukannya budaya asing yang terkesan negatif.
Pemahaman-pemahaman tersebut, pada dasarnya, bertujuan menyukseskan Trilogi Pembangunan (stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan hasil-hasil Pembangunan) sebagai acuan utama rezim Orba dalam menjalankan pembangunan nasional.
Penekanan utamanya adalah pada aspek pertumbuhan dan kemajuan ekonomi, baik dalam lingkup kota besar maupun daerah terpencil karena diidealisasi akan menurunkan angka kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Bukan hanya aspek industri yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan ekonomi nasional, tetapi juga sektor pertanian dengan program intensifikasi dan massifikasi.
Sementara, industri budaya pop yang memberikan hiburan kepada massa dan berorientasi komersil berkembang pesat. Untuk mendukung target ekonomi tersebut dibutuhkan “stabilitas nasional” berupa ketertiban, keamanan, dan integrasi sosial.
Menjadi wajar kalau pada masa Orba konsep tepo sliro, tenggang rasa, dan toleransi menjadi formasi utama yang diproduksi secara massif, dari buku pelajaran, ucapan para pejabat, hingga Penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Dengan cara itu, rezim berusaha mengeliminir potensi kritik dan resistensi dari warga negara yang bisa mengganggu pembangunan.
Dengan konsep budaya nasional yang demikian, rezim Orba berusaha mengatasi kompleksitas permasalahan kultural, utamanya masuknya pengaruh negatif budaya modern yang sebenarnya menjadi orientasi kamajuan ekonomi dan berkembangnya sentimen kedaerahaan yang memunculkan-kembali kekuasaan feodal.
Dalam konteks demikian, budaya nasional, alih-alih menjadi kekuatan strategis pembangunan, menjelma sebagai kekuatan represif yang penuh dengan ambivalensi; saya menyebutnya ambivalensi berlapis.
Berbeda dengan konsep Bhabha (1994) tentang ambivalensi dalam memandang budaya kolonial/modern yang dicintai sekaligus dibenci, ambivalensi berlapis menunjukkan kerumitan pola pikir rezim negara dalam memahami kondisi-kondisi kultural yang berkembang seiring menguatnya semangat kemajuan dalam bentuk pembangunan nasional dan eksistensi budaya-budaya tradisional.
Di satu sisi, budaya tradisional yang sesuai dengan Pancasila diyakini sebagai resep mujarab bagi bangunan budaya nasional yang menunjukkan karakteristik bangsa serta bisa digunakan untuk menangkal hasrat-hasrat kebebasan individual. Di sisi lain, karakter kedaerahaan yang menghambat pembangunan dianggap subversif, sama seperti ajaran komunis.
Adapun, budaya modern yang mengusung aspek kemajuan pendidikan maupun ekonomi diposisikan sebagai rezim kebenaran melalui pembangunan, sedangkan aspek-aspek negatif yang bertentangan dengan kepribadian bangsa ditolak karena dianggap menganggu stabilitas negara.
Fungsi represif budaya nasional yang berkutat dalam ambivalensi berlapisnya sejatinya menunjukkan ketidakjelasan konsep budaya nasional karena hanya didasari kepentingan ekonomi politik penguasa.
Kleden (1988: 233-235) melihat timbulnya beberapa permasalahan terkait ketidakjelasan konsep tersebut. Pertama, kebudayaan tradisional dan kebudayaan baru, dibiarkan tumbuh bersama-sama, tetapi tanpa arah suatu kebijaksanaan untuk menghubungkan atau mengintegrasikan perkembangan keduanya dalam dialektika yang produktif.
Kedua, sejalan dengan ekspansifnya sektor modern yang menggeser sektor tradisional dalam kehidupan ekonomi, maka nilai-nilai kebudayaan modern, khususnya dalam aspeknya yang konsumtif dan permisif, menggeser pula nilai-nilai tradisional yang sebetulnya masih besar peranannya sebagai pembentuk identitas, kontrol sosial, dan kontrol moral.
Selain itu, ketidakjelasan konsep budaya nasional, di masa Orba membawa konsekuensi lanjut berupa kuatnya isu politik budaya nasional dibandingkan isu kebudayaan itu sendiri.
Tindakan atau ekspresi kultural apapun yang dianggap pemerintah yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan mengganggu stabilitas akan ditolak dan diberikan sanksi tegas; budaya nasional sebagai bentuk legitimasi kontrol politik.
Dengan kata lain, penggunaan nilai-nilai keindonesiaan sebagai patokan dalam berkebudayaan punya misi khusus untuk menghadapi pengaruh budaya asing yang mulai berkembang sejalan dengan tumbuhnya budaya konsumen. Kebijakan pemerintah Indonesia ini, ternyata, sejalan dengan kebijakan serupa yang diambil oleh beberapa negara Asia Tenggara.
Jones (2012: 153) memaparkan bahwa penyebaran budaya konsumen dan cepatnya pergerakan informasi yang berkaitan dengan barang dan jasa kapitalis memunculkan kekhawatiran di antara pemerintah nasional.
Pemerintah Singapura, Malaysia, Indonesia, Cina, dan Burma melawan perubahan budaya dan pesan politik dan sosial terkait yang diduga disebarluaskan oleh kapitalisme internasional dengan wacana yang disebut “nilai-nilai Asia” yang menekankan kerja keras, nilai keluarga, penghormatan terhadap penguasa, tanggung jawab sosial, disiplin, dan dukungan warga negara terhadap pemimpin.
Atas nama melestarikan nilai-nilai Asia, negara mengkonsolidasikan kekuatan politik dengan mengarahkan oposisi populis melawan Sang Barat. Mereka menjalankan kontrol politik dengan membatasi kebebasan pers dan hak asasi manusia dengan melabeli mereka sebagai “Barat”. Dengan demikian, pemerintah mendefinisikan mereka sebagai yang bertentangan dengan cara hidup Asi
Tidak mengherankan, di Indonesia, melalui pendidikan, seminar, dan banyak penelitian, pemerintah menggiatkan nilai-nilai keindonesiaan sebagai bagian dari nilai-nilai Asia yang tampak memperkuat budaya lokal dan budaya nasional.
Namun, kita tidak boleh lupa, bahwa target sebenarnya adalah terjaganya kekuasaan karena masyarakat diberikan acuan-acuan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak yang tidak menimbulkan peluang resistensi terhadap pemerintah.
Beragam budaya daerah diteliti oleh para dosen atau peneliti dari universitas negeri dan swasta di seluruh Indonesia, dengan tujuan mengungkapkan nilai-nilai unggul yang bisa mendukung pengembangan dan penguatan budaya nasional.
Dalam keadaan demikian, praktik pelestarikan kearifan lokal, kesenian, ritual, dan bentuk-bentuk budaya daerah lainnya tidak pernah dimaksudkan untuk memberikan kemampuan ideologis-komunal bagi para pelakunya. Sebaliknya, pelestarian tersebut menjadikan budaya daerah tampai ramai di permukaan, tetapi sebetulnya sudah kehilangan mayoritas kekuatan ideologisnya.
Ritual agraris, misalnya, hanya diapahami sebagai ritual yang patut dirayakan, tetapi kemanfaatannya untuk lingkungan hanya dicatat dalam penelitian. Padahal pada masa sebelumnya, kesenian rakyat mendapatkan porsi utama dalam menyampaikan kritik ataupun ajakan untuk perjuangan sosial.
Kampanye nilai-nilai keindonesiaan dalam kerangka jati diri dan kepribadian bangsa, dengan demikian, menjadi justifikasi politik untuk mempraktikkan kekuasaan otoriter guna merespoen kritik yang berasal dari kalangan demokratik-liberal (Jones, 2012: 154).
Apa yang menarik dicermati lebih lanjut adalah bagaimana rezim negara mentransformasikan hubungan rakyat dengan praktik budaya; ikatan ideologis perlahan-lahan dimarjinalkan untuk kemudian ditiadakan.
Acciaioli (1985) memaparkan bagaimana di tengah-tengah kuatnya ‘agama sipil’, Pancasila dan pembangunan, rezim Suharto mengubah fungsi ritual dari kesenian, mentransformasi adat tertentu menjadi ‘kesenian’ dan menata-kembali kehidupan dalam komunitas di mana adat masih diikuti.
Acciaicoli (dikutip dalam Jones, 2012: 154), setidaknya, mengidentifikasi 3 elemen terkait proses tersebut yang berhubungan dengan kebijakan budaya. Pertama, transformasi ritual untuk memenuhi agama sipil negara, termasuk penerapan standar moral yang sesuai dengan agama lokal dominan (seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha).
Kedua, para aparat harus mampu mengarahkan perubahan tersebut ke dalam komunitas. Ketiga, pemerintah Indonesia mengkonsepsikan dirinya sebagai “pembawa budaya yang benar”, alih-alih sebagai pembawa pandangan yang lebih antropologis dari budaya.
Dengan perspektif itulah, pemerintah daerah melakukan proyek-proyek budaya yang sesuai dengan keinginan Jakarta. Kesenian-kesenian daerah dihidupkan lagi setelah sempat mati suri pasca 1965.
Ritual-ritual adat disemarakkan dengan arahan yang sesuai dengan keinginan pemerintah dalam menyukseskan pembangunan. Bentuk-bentuk budaya lain seperti bahasa daerah atau bahasa ibu juga dikembangkan untuk mendukung dan memperkuat identitas budaya lokal dalam kendali negara.
Salah satu dampak nyata dari kebijakan budaya nasional dan budaya daerah tersebut adalah semaraknya ekspresi budaya di setiap daerah. Namun demikian, kesemarakkan tersebut menghilangkan kekuatan ideologis budaya lokal terkait permasalahan-permasalahan sosial, ekonomi, dan politik.
Reduksi budaya daerah sekedar sebagai perayaan yang dimeriahkan menjadikan rakyat kehilangan ikatan strategisnya dengan ekspresi budaya mereka. Bahkan, gerakan ekologis dan pertanian yang bisa diberdayakan melalui kekuatan lokalitas juga berusaha ditiadakan karena pemerintah lebih memilih Revolusi Hijau sebagai solusi untuk memajukan pertanian demi swasembada pangan.
Bersama-sama dengan Penataran P-4, penyebarluasan budaya bangsa benar-benar menjadi alat kontrol negara terhadap tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai modernitas yang bisa membahayakan kemapanan rezim Suharto.
Dampak lain yang mengerikan dari kebijakan tersebut adalah menguatnya sensor untuk semua produk kebudayaan. Pembatasan sensor benar-benar memberangus gagasan kritis yang ada dalam industri budaya di Indonesia. Itu semua menjadikan kebudayaan Indonesia memang tambak hebat, tetapi sejatinya masih kurang berkembang dengan baik.
Daftar Bacaan
Acciaioli, Greg. 1985. “Culture as Art: From Practice to Spectacle in Indonesia”. Canberra Anthhropology, Vol. 8 (1 & 2), hlm. 148-172.
Bhabha, Hommi. 1994. The Location of Culture. London: Routledge.
Boggs, Carl. 1984. The Two Revolution: Gramsci and the Dilemas of Western Marxism. Boston: South End Press.
Boothman, Derek. 2008. “Hegemony: Political and Linguistic Sources for Gramsci’s Concept of Hegemony,” dalam Richard Howson & Kylie Smith (eds). Hegemony: Studies in Consensus and Coercion. London: Routledge.
Fontana, Benedetto. 2008. “Hegemony and Power in Gramsci,” dalam Richard Howson & Kylie Smith. Hegemony: Studies in Consensus and Coercion. London: Routledge.
Foucault, Michel. 2013. Archaeology of Knowledge. London: Routledge.
Foucault,. 1998. The Will to Knowledge, The History of Sexualities Volume 1 (English trans. Robert Hurley). London: Penguin Books.
Foucault, Michel. 1984. “Truth and Power”. Dalam Paul Rainbow (ed). Foucault Reader. New York: Panthean Books.
Foucault, Michel. 1981. “The Order of Discourse”, Inaugural Lecture at the College de France, 2 Desember 1976, dipublikasikan kembali dalam Robert Young (ed). Untying the Text: A Post-Structuralist Reader. Boston: Routledge & Kegan Paul Ltd.
Foucault, Michel. 1980. Power/Knowledge. Brighton: Harvester.
Gramsci, Antonio. 1981. “Class, Culture, and Hegemony,” dalam Tony Bennett, Graham Martin, Collin Mercer, & Janet Woolacott (eds). Culture, Ideology, and Social Process. Batsford: The Open University Press.
Howson, Richard & Kylie Smith. 2008. “Hegemony and the Operation of Consensus and Coercion,” dalam Richard Howson & Kylie Smith (Eds). Hegemony: Studies in Consensus and Coercion. London: Routledge.
Jones, Todd. 2012. “Indonesian Cultural Policy in the Reform Era”. Indonesia, hlm. 147-176.
Kleden, Ignas. 1988. Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan. Jakarta: LP3ES.
Setiawan, Ikwan. 2011. “Modernitas, Lokalitas, dan Poskolonialitas Masyarakat Desa di Era 80-an.” Literasi, Vol. 1, No. 1, hlm. 117-134.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI