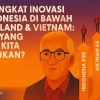1.1. latar belakang
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu secara kodrati, universal, tidak dapat dicabut, dan wajib dilindungi oleh negara. HAM mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar bagi sistem hukum dan tatanan sosial yang adil dan beradab. Di Indonesia, jaminan terhadap HAM diatur secara konstitusional melalui Pasal 28A--28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan diperkuat melalui UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Kusnadi, 2020). Meskipun kerangka normatif tersebut telah terbentuk, pelaksanaan dan penegakan HAM masih menghadapi tantangan yang kompleks. Sejumlah kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, seperti tragedi 1965, Timor Timur, dan pelanggaran di Papua, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip hukum dengan praktik di lapangan (Rachmad, 2019).
Reformasi yang dimulai sejak 1998 telah membuka ruang bagi penguatan institusi demokrasi dan hukum, namun berbagai bentuk pelanggaran HAM, baik oleh individu maupun institusi negara, masih terus berlangsung. Permasalahan utama dalam penegakan HAM di Indonesia meliputi lemahnya integritas aparat penegak hukum, praktik korupsi, diskriminasi dalam penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat (Sutiyoso, 2021). Kondisi ini menciptakan jurang antara idealisme hukum dan realitas sosial, serta mengikis kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negaranya. Sebagai negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila, pelaksanaan HAM di Indonesia tidak hanya mengacu pada norma internasional, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai lokal seperti agama, moralitas, dan budaya bangsa. Oleh karena itu, pendekatan dalam perlindungan HAM harus bersifat holistik tidak hanya legalistik, tetapi juga kontekstual dan berkeadilan sosial (Suryono, 2020). Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian ilmiah yang mendalam untuk memahami dinamika perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia secara kritis. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan, penguatan sistem hukum, serta peningkatan kesadaran kolektif demi terwujudnya negara hukum yang demokratis dan menghormati martabat setiap manusia.
1.2. Metode Penelitian
Pembahasan dalam artikel ini diarahkan pada penelusuran kepustakaan (library research) dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Dari penulusuran kepustakaan dan dokumen tersebut dihasilkan karya tulis yang sistematis dengan menggunakan pendekatan yuridisanalitis dan diperoleh hasil yang kualitatif.
BAB 2
KAJIAN TEORI
2.1.1. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan konsep normatif yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak lahir, tidak dapat dicabut, bersifat universal, dan wajib dilindungi oleh negara, hukum, serta masyarakat. Dalam konteks hukum Indonesia, HAM diatur secara komprehensif melalui Pasal 28A--28J UUD 1945 serta diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. HAM mencakup hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hak-hak kolektif yang lebih luas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Kusnadi, 2020). Secara historis, konsep HAM modern lahir dari pemikiran filsuf John Locke yang menyatakan bahwa manusia secara kodrati memiliki hak hidup, hak atas kebebasan, dan hak milik. Pandangan ini menginspirasi lahirnya dokumen penting seperti Magna Charta (1215), Declaration of Independence Amerika Serikat (1776), dan Declaration of the Rights of Man and of the Citizen pada Revolusi Prancis (1789). Perkembangan paling signifikan muncul setelah Perang Dunia II, saat Perserikatan Bangsa-Bangsa merumuskan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) tahun 1948, yang menjadi landasan global pengakuan dan perlindungan HAM (Alfitri, 2018). Dalam praktik internasional, HAM diawasi oleh lembaga seperti Dewan HAM PBB dan badan traktat seperti Komite Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Indonesia sendiri telah meratifikasi kedua kovenan internasional tersebut, menunjukkan komitmen global terhadap perlindungan HAM (Sutiyoso, 2021).
Namun, konsep HAM tidak selalu diterima secara mutlak. Beberapa pihak memandang HAM sebagai produk nilai Barat yang belum tentu selaras dengan nilai lokal atau budaya Timur. Bahkan, dalam situasi tertentu seperti keadaan darurat, beberapa hak dapat dibatasi sesuai dengan prinsip proportionality dan legality, meskipun hak-hak tertentu seperti kebebasan dari penyiksaan dan perbudakan tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun (non-derogable rights) (Irene, 2022). Di Indonesia, HAM tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum internasional atau Barat, tetapi juga dikontekstualisasikan dalam nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, perlindungan HAM harus dilakukan dengan pendekatan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghargai norma-norma sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat (Suryono, 2020). Konsep ini menegaskan bahwa HAM bukan hanya klaim individual terhadap negara, melainkan juga tanggung jawab sosial terhadap sesama.
2.1.2. Kerangka Hukum dan Institusional HAM di Indonesia
Kerangka hukum dan kelembagaan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak masa reformasi 1998. Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia menjamin perlindungan HAM secara konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J. Ketentuan ini menunjukkan adanya komitmen negara terhadap prinsip universal HAM yang sejalan dengan perkembangan hukum internasional (Kusnadi, 2020). Kerangka hukum HAM di Indonesia diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjadi landasan hukum nasional dalam perlindungan HAM. Undang-undang ini mendefinisikan HAM sebagai hak dasar yang melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Darmawan, 2017).
Selain itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menjadi instrumen hukum khusus untuk menangani pelanggaran HAM berat, seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Meskipun pengadilan ini telah dibentuk, efektivitasnya dalam mengadili kasus pelanggaran HAM berat masih menjadi sorotan karena hambatan politik, teknis, dan keterbatasan dalam perlindungan saksi dan korban (Febrianti, 2021). Di sisi kelembagaan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan institusi independen yang memiliki peran strategis dalam mempromosikan dan menegakkan HAM. Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999, Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, mediasi, pemantauan, dan pendidikan HAM. Dalam praktiknya, Komnas HAM seringkali menghadapi tantangan dalam bentuk keterbatasan kewenangan eksekusi serta resistensi dari institusi penegak hukum lainnya (Simanjutak, 2019).
Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005. Ratifikasi ini memperkuat kerangka hukum nasional serta membuka peluang bagi masyarakat untuk menggunakan mekanisme HAM internasional jika perlindungan domestik terbukti tidak efektif (Alfitri, 2018). Namun demikian, efektivitas kerangka hukum dan institusional tersebut masih menghadapi tantangan, seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya akuntabilitas aparat negara dalam kasus-kasus pelanggaran HAM. Oleh karena itu, penguatan kapasitas institusi, harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional, dan pengawasan publik yang kuat diperlukan guna menciptakan sistem perlindungan HAM yang lebih responsif dan akuntabel (Sutiyoso, 2021).
2.1.3. Tantangan dalam Penegakan HAM
Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum dan kelembagaan yang relatif lengkap dalam menjamin perlindungan HAM, implementasi di tingkat praktis masih menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari aspek hukum, tetapi juga dari faktor politik, sosial, dan budaya yang saling terkait. Salah satu persoalan krusial yang hingga kini belum terselesaikan adalah adanya impunitas terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu seperti tragedi 1965, kekerasan di Timor Timur, serta konflik di Papua. Upaya penuntasan kasus-kasus tersebut sering kali mandek di tengah jalan akibat tarik menarik kepentingan antara aktor politik dan institusi hukum (Savitri, 2020). Selain itu, sistem peradilan yang belum sepenuhnya netral dan profesional turut menjadi hambatan. Lemahnya akuntabilitas lembaga yudikatif, campur tangan kekuasaan, serta korupsi dalam aparat penegak hukum menurunkan efektivitas penegakan HAM. Akibatnya, banyak pelanggaran HAM tidak diproses secara tuntas, yang pada gilirannya menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap keadilan (Simanjuntak, 2019).
Tidak kalah penting, tumpang tindih peraturan serta ketidaksesuaian antara hukum nasional dengan standar HAM internasional juga menyulitkan upaya perlindungan HAM, terutama bagi kelompok rentan. Beberapa kebijakan pemerintah daerah bahkan bersifat diskriminatif terhadap kelompok minoritas agama, gender, maupun masyarakat adat, yang menunjukkan lemahnya integrasi nilai-nilai HAM dalam perumusan kebijakan (Zainal, 2021). Kendala lain yang juga signifikan adalah minimnya kesadaran masyarakat mengenai HAM. Dalam banyak kasus, pelanggaran HAM dianggap sebagai hal biasa dan tidak dilaporkan, terutama di wilayah yang masih kuat dengan nilai patriarki dan budaya otoriter. Keterbatasan pendidikan HAM menyebabkan masyarakat tidak mengetahui hak-hak dasarnya atau bahkan takut untuk menuntut keadilan (Yani, 2019).
Dari sisi kelembagaan, Komnas HAM sebagai lembaga independen sering menghadapi tantangan karena hanya memiliki kewenangan rekomendatif. Banyak hasil penyelidikan yang tidak ditindaklanjuti secara memadai oleh lembaga eksekutif atau aparat hukum. Selain itu, tidak adanya jaminan perlindungan terhadap korban dan saksi memperburuk situasi (Fauzi, 2018). Tantangan lain yang muncul di era digital adalah kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat melalui internet. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kerap digunakan untuk membungkam kritik masyarakat, yang berpotensi melanggar hak atas kebebasan berekspresi sebagai bagian dari HAM sipil dan politik (Pakpahan, 2021). Secara keseluruhan, tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia bersifat struktural dan multidimensional. Oleh karena itu, penyelesaiannya menuntut reformasi hukum yang menyeluruh, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendorong akuntabilitas dan demokratisasi.
2.1.4. Pendekatan Kultural dan Nilai Pancasila dalam HAM
Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya dan etnis memiliki pendekatan kultural dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Pendekatan ini mengintegrasikan nilai-nilai luhur bangsa yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Pancasila tidak hanya sebagai simbol negara, tetapi juga sebagai landasan moral dan filosofis dalam penghormatan terhadap martabat manusia. Pada sila kedua Pancasila berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan beradab" yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak individu tanpa diskriminasi. Implementasinya tercermin dalam kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan ratifikasi instrumen internasional seperti ICCPR dan ICESCR. Namun, tantangan masih ditemukan dalam pelaksanaannya, termasuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan masyarakat adat, serta inkonsistensi penegakan hukum. Pendekatan humanis memberikan perspektif inklusif untuk mengatasi tantangan ini melalui pendidikan HAM, dialog sosial, dan reformasi hukum yang adil (Savitri, 2020).
Implementasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam penegakan HAM di Indonesia dapat diwujudkan melalui dua langkah utama: pertama, institusi penegak hukum seperti Komnas HAM, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan berperan sebagai katalis dalam pengembangan wacana Pancasila di lingkungannya; kedua, pembentukan kader pemimpin bangsa yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 (Simanjuntak, 2018). Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia juga berperan sebagai dasar negara hukum yang menganut sistem hukum Pancasila, yang menjadi ciri khas negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dalam sebuah negara hukum akan menjadi suatu ciri khas sebagai negara demokrasi Pancasila yang mana hal ini membuat Indonesia menjalankan asas negara hukum yang berbeda dari negara hukum lainnya (Zainal, 2021). Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam penegakan HAM, Indonesia tidak hanya menghormati hak-hak individu tetapi juga menjaga identitas budaya dan kearifan lokal yang menjadi ciri khas bangsa. Pendekatan kultural ini memperkuat fondasi moral dan sosial dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
BAB 3
PEMBAHASAN
Secara obyektif prinsip perlindungan terhadap HAM antara negara satu dengan negara lain adalah sama, tetapi secara subyektif dalam pelaksanannya tidak demikian, artinya pada suatu waktu ada persamaan hakikat terhadap apa yang sebaiknya dilindungi dan diatur, tetapi pada saat yang bersamaan ada perbedaan persepsi HAM antara negara yang satu dengan yang lain. Keadaan ini lebih disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan juga perbedaan kepentingan nasional dari masing-masing negara tersebut. Di negara Indonesia antara masa Orde Baru dan pada era Reformasi. Pada era reformasi perjuangan untuk penegakan HAM lebih memberikan harapan. Berbagai upaya baik yang dilakukan pemerintah dan masyarakat meskipun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan bangsa Indonesia, tapi sudah adanya kemajuan dari masa sebelumnya (Orde Baru) sudah mulai tampak. Berbagai upaya perlindungan HAM yang sudah mulai dirintis dan sedang berjalan hingga sekarang perlu diapresiasi. HAM di Indonesia yang pernah carut marut bahkan dianggap sebagai yang terberat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia dibandingkan dengan perkembangan sekarang tentu sudah berbeda teramat jauh.
Kemajuan dalam perlindungan HAM telah menjadi salah satu program pemerintah sejalan dengan proses reformasi dan pemantapan kehidupan berdemokrasi yang sedang berlangsung, upaya perlindungan terhadap HAM di Indonesia di antaranya adanya bentuk hukum tertulis yang memuat peraturan tentang HAM yaitu dalam konstitusi, Ketetapan MPR dan pada Undang Undang. Kelebihan Pengaturan HAM dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat erat karena perubahan dan atau penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan Indonesia mengalami proses yang sangat berat dan panjang antara lain melalui amandemen dan referendum. Sedangkan kelemahannya karena yang diatur dalam konstitusi hanya memuat aturan-aturan yang masih global seperti ketentuan tentang HAM yang termuat dalam ketentuan-ketentuan UUD RI 1945 yang masih bersifat global. Upaya perlindungan HAM telah ditekankan pada tindakan penegakan terhadap terjadinya pelanggaran HAM. faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan HAM yang dilakukan individu maupun masyarakat dan negara. Masyarakat yang memiliki tugas utama untuk melindungi warga negara termasuk hak-hak asasinya sebagaimana hal ini dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945, yang pada intinya tujuan NKRI adalah :
a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
b) Memajukan kesejahteraan umum.
c) Mencerdaskan kehidupan bangsa.
d) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional maupun telah dibentuk lembaga untuk penegakannya, tetapi belum menjamin bahwa HAM dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Di bidang hukum masih terlihat lembaga penegakan hukum, banyak pejabat yang melakukan pelanggaran hukum sulit dijamah hukum, tetapi ketika pelanggaran itu dilakukan oleh rakyat kecil maka tampak kuat cengkeramnya. Di samping itu di masyarakat masih banyak terjadi bentrokan atau konflik tentang SARA. Meskipun demikian pemerintah telah berupaya untuk melindungi warga negaranya terhadap HAM seperti tersebut di atas, dengan harapan semoga pelaksanaan dan perlindungan HAM lebih baik di masa mendatang.
BAB IV
PENUTUPAN
4.1. Kesimpulan
1) HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal usul sosial dan bangsa.
2) HAM tidak boleh bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain.
3) Dengan mendasarkan pada pengertian HAM, maka HAM memiliki landasan utama, yaitu Landasan langsung seperti sesama kodrat manusia dan Landasan Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan manusia.
4) Menghargai perlindungan HAM berarti juga menghargai upaya penegakan HAM.
4.2. Saran
1) Kita sebagai makhluk sosial harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain, jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain. Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan HAM orang lain.
2) Kita sebagai warga negara yang baik, bila melihat dan mendengar terjadinya pelanggaran HAM kita harus memiliki kepedulian, meskipun pelanggaran itu tak mengenai pada diri kita atau keluarga kita Sebagai sesama anak bangsa harus peduli terhadap korban pelanggaran HAM atas sesamanya.
3) Kepedulian kita semua sebagai warga negara Indonesia terhadap penegakan HAM merupakan amanat dari nilai-nilai Pancasila yakni kemanusiaan yang adil dan beradab yang sama-sama kita junjung tinggi, karena akan dapat menghantarkan sebagai bangsa yang beradab.
4) Bagi aparat hukum harus adil dalam menangani kasus hukum antara yang terjadi pada pejabat dan rakyat kecil.
DAFTAR PUSTAKA
Alfitri. (2018). Human Rights in Indonesia: Between Universalism and Cultural Relativism. Indonesian Journal of International & Comparative Law, 5(1), 21--40.
Darmawan, D. (2017). Hukum Hak Asasi Manusia. Bandung: Refika Aditama.
Febrianti, R. (2021). Evaluasi Efektivitas Pengadilan HAM dalam Penanganan Pelanggaran HAM Berat. Jurnal Hukum dan Keadilan, 16(2), 243--260.
Fauzi,. (2018). Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer (1). Jakarta: Kencana.
Irene, R. (2022). Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Situasi Darurat. Jurnal Konstitusi dan Hukum, 9(2), 145--160.
Kusnadi, E. (2020). Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Konstitusi Indonesia. Jurnal Konstitusi, 17(3), 525--543.
Pakpahan, R. (2021). ANALISA IMPLEMENTASI UU ITE PASAL 28 AYAT 2 DALAM MENGURANGI UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL. Journal of Information System, Informatics and Computing, 5(1), 111. https://doi.org/10.52362/jisicom.v5i1.465.
Sutiyoso, B. (2021). Tantangan Penegakan HAM di Indonesia: Perspektif Hukum dan Sosial. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(1), 37--52.
Suryono, D. (2020). Nilai-Nilai Pancasila dalam Penegakan HAM. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Simanjutak, B. (2019). Peran Komnas HAM dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.
Savitri, W. (2020). Menyoal Impunitas dan Keadilan Transisional di Indonesia. Indonesian Journal of Human Rights Law, 6(2), 121-- 139.
Zainal, A. (2021). Diskriminasi Struktural dan Tantangan HAM dalam Kebijakan Lokal. Jurnal Kebijakan dan HAM, 7(1), 97--115.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI