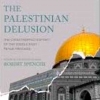Di era globalisasi, kita hidup dalam keterhubungan yang sangat intens dengan dunia luar. Film Hollywood bisa kita nikmati hanya dengan sekali klik. Musik Korea menjadi pengiring harian di berbagai platform digital. Gaya busana Tokyo atau Paris hadir di etalase mall-mall kota besar. Bahkan makanan khas luar negeri seperti ramen, sushi, burger, hingga croissant kini mudah ditemukan di pinggir jalan. Semua itu menunjukkan betapa derasnya arus budaya global yang masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari.
Namun, di balik kemudahan dan keberagaman yang ditawarkan globalisasi, terselip satu tantangan besar yang tidak boleh kita abaikan: bagaimana kita tetap mampu merawat dan membanggakan identitas budaya lokal di tengah serbuan budaya asing yang semakin dominan?
Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan warisan budaya Indonesia. Menjaga bukan berarti menolak atau memusuhi budaya luar. Globalisasi tidak bisa dan tidak perlu dihentikan. Namun, kita perlu menjadi generasi yang bijak dalam menyaring pengaruh budaya asing, serta tetap menjadikan budaya lokal sebagai pijakan utama dalam membentuk identitas diri.
Hal ini bisa dimulai dari langkah sederhana. Misalnya, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah dalam keseharian, khususnya saat berinteraksi dengan sesama warga lokal. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga cerminan cara pikir dan cara hidup suatu masyarakat. Ketika bahasa daerah mulai ditinggalkan, nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya pun perlahan bisa menghilang.
Dukungan terhadap seni tradisional juga menjadi bentuk konkret dalam merawat budaya lokal. Menonton pertunjukan tari tradisional, mengikuti pelatihan gamelan, atau menghadiri festival budaya di daerah bisa menjadi bentuk apresiasi sekaligus bentuk pelestarian. Mengenalkan kuliner lokal kepada teman dari luar kota atau luar negeri juga merupakan diplomasi budaya yang sederhana namun berdampak.
Kampus sebagai ruang intelektual seharusnya turut menjadi arena subur bagi tumbuhnya apresiasi budaya. Unit kegiatan mahasiswa (UKM) berbasis kesenian daerah, forum diskusi sastra lokal, maupun komunitas pelestarian budaya bisa menjadi motor penggerak bagi mahasiswa untuk tetap terhubung dengan akar budayanya. Kampus bukan hanya tempat menimba ilmu akademik, tetapi juga medan pembentukan karakter dan identitas.
Lebih dari itu, dunia akademik juga memiliki peran besar dalam pelestarian budaya melalui pendekatan ilmiah. Mahasiswa dapat mengangkat topik-topik kebudayaan lokal sebagai tema tugas akhir, skripsi, atau riset lapangan. Pengabdian kepada masyarakat pun bisa diarahkan pada kegiatan dokumentasi tradisi lisan, revitalisasi upacara adat, atau pelatihan kreatif berbasis kearifan lokal. Bahkan pembuatan film pendek, podcast berbahasa daerah, atau komik digital tentang cerita rakyat bisa menjadi media edukasi yang menarik bagi generasi muda.
Dalam konteks teknologi dan media sosial, kita sebenarnya memiliki alat yang sangat kuat untuk menyuarakan kekayaan budaya lokal. Instagram, TikTok, dan YouTube tidak harus selalu diisi dengan tarian viral atau tren luar negeri. Kita bisa menggunakan platform ini untuk membagikan konten yang mengangkat identitas lokal: cerita rakyat yang mulai terlupakan, resep masakan khas nenek, sejarah kampung halaman, atau tutorial mengenakan pakaian adat. Jika dikelola secara kreatif dan konsisten, media sosial bisa menjadi panggung budaya yang menjangkau audiens global.
Namun, merawat budaya juga berarti membuka diri terhadap perbedaan. Kampus yang menjadi miniatur Indonesia adalah tempat bertemunya beragam etnis, bahasa, dan tradisi. Ini adalah peluang emas untuk membuka dialog antarbudaya. Dengan saling mengenal dan menghargai budaya satu sama lain, kita bisa menciptakan ruang inklusif di mana identitas lokal tidak tenggelam, tetapi justru diperkaya oleh keberagaman.
Menjadi warga dunia bukan berarti mencabut akar lokal. Justru, seseorang yang memiliki akar budaya yang kuat akan lebih percaya diri dalam berinteraksi di kancah global. Mereka tahu siapa dirinya, dari mana ia berasal, dan apa yang menjadi kekuatannya. Ketika identitas lokal terjaga, maka kebudayaan nasional juga akan lebih kokoh berdiri di tengah pusaran perubahan dunia.
Budaya bukan sekadar warisan masa lalu yang harus dilestarikan secara pasif. Budaya adalah energi hidup yang bisa terus diolah, dikembangkan, dan dimodernisasi tanpa kehilangan makna dasarnya. Dengan sikap terbuka namun tetap teguh pada jati diri, kita bisa menjadi generasi yang menjadi jembatan antara tradisi dan inovasi, antara lokal dan global.