Kebijakan pendidikan kembali dipusatkan pada pendekatan standarisasi. Melalui pernyataan resmi Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Asrijanty, pada 11 Juli 2025, pemerintah mewajibkan seluruh sekolah negeri dan swasta menyelenggarakan Tes Kompetensi Akademik (TKA). Kebijakan ini diklaim sebagai upaya untuk memetakan capaian belajar siswa, mengukur mutu pendidikan, dan menyetarakan standar antarwilayah.
Namun, dari sudut pandang kebijakan berbasis keadilan distributif, pendekatan ini justru menampilkan ilusi keadilan: ketika standar diberlakukan seragam atas realitas yang tidak setara. Hal ini menjadi pengulangan dari problem lama dalam tata kelola pendidikan Indonesia ketidaksesuaian antara logika kebijakan pusat dan realitas pendidikan lokal.
Rasionalitas Kebijakan vs Rasionalitas Lapangan
Dalam teori kebijakan publik, khususnya pendekatan street-level bureaucracy (Lipsky, 1980), perumusan kebijakan sering kali mengandalkan rasionalitas teknokratis yang jauh dari kompleksitas mikro di lapangan. Negara memandang mutu sebagai variabel yang dapat diukur melalui angka dan statistik, sementara guru dan kepala sekolah berhadapan dengan kondisi riil yang sarat kendala struktural. Seorang kepala sekolah swasta di Kabupaten Kupang menyatakan:
“Kami tidak menolak evaluasi, tapi kami belum siap. Dua laptop sekolah rusak. Jaringan internet hanya stabil kalau pakai kuota pribadi guru. Kami bertahan karena komitmen, bukan karena sistem mendukung.”
Pernyataan ini merepresentasikan gap antara kewajiban legal dan kapabilitas riil. Dalam terminologi Amartya Sen (1999), keadilan bukan semata equality of treatment, melainkan equality of capability kemampuan aktual untuk memanfaatkan peluang. Ketika sekolah diminta menyelenggarakan TKA dalam kondisi yang timpang, maka kebijakan ini gagal memenuhi prinsip keadilan substantif.
Ketimpangan Struktural dalam Wajah Asesmen
Pertanyaan fundamental yang perlu diajukan adalah: Siapa yang benar-benar mendapat manfaat dari standarisasi TKA? Dalam struktur pendidikan yang belum merata secara infrastruktur, akses digital, dan ketersediaan sumber daya manusia, kebijakan ini secara sistemik menguntungkan sekolah-sekolah di pusat pertumbuhan, dan membebani sekolah-sekolah di wilayah pinggiran. Seorang guru kelas V di SD Negeri Amarasi Barat menyampaikan:
“TKA hanya akan jadi angka. Siswa kami tidak terbiasa ujian daring. Mereka lebih nyaman membaca buku fisik dan berdiskusi di kelas. Lalu siapa yang sedang kita nilai sebenarnya?”
TKA, dalam konteks ini, berisiko menjadi bentuk false measurement pengukuran yang tampak objektif namun tidak valid secara pedagogis. Ketika indikator penilaian tidak mempertimbangkan konteks kultural, geografis, dan pedagogis siswa, maka hasil asesmen lebih mencerminkan akses terhadap teknologi dibanding kapasitas akademik sejati.
Reduksi Mutu Menjadi Skor: Kekerasan Epistemik dalam Kebijakan

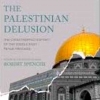

![[SimpulanSeptember]: Menulis sebagai Napas, Doa, dan Tanggung Jawab](https://assets-a2.kompasiana.com/items/album/2025/09/30/file275aab56-384d-4a3d-825a-2cd7c7738b6a-68db31b7c925c406eb18bee2.png?t=t&v=100&x=100&info=meta_related)



