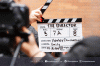Industri film dunia tengah memasuki babak baru. Layar perak yang dahulu menjadi panggung sakral bagi imajinasi sutradara, kini semakin terpinggirkan oleh layar datar di ruang keluarga atau layar ponsel dalam genggaman. Netflix, Disney+, hingga Prime Video tak hanya mengubah cara kita menonton, melainkan juga cara film itu sendiri diproduksi. Pertanyaan mendasar pun muncul: apakah film yang hadir di hadapan kita hari ini masih buah dari visi kreatif sutradara, atau sekadar hasil rumus algoritma yang disesuaikan dengan klik penonton?
Fenomena "sinema algoritma" menjadi perbincangan serius di kalangan kritikus. Platform streaming global kini tak sekadar menjadi penyalur konten, melainkan juga produsen dengan kekuatan raksasa. Netflix, misalnya, menganalisis perilaku jutaan penggunanya: genre apa yang paling banyak ditonton, aktor siapa yang paling disukai, durasi ideal untuk menjaga atensi, hingga adegan yang paling sering diulang. Dari data ini, lahirlah formula produksi. Sutradara dan penulis skenario bekerja dengan batasan "kerangka algoritma" yang ditetapkan berdasarkan pola konsumsi penonton.
Contoh paling mencolok adalah serial House of Cards yang rilis pada 2013. Keputusan menggandeng Kevin Spacey, sutradara David Fincher, dan tema politik yang gelap bukan sekadar hasil intuisi kreatif. Itu semua ditopang analisis data yang menyimpulkan bahwa penonton Netflix kala itu menggemari perpaduan antara bintang besar, sutradara visioner, dan drama politik. Dengan kata lain, algoritma telah duduk sebagai produser tak kasat mata.
Antara Keuntungan Pasar dan Hilangnya Eksperimen
Pendekatan ini membawa keuntungan nyata. Risiko kegagalan produksi dapat ditekan karena film dan serial dibuat sesuai selera pasar. Penonton merasa puas karena mendapatkan tontonan yang dekat dengan preferensinya, sementara perusahaan meraih keuntungan finansial berlipat. Pada titik ini, algoritma memang bekerja efektif sebagai jembatan antara industri dan konsumen.
Namun, di balik efisiensi itu, terdapat risiko homogenisasi. Film yang terlalu dikendalikan oleh data bisa kehilangan "jiwa". Narasi cenderung repetitif: drama romantis dengan konflik sederhana, horor dengan jumpscare instan, atau komedi dengan durasi tak lebih dari dua jam. Kreativitas sutradara dan keberanian untuk menantang pola pikir penonton sering kali dikorbankan demi mengejar formula yang aman.
Kritikus film dari Eropa hingga Amerika telah lama mengingatkan bahaya ini. Sutradara yang ingin bereksperimen sering kali terpinggirkan karena idenya dianggap "tidak ramah pasar". Sebaliknya, film yang "dibuat oleh algoritma" lebih mudah lolos produksi. Dengan demikian, pasar film global berisiko dipenuhi karya-karya yang seragam, aman, namun miskin kedalaman.
Jejak di Indonesia
Fenomena ini juga terasa di Indonesia. Beberapa film yang diproduksi langsung untuk platform digital tampak mengejar tren penonton: kisah cinta remaja urban, horor ringan, atau drama keluarga dengan alur sederhana. Format ini jelas memudahkan konsumsi, tetapi perlahan mengikis ruang bagi film-film yang menantang wacana sosial atau mengusung eksperimen artistik.
Padahal, sejarah film Indonesia membuktikan bahwa karya yang kuat justru lahir dari keberanian melawan arus. Film seperti Lewat Djam Malam (1954) atau Pengkhianatan G30S/PKI (1984), meskipun berbeda konteks, memiliki keberanian artistik dan politis yang membekas di memori bangsa. Di era algoritma, keberanian semacam ini terancam sirna, digantikan oleh tontonan "aman" yang sesuai selera mayoritas.