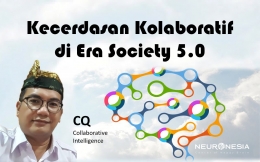Oleh: Bambang Iman Santoso, Neuronesia Community
Jakarta, 21 Desember 2020. Begitu kompleksnya otak pikiran manusia. Kemampuan berpikirnya hampir-hampir tak terbatas. Dibuktikan secara ilmiah, melalui kajian neurosains bahwasannya setiap manusia memiliki 86 milyar sampai dengan 100 milyar sel-sel otak yang belistrik yang disebut neurons.
Jumlah tersebut di luar sel-sel otak pendukungnya yang disebut neuroglia. Masing-masing neuron memiliki kaki (axon) dan tangan (dendrit) bisa mencapai ribuan. Bayangkan dengan jumlah yang besar itu bila sel-sel otak tersebut saling berhubungan, menghasilkan berapa triliun sinaps (koneksi antar neurons).
Sementara menurut penelitian; kepintaran seseorang diwakili jumlah sinaps atau hubungan antar neurons tersebut. Hal ini terbukti dari hasil penelitian pada isi kepala ilmuwan terkenal Albert Einstein yang ternyata memiliki otak dengan volume dan berat timbangannya di bawah rata-rata manusia pada umumnya. Namun jumlah sambungan sinaps beliau tadi sangat rumit dan padat, seperti benang kusut yang terlihat pada bagian white matter area.
Salah satu sifat otak manusia sering kali senang menyederhanakan segala sesuatu yang rumit. Termasuk mendefinisikan kecerdasan majemuk; multiple intelligences (Horward Gardner) dan multiple quotients (IQ, EQ, SQ, AQ, CQ, HQ, MQ dan lain sebagainya). Penggalian konsep dan teori kecerdasan manusia ini pun masih terus berkembang. Menunjukkan begitu rumit dan besarnya kapasitas manusia berpikir. Sesungguhnya otak kita memang tidak sesederhana seperti yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Teori dan konsep kecerdasan berkembang sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing jamannya.
Faktanya dunia terus berubah dan semakin cepat perubahannya terjadi. Perubahan yang terdisrupsi, bergejolak, penuh ketidakpastian, rumit, dan membingungkan. Terutama disrupsi teknologi digital, khususnya di bidang ICT (information, communication, telecommunication) berdampak signifikan yaitu manusia semakin cerdas dan menimbulkan keberagaman pola pikir, sikap dan perilaku yang semakin kompleks. Bagaimana informasi yang masuk ke dalam kepalanya dikelola dengan proses yang sangat unik berbeda oleh setiap individu.
Tantangan masa depan yang harus dipersiapkan dari sekarang; diperlukan dan ditingkatkannya suatu kecerdasan baru yang sebelumnya dikenal namun tidak dimaknai lebih dalam. Untuk mencapai tujuan hidupnya, manusia perlu bekerjasama dan berkolaborasi. Bukan IQ, tapi CQ yang penting di dalam komponen era 'mind share' dan 'heart share', ketimbang era 'market share' yang mulai ditinggalkan.
Dari profit oriented manjadi mutual benefit. Sehingga mereka tahu masing-masing keahlian apa yang dimiliki dan tidak dimiliki. Kemudian merasakan saling membutuhkan untuk mencapai tujuan bersama tadi. Memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya bersama (crowd resources). Otak mengoptimasi kinerja dorsolateral prefrontal cortex untuk mengendalikan secara sistematik berbasis kecerdasan terstruktur berbagai upaya untuk mencapai tujuan bersama; goal directed control (TNA, 17/12/2020).
Perbedaan IQ dan CQ adalah dimensi sosial dan kemampuan kelompok untuk mencapai kesatuan tujuan, tindakan dan pemikiran. Tim dengan tingkat CQ yang tinggi mencapai keadaan saling ketergantungan dan mengalir saat bekerja sama. CQ yang dimaksud di sini bukan sebatas collective intelligence, bukan pula collegial intelligence, atau kecerdasan bersama lainnya, seperti; kecerdasan sistematis fungsional, kecerdasan berkoloni atau bersekutu (swarm intelligence).
Pelajaran yang diambil dari sekawanan binatang, di mana mereka bergerombol karena memiliki persyaratan yang sama. Memiliki predator atau musuh bersama yang mengancam kehidupan mereka. Ada domain of danger-nya. Dalam berkelompok mencapai suatu tujuan bersama, masing-masing mengetahui peranan dan aturan mainnya. Ada pola yang harus diikuti dan dibentuk. Namun perlu diwaspadai, yang membedakan kita sebagai manusia jangan sampai terjebak dengan 'keegoisan bersama' tanpa mengindahkan kelompok lainnya.
Kecerdasan kolektif mengacu pada kapasitas dan kemampuan gabungan kelompok atau tim untuk melakukan berbagai tugas dan memecahkan berbagai masalah. Kecerdasan kolektif telah terbukti secara konsisten memprediksi kinerja kelompok dan tim di masa depan. (Chikersal, P et al 2017). Sedangkan Dawna Markova, PhD bersama menantunya Angie McArthur, di dalam bukunya yang berjudul "Collaborative Intelligence - Thinking with People Who Think Differently", mendefinisikan kecerdasan kolaboratif sebagai ukuran kemampuan kita untuk berpikir dengan orang lain atas dasar apa saja yang penting baik bagi kita semua.
Diversity berpotensi memunculkan kreativitas, inovasi, dan produktivitas serta kinerja tim yang terbaik. Namun menurut Geil Browning di dalam bukunya: "Work that Works" bila kita tak cakap mengelola cognitive diversity juga memungkinkan terjadinya kehancuran tim atau kelompok.
Penyebab utamanya tidak memahami adanya perbedaan kognitif, sehingga komunikasi yang terjalin tidak efektif dan cederung destrutktif. Geil memiliki latar belakang sebagai guru yang belajar psikologi dan mendalami aplikasi neurosains saat meraih gelar PhD-nya. Bersama Dr. Wendell Williams mereka merumuskan konsep Emergenetics. Berasal dari dua kata; 'emerge' dan 'genetics'. Kecenderungan pola berpikir dan beperilaku setiap manusia berbeda, yang diwariskan dari cetak biru genetika masing-masing orang tua mereka bercampur dengan lingkungan pengalaman hidupnya.
Menurutnya tim yang baik adalah mereka yang bisa memadukan keberagaman berpikir dan berperilakunya. Terutama dalam berpikir, berkomunikasi, dan bekerjasama. Masing-masing individu bertransformasi dari orientasi 'saya' ke 'kita'. WE tidak saja mengartikan kita, tapi singkatan dari 'whole emergenetics' yang mengaplikasikan konsep teorinya Ned Herrmann; 'the whole brain'. 'Emergineering a Positive Organizational Culture' yang diterapkan pada latihan WEteam merupakan salah satu contoh praktik nyata bagaimana menerapkan konsep emergenetics membangun kultur budaya positif melalui cognitive collaborations yang mengoptimalkan kinerja organisasi kita.
Dengan mengetahui kecenderungan pola pikir dan perilaku, menjadi lebih mengenal diri kita sendiri. Kemudian kita dapat pula memahami orang lain dengan baik. Di tingkatan terakhir yang tersulit adalah bagaimana memastikan orang lain benar-benar bisa mengerti kita.
Kemajuan teknologi, terutama kamajuan teknologi informasi khususnya di bidang selular, menjadikan setiap manusia Indonesia memiliki akses informasi yang sama selama dapat menangkap sinyal dan memiliki pulsa yang cukup, atau memperoleh free-wifi. Sementara dengan latar belakang individu yang berbeda-beda.
Berbeda bahasa, suku, adat, tradisi, kebiasaan, norma, sub kultur, agama, keyakinan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Termasuk berbeda latar belakang pendidikan dan kemampuan literasi bacanya. Sehingga menimbulkan lebih banyak variabel keberagaman perbedaan (diversity).
Nature-nya otak kita itu sangat sensitif dari ancaman ketimbang reward, dan itu memang sangat manusiawi bagian dari mekanisme kerja otak limbik dan batang otak kita yang tugas utamanya memproteksi diri. Namun kita bisa melatihnya agar otak PFC (prefrontal cortex) cakap meregulasi sistem limbik kita, sehingga selalu berupaya meminimalis ancaman dan memaksimalkan penghargaan (reward).
Fungsi utama otak eksekutif PFC kita di antaranya; berpikir analitik, meregulasi perilaku kita, mengatur kendali sosial (di social brain selalu ingat: "monkey see, monkey do" neurons, yang dikenal dengan MNS - mirror neurons system). Wilayah PFC ini sangat penting untuk capai kesuksesan kita.
PFC bertanggungjawab atas; proses pengambilan keputusan, pemahaman dan pemaknaan, proses mengingat (memorizing), perencanaan, inhibitasi dan recall.
Namun sayangnya, fungsi PFC akan segera menurun seketika (cognitive shutdown) manakala otak limbik emosional kita merasakan sinyal ancaman yang membahayakan diri kita. Engagement yang sudah terjalin drop, neurotransmitter oksitosin tak disemprotkan lagi (inhibitasi), banjir kortisol di kepala.
Hal ini yang perlu diperhatikan agar semakin lihai saat kita berkolaborasi. Kecerdasan kolaboratif, atau CQ, adalah ukuran kemampuan kita untuk berpikir dengan orang lain atas mencapai tujuan dan keuntungan bersama (mutualisme). CI atau CQ atau kecerdasan kolaboratif tadi menjadi suatu faktor yang krusial manakala kita ingin meningkatkan profesionalisme dalam bekerjasama (berpikir, berinteraksi, dan berinovasi).
Model kepemimpinan yang kuno di masa lalu, manajemen perusahaan masih diatur oleh hierarki dan kepemimpinan dari atas ke bawah (top down). Saat ini, manajemen perusahaan modern "berbagi pikiran", lebih flat - lebih datar, tak berjenjang tinggi, di mana pengaruh lebih penting daripada kekuasaan, dan kesuksesan bergantung pada kolaborasi dan kemampuan untuk menginspirasi.
Setelah belajar sedikitnya tentang neurosains atau brain science, belajar esensi utama berkolaborasi akan lebih mudah dimengerti. Dibahas tuntas oleh Markova dan McArthur yang ahli dalam membuat orang yang brilian namun sulit untuk berpikir bersama. Mereka telah banyak membantu memecahkan masalah bagi para pemimpin dunia (Fortune 500 leaders) dalam krisis dan para manajer yang berjuang memberikan inspirasi tim mereka.
Di Era Digital atau Era Society 5.0 strategi bersaing yang berdarah-darah telah ditinggalkan. Persaingan hanya menciptakan lingkungan yang penuh ketakutan dengan ancaman, kecurigaan dan kewaspadaan yang tinggi. Persaingan hanya menstimuli banjir kortisol. Munculnya Blue Ocean Strategy mencerminkan kejenuhan pasar yang senantiasa bersaing tanpa habis di lautan merah yang penuh darah. Di manajemen stratejik, strategic competitiveness akan segera digantikan dengan strategic collaborativeness.
Kita sekarang sedang memasuki dunia "berbagi pikiran" (mindshare), tidak lagi hanya berurusan dengan analitik dan masalah prosedural yang membutuhkan solusi rasional melulu. Kita diminta untuk berpikir bersama-sama dengan cara yang inovatif dan relasional.
Di era modern yang serba digital ini, bahkan kita tidak perlu benar-benar 'berteman' untuk dapat berkolaborasi dengan mitra kita yang berasal dari negeri mana saja. Banyak yang sukses bekerjasama dan berkolaborasi menjalankan suatu proyek secara virtual tanpa pernah berjumpa fisik.
Kita dituntut harus mampu bekerja dan berpikir lintas benua, budaya, zona waktu, dan temperamen. Dalam cara berpikir pangsa pasar (market share), nilai ditentukan oleh kekurangan. Seperti; saya memilikinya dan kamu tidak. Benda dinilai menurut kelangkaannya, misalkan; berlian sebagai contoh. Mentalitas pangsa pasar memecahkan masalah dengan meminta pikiran kita untuk berpikir praktis, analitis, dan prosedural.
Kekayaan diciptakan dan dibawa oleh lebih banyak ide dan hubungan daripada berdasarkan transaksi. Ketika sesuatu membawa nilai, jika kita memilikinya dan memberikannya, kita kehilangan sesuatu. Tapi ketika ide membawa nilai, semuanya menjadi terbalik. Ketika Anda punya ide cemerlang dan saya pun punya ide yang bagus, kita dapat menukarnya. Lihat apa yang terjadi? Anda pulang membawa dua ide baru dan saya pun memiliki dua ide baru. Semakin banyak kita berbagi, semakin banyak kita memiliki. Kapasitas kita untuk menghasilkan, berbagi, dan menerapkan ide menjadi yang paling berharga.
Di dunia berbagi pikiran, mengharuskan kita belajar memengaruhi orang lain ketimbang berkuasa atas mereka. Hal ini sangat penting sekarang, karena di zaman now yang serba cepat membentuk tim yang selalu siap siaga, bekerja sama dari seluruh benua dari jarak jauh dengan waktu yang singkat, pengaruh, bukan kekuasaan, dibutuhkan agar pekerjaan terobosan selesai. Berbagi pikiran juga membutuhkan pengembangan kapasitas dalam diri kita untuk menjadi dipengaruhi oleh orang lain dan menggunakan kolaborasi yang terampil untuk menciptakan gerakan maju.
Dengan cara ini, kepemimpinan menjadi kata kerja (to host), bukan kata benda (the hero). Pada akhirnya, dalam dunia berbagi pikiran, mereka yang paling fleksibel dalam berpikir akan menjadi orang-orang yang paling berpengaruh. Sementara di dunia market share, mengharuskan kita menjawab pertanyaan dengan cepat dan ahli. Sedangkan di dunia mind share mengharuskan kita mengetahui bagaimana mengajukan jenis pertanyaan yang membuka peluang pemikiran-pemikiran baru dari orang lain. Di dunia market share menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Sedangkan di dunia mind share menanyakan apa-apa yang mungkin.
Pada kajian-kajian neurosains modern diperlihatkan connectome setiap kabel listrik otak manusia tidak ada yang sama. Connectome adalah kumpulan sirkuit neural pathways jalan-jalan pikiran dan kebiasaan-kebiasaan kita. Every connectome or every brain is unique! (Sebastian Seung, 2012). Setiap otak manusia unik. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekuatannya. Fokus pada kekuatannya.
Di era sekarang lebih cenderung menggunakan pendekatan strengths based menggantikan competency based. Namun bukan berarti tidak perlu mengasah dan menajamkan kompetensi kita. Nasihatnya; kita tidak usah berubah menjadi orang lain. Fokuslah pada kekuatan diri kita, sehingga dapat berkontribusi yang terbaik kepada tim atau kelompok kerja. Sebaliknya, kita harus menganggap setiap manusia di depan kita adalah mahluk sempurna yang pasti memiliki kekuatan ataupun kelebihan. Dengan begitu proses berkolaborasi akan efektif dan lebih mudah dijalani. Simpati, empati dan trust akan muncul dengan sendirinya, menuju mutual benefit.
Kecenderung connectome seseorang tidak berubah, namun dapat berubah sesuai konsep neuroplasticity atau neuroplastisitas dalam bahasa Indonesia. Terutama karena ada kejadian khusus yang membekas (trauma), dan akibat mengkonsumsi narkoba, serta bila kita memang niatkan program khusus merubah sikap perilaku kebiasaan kita melalui pelatihan serius rutin dalam jangka waktu tertentu. Aslinya otak kita memang selalu berubah, sifatnya plastis. Karenanya di dalam berkolaborasi, memengaruhi orang lain lebih penting dibanding menguasai atau memaksa kehendak melaui perintah kita.
Di dalam konsep neuroplastisitas memang otak kita plastis, tidak tetap, berubah sepanjang usia. Hal ini yang menunjukkan kemampuan otak kita yang dapat beradaptasi dan kita bisa berlatih untuk selalu agile, open mind, growth mindset, dan melatih untuk senantiasa positive thinking dalam berkolaborasi.
Proses neuroplastisitas di antaranya: pembentukan koneksitivitas antar neuron (new synapses) pada saat learning process, pelepasan sambungan-sambungan sinaps (synaptic pruning) ketika unlearning process, dan menyambung-nyambungkan kembali pada saat relearning process terjadi. Selain rontok atau terputusnya sambungan-sambungan sinaps, juga terkadang proses keguguran neurons yang direncanakan tubuh demi efisiensi yang disebut apoptosis.
Strenghening synapses dengan jalan melatihnya berulang-ulang atau repitisi. Kemahiran berkolaborasi dengan manusia siapa saja yang beragam dapat diasah dengan pengulangan atau jam terbang. Persistensi, konsistensi dan memiliki komitmen yang kuat untuk melakukannya.
Sama seperti membangun neural pathways kebiasaan-kebiasaan positif yang baru. Sedangkan pelemahan sinaps atau weakening synapses juga akan terjadi manakala jarang digunakan. Neurons that fire together wire together. If we don't use it we loose it. Selain itu proses neuroplastisitas lainnya yang mungkin perlu diketahui seperti: pertumbuhan neuron-neuron baru (neurogenesis), kompensasi fungsi neurons (neurocompensation) dan penyakit rontoknya sinaps, serta kematian sel-sel neuron yang cepat (neurodegenerative disease).
Menurut John Assaraf, dalam membangun bisnis yang dapat diprediksi sukses diperlukan 3 komponen besar, yaitu: 1) pondasi kuat, 2) implementasi yang baik dan 3) optimalisasi bisnis. Di dalam pondasi yang kuat tidak hanya memerlukan mindset dan actionset yang baik. Namun juga dibutuhkan memiliki skillset yang kuat.
Apakah skillset yang dimaksud, ternyata justru keahlian menyadari kekuatan dan kelemahan diri kita untuk saling berbagi pekerjaan, yang tidak lain kelihaian menerapkan CQ. Kalaupun dia membuka usaha baru, akan merekrut mitra bisnis atau karyawan yang tidak sejenis atau serupa dia. Namun dicari yang dapat melengkapi kelemahan dia. Kecerdasan kolaboratif yang bagus akan mendistribusikan pekerjaan dengan baik, tidak mengerjakan semuanya sendiri. Berdasarkan konsep neuroplastisitas tadi kecerdasan ini dapat diasah, terus dilatih untuk ditingkatkan.
Untuk meningkatkan kemampuan kita berkomunikasi di dalam berkolaborasi, menurut Downa Markova dan Angie McArthur kita harus mengetahui mind patterns kita bagaimana proses atensi dalam berkomunikasi setiap orang berbeda-beda. Apakah kecenderungan kinestetik, auditif, atau lebih ke visual di masing-masing 'mind state'.
Di tingkat conscious mind atau sadar focused thinking-nya seperti apa. Kemudian di sub-conscious mind level atau setengah sadar sorting thinking kita cenderung bagaimana. Terakhir di tingkat tidak sadar atau non-conscious mind, open thinking kita lebih ke mana. Kita harus bisa mengindentifikasi diri kita.
Misal, katakan mind pattern saya A-K-V. Artinya focused thinking saya lebih ke auditif, atau melalui suara. Sedangkan sorting thinking saya cenderung kinestetik. Serta open thinking saya lebih ke visual atau melalui penglihatan. Kemudian identifikasikan lawan bicara atau teman kolaborasi kita pola mind pattern-nya seperti apa. Akhirnya kita dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan cepat dan tepat. Dalam kesehariannya seseorang yang telah mengantongi jam terbang tinggi, sering kali telah menguasai keahlian berkomunikasi dan berkolaborasi tanpa dapat menjelaskan secara rinci.
Sedangkan menurut Geil Browining, every brain is unique dibuktikan dengan memeriksa profil kecenderungan pola otak berpikir dan berperilaku kita, yang disebut dengan profil emergenetics tadi. Mengikuti teori the whole brain dari Ned Herrmann, menurutnya pola berpikir atau thinking preference manusia selalu memiliki 4 komponen kencenderungan berpikir, yaitu; analitik, struktural, sosial, dan konseptual. Dengan kombinasinya akan dapat menjelaskan kecenderungan orang berpikir apakah abstrak atau kongkrit, dan kecenderungan orang berpikir apakah divergen atau konvergen. Serta setiap manusia memiliki 3 komponen perilaku, yaitu; keekspresifan, keasertifan dan fleksibilitas.
Menurutnya kita harus bisa memanfaatkan keberagaman profil tadi, atau sering disebut 'harnessing diversity'. Tim yang baik dapat memasukan pendapat seluruh profil untuk memberikan kontribusi pemikiran dan perilaku yang optimal. Semua profil individu baik, tidak ada yang terbaik. Namun setiap manusia mempunyai peluang yang sama untuk menjadi atau memunculkan kinerja terbaiknya.
Di dalam konsep ini setiap profil manusia berpotensi menjadi pemimpin yang baik. Akan tetapi profil group diharapkan merata kecenderungan berpikirnya. Bila tidak merata atau masing-masing minimal 23%, ada beberapa teknik untuk menyisiatinya sehingga hasil diskusi, brainstorming ataupun kinerja bersama akan menjadi optimal.
Dengan kita memahami kecenderungan manusia berpikir dan berperilaku setiap manusia yang unik sehingga kita dapat berkomunikasi dan berkolaborasi secara optimal. Bertutur kata yang baik, tidak menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain - using the language of grace. Words are powerful.
Merupakan kunci keberhasian adalah komunikasi yang efektif. Hal ini menjadi pilar utama yang penting di dalam berkolaborasi seperti halnya keberhasilan dalam kepemimpinan, komunikasi pemasaran dan komunikasi bisnis, pendidikan dan pengasuhan anak, dan bidang-bidang sosial lainnya.
Untuk sukes berkolaborasi kita harus memahami keragaman perbedaan-perbedaan seperti yang diuraikan di atas. Termasuk perbedaan gender pria dan perempuan, yang memang jelas-jelas perbeda tidak hanya cara pikir dan perilaku, tetapi memang memiliki struktur otak secara fisik pun berbeda.
Contohya; perempuan seakan-akan lebih berpikir holistik dan mampu berkerja multitasking. Karena perempuan memiliki kemampuan bandwith interkoneksi corpus callosum yang menghubungkan antar kedua belahan otak jauh lebih baik ketimbang pria. Demikian pula dengan perbedaan-perbedaan kecenderungan berpikir dan berperilaku lainnya.
Kita juga mampu meningkatkan kepintaran berkolaborasi saat kita memahami perbedaan lintas generasi dengan lebih baik. Sehingga dapat meminimalis gap yang ada. Masing-masing generasi memiliki kecenderungan yang berbeda. Contoh di dalam literasi digital mereka yang lahir di lingkungan yang serba digital akan lebih cepat beradaptasi dan kecenderungan berkemampuan literasi digital yang lebih baik, karenanya dikenal dengan istilah 'digital natives'. Sedangkan seniornya atau digital immigrants berusaha untuk menyesuaikan dengan meningkatkan daya resiliensi digital yang optimal agar efektif berkolaborasi dengan generasi milenial atau generasi-generasi di bawahnya.
Generasi X atau dikenal dengan generasi facebook. Generasi Y yang lebih memilih menggunakan instagram ketimbang facebook sebagai media komunikasi efektifnya.
Sedangkan generasi di bawahnya lagi - generasi Z yang sering disebut snapchat generation menyukai memakai aplikasi snapchat seperti tiktok. Demikian generasi yang lahir sekarang-sekarang ini di masa pandemi, generasi pots-Z ini mungkin nantinya akan dikenal dengan generasi zoom atau pun generasi corona, pastinya akan memiliki kecenderungan berkomunikasi yang berbeda lagi khususnya dalam berkolaborasi.
Di era digital yang cenderung tanpa batas, kita dapat berkolaborasi dengan latar belakang budaya yang berbeda. Memiliki ciri khas kerangka berpikir dan mindset global namun tetap masing-masing menjaga kearifan lokalnya. Jenis-jenis kolaborasi seperti crowd funding dan crowd sourcing sangat dibutuhkan, terutama di masa-masa sulit seperti dalam menghadapi pandemi COVID-19, agar segera dapat mengatasi permasalahannya. Penyediaan vaksin, penyediaan pasokan alat pelindung diri, penanganan pengobatan pasien yang terdampak, dan seterusnya.
Kolaborasi yang sukses juga dapat memahami perbedaan yang diwarnai oleh perbedaan tingkat berpikir (level of thinking), dan perbedan tingkat kesadaran (level of awareness atau level of consciousness). Di dunia yang VUCA atau TUNA (volatility/turbulence, uncertainty, complexity/novelty, dan ambiguity) menyikapi perubahan seperti pandemi pun berbeda-beda.
Ada yang melihatnya lebih di domain 'volatile' atau bergejolak, karena baginya perubahan dikenal dan masih bisa diprediksi. Biasanya hanya memerlukan visi arah perubahan yang jelas. Tapi bagi sebagian orang yang merasa perubahan dikenal namun tidak dapat diprediksi atau di area 'uncertain' penuh ketidakpastian tinggi mereka memerlukan pemahaman yang lebih dalam terkait perubahan itu.
Sedangkan bagi mereka yang berada di zona 'complex' melihat perubahan ini rumit tidak dikenal walau masih dapat diprediksi, mereka memerlukan bantuan untuk dapat diuraikan, seperti menguraikan benang kusut. Bila seseorang telah merasakan perubahannya tidak dikenal dan tidak dapat diprediksi atau sering disebut dengan area 'ambiguous' tadi, ini merupakan tantangan tersulit, kita hanya dapat memengaruhi dia untuk tetap agile terhadap perubahan itu sendiri. Agar tidak kaku menyikapinya.
Catatan lainnya yang perlu diperhatikan agar sukses berkolaborasi kita harus dapat memaknai perubahan dengan pengertian kolaborasi yang sesungguhnya. Jadi tidak sekedar mengenal perubahan yang terus terjadi dan semakin cepat, dan tak terjebak hanya dengan istilah-istilahnya.
Berkolaborasi antar institusi yang berbeda akan sukses bila kita telah berhasil berkolaborasi di internal antar departemen atau antar bagian fungsi organisasi kita. Ingat kecerdasan kolaborasi telah merupakan skillset yang harus dimiliki di dalam fundamental sukses berbisnis, bekerja dan berorganisasi. Terutama di dalam teaming dan kepemimpinan.
Kecerdasan kolaboratif menentukan peforma di dalam bekerjasama lintas departemen baik itu di dalam usaha kecil seperti UKM dan UMKM, di perusahaan-perusahaan swasta dan pemerintah seperti BUMDES, BUMD, dan BUMN. Kinerja pemerintahan suatu negara juga dapat dilihat dari kemampuan kerjasama dan kolaborasinya antar kantor kementrian, antar departemen, serta lintas fungsional kenegeraan; eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Transformasi dari kekuasaan menjadi pelayanan yang baik, today government is public service provider. Permasalahan bangsa bisa berakar dari sini. Sekat-sekatnya harus sudah mampu dilepas, tidak ada lagi ego departemen atau ego kelembagaan negara. Bahkan di dalam kehidupan berpolitik sekarang ini, kecenderungan iklimnya masih fokus pada persaingan yang berdarah-darah.
Tidak kondusif untuk mengejar kertinggalan kemajuan bangsa. Sibuk dengan kisruh internal politik bangsa yang hanya membuang-buang waktu saja. Kehidupan berpolitik yang sehat sangat dirindukan dan diharapkan oleh masyarakat yang rukun, damai dan sejahtera. Terutama kekacauaan kehidupan berpolitik kita bersumber dari sistem pendanaan pembiayaan multi partai dan sistem perekrutan atau perkaderan yang harus segera diperbaiki. Sehingga dapat memupus habis kegemaran berkorupsi yang tiada berujung akhir.
Menurut Markova dan McArthur di dalam bukunya yang kedua berjudul "Reconciable Differences - Connecting in Disconnected World", kegagalan berkolaborasi dikarenakan bias-bias pikiran kita (dijelaskan juga di bukunya Daniel Kahneman dan Bruce Lipton). Empat bias utama yang sering terjadi; 1) perbedaan berkomunikasi (communicate), 2) perbedaan pemahaman (understanding), 3) perbedaan pembelajaran (learn), dan 4) perbedaan kepercayaan (trust).
Kecerdasan kolaboratif sangat erat dengan optimalisasi fungsi eksekutif otak kita. Meningkatkan kecerdasan berkolaborasi identik degan meningkatkan kinerja fungsi otak eksekutif kita berpikir. Terutama meningkatkan pay attention di dalam working memory otak PFC kita. Juga dapat menahan diri untuk tidak memaksakan kehendak kita (inhibitory control), memberikan ruang orang lain mengisi kekosongan atau kekurangan kita. Serta yang paling penting fleksibiilitas berpikir kognitif kita harus terus dilatih dan ditingkatkan (cognitive flexibility), mau mendengar masukan orang lain dan mengakui kelebihan orang lain.
Sehingga di era Society 5.0 ini kita dapat meraih sukses menyikapi dan memanfaatkan perubahan karena selau agile, berpikiran terbuka (open mind), berpikiran bertumbuh (growth mindset), berpikiran positif (positive thinking) serta memiliki ketangguhan mental yang kuat (mental toughness). Kecerdasan kolaboratif melalui kolaborasi kognitif (cognitive collaboration) harus dapat memanfaatkan keberagaman perbedaan kognitif (harnessing cognitive diversity), sehingga memunculkan kreativitas bersama, inovatif, produktivitas, dan kinerja lebih baik.
Dalam mengarungi arus perubahaan kita tidak sekedar latah ikut berubah. Karena memang mirror neurons system otak kita bekerja dengan sangat baik. Namun, yang terpenting adalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi bagaimana cara kita menyikapinya. Bagaimana caranya hari ini lebih baik dari sebelumnya, dan hari esok tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya bisa diproyeksikan lebih baik dari sekarang. Sehingga continuous improvement dan sustainable growth dapat tercapai. (BIS)