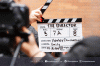Untuk pertama kali, saya menulis langsung sebuah review film yang biasanya saya diskusikan dengan teman-teman lain yang hobinya menonton film. Salah satu karya sinema di Indonesia yang menjadi perbincangan karena mengangkat tema-tema sosial yang relevan, seperti kekerasan di kalangan remaja, krisis dunia pendidikan, dan ketegangan sosial di masyarakat. Melalui narasi yang intens, film ini menggambarkan bagaimana perpecahan dan kekerasan terus berlangsung, menciptakan lingkungan penuh permusuhan. Film ke-11 salah satu sutradara yang sudah tidak asing lagi dan pasti banyak yang bilang overated, siapa lagi kalau bukan Joko Anwar, dengan judul filmnya Pengepungan di Bukit Duri. Film ini berlatar belakang tahun 2027, mengisahkan seorang guru pengganti bernama Edwin yang baru mulai mengajar di SMA Duri, sebuah sekolah yang dikenal dengan murid-muridnya yang berandal dan sulit diatur. Edwin terjebak dalam konflik sosial besar yang melibatkan kekerasan, diskriminasi rasial, dan ketegangan politik yang mengancam keselamatan dirinya dan para siswa. Namun, alasan lain Edwin ingin mengajar adalah mencari keponakannya yang ... jika ingin tahu tonton saja.
Review saya cukup simpel, Pengepungan di Bukit Duri (2025) membawa kita ke dalam "alternate reality" apabila revolusi 98 gagal, dan Jakarta terjebak dalam distopia yang penuh kerusuhan. Film ini cukup berat, terutama untuk orang Cina, karena menghadirkan isu sensitif yang bikin trauma. Cerita inti film ini berfokus pada Edwin dan kakaknya yang terjebak dalam kerusuhan. In a nutshell, MC dan kakaknya terlibat kerusuhan, kakaknya punya anak, karena keadaan chaos dititipin, kakak meninggal MC dikasih misi buat nyari keponakannya, eh malah di SMA para berandal.
Salah satu trademark Joko Anwar muncul lewat jokes gay yang selalu muncul, ini sih udah jadi signature beliau, nggak bisa dihindari. Kalau mau dianalisis lebih lanjut, sangat, ada terlalu banyak side karakter yang sebenarnya punya potensi besar, namun malah jadi kebuang sia-sia. Banyak sekali plot hole dalam film seperti clue bahwa keponakan Edwin bisa menghindar, jika ingin mencari keponakan kenapa tidak melalui cara lain seperti mencoba membuat event seni menggambar untuk siswa di Jakarta Timur, jika dipikir lebih dalam, Edwin punya sertifikasi guru. Lalu gejolak emosional dan konflik yang memancing amarah Jefri, Edwin juga penyebab utamanya. Dan kalau dipikir lebih dalam, Edwin menganggap (SPOILER) si Jefri adalah keponakannya hanya dengan melihat video bahwa Jefri bilang "gw Cina" menurut saya belum cukup untuk memperkuat bahwa dia keponakan Edwin. Karena kerusuhan diawal scene film, tentu selain kakaknya Edwin, masih banyak perempuan Cina yang mengalami pemerkosaan. Masih banyak plot hole yang bisa dibantah dari film tersebut. Secara keseluruhan, karena ekspektasi saya yang terlalu tinggi, jadi saya memberikan rating 7.9/10. Namun, fokus saya di tulisan artikel bukan hanya pada alur filmnya, namun pemahaman dan korelasi sosiologi pada film ini.
Teori Konflik dan Ketegangan Rasial Menjelaskan Inti Permasalahan Film
Film Pengepungan di Bukit Duri menghadirkan narasi tentang ketegangan sosial di sebuah kawasan urban yang dipenuhi oleh ketidakadilan, ketegangan antarkelompok, dan kegagalan sistem institusional. Sebagai karya yang kaya dengan simbolisme sosial, film ini dapat dianalisis dengan menggunakan berbagai teori sosiologi klasik dan kontemporer.
Dalam Pengepungan di Bukit Duri, secara eksplisit banyak sekali clue yang menjelaskan bahwa keturunan Cina, walaupun hanya minoritas, dipersepsikan memiliki akses lebih besar terhadap modal ekonomi, dibandingkan masyarakat lokal pribumi yang termarginalkan. Persepsi ini memunculkan kebencian kelas yang direduksi menjadi kebencian rasial, sesuai dengan analisis kritis dalam Racial Formation in the United States (Omi & Winant, 1986). Kebencian ini berkembang menjadi kekerasan kolektif, yang dalam struktur konflik Marxian dianggap sebagai upaya spontan proletariat untuk menggulingkan dominasi, meski seringkali tanpa arah teoritis yang jelas inilah sebabnya banyak tindakan kekerasan tampak terjadi "tanpa sebab rasional", melainkan murni karena internalisasi kebencian oleh kelompok marjinal yang frustrasi terhadap ketidakadilan struktural.
Munculnya Interaksionisme Simbolik Antar Ras sebagai Simbol Perlawanan Konflik Rasial
Beberapa scene memperlihatkan pengelompokan diri etnis Cina dalam film, misalnya pada saat scene bar khusus komunitas mereka sendiri di tengah ketegangan sosial, dapat dijelaskan melalui konsep social solidarity dan in-group favoritism dalam Interaksionisme Simbolik serta melalui teori social identity. Menurut teori tersebut, dalam situasi konflik atau diskriminasi, individu akan semakin mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok asalnya untuk mempertahankan harga diri sosialnya (social self-esteem).
Dalam interaksionisme simbolik, identitas kelompok terbentuk dari persepsi luar (apa yang orang lain pikirkan tentang kita) dan internalisasi identitas tersebut (apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri). Karena mereka terus menerus menerima perlakuan diskriminatif, warga keturunan Cina dalam film ini memperkuat batas-batas sosial mereka dengan cara eksklusif membuat tempat berkumpul sendiri, membatasi interaksi dengan masyarakat luas. Ini adalah mekanisme pertahanan terhadap dunia luar yang bermusuhan, sekaligus upaya mempertahankan solidaritas internal. Dengan kata lain, diskriminasi sistemik tidak hanya memperparah ketegangan, tapi juga secara tidak langsung memperkuat segregasi sosial berbasis identitas kelompok.
Konflik rasial di film ini juga bisa dianalisis sebagai konstruksi makna kolektif yang terbentuk melalui interaksi sosial sehari-hari. Mead berteori bahwa identitas diri dan persepsi kita tentang orang lain dibentuk secara dinamis dalam proses pertukaran simbolik: lewat bahasa, gestur, dan tindakan. Dalam film, kita melihat bagaimana label-label negatif yang disebarkan lewat percakapan dialog film di berbagai latar. Proses pelabelan ini menjadi kunci pembentukan "the generalized other" yaitu bagaimana kelompok Cina dipandang secara seragam sebagai "musuh" atau "bukan bagian dari kita". Ketika seorang anak atau remaja berinteraksi dengan orang tua, guru, teman, dan semua mengafirmasi simbol-simbol kebencian itu, ia menyerap makna tersebut ke dalam struktur dirinya. Simbolisasi di ending film ini benar benar sesuai, ketika seorang anak yang belum menyerap simbol kebencian dan afirmasi dari segala bentuk hegemoni kebencian terhadap Cina, justru menyelamatkan siswa Cina yang ada di dalam lemari loker karena digambarkan seperti kepolosan yang belum tersentuh dengan kebencian.
Konsep Anomie Menjelaskan Alasan Kekerasan yang Dialami Edwin dan Sesama "Cina" dalam Film
Jika diteliti perilaku kebanyakan masyarakat, khususnya para siswa SMA Duri di film yang digambarkan selalu menargetkan dan membenci orang Cina, sebenarnya mereka melakukan kekerasan tersebut tanpa memahami sepenuhnya alasan historis atau strukturalnya. Hal tersebut dijelaskan secara kuat melalui konsep normative conformity dalam teori anomie mile Durkheim dan teori deviant subculture Albert Cohen (1955). Durkheim menyatakan dalam The Division of Labor in Society bahwa dalam masyarakat yang mengalami anomie (kehilangan norma), individu tidak lagi berpegang pada nilai-nilai universal seperti keadilan atau solidaritas, melainkan mengikuti norma lokal yang berkembang dalam kelompoknya. Jika norma lokal tersebut mengajarkan kebencian, maka anggota kelompok termasuk anak-anak muda akan menginternalisasi kebencian itu tanpa harus memahami alasan rasional di baliknya. Sementara Cohen dalam teorinya tentang subkultur devian menjelaskan bahwa ketika kelompok muda mengalami ketidakberdayaan sistemik, mereka membentuk norma sendiri yang menentang nilai masyarakat luas.
Dalam konteks film, siswa-siswa itu, hidup dalam realitas penuh frustrasi sosial dan ketidakpastian masa depan, mengadopsi narasi kebencian yang diwariskan lingkungan mereka tanpa pertimbangan moral kritis. Mereka memukul, menghina, dan mengejek orang-orang keturunan Cina hanya karena itu adalah "norma" di komunitas mereka, sesuai dengan temuan-temuan sosiologi urban yang mengkaji transfer nilai devian antar generasi miskin kota.
Hadirnya Hegemoni Memperkeruh Distopia di "Jakarta"
Kekerasan dan diskriminasi terhadap etnis Cina di film Pengepungan di Bukit Duri dapat dipahami sebagai hasil dari dominasi ideologi kelompok penguasa yang membentuk kesadaran kolektif masyarakat. Teori hegemoni budaya dari Gramsci, berpendapat bahwa kekuasaan tidak hanya dipertahankan melalui kekerasan fisik, tetapi lebih efektif melalui penanaman nilai, norma, dan keyakinan dalam benak masyarakat sehingga ketidakadilan dianggap wajar dan normal. Dalam konteks film ini, prasangka rasial terhadap orang Cina telah terinternalisasi begitu dalam hingga dianggap sebagai bagian "alami" dari kehidupan sosial sehari-hari. Dalam film, latar waktu waktu dijelaskan sekitar tahun 90'an sampai 2027, tentu merupakan waktu yang lama untuk menanam prasangka tersebut. Hasilnya, membenci orang Cina bukanlah keputusan individu rasional, melainkan sesuatu yang diajarkan, diwariskan, dan diperkuat melalui sekolah, media, bahkan melalui percakapan sehari-hari.
Sehingga, hegemoni ini membuat bahkan mereka yang tertindas kelas pekerja miskin pribumi tidak lagi mempertanyakan kenapa mereka membenci, melainkan hanya mengikuti arus budaya yang mendikte siapa yang menjadi "lawan" mereka. Ini menjelaskan mengapa kekerasan terhadap orang Cina dalam film seringkali berlangsung tanpa motif ekonomi langsung atau provokasi nyata; kekerasan itu adalah produk dari hegemoni budaya yang telah mengaburkan realitas struktur sosial, mengalihkan kemarahan rakyat dari penguasa sejati ke kelompok minoritas yang lebih mudah dijadikan kambing hitam.
Pada intinya, teori sosiologi menganalisis bahwa film ini menggambarkan bagaimana ketidakadilan struktural, ketegangan antaretnis, kegagalan institusi pendidikan, serta keruntuhan norma sosial berkontribusi terhadap siklus kekerasan dan resistensi di masyarakat urban kontemporer. Dengan demikian, film ini merepresentasikan kompleksitas struktur sosial, konflik kepentingan, pembentukan identitas, hingga reproduksi ideologi dalam ketegangan rasial.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

![KEKUASAAN KATA [5]: Buku Kecil di Meja Guru](https://assets-a2.kompasiana.com/items/album/2025/09/18/file05152b08-f028-41e6-a465-5d3f97248571-68cb9222c925c462da1f48b6.png?t=t&v=100&x=100&info=meta_related)