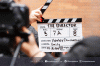Konsep Anomie Menjelaskan Alasan Kekerasan yang Dialami Edwin dan Sesama "Cina" dalam Film
Jika diteliti perilaku kebanyakan masyarakat, khususnya para siswa SMA Duri di film yang digambarkan selalu menargetkan dan membenci orang Cina, sebenarnya mereka melakukan kekerasan tersebut tanpa memahami sepenuhnya alasan historis atau strukturalnya. Hal tersebut dijelaskan secara kuat melalui konsep normative conformity dalam teori anomie mile Durkheim dan teori deviant subculture Albert Cohen (1955). Durkheim menyatakan dalam The Division of Labor in Society bahwa dalam masyarakat yang mengalami anomie (kehilangan norma), individu tidak lagi berpegang pada nilai-nilai universal seperti keadilan atau solidaritas, melainkan mengikuti norma lokal yang berkembang dalam kelompoknya. Jika norma lokal tersebut mengajarkan kebencian, maka anggota kelompok termasuk anak-anak muda akan menginternalisasi kebencian itu tanpa harus memahami alasan rasional di baliknya. Sementara Cohen dalam teorinya tentang subkultur devian menjelaskan bahwa ketika kelompok muda mengalami ketidakberdayaan sistemik, mereka membentuk norma sendiri yang menentang nilai masyarakat luas.
Dalam konteks film, siswa-siswa itu, hidup dalam realitas penuh frustrasi sosial dan ketidakpastian masa depan, mengadopsi narasi kebencian yang diwariskan lingkungan mereka tanpa pertimbangan moral kritis. Mereka memukul, menghina, dan mengejek orang-orang keturunan Cina hanya karena itu adalah "norma" di komunitas mereka, sesuai dengan temuan-temuan sosiologi urban yang mengkaji transfer nilai devian antar generasi miskin kota.
Hadirnya Hegemoni Memperkeruh Distopia di "Jakarta"
Kekerasan dan diskriminasi terhadap etnis Cina di film Pengepungan di Bukit Duri dapat dipahami sebagai hasil dari dominasi ideologi kelompok penguasa yang membentuk kesadaran kolektif masyarakat. Teori hegemoni budaya dari Gramsci, berpendapat bahwa kekuasaan tidak hanya dipertahankan melalui kekerasan fisik, tetapi lebih efektif melalui penanaman nilai, norma, dan keyakinan dalam benak masyarakat sehingga ketidakadilan dianggap wajar dan normal. Dalam konteks film ini, prasangka rasial terhadap orang Cina telah terinternalisasi begitu dalam hingga dianggap sebagai bagian "alami" dari kehidupan sosial sehari-hari. Dalam film, latar waktu waktu dijelaskan sekitar tahun 90'an sampai 2027, tentu merupakan waktu yang lama untuk menanam prasangka tersebut. Hasilnya, membenci orang Cina bukanlah keputusan individu rasional, melainkan sesuatu yang diajarkan, diwariskan, dan diperkuat melalui sekolah, media, bahkan melalui percakapan sehari-hari.
Sehingga, hegemoni ini membuat bahkan mereka yang tertindas kelas pekerja miskin pribumi tidak lagi mempertanyakan kenapa mereka membenci, melainkan hanya mengikuti arus budaya yang mendikte siapa yang menjadi "lawan" mereka. Ini menjelaskan mengapa kekerasan terhadap orang Cina dalam film seringkali berlangsung tanpa motif ekonomi langsung atau provokasi nyata; kekerasan itu adalah produk dari hegemoni budaya yang telah mengaburkan realitas struktur sosial, mengalihkan kemarahan rakyat dari penguasa sejati ke kelompok minoritas yang lebih mudah dijadikan kambing hitam.
Pada intinya, teori sosiologi menganalisis bahwa film ini menggambarkan bagaimana ketidakadilan struktural, ketegangan antaretnis, kegagalan institusi pendidikan, serta keruntuhan norma sosial berkontribusi terhadap siklus kekerasan dan resistensi di masyarakat urban kontemporer. Dengan demikian, film ini merepresentasikan kompleksitas struktur sosial, konflik kepentingan, pembentukan identitas, hingga reproduksi ideologi dalam ketegangan rasial.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI