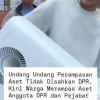Bagi banyak aktivis, pilihan itu dianggap kekuatan. Tanpa tuntutan spesifik, gerakan terasa inklusif.
Siapa saja bisa ikut, sementara fokus diarahkan ke akar persoalan, yaitu ketidakadilan sistemik.
Masalahnya, waktu berjalan dan pilihan itu berbalik menggigit. Inilah titik lemah yang belakangan sering dibahas.
The Atlantic pada 2012 mencatat bagaimana media dan politisi berulang kali bertanya, “Sebenarnya kalian mau apa?” Tidak pernah ada satu jawaban yang tegas. Akibatnya, pemerintah dan para pembuat kebijakan punya alasan nyaman untuk tak bergerak.
Energi protes yang awalnya besar pelan-pelan kehilangan momentum. Tanpa tujuan konkret, mempertahankan relevansi menjadi susah. Kamp bubar, sementara sistem tetap seperti sedia kala.
Ada pula romantisasi tentang komunitas yang sangat inklusif tanpa pemimpin. Sebuah laboratorium sosial tempat semua suara setara.
Realitasnya, komunitas tanpa struktur formal membawa tantangannya sendiri. Forum Majelis Umum memakai konsensus, dan prosesnya sering berjalan lambat serta tidak efisien.
Kelompok yang paling vokal atau paling terorganisir kerap mendominasi arah pembicaraan. Konflik internal bermunculan, sebagian menyangkut isu ras dan gender, sebagian lagi soal keamanan di perkemahan.
Gambaran demokrasi langsung yang mulus menutupi gesekan keras, perdebatan panjang, bahkan perpecahan di belakang layar.
Namun menutup buku dengan label “gagal total” juga gegabah. Mungkin kita yang keliru memakai tolok ukur.
Kalau ukurannya perubahan undang-undang, pencapaiannya memang tipis. Tapi kalau kita menilai dari pengaruh budaya, ceritanya lain sama sekali.