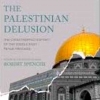Kalau ditanya, "Apa makanan khas Indonesia?" sebagian orang mungkin spontan menjawab nasi goreng, yang hampir bisa ditemukan di setiap sudut negeri. Ada pula yang menjawab rendang, yang sudah mendunia setelah dinobatkan CNN sebagai salah satu makanan terenak di dunia. Namun, tak sedikit yang lebih memilih soto, karena tiap daerah punya cita rasa tersendiri. Dari ketiga hidangan tersebut sering dianggap mewakili rasa Indonesia. Namun, dari sekian banyak pilihan, muncul pertanyaan yang lebih dalam: apakah Indonesia memang memiliki satu cita rasa nasional, atau justru kekayaan kuliner kita tidak bisa diseragamkan dalam satu rasa tunggal?
Kuliner Indonesia lahir dari perjalanan panjang sejarah dan pertemuan berbagai budaya. Setiap bumbu dan resep menyimpan kisah sosial, ekonomi, dan geografis masyarakatnya. Misalnya Rendang, berasal dari masyarakat Minangkabau yang hidup merantau, mereka butuh makanan yang tahan lama di perjalanan. Soto hadir dalam banyak versi mulai dari Soto Lamongan, Soto Betawi, Soto Kudus, hingga Soto Banjar. Semuanya merupakan hasil adaptasi daerah terhadap bahan lokal dan pengaruh luar. Sementara nasi goreng berakar dari tradisi Tionghoa, tetapi kini menjadi makanan sejuta umat di Indonesia. Menurut antropolog makanan Sidney Mintz (1985) pernah mengatakan, bahwa makanan bukan sekadar kebutuhan biologis, melainkan juga cermin sosial dan simbol identitas. Melalui makanan, masyarakat membangun makna tentang siapa mereka dan dari mana mereka berasal. Jadi, ketika kita bicara "kuliner nasional", sebenarnya kita sedang bicara tentang bagaimana bangsa ini mendefinisikan dirinya lewat rasa. Pandangan ini juga sejalan dengan pernyataan Ikhsan Rosyid Mujahidul Anwari, dosen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, yang menegaskan bahwa kuliner tradisional adalah refleksi akar budaya, bukan sekadar tren modern.
"Yang abadi itu adalah yang punya akar kuat di tradisi akhirnya menjadi kuliner tradisional. Kalau tidak ada basis kulturalnya, itu hanya sekadar branding artifisial." (Ikhsan Rosyid Mujahidul Anwari, FIB UNAIR, 2024)
Pernyataan ini mengingatkan bahwa kekayaan kuliner Indonesia tidak lahir dari pencitraan atau festival semata, tetapi dari tradisi yang hidup dan diwariskan antar generasi. Justru dari keragaman itulah harmoni muncul sebagai identitas yang bersatu bukan karena sama, tetapi karena saling menghargai perbedaan.
Pencarian "kuliner nasional" sering kali dipicu oleh kebutuhan simbol kebangsaan. Negara lain memiliki ikon yang mudah dikenali, seperti Jepang dengan sushi, Thailand dengan pad thai, Korea dengan kimchi. Indonesia pun ingin punya simbol yang serupa agar dunia mengenal kita lewat rasa. Tapi disinilah letak keunikannya. Indonesia terlalu kaya untuk diwakili oleh satu menu saja. Dari Aceh hingga Papua, setiap daerah memiliki rasa dan kebanggaannya sendiri. Kalau satu ditetapkan, yang lain pasti merasa tersisih. Maka, identitas kuliner Indonesia bersifat plural dan desentralistik mewakili jiwa bangsa yang majemuk.
Di zaman globalisasi, kuliner bukan hanya urusan perut, tapi juga alat diplomasi budaya. Melalui program Indonesian Spice Up the World, pemerintah mencoba memperkenalkan kekayaan rempah dan kuliner Nusantara ke panggung dunia. Namun tantangannya adalah makanan mana yang akan dijadikan ikon? Apakah cukup satu menu, atau justru seluruh keberagaman rasa Indonesia yang perlu diangkat? Alih-alih mencari satu simbol tunggal, diplomasi kuliner Indonesia seharusnya menonjolkan keragaman dan kekayaan rasa. Di sanalah kekuatan kita dibanding negara lain kita tak punya satu rasa dominan, melainkan ribuan rasa yang tumbuh dari budaya dan tradisi berbeda. Selain menjadi kebanggaan, pelestarian kuliner juga terkait langsung dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama SDGs Kota dan Komunitas Berkelanjutan.
Pada akhirnya, pertanyaan "Apa makanan nasional kita?" mungkin tak perlu dijawab dengan satu nama. Justru keberagaman itulah yang menjadi jawabannya. Indonesia tidak butuh satu cita rasa tunggal untuk dikenal dunia. Yang dibutuhkan adalah kesadaran bahwa setiap rasa lokal adalah bagian dari rasa nasional. Makanan adalah medium yang menyatukan tanpa memaksa. Di meja makan, latar belakang sosial, budaya, dan etnis bisa larut dalam satu piring. Saat seseorang menikmati sate Madura di Yogyakarta, pempek di Jakarta, atau papeda di Surabaya, ia sesungguhnya sedang menjelajahi wajah Indonesia yang beragam. Sebagaimana semboyan kita "Bhinneka Tunggal Ika", kuliner Indonesia hidup dari keberagaman. Nasi goreng, rendang, soto, dan ribuan hidangan lainnya bukan sekadar makanan, melainkan penanda perjalanan sejarah dan identitas bangsa yang terus tumbuh dan menyesuaikan zaman. Mungkin Indonesia tak perlu menetapkan satu "makanan nasional". Karena sejatinya, rasa nasional itu sudah ada di setiap dapur, aroma bumbu, dan di setiap perbedaan yang kita rayakan bersama.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI