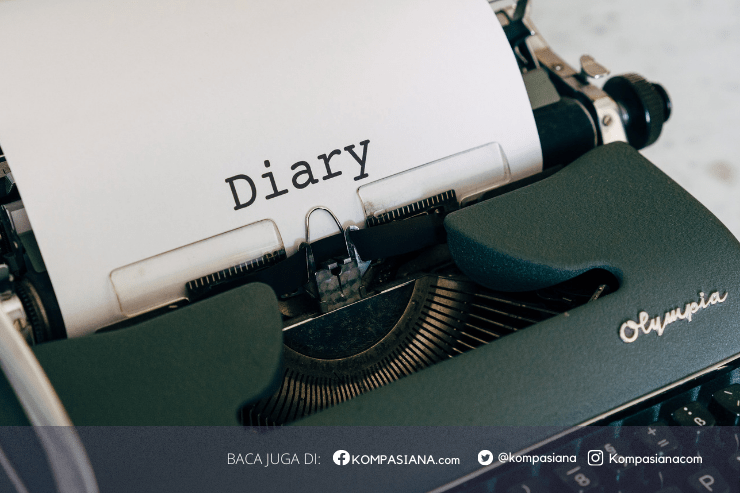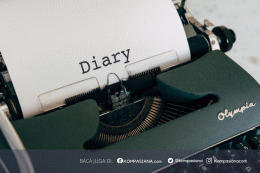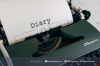Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dirumuskan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Secara etimologis, kata "Pancasila" berasal dari bahasa Sanskerta, yakni "panca" berarti lima dan "sila" berarti prinsip atau asas. Pancasila terdiri dari lima sila yang mencerminkan pandangan hidup bangsa, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam kajian sejarah, Pancasila lahir dari perumusan panjang yang melibatkan berbagai golongan, mulai dari sidang BPUPKI, Piagam Jakarta, hingga disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI sebagai dasar negara. Proses ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan produk instan, melainkan hasil kompromi politik yang matang dan representatif dari kepribadian bangsa Indonesia yang majemuk.
Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa terletak pada perannya sebagai fondasi yang mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya. Pada masa perumusan dasar negara, terdapat perbedaan pendapat yang cukup tajam di antara kelompok nasionalis, Islam, dan golongan lain. Namun, Pancasila menjadi jalan tengah yang mampu mengakomodasi semua kepentingan sehingga terbentuklah konsensus nasional. Hal ini menjadikan Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga perekat persatuan yang mampu menghindarkan Indonesia dari perpecahan sejak awal kemerdekaan. Tanpa Pancasila, bangsa Indonesia yang begitu majemuk mungkin akan sulit bersatu dalam satu kesepakatan bersama untuk mendirikan negara merdeka.
Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga memiliki fungsi sebagai pandangan hidup bangsa (weltanschauung). Artinya, nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Nilai Ketuhanan menuntun rakyat untuk menjunjung moralitas dan spiritualitas, nilai Kemanusiaan mengajarkan untuk menghormati hak asasi manusia, nilai Persatuan menumbuhkan rasa kebangsaan, nilai Kerakyatan mengedepankan musyawarah dan demokrasi, serta nilai Keadilan Sosial mengarahkan pada pemerataan kesejahteraan. Dengan demikian, Pancasila membentuk karakter bangsa yang berkeadaban, gotong royong, dan berorientasi pada kebaikan bersama.
Dalam konteks kekinian, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan globalisasi, perpecahan sosial, dan radikalisme. Pancasila berperan sebagai filter yang menjaga jati diri bangsa agar tidak hilang ditelan arus budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian nasional. Nilai-nilainya mendorong terciptanya toleransi, keadilan, serta demokrasi yang sehat di tengah masyarakat. Oleh karena itu, mempelajari dan mengamalkan Pancasila bukan hanya kewajiban formal, tetapi juga kebutuhan moral dan sosial agar bangsa Indonesia tetap kokoh, maju, dan berdaulat di tengah persaingan dunia.
Terlepas dari hal tersebut, membuat kita bertanya-tanya mengenai:
1. Apa pengamalan nilai simultan dalam Pancasila dan bagaimana jadinya ketika hasil Pancasila tidak dilakukan secara simultan?
Tentu saja, pengamalan simultan Pancasila berarti melaksanakan kelima silanya secara bersamaan, seimbang, dan saling melengkapi. Setiap sila tidak boleh dipisahkan atau dijalankan secara bertentangan, karena Pancasila merupakan satu kesatuan utuh. Jika pengamalannya tidak simultan, akan timbul ketidakseimbangan, seperti konflik sosial, ketidakadilan, bahkan perpecahan bangsa. Misalnya, hanya menonjolkan persatuan tanpa musyawarah bisa memunculkan pemerintahan otoriter, atau menekankan kebebasan tanpa kemanusiaan bisa memicu ujaran kebencian. Karena itu, pengamalan kelima sila harus dilakukan bersama-sama agar kehidupan masyarakat tetap harmonis, adil, dan berkeadaban, dan jika Pancasila tidak diamalkan secara simultan, akan timbul ketidakseimbangan dalam kehidupan berbangsa. Mengutamakan satu sila sambil mengabaikan yang lain dapat memicu konflik, ketidakadilan, atau bahkan perpecahan. Misalnya, hanya menonjolkan persatuan tetapi mengabaikan demokrasi bisa melahirkan pemerintahan otoriter, atau menekankan kebebasan tanpa nilai kemanusiaan bisa memicu ujaran kebencian. Karena itu, seluruh sila harus diamalkan secara bersama agar kehidupan masyarakat tetap harmonis.
2. Bagaimana bentuk nyata kesepakatan political consensus dalam lahirnya sejarah pancasila?
Bentuk nyata kesepakatan political consensus dalam lahirnya Pancasila adalah melalui proses diskusi dan musyawarah para pendiri bangsa. Mereka mencapai kesepakatan dengan mengubah sila pertama dari "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" untuk menjaga kesatuan bangsa. Pancasila kemudian disahkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. Proses ini menunjukkan bahwa Pancasila lahir dari kompromi dan musyawarah untuk menciptakan dasar negara yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia.
3. Di era sekarang mungkin atau tidak terjadi krisis identitas mengenai pancasila dan bagaimana cara mengatasinya?
Tentu bisa, di era sekarang krisis identitas Pancasila mungkin terjadi, terutama karena pengaruh globalisasi, arus informasi bebas, dan masuknya ideologi asing yang bisa menggeser nilai-nilai asli bangsa.
Cara mengatasinya adalah dengan memperkuat pendidikan Pancasila, meningkatkan literasi digital agar masyarakat bijak memilah informasi, memperbanyak keteladanan dari pemimpin, dan membiasakan penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti toleransi, musyawarah, dan gotong royong.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI