Indonesia dengan jumlah penduduk yang telah melampaui 270 juta jiwa menampilkan potret kemasyarakatan bak kaleidoskop: indah sekaligus rumit. Salah satu fragmen paling kontras adalah kesenjangan sosial. Ketidakmerataan akses ekonomi, pendidikan, dan teknologi menempatkan sebagian warga pada posisi yang jauh dari sejahtera. Ironisnya, di tengah ledakan media sosial, realitas getir tersebut bertransformasi menjadi bahan lelucon populer meme bertema “kesenjangan sosial” di TikTok. Fenomena yang muncul sejak kuartal pertama 2025 ini meraih ratusan juta penayangan, memicu perbincangan luas, dan lebih penting mengundang refleksi sosiologis mendalam.
Ketimpangan sosial di Indonesia bukan isu baru. Sejak Reformasi, koefisien Gini nasional bergerak di kisaran 0,38–0,40; angka yang mengindikasikan ketimpangan pendapatan masih tinggi. Di lapangan, jurang itu tampak pada disparitas upah, perbedaan kualitas sekolah, hingga kesenjangan akses layanan kesehatan. Di dunia maya, narasi ketimpangan menjadi konten yang “menjual” karena menyentuh pengalaman sehari‑hari: ajakan makan di restoran mewah yang ditanggapi dengan punchline soal saldo dompet, atau ajakan liburan mahal yang dijawab dengan tawa getir.
Platform TikTok memfasilitasi tren ini melalui algoritma yang mengangkat konten “relatable” semakin banyak warganet merasa “itu gue banget”, semakin tinggi peluang sebuah video masuk For You Page. Skema cerita sederhana tokoh kaya vs. tokoh pas‑pasan menjadi formula viral. Si kaya pamer kemewahan; si miskin merespons dengan kecerdasan humor yang mengandung kritik. Dalam tiga bulan, tagar #KesenjanganSosial menembus 500 juta tayangan, menjelma wadah keluh kesah kolektif sekaligus “katup pelepas tekanan”. Keviralan ini memancing tanya: Apakah humor sekadar penawar luka struktural, atau ia justru memperlebar jarak dengan menormalisasi ketimpangan? Bagaimana sosiologi membaca dinamika di mana kelompok terpinggir menertawakan diri, tetapi tetap menyadari realitas pahit? Pertanyaan‑pertanyaan ini mendasari kebutuhan pengkajian lebih dalam.
Dalam teori Marx, kelas sosial ditentukan oleh relasi terhadap alat produksi. Di ruang digital, device, kuota internet, dan skill konten menjadi “alat produksi” baru. Kreator berpenghasilan rendah mungkin tak memiliki kamera canggih, tapi mereka punya kreativitas untuk memproduksi sketsa yang menyentil. Alhasil, ketimpangan fisik berpindah ke ranah simbolik di mana “modal digital” menentukan kapasitas menjangkau audiens. Tokoh kaya lengkap dengan background kafe estetik dan barang bermerek merepresentasikan kelas dengan modal ekonomi tinggi. Sebaliknya, tokoh miskin memakai lagu back‑sound lucu, sudut rumah sempit, dan dialog sederhana. Kontras visual ini adalah strategi estetika sekaligus penegasan struktur sosial, layaknya panggung teater tempat peran sosial ditampilkan tanpa tedeng aling‑aling.
Bourdieu menggarisbawahi tiga bentuk modal: ekonomi (uang, aset), kultural (pengetahuan, gaya hidup), dan sosial (relasi). Dalam meme TikTok, ketiganya saling bertarung. Si kaya jelas unggul dalam modal ekonomi. Namun, si miskin menandingi melalui modal kultural berupa kelucuan, dialek autentik, dan “kemahiran mencandai diri”. Viralitas memberi mereka modal sosial berupa followers, kolaborasi, bahkan donasi, yang kemudian dapat dikonversi menjadi rupiah melalui endorsement. Fenomena ini memperlihatkan “jalan pintas” mobilitas sosial di era digital: popularitas dapat meningkatkan taraf ekonomi, meski sifatnya tidak selalu stabil. Di sisi lain, fakta bahwa orang miskin harus menghibur untuk bertahan menandakan reproduksi relasi kuasa masyarakat yang menonton tertawa tanpa harus menanggung beban struktural sang kreator.
Konsep dramaturgy Goffman memposisikan kehidupan sosial sebagai panggung, tempat individu “menjual” kesan terbaik. TikTok, dengan duet dan stitch, menyediakan ruang front stage serba terbuka. Kreator memilih kostum, lokasi, dan script untuk menguatkan persona kelasnya. Kadang, seorang kreator sebenarnya kelas menengah, namun rela berdandan sederhana demi memerankan “si melarat” praktik yang menekankan bahwa identitas kelas di media sosial bersifat performatif dan cair. Performa ini punya sisi ganda: ia bisa meneguhkan stereotip (si miskin identik dengan tampilan kusam), tetapi juga membuka diskusi publik tentang betapa sempitnya kategori “miskin” atau “kaya”. Dengan kata lain, TikTok menjadi arena renegosiasi identitas kelas.
Thorstein Veblen memperkenalkan konsumsi mencolok (conspicuous consumption) pamer barang mewah demi gengsi. Meme memparodikan praktik ini. Pamer iPhone 16 Pro Max, contohnya, dibalas si miskin: “Keren, Kak. Saya masih cicil paket data.” Narasi pamer dibalik menjadi lelucon yang menyeimbangkan kuasa simbolik; audiens diajak melihat absurditas gaya hidup hiper‑konsumtif.
Durkheim berbicara tentang collective effervescence, momen ketika individu tenggelam dalam emosi kolektif dan mencipta solidaritas. Challenge TikTok berfungsi sebagai ritual digital: setiap kali sebuah format populer, ribuan akun membuat versi serupa, menciptakan gelombang tawa bersama. Meskipun interaksi bersifat temporer, rasa senasib sejenak memperkuat jaringan solidaritas “kita sama‑sama susah, mari tertawa”.
Mazhab Frankfurt dan teori budaya populer menekankan bahwa massa bukan konsumen pasif; mereka punya kemampuan decoding dan resistensi. Kreator menggugat narasi kemiskinan yang biasanya sentimental menjadi satir yang menghadapkan audiens pada realitas: “Kami miskin, tapi kami bisa bikin kalian tertawa sekaligus berpikir.” Ini bukti agensi kelas tertindas dalam ranah simbolik.
Pendidikan abad ke‑21 menuntut literasi ganda: digital dan sosial. Guru perlu mengajak siswa membedah meme sebagai teks sosial, menemukan makna di balik punchline. Latihan ini tidak hanya menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, tetapi juga kesadaran posisi diri dalam struktur sosial. Kelas maya sering memperlebar jarak (mereka yang belajar lewat laptop vs. mereka yang berbagi gawai). Sekolah dapat menjadi ruang kompensasi: forum cerita lintas ekonomi, peer mentoring, hingga program virtual exchange dengan sekolah lain. Empati antarkelas tak lahir otomatis; ia perlu fasilitasi dan kurikulum sengaja.
Alih‑alih melarang gadget, pendidik bisa meminta tugas membuat meme bertema ketimpangan ekonomi atau hak asasi. Setelahnya, kelas mendiskusikan pesan dan bias konten. Pendekatan ini relevan dengan budaya Gen Z yang visual‑auditori serta gemar konten singkat. Kesenjangan harus diangkat eksplisit dalam pelajaran PPKn, Sosiologi, dan Ekonomi. Proyek riset lapangan misalnya survei harga kebutuhan pokok di pasar tradisional vs. supermarket akan menumbuhkan pemahaman empirik. Guru perlu mengaitkan temuan dengan teori struktural (Marx, Weber) dan solusi kebijakan.


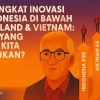
![[teenlit] Bumi yang Hijau Jiwa Gen Z](https://assets-a2.kompasiana.com/items/album/2025/09/15/file11a04266-dd2f-4fdb-a332-fa005ad7ab3e-68c82a0a34777c559a4c8a92.png?t=t&v=100&x=100&info=meta_related)



