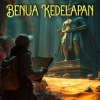Pada tahun 2024 kemarin, Indonesia mencetak rekor baru yang tak patut dirayakan: tahun terpanas sepanjang sejarah pengamatan sejak 1981. Data resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa suhu rata-rata tahunan di Indonesia mencapai 27,5°C, atau 0,8°C lebih tinggi dari rerata suhu periode 1981–2020, fakta yang mengejutkan dan miris bukan?. Ledakan dari tingkat suhu ini bukan hanya sekadar angka statistik saja melainkan ini merupakan sinyal darurat bahwa krisis iklim yang kita takutkan kemarin sudah menjadi kenyataan hari ini.
Di sisi yang lain, Indonesia juga berpacu dengan tekanan ekonomi global: menarik investasi, mempercepat pertumbuhan, dan memenuhi kebutuhan energi dunia, salah satunya lewat ekspansi pertambangan nikel di wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati seperti yang masih terjadi sekarang di Raja Ampat. Yap surga terakhir yang diagung agungkan di Indonesia, yang kabarnya telah dinobatkan sebagai “Best Dive Destination in the World” oleh Dive Magazine 2007, dan masuk ke dalam Coral Triangle yang diakui UNESCO. Dua krisis iklim dan ekonomi terlihat sedang beradu lari di jalur yang sama, tetapi menuju jurang yang berbeda. Alih-alih menjaga keberlangsungan hidup ekologis, sekarang justru sibuk memenuhi tuntutan pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Lalu haruskah kita memilih salah satunya? Atau justru bisakah kita menjaawab keduanya dengan solusi yang sama-sama hijau?.
Raja Ampat, surga terakhir kita yang terletak di kepulauan ujung barat daya Pulau Papua adalah salah satu wilayah paling kaya biodiversitas laut di dunia, tapi saat ini sedang menjadi sorotan publik karena ekspansi tambang nikel yang agresif. Deforestasi, sedimentasi laut, dan kerusakan terumbu karang diketahui meningkat sebab aktivitas tambang dan infrastruktur pendukungnya. Sangat disayangkan, padahal Raja Ampat menjadi penyumbang ekonomi lokal yang lestari dari sektor wisata dan perikanan tradisionalnya. Saat pertambangan mengambil alih, ironisnya bukan hanya alam yang rusak, tapi ada masyarakat adat yang terkorbankan sumber untuk mereka hidup.
Sebagian besar pabrik pengolahan nikel yang dikembangkan justru menggunakan batu bara, yang mana hal ini memperparah emisi karbon yang menjadi krisis iklim itu sendiri. Nah, di sinilah paradoksnya: saat berupaya untuk menyediakan bahan baku untuk transisi enegi global, ternyata justru mempercepat lingkungan domestik yang berakhir sudah.
Meski pemerintah telah menerapkan kebijakan seperti moratorium izin tambang baru dan evaluasi lingkungan, langkah ini belum menyelesaikan akar persoalan: absensinya kerangka ekonomi hijau terintegrasi dalam kebijakan industri ekstraktif. Respons kebijakan masih bersifat reaktif dan sektoral, bukan transformatif.
Padahal, ekonomi hijau merupakan solusi konkret—bukan sekadar jargon—yang menyinergikan pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Transisi ini berpotensi menciptakan jutaan lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan, ekowisata, pertanian organik, hingga restorasi ekosistem. Bahkan menurut World Resources Institute (WRI), ekonomi hijau dapat mendongkrak pertumbuhan PDB Indonesia hingga 6,3% per tahun hingga 2045 jika diimplementasikan secara serius.
Untuk mewujudkannya, diperlukan:
- Penghentian izin tambang di kawasan bernilai ekologis tinggi (seperti Raja Ampat).
- Insentif khusus bagi industri ramah lingkungan, termasuk ekowisata berbasis masyarakat.
- Hilirisasi nikel berbasis energi bersih, bukan PLTU batubara.
- Audit lingkungan wajib untuk perusahaan tambang dan penyesuaian rantai pasok dengan standar keberlanjutan global.
Krisis iklim dan ekonomi saling berkait; keduanya harus diselesaikan secara simultan melalui ekonomi hijau. Ini adalah peluang emas bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin transisi global—dengan syarat: keberanian mengambil langkah berbeda sekarang juga.
Papua bukan tanah kosong, tanah air kita pantas mendapatkan indahnya kembali.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI