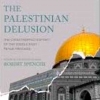Julukan "preman global" yang kerap disematkan pada Donald Trump mencerminkan gaya kepemimpinan unilateral, agresif, dan transaksional yang diusungnya selama menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat (2017--2021) dan (2025-sekarang). Dalam konteks politik internasional, Donald Trump cenderung menanggalkan prinsip multilateralisme yang telah lama menjadi pilar kebijakan luar negeri Amerika Serikat pasca-Perang Dunia II, dan menggantinya dengan pendekatan nasionalistik bertajuk America First "Make America Great Again."
Pendekatan ini tidak hanya menimbulkan ketegangan dengan sekutu-sekutu tradisional Amerika Serikat, tetapi juga mengacaukan tatanan global berbasis hukum internasional dan kerja sama multilateral. Salah satu contoh nyata adalah penarikan Amerika Serikat dari berbagai perjanjian penting, termasuk Perjanjian Paris tentang perubahan iklim, Kesepakatan Nuklir Iran, dan Organisasi Kesehatan Dunia, yang menunjukkan sikap oportunistik dan dominatif yang mencerminkan karakter "premanisme" dalam politik global.
Salah satu aspek paling menonjol dari kebijakan luar negeri Trump adalah penggunaan sanksi ekonomi dan tarif perdagangan sebagai alat tekanan terhadap negara-negara yang tidak sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat. Selama kepemimpinannya, Trump memicu perang dagang besar dengan Tiongkok, memberlakukan tarif miliaran dolar terhadap produk impor, dan memaksa negara lain untuk tunduk pada keinginannya melalui ancaman ekonomi.
Data dari Peterson Institute for International Economics menunjukkan bahwa pada akhir 2019, lebih dari 66% impor dari Tiongkok dikenakan tarif tambahan oleh pemerintah Trump, yang menyebabkan penurunan signifikan dalam perdagangan bilateral dan ketidakpastian pasar global. Di samping itu, pendekatan serupa digunakan terhadap Uni Eropa, Meksiko, dan Kanada, bahkan terhadap sekutu utama seperti Jepang dan Korea Selatan.
Kebijakan ini berlanjut di masa periode keduanya setelah kembali ke gedung putih. Pada 2 April 2025, Trump menetapkan kebijakan "Liberation Day" yang menerapkan tarif impor 10% secara universal terhadap seluruh negara, serta tarif tambahan "resiprokal" yang dikenakan kepada lebih dari 60 negara berdasarkan neraca dagang dan hambatan non-tarif mereka. Tarif tertinggi mencapai 145% atas impor dari Cina, yang menjadi negara paling terdampak.
Selain itu, beberapa negara dengan tarif eksesif mencakup Lesotho 50%, Kamboja 49%, Vietnam 46%, Sri Lanka 44%, Bangladesh 37%, Thailand 36%, dan Myanmar 44%. Secara regional, ASEAN turut merasakan peningkatan signifikan: Indonesia dan Malaysia masingmasing dikenai tarif resiprokal sebesar 32%, Thailand 36%, Kamboja 49%, dan Vietnam 46%. Negara-negara besar mitra dagang juga terpengaruh: Uni Eropa 20%, India 26%, Korea Selatan 25%, Jepang 24%, Swiss 31%, Taiwan 32%, Australia dan Inggris 10% tanpa tambahan resiprokal.
Kebijakan ini mencerminkan pendekatan Amerika Serikat yang secara simultan mengenakan tarif dasar yang luas sekaligus membedakan tingkatan berdasarkan neraca dan hambatan perdagangan, mendorong gelombang negara-negara berupaya merundingkan perjanjian untuk memperoleh pengecualian atau penurunan tarif. Sebagai ilustrasi, Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan awal dengan Inggris (tetap 10%), dan Vietnam (mengurangi usulan tarif 46% menjadi 20%), dan yang paling ironi pasca negosiasi Indonesia justru mengalami kenaikan tarif dari 32% menjadi 47%.
Secara keseluruhan, struktur tarif impor Amerika Serikat pada 2025 menandai eskalasi proteksionisme. Sebanyak lebih dari 60 negara terdampak langsung oleh tarif di atas ambang, dengan negara-negara yang memiliki neraca dagang defisit atau hambatan internal yang besar menjadi target utama. Kebijakan ini tidak hanya mempengaruhi arus perdagangan global dan rantai pasokan, tetapi juga menciptakan tekanan bagi negara terdampak untuk berunding atau menghadapi lonjakan biaya impor. Hal ini menggambarkan strategi tekanan khas preman jalanan yang mengandalkan intimidasi ekonomi ketimbang diplomasi yang setara.
Tidak hanya itu, Trump juga kerap meremehkan aliansi pertahanan dan sistem keamanan kolektif yang telah menjadi fondasi perdamaian internasional. Sikap skeptisnya terhadap NATO menjadi simbol dari erosi komitmen Amerika terhadap sekutu-sekutunya di Eropa. Trump menuduh negara-negara anggota NATO memanfaatkan Amerika Serikat dan mengancam akan menarik dukungan jika mereka tidak menaikkan kontribusi belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB masing-masing. Dalam sebuah pertemuan puncak NATO, ia bahkan mengeluarkan ultimatum bahwa Amerika Serikat akan "go it alone" jika permintaannya tidak dipenuhi. Sikap tersebut menciptakan ketegangan internal dalam aliansi trans-Atlantik dan memunculkan keraguan atas reliabilitas Amerika Serikat sebagai mitra keamanan.
Tidak hanya itu, rencana ekspansionis Donald Trump juga menimbulkan kontroversi global, terutama setelah ia secara terbuka menyatakan keinginannya untuk mencaplok Kanada, Greenland, Meksiko, serta mengambil alih kendali atas Terusan Panama. Dalam berbagai pidato dan konferensi pers, Trump menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut didorong oleh alasan strategis dan ekonomi, seperti keamanan nasional, ketidakseimbangan perdagangan, serta kekhawatiran atas pengaruh negara lain, khususnya China, di kawasan vital seperti Terusan Panama.