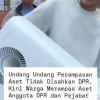Pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur, bukanlah keputusan kecil. Ia adalah proyek politik, ekonomi, sosial, bahkan psikologis terbesar dalam sejarah Indonesia modern setelah kemerdekaan. Pemerintah mengajukan berbagai alasan rasional: tekanan ekologis Jakarta yang semakin parah, ketimpangan pembangunan antar wilayah, beban ekonomi yang terkonsentrasi di Pulau Jawa, serta kebutuhan membangun pusat pemerintahan yang lebih "efisien" dan "berkelanjutan".
Jakarta saat ini menghadapi tantangan serius. Laju penurunan muka tanah mencapai sekitar 7,5--10 cm per tahun di beberapa wilayah pesisir utara, menjadikannya salah satu kota dengan risiko tenggelam tertinggi di dunia. Infrastruktur publik menua, lalu lintas macet, polusi udara ekstrem, dan kepadatan penduduk mencapai 11.000 jiwa/km. Pemerintah berargumen bahwa memindahkan ibu kota ke wilayah baru dapat mendukung pemerataan pembangunan, memperbaiki kualitas birokrasi, serta menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa.
Jika kita mencermati lebih dalam, pemindahan ini tidak hanya bermakna teknokratis. Ia juga menyimpan dimensi politik yang sangat kental. Seperti banyak kasus dalam sejarah negara lainBrasil dengan Braslia, Nigeria dengan Abuja, atau Kazakhstan dengan Astanapemindahan ibu kota sering kali menjadi cara rezim politik meninggalkan "jejak monumental" dan menandai era baru kekuasaan. Nusantara muncul bukan sekadar sebagai solusi atas permasalahan Jakarta, tetapi juga sebagai simbol politik pemerintahan yang ingin dikenang dalam sejarah sebagai pembawa "Indonesia baru".
Dalam politik, simbol selalu memainkan peran sentral. Pemindahan ibu kota tidak hanya memindahkan pusat administrasi negara, tetapi juga menggeser pusat makna dan representasi kekuasaan. Nusantara dirancang dengan arsitektur megah, konsep "green city", dan teknologi canggih. Semua ini membentuk citra bahwa negara sedang melangkah menuju masa depan modern, inklusif, dan berkelanjutan. Namun, simbolisme ini juga dapat dibaca sebagai upaya penguasa untuk meneguhkan legitimasi politiknya di tengah tantangan demokrasi, polarisasi politik, dan ketidakpastian global.
Proyek Nusantara diluncurkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, menjelang akhir periode kepemimpinannya. Banyak pengamat menilai proyek ini sebagai "legacy project" sebuah warisan politik yang akan terus mengingatkan publik pada kepemimpinan Jokowi. Secara simbolik, Nusantara mencerminkan cita-cita besar keluar dari bayang-bayang kolonialisme (Jakarta yang berakar pada Batavia), menuju wajah Indonesia yang lebih mandiri dan Indonesia-sentris. Namun secara politik, simbol ini juga dapat berfungsi sebagai "monumen kekuasaan", yang digunakan untuk menandai pergeseran pusat kontrol dan kepentingan ekonomi.
Untuk memahami fenomena ini lebih dalam, kita dapat menggunakan Teori Legitimitas Kekuasaan dalam psikologi politik. Teori ini berangkat dari pemikiran bahwa kekuasaan tidak hanya bertumpu pada kontrol fisik atau militer, tetapi juga pada penerimaan psikologis masyarakat terhadap otoritas tersebut. Pemerintah, untuk mempertahankan legitimasi, perlu menciptakan simbol-simbol yang kuat dan meyakinkan publik bahwa mereka memegang kendali dan arah yang benar.
Pemindahan ibu kota dapat dipahami sebagai bentuk symbolic politics, di mana simbol (dalam hal ini kota baru) digunakan untuk mengirim pesan psikologis kepada masyarakat. Pesannya adalah: "Kami sedang membangun masa depan yang lebih baik." Simbol ini menciptakan efek psikologis tertentu: rasa bangga, optimisme kolektif, dan persepsi bahwa negara bergerak maju. Dalam konteks politik modern, efek simbolik seperti ini sering lebih kuat daripada argumen rasional, terutama ketika masyarakat haus akan perubahan dan narasi besar.
Teori ini juga memperingatkan bahwa simbol hanya akan efektif selama realitas mendukungnya. Jika simbol besar seperti Nusantara tidak diikuti dengan perubahan nyata, maka publik dapat mengalami disonansi kognitif ketegangan antara ekspektasi tinggi dan realitas yang mengecewakan. Ketegangan ini, bila dibiarkan, bisa berbalik menjadi ketidakpercayaan terhadap institusi negara.
Dalam skenario ideal, Nusantara dapat menjadi motor transformasi nasional. Infrastruktur pemerintahan yang modern dapat mempercepat efisiensi birokrasi. Lokasinya yang strategis di tengah kepulauan Indonesia bisa memperkuat konektivitas antar wilayah. Pembangunan ibu kota baru bisa memicu pertumbuhan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja baru, serta menggeser fokus pembangunan dari Jawa ke luar Jawa, menciptakan keseimbangan nasional.
Namun, skenario ini sangat bergantung pada konsistensi kebijakan lintas pemerintahan, transparansi pembiayaan, dan partisipasi publik. Proyek sebesar ini membutuhkan waktu puluhan tahun, bukan sekadar satu periode pemerintahan. Jika rezim berikutnya tidak memiliki komitmen yang sama, Nusantara berpotensi menjadi kota "setengah jadi" yang membebani anggaran negara tanpa manfaat nyata.
Sebaliknya, dalam skenario buruk, Nusantara bisa menjadi bencana politik dan ekonomi. Biaya pembangunan yang diperkirakan mencapai lebih dari 400 triliun rupiah, dengan skema pembiayaan publik-swasta yang belum sepenuhnya jelas, menimbulkan risiko besar. Pemindahan birokrasi tanpa pemindahan pusat ekonomi dapat menimbulkan dualisme antara Jakarta sebagai pusat bisnis dan Nusantara sebagai pusat administrasi. Hal ini dapat memperlemah koordinasi nasional, meningkatkan biaya transaksi politik, dan memperbesar kesenjangan wilayah.
Dari perspektif psikologi sosial-politik, simbol besar seperti Nusantara dapat menciptakan euforia politik jangka pendek. Masyarakat merasakan kebanggaan, media dipenuhi narasi positif, dan elite politik mendapatkan legitimasi baru. Euforia ini tidak bertahan lama jika tidak ditopang oleh pengalaman nyata. Ketika masyarakat mulai menyadari bahwa hidup mereka tidak berubah secara signifikan, bahwa pusat ekonomi masih tetap di Jawa, dan bahwa pembangunan Nusantara menguras APBN tanpa manfaat langsung, maka muncul disonansi kognitif.
Disonansi ini dapat berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap institusi negara. Masyarakat mulai mempertanyakan motif di balik proyek tersebut apakah ini benar untuk rakyat, atau sekadar proyek prestise elite? Dalam kondisi politik yang sudah terpolarisasi, kekecewaan publik terhadap simbol besar dapat menjadi bahan bakar bagi gerakan politik oposisi, delegitimasi pemerintah, atau bahkan konflik sosial.
Pemindahan ibu kota ke Nusantara adalah pertaruhan politik besar. Ia memiliki potensi luar biasa untuk mendistribusikan pembangunan secara lebih adil dan mendorong transformasi birokrasi. Namun, proyek sebesar ini tidak bisa hanya bertumpu pada simbolisme kekuasaan. Tanpa strategi implementasi yang matang, tanpa kejelasan pembiayaan, tanpa partisipasi publik yang bermakna, Nusantara berisiko menjadi monumen politik yang indah di atas kertas tetapi kosong dalam kenyataan.
Dalam kerangka Teori Legitimitas Kekuasaan, simbol hanya akan bertahan jika masyarakat merasakan manfaatnya secara nyata. Nusantara bisa menjadi simbol kemajuan atau justru simbol kegagalan elite dalam memahami psikologi publik dan realitas politik. Sejarah akan mencatat keputusan ini, bukan hanya dari arsitektur kota yang berdiri, tetapi dari sejauh mana keputusan ini benar-benar menjawab kebutuhan rakyat Indonesia.
Referensi
Tyler, T. R. (2006). Why People Obey the Law. Princeton University Press.
Easton, D. (1975). "A Re-assessment of the Concept of Political Support." British Journal of Political Science, 5(4), 435--457.
Edelman, M. (1964). The Symbolic Uses of Politics. University of Illinois Press.
Data Bappenas & Kementerian PUPR tentang IKN (2023--2025).
Laporan World Bank tentang Urbanisasi Indonesia (2022).
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI