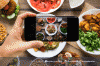Beberapa waktu terakhir, media sosial diramaikan oleh sosok Putri Padang atau yang dikenal juga dengan nama Iput---yang viral karena jualan Roti Sweety, roti sederhana dengan topping meses yang dijual seharga Rp6.000 per potong. Secara tampilan, tidak ada yang istimewa dari produk ini. Namun yang membuat namanya melejit justru bukan rotinya, melainkan cara ia menjualnya. Putri dikenal karena gaya bicaranya yang emosional, seringkali meledak-ledak dan terkesan marah-marah kepada para pembeli. Anehnya, justru karena itu, warungnya diserbu. Banyak orang datang bukan karena lapar, melainkan karena ingin merasakan sensasi "dibentak Iput" lalu merekam momen tersebut untuk konten TikTok atau Instagram. Fenomena ini dengan cepat menjadi viral. Banyak pengguna media sosial menyoroti harga roti yang dianggap tidak masuk akal, sementara yang lain justru membela Putri Padang karena menganggapnya sebagai contoh kreatif dalam pemasaran. Namun di balik perdebatan antara pro dan kontra, terselip sebuah pertanyaan yang lebih dalam: kenapa semakin banyak orang rela mengeluarkan uang bukan untuk membeli makanan, tetapi untuk pengalaman dibentak dan ikut viral? Kenapa banyak orang justru merasa bangga setelah "dipermalukan" di depan kamera? Hal ini mencerminkan perubahan besar dalam cara masyarakat kita memandang interaksi sosial, konsumsi, dan status. Di era digital, terutama di kalangan generasi muda, nilai sebuah pengalaman bukan lagi diukur dari kenyamanan atau kualitas produk, tapi dari seberapa besar peluang pengalaman itu bisa menjadi konten. Konten menjadi komoditas. Bahkan momen dimarahi sekalipun, jika berhasil menarik simpati atau perhatian penonton, dianggap sebagai hal yang berharga.
Dalam konteks sosiologi, hal ini bisa dilihat sebagai bentuk dari perubahan perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan media sosial. Dahulu, transaksi jual beli berlangsung secara pribadi, sederhana, dan tujuannya jelas: membeli kebutuhan. Sekarang, transaksi tersebut berubah menjadi tontonan. Pembeli tidak lagi sekadar membeli barang, tapi juga membeli kesempatan untuk tampil di depan kamera, mendapatkan views, komentar, dan followers. Bahkan beberapa di antaranya sengaja membuat drama tambahan supaya video mereka makin menarik dan menembus algoritma. Kita sedang hidup di zaman di mana sensasi menjadi alat tukar baru. Apa pun bisa viral selama bisa menyentuh emosi orang lain: entah lucu, menyedihkan, menyentuh, atau bahkan marah-marah seperti yang dilakukan oleh Putri Padang. Emosi, dalam hal ini, telah menjadi barang dagangan. Apa yang dijual oleh Putri bukan hanya roti, tapi adalah pengalaman emosional. Penonton dibuat merasa penasaran, lalu terhibur, lalu ingin mencoba sendiri. Inilah bentuk baru dari komodifikasi: di mana sesuatu yang sebelumnya bersifat pribadi dan emosional, kini bisa dijual dan dibeli. Sosiolog klasik Emile Durkheim menyatakan bahwa fenomena sosial adalah fakta sosial, yaitu cara bertindak, berpikir, dan merasa yang berada di luar individu namun memengaruhi perilaku mereka. Dalam kasus ini, budaya viral, pansos, dan konsumsi konten digital adalah bentuk fakta sosial baru yang menekan individu untuk ikut serta. Ketika masyarakat secara kolektif menganggap bahwa menjadi viral adalah hal yang prestisius, maka individu akan merasa terdorong untuk berpartisipasi---bahkan jika itu berarti membeli roti mahal dan dimarahi hanya demi konten.
Durkheim juga menekankan pentingnya solidaritas sosial. Fenomena Putri Padang bisa dilihat sebagai bentuk solidaritas mekanik, di mana orang-orang terhubung bukan karena kebutuhan ekonomi, tapi karena kesamaan minat dalam budaya populer. Mereka berkumpul, antre, dan merekam pengalaman yang sama untuk dibagikan. Meski tampak sepele, ini memperlihatkan bagaimana masyarakat membentuk kesatuan melalui budaya digital. Yang menarik, bukan hanya Putri Padang yang mengambil keuntungan dari viralitas ini. Para pembeli juga ikut mendapatkan "cuan sosial"---yakni kenaikan popularitas di media sosial karena video mereka bersama Putri Padang. Ini adalah bentuk lain dari panjat sosial atau pansos, di mana seseorang memanfaatkan sosok yang sedang viral agar ikut terkena pantulan popularitas. Bahkan banyak pembeli yang datang bukan karena penasaran dengan rasa roti, tapi karena ingin masuk konten atau mengejar view. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana struktur sosial dan cara orang membangun status kini telah berubah. Jika dulu status sosial ditentukan oleh jabatan, kekayaan, atau pendidikan, kini media sosial menciptakan status baru: viralitas. Siapa yang paling sering muncul di timeline orang lain, siapa yang punya engagement tinggi, siapa yang punya konten paling dramatis mereka dianggap punya posisi sosial lebih tinggi di dunia maya, meski belum tentu di dunia nyata. Budaya seperti ini bukan hanya terjadi di level masyarakat bawah, tapi juga menular ke kalangan pelajar dan mahasiswa. Banyak dari kita yang sekarang menganggap konten sebagai prioritas. Pergi ke mana pun, bukan lagi tentang menikmati momen, tapi tentang "apa yang bisa direkam?" dan "bagaimana tampilannya di feed?". Logika semacam ini tanpa sadar membentuk generasi yang lebih peduli pada persepsi digital dibandingkan kenyataan.
Di sinilah pentingnya peran pendidikan untuk hadir sebagai penyeimbang. Fenomena viral Putri Padang harusnya bisa menjadi bahan refleksi, terutama dalam dunia pendidikan formal. Apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Pertama, bahwa masyarakat kita membutuhkan pendidikan literasi digital yang lebih kuat. Banyak orang---termasuk anak muda---masih belum memahami bahwa tidak semua yang viral itu sehat, dan tidak semua konten itu mendidik. Perlu diajarkan bahwa media sosial bukan hanya tempat hiburan, tetapi juga ruang interaksi yang memiliki konsekuensi sosial. Pendidikan juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Sekolah dan kampus tidak bisa terus bicara soal teori komunikasi konvensional atau etika dalam ruang tertutup, sementara dunia nyata anak-anak muda hari ini adalah TikTok, YouTube Shorts, dan Instagram Reels. Mereka butuh bimbingan tentang bagaimana menciptakan konten yang kreatif tapi tetap beretika, bagaimana membangun personal branding tanpa menjatuhkan orang lain, dan bagaimana menjadi "dilihat" tanpa harus menjual emosi palsu. Pendidikan karakter juga harus berkembang. Kita tidak bisa hanya menekankan sopan santun di dunia nyata tapi membiarkan kebebasan penuh di dunia maya. Perilaku seperti memaki pelanggan, menghina pembeli, atau sengaja bersikap kasar demi lucu-lucuan adalah bentuk penyimpangan norma interaksi sosial. Jika ini terus dianggap wajar karena "demi konten", maka akan sulit membentuk generasi yang memahami batas antara hiburan dan pelecehan sosial. Namun kita juga harus melihat sisi lain dari fenomena ini. Putri Padang bisa menjadi contoh nyata bagaimana seseorang dari latar belakang sederhana bisa memanfaatkan media sosial untuk membangun usahanya sendiri.
Dalam situasi ekonomi yang sulit, banyak orang tidak punya pilihan selain "jualan diri", bukan dalam arti harfiah, tapi menjual personalitas, karakter, atau bahkan sisi dramatisnya. Maka, pendidikan juga harus mampu mengarahkan potensi kreatif ini ke arah yang lebih positif. Misalnya, dalam pelajaran kewirausahaan, kisah Putri Padang bisa dijadikan bahan diskusi: apakah strategi seperti itu etis? Apakah kita harus meniru gaya marah-marah demi menarik pembeli? Apa yang bisa kita pelajari dari viralitas yang dibangun dengan cara seperti itu? Dengan membahasnya secara terbuka, pendidikan bisa membantu anak muda membentuk prinsip yang kuat sejak awal: bahwa sukses itu bukan hanya soal viral, tapi juga tentang nilai yang kita bawa dalam prosesnya. Fenomena ini juga menyadarkan kita bahwa masyarakat digital bukan hanya tempat untuk eksis, tapi juga ruang ekonomi baru. Banyak orang mencari rejeki dari konten, baik sebagai kreator maupun objek. Tapi jika tidak diiringi dengan kesadaran etis, ruang ini bisa menjadi medan penuh manipulasi, adu nasib, dan eksploitasi emosional. Maka, pendidikan harus hadir sebagai pagar moral yang kuat agar masyarakat tidak mudah hanyut. Akhirnya, drama roti 6 ribu bukan cuma soal harga roti atau gaya bicara penjualnya. Ini adalah simbol dari perubahan besar dalam masyarakat kita. Tentang bagaimana interaksi sosial dipertontonkan, tentang bagaimana orang menjadikan diri mereka sebagai konten, dan tentang bagaimana nilai-nilai dalam kehidupan mengalami pergeseran. Di dunia yang serba digital ini, kadang yang lebih mahal dari produk adalah kesempatan untuk tampil. Dan jika dunia pendidikan tidak ikut berubah dan menyesuaikan diri, maka akan semakin sulit untuk mendidik generasi yang bisa berpikir kritis dan punya prinsip dalam menghadapi banjir sensasi dan informasi. Kita tidak bisa melarang orang untuk viral, tapi kita bisa mengajarkan bagaimana menjadi viral dengan cara yang tetap bermartabat.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI