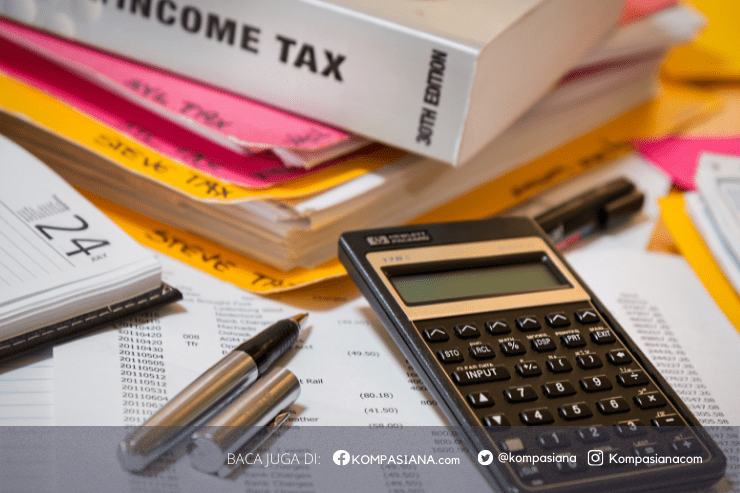Dalam beberapa tahun terakhir, istilah Paylater seolah menjadi mantra baru di kalangan masyarakat muda. Fitur ini hadir di hampir semua platform digital mulai dari marketplace, aplikasi transportasi, hingga layanan pesan-antar makanan. Dengan sekali klik, siapa pun bisa membeli barang impian tanpa harus menunggu gajian. Di permukaan, ini terlihat sebagai inovasi finansial yang mempermudah hidup. Namun di balik kemudahan itu, tersimpan dinamika perilaku ekonomi yang menarik, bahkan berisiko.
Bagi generasi muda, terutama Gen Z dan milenial awal, Paylater memberi sensasi instan yang sangat sesuai dengan ritme hidup cepat dan budaya digital mereka. Keputusan pembelian kini tidak lagi didasarkan pada kemampuan finansial saat ini, melainkan pada ekspektasi kemampuan membayar di masa depan. Dalam istilah ekonomi perilaku, fenomena ini menggambarkan terjadinya “present bias” kecenderungan manusia untuk lebih menghargai kepuasan saat ini dibandingkan konsekuensi di masa mendatang.
Dari sisi bisnis, Paylater jelas menguntungkan. Platform e-commerce mencatat peningkatan transaksi signifikan karena konsumen merasa lebih “mampu” membeli. Lembaga keuangan digital dan fintech pun menikmati pertumbuhan pengguna, dengan margin bunga atau biaya layanan sebagai sumber profit. Namun, dari sisi individu, efeknya tidak selalu positif. Banyak pengguna muda yang terjebak pada pola konsumsi berlebihan membeli bukan karena butuh, melainkan karena bisa.
Akibatnya, muncul fenomena baru yang bisa disebut “ilusi likuiditas”: perasaan seolah memiliki uang lebih padahal yang digunakan adalah utang. Ketika tagihan mulai menumpuk dan jatuh tempo datang bersamaan, barulah muncul kesadaran bahwa gaya hidup digital ini membawa konsekuensi nyata. Tidak sedikit anak muda yang akhirnya harus menambal lubang keuangan dengan utang baru — sebuah lingkaran yang sulit diputus.
Meski demikian, menyalahkan Paylater sepenuhnya tentu tidak adil. Inovasi finansial digital ini pada dasarnya lahir untuk memberi akses, fleksibilitas, dan efisiensi dalam transaksi. Masalah muncul ketika literasi keuangan tidak sejalan dengan kemajuan teknologi. Banyak pengguna muda yang belum memahami cara mengelola arus kas pribadi, belum membedakan antara kebutuhan dan keinginan, atau belum menghitung beban bunga yang tersembunyi di balik cicilan.
Pemerintah dan lembaga keuangan sebenarnya telah berupaya menekan risiko dengan regulasi dan edukasi. Namun, tanggung jawab terbesar tetap ada pada individu. Di era digital ini, melek finansial bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Generasi muda perlu belajar bahwa kemerdekaan finansial bukan diukur dari kemampuan berutang, tetapi dari kemampuan menunda keinginan dan mengatur prioritas.
Paylater memang memudahkan, tetapi kemudahan itu bisa menjadi jebakan jika tidak disertai kesadaran finansial. Mungkin benar bahwa hidup di zaman sekarang sulit lepas dari utang digital, tetapi setidaknya kita masih punya kendali atas pilihan kita sendiri. Karena pada akhirnya, kemajuan teknologi seharusnya membuat kita lebih bijak — bukan lebih boros.
"Paylater mungkin membuat hidup terasa ringan hari ini, tapi ingat yang ringan di depan sering kali berat di belakang.”
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI


![[media] Menyalakan Harapan di Tengah Badai, Bersama Media yang Berintegritas](https://assets-a2.kompasiana.com/items/album/2025/09/01/mhsiswa2-68b5a080c925c4498c7d9902.jpg?t=t&v=100&x=100&info=meta_related)