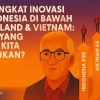Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul serta menjadi indikator kemajuan suatu bangsa. Di Indonesia, pendidikan telah mengalami berbagai reformasi dan pembaruan, namun sejumlah persoalan mendasar masih menghambat terwujudnya sistem pendidikan yang merata dan berkualitas. Problematika yang muncul tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan sistemik, mencakup ketimpangan akses pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pendidik, kurikulum yang belum kontekstual, serta berbagai tantangan sosial-ekonomi yang turut memperparah kondisi.
Salah satu permasalahan utama adalah ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Banyak anak di daerah terpencil masih kesulitan mengakses pendidikan karena keterbatasan infrastruktur, minimnya fasilitas, dan sulitnya transportasi. Hal ini menyebabkan rendahnya angka partisipasi sekolah di daerah-daerah tersebut dibandingkan wilayah perkotaan. Data dari BPS (2023) menunjukkan bahwa ketimpangan tersebut masih menjadi tantangan serius dalam upaya pemerataan pendidikan nasional.
Selain akses, kualitas tenaga pendidik juga masih menjadi sorotan. Banyak guru yang belum memenuhi standar kompetensi profesional, baik dari sisi penguasaan materi maupun metodologi pembelajaran. Laporan dari Kemendikbudristek (2022) menunjukkan bahwa hasil Uji Kompetensi Guru masih rendah, terutama di wilayah terpencil. Ketimpangan distribusi guru berkualitas juga turut memperparah kondisi ini. Akibatnya, kualitas pembelajaran antarwilayah menjadi tidak seimbang dan berdampak pada rendahnya capaian belajar siswa.
Permasalahan lain yang tak kalah penting adalah kurikulum yang dinilai terlalu padat, teoritis, dan kurang kontekstual. Kurikulum nasional masih berorientasi pada hafalan dan ujian, sehingga kurang memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, dan keterampilan abad 21. UNESCO (2021) menekankan pentingnya pengembangan kurikulum yang berakar pada konteks lokal dan global, serta mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Ketika kurikulum gagal menjawab kebutuhan zaman, maka lulusan pendidikan akan kesulitan menghadapi tantangan dunia nyata.
Dampak dari berbagai masalah di atas semakin diperburuk oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Kemiskinan, pernikahan dini, dan tuntutan ekonomi keluarga seringkali memaksa anak-anak putus sekolah. UNICEF (2022) mencatat bahwa anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah rentan mengalami hambatan dalam pendidikan, baik dari segi partisipasi maupun keberlanjutan. Selain itu, rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan juga menjadi penghalang besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung.
Tak hanya itu, persoalan literasi dan numerasi siswa Indonesia juga mengemuka. Berdasarkan hasil survei PISA (2018), Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara OECD dalam bidang membaca, matematika, dan sains. Hal ini menunjukkan lemahnya fondasi pendidikan dasar yang semestinya menjadi fokus utama sistem pendidikan. Kurangnya bahan bacaan bermutu dan pendekatan pengajaran yang monoton membuat siswa kesulitan membangun kemampuan dasar yang penting dalam kehidupan sehari-hari.
Permasalahan lain yang mengemuka adalah kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, terutama di daerah 3T. Meski pemerintah telah menggulirkan program digitalisasi sekolah, implementasinya masih timpang. Banyak sekolah yang belum memiliki akses internet atau perangkat yang memadai, bahkan guru-guru pun belum sepenuhnya melek teknologi. Kondisi ini menghambat pemanfaatan pembelajaran berbasis digital yang sangat dibutuhkan pasca pandemi.
Di sisi lain, kebijakan pendidikan di Indonesia masih sering berubah tanpa evaluasi yang matang. Perubahan kurikulum, sistem zonasi, dan kebijakan evaluasi seringkali membingungkan satuan pendidikan. Beban administratif bagi guru pun meningkat akibat perubahan kebijakan yang tidak diiringi dengan dukungan teknis dan pelatihan memadai. Puslitjakdik (2021) menekankan bahwa setiap kebijakan seharusnya melibatkan para pemangku kepentingan di lapangan, termasuk guru dan komunitas lokal.
Faktor kesejahteraan guru juga menjadi isu penting yang belum tuntas. Meskipun pemerintah telah memberikan tunjangan profesi melalui program sertifikasi, distribusinya masih belum merata. Banyak guru honorer yang digaji di bawah standar, terutama di pelosok negeri. Ketimpangan kesejahteraan ini berdampak pada motivasi dan kinerja guru, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap mutu pendidikan itu sendiri.
Melihat kompleksitas permasalahan pendidikan di Indonesia, tentu dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Upaya perbaikan tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus melibatkan sinergi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas lokal, hingga peran aktif orang tua. Model kolaborasi seperti Public-Private Partnership (PPP) perlu didorong untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas.
Kesimpulannya, pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan yang multidimensi dan saling berkaitan. Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan strategi terpadu yang mencakup reformasi kurikulum, peningkatan kompetensi guru, pembangunan infrastruktur pendidikan, dan penguatan peran masyarakat dalam pendidikan. Dengan komitmen bersama dan pendekatan yang holistik, harapan menuju sistem pendidikan yang adil, berkualitas, dan relevan bagi masa depan bangsa dapat diwujudkan.