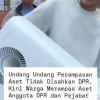Seorang ayah di Parepare yang setiap hari berkeliling membawa map lusuh, melamar kerja ke sana kemari. Ia pulang dengan wajah letih, istrinya hanya bisa menatap kosong sambil menghitung sisa uang belanja. Di layar ponselnya, tiba-tiba muncul berita: pemerintah menyimpan Rp425 triliun "mengendap" di Bank Indonesia. Lalu pertanyaan itu muncul: Mengapa ada uang sebesar itu yang tidak mengalir ke kehidupan nyata, sementara banyak keluarga berjuang sekadar untuk bertahan hidup?
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut dana raksasa itu salah satu penyebab sulitnya masyarakat mencari kerja. "Sistem finansial kita agak kering, makanya ekonominya melambat," katanya di DPR. Narasi ini memicu pro dan kontra. Sebagian pihak melihat langkah pemerintah menarik Rp200 triliun ke bank umum sebagai koreksi yang berani. Namun, sebagian lain menilai pernyataan itu terlalu bombastis, karena menyimpan dana di BI sejatinya adalah hal normal dalam sistem kas negara.
Kita sering bicara triliunan rupiah seakan itu hanya angka di kertas. Padahal di baliknya ada jutaan orang seperti Ibu Sari, pedagang kecil di Makassar yang tak bisa memperluas warungnya karena bank menolak pinjaman: "Modal ada, Bu, tapi kami lagi hati-hati," kata petugas bank. Baginya, Rp425 triliun yang diam itu bukan soal makroekonomi. Itu soal harapannya yang tertunda, soal mimpi anaknya masuk sekolah yang lebih baik.
Apakah benar uang yang "ngendap" ini biang kerok utama sulitnya mencari kerja? Di atas kertas, logika Menkeu masuk akal: jika dana pemerintah terlalu lama parkir di BI, likuiditas perbankan seret, kredit susah mengalir, dan ekonomi pun lambat. Tetapi faktanya, problem ketenagakerjaan tidak sesederhana itu. Bank bisa saja tetap menahan penyaluran kredit karena khawatir risiko macet, sementara pengusaha pun enggan meminjam bila prospek usaha suram. Jadi, saldo kas di BI hanyalah salah satu faktor, bukan satu-satunya penentu.
Fenomena ini bukan khas Indonesia. India, Brasil, hingga negara-negara Eropa juga berhadapan dengan dilema yang sama: bagaimana menjaga saldo kas negara tetap aman sekaligus memastikan likuiditas perbankan mencukupi. Bahkan IMF pernah mengingatkan, penempatan dana pemerintah secara agresif di bank umum bisa memicu inflasi dan moral hazard. Maka, pertanyaannya bukan sekadar "uang tidur atau tidak," melainkan bagaimana memastikan uang itu betul-betul bekerja untuk rakyat.
Retorika bombastis memang punya daya tarik. Angka Rp425 triliun terdengar seperti harta karun yang terbengkalai. Padahal sesungguhnya itu hanyalah catatan saldo kas negara, wajar adanya. Yang luar biasa hanyalah porsinya yang dianggap terlalu besar dan terlalu lama mengendap. Di sinilah publik harus berhati-hati: jangan sampai narasi besar sekadar jadi alat politik untuk memberi kesan ada "kesalahan lama" yang perlu dikoreksi. Apa yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan korektif itu dijalankan secara nyata, bukan hanya diucapkan di ruang rapat.
Masyarakat tidak butuh angka fantastis, mereka butuh kepastian esok masih bisa bekerja dan makan. Jika Rp200 triliun benar-benar akan dialirkan ke bank, publik berhak tahu: bank mana yang menerima, berapa kredit yang disalurkan, siapa penerima manfaat utamanya. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci. Retorika bombastis boleh saja jadi alat komunikasi, tapi tanpa aksi nyata, ia hanya jadi headline sementara. Uang negara harus benar-benar berubah menjadi lapangan kerja, harapan baru, dan kepercayaan publik yang tumbuh kembali.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI