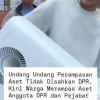Penghancuran sistematis dan terencana terhadap masyarakat etnis Rohingya di Myanmar telah menjadi salah satu krisis kemanusiaan yang paling parah dalam abad ke-21. Persekusi dan pembantaian sistematis yang disulut oleh api nasionalisme ekstrim dan islamofobia yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Myanmar. Sejak tahun 2016, ratusan, bahkan ribuan dari masyarakat etnis Rohingya terpaksa kabur dari tempat tinggalnya dan lari ke lautan demi keselamatan mereka. (Freeman, 2017) Data dari UNHCR menunjukkan bahwa ada setidaknya ada lebih dari 1,3 juta masyarakat Rohingya yang terlantar di Myanmar. (UNHCR, 2024) Hilangnya tempat tinggal dan operasi militer yang terus berlanjut, para masyarakat etnis Rohingya tidak memiliki tujuan lain selain mencari keamanan di tanah yang asing. Dengan kapal yang kualitasnya tidak begitu baik, para pengungsi ini mempertaruhkan nyawanya demi merasakan keamanan dan kenyamanan. (Al Jazeera, 2025)
Dengan letak geografis Indonesia yang cukup dekat dan demografinya yang setidaknya memiliki banyak kesamaan dengan masyarakat etnis Rohingya, Indonesia menjadi salah satu opsi terbaik mereka. Data dari UNHCR menunjukkan bahwa lebih dari 1.200 pengungsi Rohingya tiba di Indonesia pada akhir 2023, dengan 300 di antaranya datang hanya dalam waktu satu minggu. (Sulistya, 2024) Ironisnya, dengan segala kesamaan yang dimiliki masyarakat Indonesia secara demografis, sebagian masyarakat Indonesia justru merespons dengan sentimen negatif terhadap masyarakat etnis Rohingya. Di media sosial, fenomena ini terlihat jelas, bagaimana kemudian muncul retorika-retorika diskriminatif terhadap masyarakat etnis Rohingya yang dianggap memiliki perilaku buruk. Fenomena xenofobia terhadap masyarakat etnis Rohingya yang tiba-tiba melonjak menunjukkan sebuah pola yang tidak organik, dalam kata lain fenomena ini menunjukkan adanya upaya sistematis dalam membentuk opini publik yang xenofobik. (BBC News, 2023)
Suatu hal yang sangat janggal adalah topik tersebut kian meningkat dan mendapatkan jutaan engagement sebelum diadakannya Pemilihan Presiden 2024, jika dilihat secara kasar hal itu merupakan hal yang normal, karena sebuah topik tidak akan mungkin terus menerus mendapatkan engagement yang statis, melainkan dinamis. (Narasi Newsroom, 2024) Tetapi, suatu hal yang janggal adalah hilangnya atau matinya topik tersebut setelah Pemilihan Presiden 2024, meskipun pengungsi etnis Rohingya tetap terus mendarat di wilayah administratif Indonesia. Sebuah penemuan yang juga menarik perhatian adalah bagaimana akun-akun besar yang menyebar sentimen negatif terhadap masyarakat etnis Rohingya, kemudian selalu menjadi sponsor akan salah satu kandidat Pemilihan Presiden. Seakan-akan ada kepentingan elektoral di balik narasi diskriminatif dan xenofobik yang diarahkan kepada pengungsi etnis Rohingya. (BBC News, 2023)
Sebelum mengenal fenomena ini lebih dalam, kita harus mengerti beberapa terminologi yang kerap muncul di dalam topik ini, seperti ujaran kebencian, disinformasi, dan xenofobia yang diiringi retorika anti orang asing. Ujaran kebencian atau dalam bahasa Inggris hatespeech merujuk pada bentuk komunikasi yang menyerang kelompok berdasarkan identitas mereka, baik etnis, agama, ras, atau kewarganegaraan. Di era media sosial, ujaran kebencian dapat tersebar luas melalui algoritma yang memperkuat interaksi, terutama jika dibungkus dengan narasi yang emosional. Menurut Aliansi Jurnalis Independen (2025), setidaknya 479,350 ujaran kebencian ditemukan di platform media sosial besar, seperti TikTok dan X yang memiliki hubungan dengan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah.
Ujaran kebencian tersebut juga kerap diiringi oleh disinformasi. Disinformasi dapat dipahami sebagai penyebaran informasi salah secara sengaja untuk tujuan tertentu, dalam kasus ini untuk mendehumanisasi dan mendemonisasi pengungsi etnis Rohingya. Disinformasi yang konsisten, terarah, dan terorganisir menciptakan suatu echo chamber dalam lingkungan digital di mana individu hanya terpapar pada pandangan yang serupa dengan keyakinan mereka sendiri. (United Nations, 2023) Ujaran kebencian tersebut kemudian juga membangun xenofobia. Xenofobia dapat dipahami sebagai suatu ketakutan atau kebencian terhadap orang asing atau pihak luar. Fenomena penolakan terhadap orang asing juga diperburuk dengan adanya echo chamber di media sosial, seseorang yang tidak terlalu kritis dalam berfikir akan terus mendapatkan disinformasi dan kemudian membangun sebuah pemikiran diskriminatif dikarenakan paparan disinformasi dan ujaran kebencian yang terus terlihat. (Criss et al., 2021) Retorika semacam ini kerap dibalut dengan narasi nasionalisme, misalnya dengan dalih bahwa negara harus mengutamakan kepentingan rakyat sendiri sebelum membantu orang asing. Dalam konteks tersebut, pengungsi tidak lagi dilihat sebagai korban krisis kemanusiaan, melainkan sebagai simbol dari kebijakan globalisasi yang dianggap gagal dan merugikan rakyat kecil. (United Nations, 2018) Akibatnya, sentimen anti-pengungsi dapat menimbulkan ilusi bahwa menolak kehadiran pengungsi adalah bentuk perjuangan untuk keadilan sosial, padahal yang terjadi justru pengaburan terhadap empati dan simpati, serta normalisasi diskriminasi.
Produksi dan Penyebaran Sentimen Anti-Rohingya di Media Sosial
Narasi diskriminatif terhadap pengungsi etnis Rohingya kemudian disebarkan dan diproduksi melalui sosial media. Melalui platform seperti TikTok dan X (sebelumnya Twitter), berbagai narasi negatif terhadap pengungsi Rohingya dibangun secara terorganisir dan masif. Akun-akun anonim dan fanbase besar seperti @sosmedkeras dan @kegblgnunfaedh, yang memiliki ratusan ribu, bahkan jutaan pengikut, secara aktif menyebarkan konten yang mendemonisasi dan mendehumanisasi pengungsi etnis Rohingya. (Narasi Newsroom, 2024) Akun-akun tersebut secara aktif menyebarkan narasi bahwa pengungsi etnis Rohingya adalah ancaman terhadap stabilitas sosial dan nasional di Indonesia. Selain itu, disinformasi juga menyasar lembaga internasional seperti UNHCR yang dituduh terlibat dalam jaringan perdagangan manusia. Taktik semacam ini efektif dalam membentuk persepsi publik, terutama di tengah masyarakat yang kurang mendapatkan informasi akurat mengenai status dan kondisi pengungsi. Penyebaran konten ini diperkuat oleh influencer digital seperti Adi Syahreza dan Ali Hamza, yang melalui video bernarasi diskriminatif terhadap pengungsi etnis Rohingya yang telah menjangkau jutaan pengguna dan menciptakan sentimen negatif dalam skala luas. (BBC News, 2023)
Bukti Pola Terorganisir dan Tidak Organik
Indikasi bahwa sentimen anti-Rohingya tidak tumbuh secara alami melainkan disebarkan secara terorganisir terlihat jelas dalam analisis data digital. Narasi Newsroom (2024) menemukan bahwa dari lebih dari 54.000 komentar di akun Instagram PBB, 91% berisi ujaran kebencian terhadap pengungsi Rohingya. Pola berkomentar ini mencurigakan karena banyak menggunakan gaya bahasa yang seragam, termasuk penggunaan bahasa slang seperti "aja", dan dikirim dalam waktu yang hampir bersamaan. Aktivitas komentar yang melonjak drastis pada hari pertama upload lalu menurun tajam, serta pola interaksi berulang setiap delapan jam, mengindikasikan seakan-akan ada suatu "jadwal" seperti sebuah shift. Bahkan terdeteksi setidaknya 80 momen di mana puluhan akun memposting komentar serentak, praktik yang sangat identik dengan penggunaan bot yang terkoordinasi. Sekitar 20% komentar mengulang frasa tertentu seperti "Bubarkan UNHCR", menunjukkan upaya membangun opini publik yang diulang terus menerus. Meskipun klaster anti-Rohingya relatif kecil, intensitas interaksinya jauh lebih tinggi, menciptakan echo chamber yang memperkuat polarisasi dan mempengaruhi opini netral menjadi bias. (Narasi Newsroom, 2024)
Xenofobia dan Diskriminasi Nyata
Narasi digital yang penuh kebencian terhadap Rohingya telah melampaui batas ruang maya dan mewujud nyata dalam bentuk xenofobia dan tindakan diskriminatif. Xenofobia, sebagai rasa takut atau benci terhadap orang asing, mencuat dalam banyak komentar publik maupun aksi langsung, terutama di Aceh. Salah satu insiden paling mengkhawatirkan adalah penyerangan terhadap pengungsi Rohingya oleh sekitar 500 mahasiswa di Banda Aceh, yang memaksa mereka untuk dipindahkan secara paksa. Ini merupakan bentuk ekstrem dari penolakan publik yang termanifestasi secara fisik. (BBC, 2023) Padahal sebelumnya, masyarakat Aceh dikenal sebagai komunitas yang ramah terhadap pengungsi, terbukti dari sikap terbuka saat menyambut lebih dari 1.000 pengungsi Rohingya sebelum Desember 2023. Namun narasi yang beredar di media sosial menyoroti "perilaku tidak sopan" pengungsi, memperkuat stigma negatif dan menggeser opini publik ke arah penolakan. Fenomena ini menunjukkan hadirnya "rasisme baru" yang tidak lagi berbasis ras, golongan, maupun etnis, melainkan pada citra dan peran sosial yang dikonstruksikan secara sistematis. (Narasi Newsroom, 2024)
Politisasi Isu Rohingya dalam Konteks Elektoral
Isu Rohingya tidak dapat dilepaskan dari konteks politik elektoral, khususnya menjelang Pilpres 2024. Salah satu titik balik penting adalah pernyataan Prabowo Subianto yang menyebut bahwa "tidak adil jika kita harus menerima semua pengungsi itu", dan bahwa negara harus mengutamakan rakyat Indonesia sendiri. Pernyataan tersebut muncul sehari sebelum terjadinya aksi pengusiran pengungsi oleh mahasiswa di Aceh, dan dengan cepat disebarluaskan oleh akun-akun pendukungnya, termasuk @sosmedkeras. (Fajri, 2023) Narasi populis ini menekankan pada perlindungan terhadap rakyat kecil dan identitas nasional, sambil menempatkan pengungsi sebagai ancaman yang menguras sumber daya negara. Data menunjukkan bahwa kelompok anti-pengungsi Rohingya banyak menggunakan pernyataan ini untuk membenarkan penolakan mereka. Meski demikian, polarisasi tidak hanya datang dari satu kubu, pendukung Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo juga turut menyebarkan narasi anti-Rohingya, menunjukkan bahwa isu ini telah menjadi alat politik yang digunakan lintas kubu untuk menarik simpati pemilih. (BBC News, 2023)
Kesimpulan
Sentimen negatif terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia bukanlah suatu hal yang bertumbuh secara organik, melainkan merupakan hasil dari penanaman opini yang bersifat terorganisir dan sistematis. Melalui disinformasi yang sengaja disebarkan dan narasi-narasi diskriminatif yang terus diulang, pengungsi etnis Rohingya dikonstruksikan sebagai "ancaman asing" yang mengganggu ketertiban sosial dan membebani negara. Narasi ini kemudian menumbuhkan xenofobia di tengah masyarakat, yang tidak hanya terbatas pada ujaran kebencian di media sosial, tetapi juga menjelma dalam bentuk tindakan nyata seperti pengusiran dan kekerasan fisik terhadap para pengungsi. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari konteks politik domestik, di mana isu pengungsi dieksploitasi untuk membangun citra populis dan meraih simpati elektoral. Ini merupakan bukti langsung, bagaimana rasa kemanusiaan dijadikan komoditas politik, dan empati dikorbankan demi kepentingan suara. Hal ini adalah bentuk degradasi moral dalam politik praktis dalam dunia kita hari ini. Di mana rasanya, perhitungan elektoral lebih diutamakan daripada solidaritas kemanusiaan yang universal.