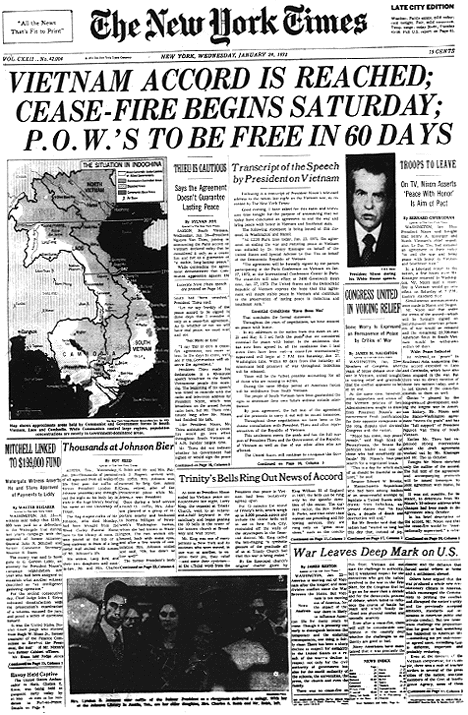Mungkin sebagian orang akan berpendapat media atau orang seperti saya adalah jurnalis pengecut atau bernyali rendah. Tapi dalam merumuskan 'What Next?', salah satu pertanyaan terpentingnya adalah 'siapa yang dirisikokan?'. Risiko kantor akan diserang orang atau diancam, itu risiko kecil dan akan diabaikan. Kalau sudah ada ancaman atau risiko pembunuhan, pasti akan dievakuasi ke luar daerah atau minta perlindungan polisi. Begitu pula risiko dituntut ke pengadilan atau dilaporkan polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Itu urusan 'remeh'. Risiko yang jangan sampai diambil adalah merisikokan masyarakat.
Tak ada berita yang sebanding dengan risiko keamanan masyarakat dan keselamatan langsung jiwa seorang reporter.
JURNALISME PENGGEBUK
Teori klasik jurnalisme harus berhadapan dengan kemarahan masyarakat Amerika Serikat dalam pemberitaan Perang Vietnam tahun 1960-an. Gaya jurnalisme Amerika yang terkenal disiplin dengan fakta menyajikan foto dan berita heroisme perang pihak AS secara maraton dan bersama-sama. Ditambah, pers AS ketika itu bertransformasi menjadi authoritarian press sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengampanyekan perang. Sementara jumlah korban di pihak AS makin bertambah, APBN terkuras. Masyarakat ingin perang diakhiri dan anak-anak mereka dipulangkan dari medan perang. Tapi pemerintah dan media seolah terus membakar sentimen nasionalisme itu lewat nafsu bertempur. Akhirnya mereka kelelahan sendiri dan pulang tanpa membawa kemenangan.
[caption caption="Halaman muka salah satu surat kabar terkenal Amerika Serikat di era Perang Vietnam (New York Times)"]

Sosiolog Norwegia Johan Galtung memperkenalkan istilah Peace Journalism atau Jurnalisme Damai di awal 1970 setelah ia menyelesaikan Journal of Peace Research di tahun 1964. Sebagai bocah yang turut jadi korban Perang Dunia II, Galtung merasakan konflik atau perang sebagai peristiwa yang saling menihilkan. Tak ada yang di tengah. Yang ada hanya kita-mereka, kalah-menang, dehumanisasi dan siklus tanpa ujung soal siapa yang pertama 'melempar batu'. Kenyataannya perang selalu diputuskan di balik meja oleh orang-orang berdasi dalam ruang berpendingan yang seumur hidupnya tak pernah pegang senjata. Kenyataannya, mereka yang menderita adalah para warga di daerah konflik, pengungsi, anak-anak yang kehilangan orangtua dan ibu yang harus merelakan anaknya berperang. Perang tidak akan berhenti sebelum ada yang menang meski keduanya mesti menanggung kerusakan amat parah. Sehingga, perang sebenarnya tidak meninggalkan siapa yang menang atau kalah, tapi siapa yang tersisa.
Jurnalisme Perang akan mengedepankan siapa pihak yang harus disalahkan dan dihukum. Dehumanisasi akan dilancarkan kepada pihak seberang. Propaganda turut dikampanyekan dalam bentuk kebohongan menyangkut pihak lawan dan menutupi kesalahan pihak sendiri. Penyelesaian semata-mata digantungkan pada elite pembuat kebijakan, bukannya sebuah upaya bersama-sama. 'Sebagus-bagusnya' perang, ia tak hanya akan menghabisi orang yang kita benci. Perang kelak akan menjalar ke halaman rumah kita dan menewaskan orang-orang terdekat yang kita kasihi. Sesuatu yang mungkin tak pernah terbayangkan oleh mereka yang sangat bernafsu menghabisi orang lain.
Galtung menawarkan jurnalisme yang berorientasi pada kelangsungan peradaban dan menyoroti penderitaan manusia yang timbul akibat konflik. Orientasi win-win solution mungkin tak bisa tercapai, tapi jurnalisme mesti mendorong untuk membangun dialog yang terbuka agar kekerasan itu segera diakhiri. Bila sebelumnya keputusan menyangkut perang hanya dibuat di ruang-ruang tertutup, maka Jurnalisme Damai harus membuatnya terbuka dengan keterlibatan seluruh masyarakat untuk memutuskan -- atau setidaknya bersuara -- untuk mencapai kembali kedamaian.
Jurnalisme Damai pada akhirnya adalah sebuah jurnalisme dengan pemikiran skeptis mengenai manfaat aksi sebuah konflik dan hikmahnya bagi umat manusia serta masa depan. Ia akan lebih mementingkan nasib korban ketimbang ambisi kemenangan serta memberi porsi yang adil. Terpenting, Jurnalisme Damai adalah jalan bagi pihak yang bertikai menemukan kembali kedamaian. Bukan soal siapa yang salah dan yang benar, tapi siapa/apa yang mesti diselamatkan. Di masa sulit, jurnalisme harus hadir sebagai seorang pelerai, bukan penggebuk.
Jurnalisme Damai tidak pernah mudah. Ia menuntut sandaran moral, kepedulian, kerja keras di lapangan, serta kemampuan menahan diri.
TOLIKARA DAN DEKONTEKSTUALISASI
Keprihatinan saya menjadi-jadi ketika memantau perkembangan berita konflik di Tolikara. Nyaris semua berita tayang dan yang populer adalah berita opini. Opini-opini itu dikutip oleh mereka yang tinggal di luar Tolikara -- mereka yang samasekali tidak bersentuhan dengan peristiwa dan terdampak langsung. Sumber tangan pertama atau saksi mata selalu menempati urutan tertinggi dalam klasifikasi fakta dalam jurnalistik. Saksi mata ini bisa narasumber yang menyaksikan, pelaku, korban terdampak langsung, atau bisa juga wartawan itu sendiri. Jenis berita seperti ini sangat minim saya temukan di pemberitaan Tolikara. Sulitnya medan Tolikara juga membuat sedikit wartawan yang menjangkau daerah itu untuk menyaksikan langsung, apalagi siaran live. Kalaupun ada keterangan tangan pertama, wawancara dilakukan lewat telepon. Bila yang memberi keterangan adalah aparat atau pejabat, cenderung tidak dipercaya. Masyarakat 'bersikukuh' pada persepsi yang sudah mereka bentuk dan sumbernya berasal dari opini -- bukan kesaksian.
Membakar properti orang lain, apalagi tempat ibadah, itu kesalahan besar. Kita semua tahu. Tapi kebanyakan media lebih suka membahas apa yang terjadi di puncak kulminasi peristiwa: pembakaran itu. Sehingga gambar yang mayoritas ditampilkan adalah gambar api dan puing musala.