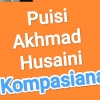Di tengah perjalanan bangsa yang majemuk, gesekan sosial kerap muncul, terutama ketika kebijakan publik dianggap memberatkan. Gejolak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Agustus 2025 menjadi contoh nyata. Rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250% memicu unjuk rasa besar pada 13 Agustus, dengan ribuan warga menuntut pembatalan kebijakan dan bahkan mendesak pengunduran diri bupati (detiknews, 2025)
Aksi ini berlangsung di Alun-Alun dan Pendopo Kabupaten Pati selama 10-13 Agustus. Warga menilai kebijakan tersebut diumumkan tanpa dialog memadai, sehingga memunculkan ketidakpuasan kolektif (Lestari, 2025). Ketegangan memuncak ketika pernyataan bupati yang dinilai menantang massa semakin memperdalam jurang ketidakpercayaan (Nashr, 2025). Situasi seperti ini menunjukkan betapa pentingnya proses komunikasi publik yang terbuka dalam setiap kebijakan strategis.
Akhirnya, gelombang protes mereda setelah bupati membatalkan kenaikan pajak dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Meski demikian, sebagian tuntutan warga, seperti reformasi kebijakan fiskal daerah, tetap mengemuka (Wahyuningtyas, 2025). Kasus Pati bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa pada 2023 terjadi 241 kasus konflik agraria di Indonesia, melibatkan 638.188 hektar lahan dan 135.608 keluarga merupakan angka tertinggi di Asia (Ahdiat, 2025). Data ini menegaskan bahwa ketegangan antara pemerintah dan masyarakat bukan hanya persoalan lokal, tetapi juga gejala struktural yang berpotensi terjadi di berbagai daerah, terutama jika kebijakan publik tidak melibatkan warga secara langsung.
Kearifan Lokal sebagai Penjernih Konflik
Indonesia memiliki modal sosial yang unik dalam menghadapi konflik, yakni kearifan lokal. Nilai seperti musyawarah untuk mufakat dan gotong royong telah terbukti menjadi perekat sosial di berbagai wilayah. Kearifan ini mendorong penyelesaian masalah melalui dialog, bukan konfrontasi.
Di Kalimantan Utara, misalnya, forum musyawarah adat lintas suku digunakan untuk mencegah gesekan menjelang pemilihan kepala daerah. Di Jawa Timur, tradisi ngopi bareng menjadi medium komunikasi informal yang efektif meredakan ketegangan. Sementara di Papua, ritual Bakar Batu berfungsi sebagai simbol rekonsiliasi yang mempertemukan kelompok yang berselisih.
Pendekatan berbasis budaya ini memiliki keunggulan karena berangkat dari pemahaman mendalam terhadap nilai, norma, dan identitas lokal. Alih-alih menjadi instrumen politik semata, kearifan lokal membangun rasa saling percaya dan keterhubungan yang kuat di antara warga.
Mengelola Konflik, Merawat Persatuan
Konflik tidak selalu membawa dampak negatif. Dalam konteks demokrasi, perbedaan pendapat merupakan hal wajar dan dapat menjadi energi positif untuk perubahan. Namun, tanpa mekanisme penyelesaian yang sehat, perbedaan bisa berubah menjadi perpecahan. Di sinilah pentingnya mengelola konflik secara konstruktif.
Kasus Pati memberikan pelajaran penting: transparansi dan partisipasi publik harus menjadi prinsip utama dalam setiap proses kebijakan. Dialog yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, dari elite lokal hingga warga akar rumput, dapat meminimalkan resistensi dan meningkatkan rasa memiliki terhadap kebijakan tersebut.
Selain itu, pemerintah daerah dapat mengintegrasikan mekanisme kearifan lokal ke dalam tata kelola kebijakan. Forum warga, musyawarah adat, dan kegiatan sosial berbasis budaya bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga media untuk memulihkan hubungan yang retak akibat perbedaan.