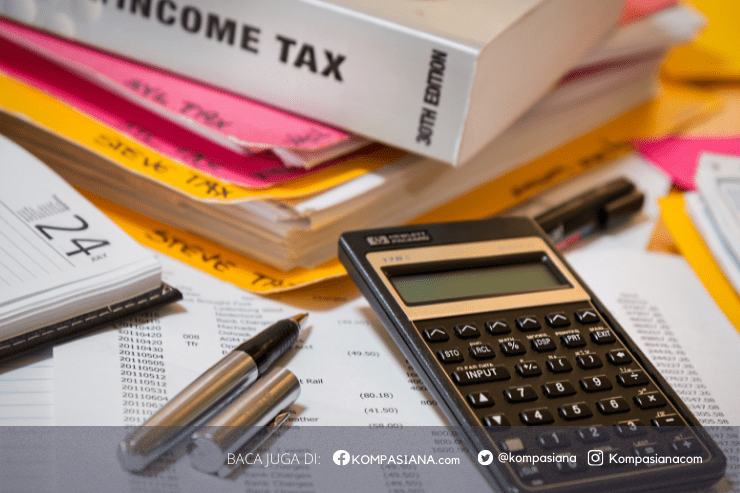Bagi banyak anak muda masa kini, momen menerima gaji justru sering diiringi rasa cemas. Jumlahnya tidak berubah banyak, sementara daftar kebutuhan, tagihan, dan cicilan seolah tidak ada habisnya. Ini bukan sekadar keluhan, melainkan realitas pahit yang dihadapi oleh Generasi Z yang baru merintis karier di tengah inflasi yang melonjak dan upah yang stagnan. Kita seakan terjebak dalam lingkaran yang tidak berujung, di mana pendapatan selalu kalah dibandingkan kenaikan harga.
Sebagai lulusan baru, kita sering kali dituntut memiliki keterampilan tinggi, pengalaman luas, sertifikat kompetensi, serta semangat kerja yang besar. Tuntutan tinggi, kompensasi rendah. Tuntutan tersebut sebenarnya tidak masalah, asalkan diimbangi dengan kesejahteraan yang sepadan. Namun, ketika lowongan pekerjaan menawarkan berbagai fasilitas menarik, ujung-ujungnya saat membahas gaji, nominal yang diberikan hanya cukup untuk membayar tempat tinggal, biaya makan, dan sesekali hiburan.
Fenomena ini membuat kita semakin sulit mewujudkan kemandirian finansial. Menabung untuk membeli rumah terasa seperti mimpi di siang hari, karena harga properti di kota besar sudah tidak masuk akal. Rasio antara gaji dan harga rumah ibarat bumi dan langit. Ingin berinvestasi dalam saham atau reksa dana pun terasa mustahil ketika uang bulanan sudah habis untuk kebutuhan pokok. Tak jarang, kita terpaksa gali lubang tutup lubang di akhir bulan.
Ironisnya, Generasi Z merupakan generasi yang paling sadar akan pentingnya literasi keuangan. Kita rajin mendengarkan podcast, membaca artikel perencanaan finansial, dan memahami pentingnya investasi maupun dana pensiun. Namun, justru kita menjadi generasi yang paling sulit mempraktikkannya karena daya beli terus menurun. Kita memiliki pengetahuan, tetapi tidak memiliki modal untuk menerapkannya.
Dampaknya tidak hanya pada kondisi keuangan pribadi. Banyak dari kita yang akhirnya menjadi bagian dari generasi sandwich lebih cepat dari perkiraan, karena harus membantu orang tua sembari mencukupi kebutuhan sendiri. Beban ganda ini memicu tekanan mental dan menjadikan kelelahan kerja (burnout) di usia muda sebagai hal yang lumrah. Kita menjadi rentan stres karena memikul tanggung jawab finansial yang seharusnya belum sepenuhnya menjadi beban di usia dua puluhan. Kesehatan mental pun terancam demi mengejar penghasilan yang selalu tertinggal dari kebutuhan hidup.
Masalah ini bukan karena kita malas, kurang berusaha, atau enggan belajar. Kita sudah berjuang keras, bekerja lembur, mencari pekerjaan sampingan, dan terus mengembangkan keterampilan. Persoalannya terletak pada struktur ekonomi dan kebijakan gaji yang belum sepenuhnya adil terhadap tingkat produktivitas dan beban hidup generasi muda.
Solusinya tidak bisa hanya dibebankan kepada individu. Pemerintah dan dunia usaha harus lebih peka dan transparan dalam menetapkan kebijakan. Perlu ada penyesuaian upah yang riil, berdasarkan indeks harga konsumen yang aktual, bukan sekadar angka statistik di atas kertas. Perhitungan tersebut juga harus memperhitungkan faktor penting seperti biaya tempat tinggal dan transportasi publik yang terus meningkat, khususnya di wilayah perkotaan. Singkatnya, komponen UMR harus benar-benar mencerminkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang sesungguhnya.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI