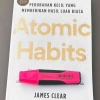Ada banyak malam, di saat aku pulang dengan tubuh yang nyaris roboh, mata yang perih karena kurang tidur, dan hati yang campur aduk antara lelah, marah, dan... entah apa lagi. Kadang, aku menatap diriku di cermin ruang jaga yang redup dan bertanya: "Kenapa aku memilih jalan ini?" Tapi tepat di saat yang sama, di balik sorot mata yang lelah itu, ada satu hal yang tak pernah padam yaitu rasa syukur.
Aku tidak tahu apa jadinya diriku jika aku bukan seorang dokter residen.
Mungkin aku akan menjadi seseorang yang lebih tenang hidupnya, memiliki lebih banyak waktu untuk tidur, atau lebih sering pulang ke rumah tanpa membawa beban pikiran yang berat. Tapi bersamaan dengan itu, mungkin aku juga tidak akan pernah mengenal siapa diriku yang sebenarnya, apa batasanku, dan kekuatanku.
Mungkin aku tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya membuat keputusan dalam hitungan detik yang bisa menentukan hidup seseorang..
Mungkin aku tidak akan pernah tahu seberapa jauh tubuh ini bisa dipaksa bertahan, seberapa dalam kesabaran bisa digali, dan seberapa kuat hati bisa bertahan meski terus diuji..
Mungkin aku tidak akan pernah belajar tentang ketangguhan, tentang bagaimana bangkit dari kesalahan, menerima teguran, lalu tetap berdiri dengan kepala tegak..
Menjadi dokter residen bukan hanya tentang mempelajari ilmu kedokteran lebih dalam. Bagiku, ini adalah fase yang mengubah manusia biasa menjadi pribadi yang luar biasa, bukan karena hebat, tapi karena terbiasa menghadapi tekanan yang luar biasa. Di ruang jaga yang sunyi, di lorong IGD yang hiruk-pikuk, atau di tengah tangis keluarga pasien, kiranya di sanalah aku dibentuk. Bukan hanya sebagai dokter, tapi sebagai seorang manusia.
Di masa residen, aku belajar bahwa tanggung jawab bukan hanya soal pekerjaan, tapi soal kemanusiaan. Bahwa dalam kelelahan, aku tetap harus bisa berpikir jernih. Bahwa dalam kemarahan, aku tetap harus berbicara dengan empati. Bahwa dalam keterbatasan, aku tetap harus berusaha sebaik mungkin. Itulah pelajaran yang tidak pernah kutemukan di bangku kuliah.
Jika aku bukan seorang dokter residen, mungkin aku tidak akan tahu betapa pentingnya kerja tim, komunikasi yang jelas, dan empati yang tulus. Aku tidak akan tahu bahwa menyelamatkan nyawa seseorang bukan hanya soal diagnosis yang tepat, tapi juga soal kehadiran, perhatian, dan keberanian mengambil keputusan. Aku tidak akan tahu bagaimana rasanya berdiri di antara hidup dan mati, dan memilih untuk tetap tenang.
Menjadi dokter residen adalah fase paling brutal sekaligus paling indah dalam perjalanan ini. Brutal karena setiap hari kami bergulat dengan batas: batas tenaga, batas emosi, batas ilmu. Tapi indah karena di tengah semua itu, tumbuh hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh apa pun: insting yang tajam, empati yang dalam, kemampuan untuk multitasking dengan kepala dingin, dan jiwa yang tak mudah runtuh. Karena tidak ada guru yang sejujur pasien-pasien yang menggantungkan nyawa pada tanganmu. Dan tidak ada cermin yang lebih jujur daripada malam-malam panjang saat kau bertanya pada dirimu sendiri: "Sudah cukupkah aku hari ini?"