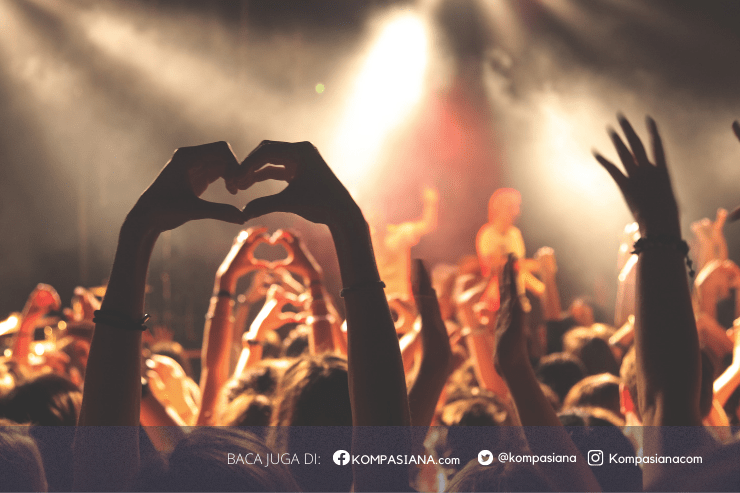Lagu "Rumah Kita" karya legendaris God Bless bukan sekadar nostalgia musik rock 80-an. Di balik aransemen yang sederhana dan lirik yang tidak rumit, lagu ini menyimpan permenungan dalam tentang makna rumah, kesederhanaan, dan relasi manusia dengan ruang hidupnya. Lagu ini bukan hanya milik generasi masa lalu, tapi juga menjadi cermin tajam bagi generasi hari ini yang sedang kalang kabut memikirkan: apakah harus ambil KPR rumah subsidi 35 tahun? Apakah layak mengejar rumah komersial yang makin tak terjangkau? Atau justru harus meredefinisi ulang apa itu rumah?
Di tengah realitas di mana rumah makin terasa seperti mimpi eksklusif yang hanya bisa dibeli dengan "menyandera" usia produktif, lagu ini seperti menyodorkan pertanyaan kontemplatif: benarkah kita harus pindah ke kota untuk merasa punya rumah? Apakah rumah itu soal luas tanah dan cicilan, atau rasa cukup dan keterikatan? Lagu ini menjadi semacam pengingat, bahwa dalam dunia yang makin materialistik dan terukur secara ekonomi, kita masih boleh (bahkan perlu) bermimpi tentang rumah dalam makna yang lebih manusiawi.
Hanya bilik bambu tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan...
Kalimat pembuka ini sangat kuat. Lirik ini menghadirkan gambaran visual yang langsung terasa akrab, terutama bagi masyarakat Indonesia pedesaan atau kelas menengah ke bawah. Tidak ada dekorasi artistik, tidak ada simbol kemewahan. Tapi justru itulah poin utamanya: rumah bukan tentang properti, tapi tentang keberpunyaan.
Lirik ini mencerminkan resistensi terhadap narasi kapitalistik yang mengukur rumah dari nilai jual, luas bangunan, atau kemegahan desain. Penulis lagu disini mengajak kita untuk melihat rumah sebagai simbol keberadaan, bukan simbol kekayaan.
Beratap jerami, beralaskan tanah...
Ini bukan lirik romantisasi kemiskinan, melainkan merupakan potret realitas. Atap jerami dan lantai tanah mewakili kondisi perumahan rakyat yang jauh dari standar hunian ideal. Tapi alih-alih mengeluh, lirik ini menyematkan kebanggaan: "Namun semua ini punya kita."
Ada kekuatan besar dalam frase itu. Dalam dunia yang penuh kontrakan, cicilan, dan rumah-rumah yang belum lunas 35 tahun, kepemilikan sederhana atas ruang hidup, meski terbatas, menjadi hal yang sangat berharga. Irik tersebut menyuarakan otonomi, sekaligus menohok kita: apakah kita masih memiliki rumah kita sendiri?
Hanya alang-alang pagar rumah kita...
Pagar alang-alang adalah metafora yang indah sekaligus getir. Maksud dari lirik tersebut bukan pagar besi yang melindungi, tapi justru tumbuhan liar yang membaur dengan alam. Rumah ini terbuka, bersahaja, dan bisa jadi tidak aman secara fisik, tapi mungkin aman secara batin. Kita diajak merenung: pagar yang kuat bahkan tinggi tidak selalu membuat hidup damai, dan pagar sederhana tidak selalu berarti kekurangan.
Hanya bunga bakung tumbuh di halaman...
Bunga bakung, bukan anyelir atau melati. Ini penegasan bahwa rumah ini tidak mengejar simbol keindahan mewah, hanya keindahan yang tumbuh alami, yang hadir tanpa dipaksa. Sebuah sindiran halus pada dunia real estate yang memaksa keindahan buatan di perumahan cluster.
Haruskah kita beranjak ke kota, yang penuh dengan tanya?
Titik kritis lagu ini ada di lirik tersebut. Sebuah pertanyaan eksistensial yang mewakili dilema jutaan orang Indonesia yang hijrah ke kota besar demi "masa depan yang lebih baik." Tapi God Bless mempertanyakan: benarkah kota adalah jawaban?
Kota penuh tanya artinya penuh ketidakpastian, tekanan, kompetisi, dan kadang kehilangan jati diri. Lagu ini secara sosiologis mengkritik narasi dominan urbanisasi sebagai satu-satunya jalan menuju "kemajuan". Di kota, rumah bisa saja lebih besar, tapi apakah rasa memiliki, keterikatan, dan kedamaian juga ikut membesar?