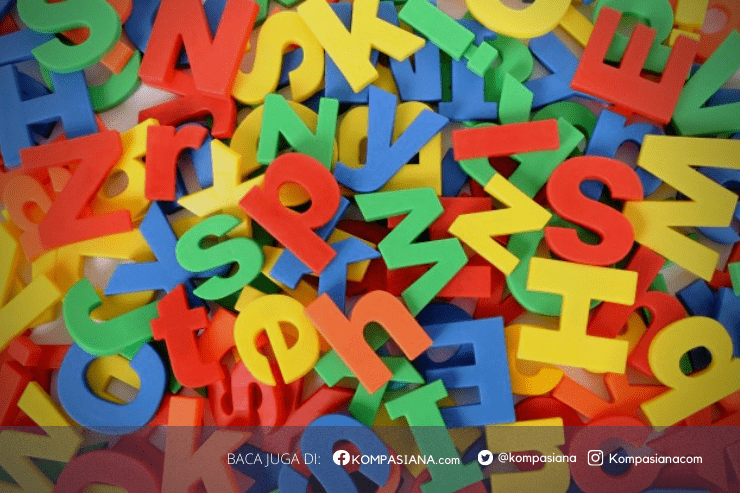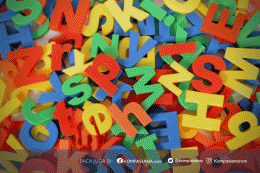"Milik siapakah sebuah kata?" Pertanyaan sederhana ini menyimpan gema pergulatan makna yang dalam, sebab di tengah dunia yang semakin terhubung, masih terdengar suara-suara yang memagari bahasa dengan klaim identitas dan eksklusivitas. Kata-kata seperti "Allah," "Amin," atau "Shalom" sering diperebutkan seolah hanya sah jika diucapkan oleh pemeluk iman tertentu, menjadikannya simbol pemisah alih-alih jembatan pemersatu. Padahal, bahasa lahir dari nurani manusia yang ingin saling memahami, bukan untuk meniadakan yang berbeda. Ketika sebuah kata diklaim sepihak dan diperlakukan sebagai warisan sakral yang tak boleh disentuh oleh yang lain, maka terancamlah kebebasan berekspresi dan semangat kemanusiaan yang universal. Karena itu, sudah saatnya kita memandang bahasa bukan sebagai benteng suci milik segelintir penjaga tradisi, melainkan jembatan yang menyeberangi batas keyakinan dan warna kulit: sebuah ruang bersama yang netral namun penuh makna, tempat kita bisa saling menyapa, bukan saling mengusir.
Bahasa sebagai Produk Sosial-Budaya
Bahasa tidak pernah lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari desir napas manusia yang saling menyapa, dari riuh pasar yang menukar barang dan makna, dari tangisan bayi hingga kidung doa. Dalam setiap detiknya, bahasa hidup, menyerap, berubah, dan berkembang: sebuah proses sosial yang tak henti bergerak bersama denyut sejarah umat manusia.
Edward Sapir, dalam Language: An Introduction to the Study of Speech (1921), menegaskan bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan cermin dari budaya, kepercayaan, dan nilai-nilai masyarakat. Bahasa adalah produk dari jaringan sosial yang saling berinteraksi, diciptakan bukan untuk diklaim, melainkan untuk dibagikan---sebagai jendela batin yang saling terbuka antarmanusia.
Contoh paling nyata adalah pergerakan kata-kata religius lintas tradisi: "Allah" yang berasal dari bahasa Arab pra-Islam hidup dalam Islam, Kristen Arab, dan Yahudi Mizrahi. "Amin" berasal dari akar kata Ibrani mn, digunakan dalam doa umat Yahudi, Kristen, dan Muslim. "Shalom" dan "Salam" berbagi akar makna damai, sementara "karma" dari filsafat India kuno yang kini mengisi ruang spiritualitas global. Semua itu memperlihatkan bagaimana kata-kata menyeberangi batas iman tanpa kehilangan makna.
Fenomena lintas bahasa ini disebut language borrowing, yakni proses ketika bahasa mengambil kata atau konsep dari bahasa lain sebagai respons atas kontak budaya, kolonialisme, perdagangan, atau migrasi spiritual. Haspelmath, dalam Lexical Borrowing: Concepts and Issues (2009), menyatakan bahwa peminjaman kata membuktikan bahwa tidak ada bahasa yang steril atau tertutup: semuanya bersifat terbuka, menyerap, dan hidup dari perjumpaan.
Maka bagaimana mungkin kita mengunci makna dan memagari kata, jika sejak awal bahasa justru lahir dari semangat berbagi dan perjumpaan? Bahasa bukan benteng pribadi, melainkan taman terbuka tempat manusia duduk bersama, bertukar nama untuk rasa yang sama. Di taman itu, tak ada yang asing, sebab setiap kata yang kita ucapkan telah melewati jalan panjang dari pelukan antarbudaya.
Bahaya Klaim Eksklusif atas Bahasa
Ketika sebuah kata dikunci dengan gembok kepemilikan, maka yang lahir bukan perlindungan, melainkan pengasingan. Bahasa, yang sejatinya jembatan antarjiwa, berubah menjadi tembok pemisah dalam masyarakat yang majemuk. Klaim eksklusif terhadap istilah-istilah tertentu---terutama yang bersifat keagamaan---dapat menjadi bara dalam sekam, menyulut ketegangan antarumat, antarsuku, bahkan antargenerasi dalam satu komunitas yang dulu saling menyapa dalam damai.
Sejarah mencatat bahwa bahasa kerap menjadi medan konflik tersembunyi. Paul Chilton, dalam Analysing Political Discourse: Theory and Practice (2004), menyatakan bahwa bahasa bukan hanya alat representasi, melainkan juga instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini, istilah spiritual tertentu berubah menjadi simbol dominasi identitas. Ketika sebuah kelompok merasa hanya merekalah yang sah menggunakan kata "Allah" atau mengucap "salam damai," ketegangan muncul bukan karena perbedaan iman, melainkan karena perebutan otoritas makna.
Dampaknya, ekspresi spiritual dan budaya pun dibatasi. Ketika kata-kata sakral dipagari untuk segolongan saja, yang lain dipaksa bungkam dan kehilangan cara untuk menyapa Yang Ilahi dengan bahasa yang akrab bagi mereka. Ngg wa Thiong'o, dalam Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature (1986), menyebut bahwa membatasi bahasa berarti membatasi jiwa. Sebab bahasa adalah medium untuk menyampaikan rasa, iman, dan harapan---dan ketika itu disita, sebagian dari kemanusiaan pun ikut terampas.