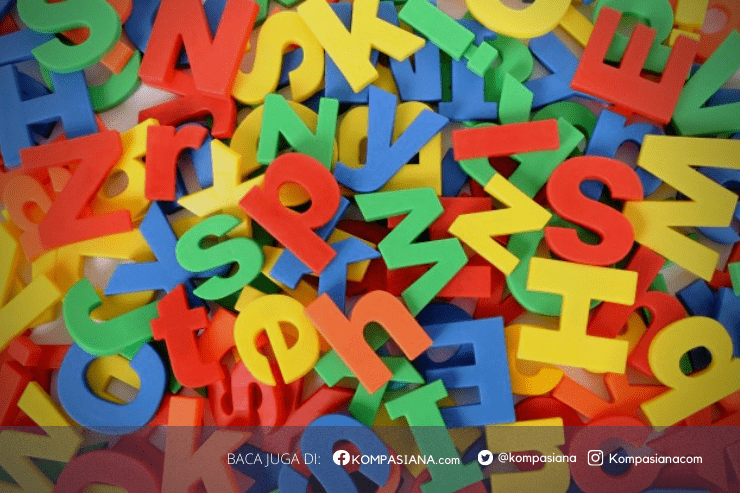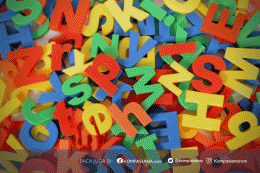Di banyak ruang sosial hari ini---baik di sekolah, kampus, tempat kerja, maupun media sosial---kemampuan berbahasa Inggris sering kali dianggap sebagai simbol kecerdasan, modernitas, bahkan status sosial. Tak jarang, orang yang fasih berbahasa Inggris langsung mendapat pujian, label "keren", dan dianggap lebih "berkelas". Di sisi lain, ketika seseorang berbicara menggunakan Bahasa Madura, reaksi yang muncul bisa sangat berbeda: cibiran, lelucon, bahkan pandangan sinis. Bahasa Madura, yang merupakan salah satu bahasa daerah terbesar di Indonesia dengan jutaan penutur, masih kerap menjadi objek diskriminasi linguistik. Pertanyaannya sederhana namun penting: kenapa bahasa asing dirayakan, sementara bahasa sendiri dihina?
Diskriminasi terhadap Bahasa Madura bukan sekadar soal selera bahasa, tapi merupakan bentuk ketidakadilan struktural terhadap kebudayaan lokal. Ini mencerminkan betapa masyarakat masih terjebak dalam cara pikir kolonial---yang mengagungkan apa yang datang dari luar, dan meremehkan apa yang tumbuh dari akar sendiri. Bahasa Madura sering dianggap kasar, keras, atau tidak sopan, padahal justru memiliki sistem tingkatan tutur yang kompleks dan sopan, seperti dalam Bahasa Jawa. Stereotip ini muncul bukan dari realitas linguistik, melainkan dari stigma sosial yang terus dilanggengkan. Dan ketika stigma itu diterima mentah-mentah, maka pelan-pelan, generasi muda mulai malu berbahasa Madura, bahkan di lingkungan keluarganya sendiri.
Yang paling menyedihkan, diskriminasi ini tidak hanya datang dari luar komunitas Madura, tapi juga terjadi di dalam. Banyak anak muda Madura yang tumbuh dengan perasaan bahwa bahasa ibunya adalah sesuatu yang harus disembunyikan agar bisa "diterima" di lingkungan yang lebih luas. Inilah bentuk kekerasan simbolik yang sering tidak disadari: ketika seseorang dipaksa meninggalkan identitas bahasanya demi dianggap "modern" atau "berpendidikan". Padahal, kehilangan bahasa berarti kehilangan sebagian dari diri sendiri---karena bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tapi cara kita memahami dunia, mengekspresikan emosi, dan terhubung dengan sejarah serta leluhur kita.
Gen Z, yang dikenal sebagai generasi digital, kritis, dan peduli pada isu keadilan sosial, seharusnya mampu membaca persoalan ini lebih dalam. Menghargai Bahasa Madura bukan berarti menolak Bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Justru, ini soal keberanian untuk berdiri di atas identitas sendiri, sambil tetap membuka diri pada dunia. Kalau kita bisa menyanyikan lagu-lagu Barat dengan bangga, kenapa harus merasa malu saat berbicara dalam bahasa ibu kita sendiri? Bukankah kepercayaan diri sejati muncul ketika kita bisa menjadi diri sendiri, tanpa harus mengorbankan akar kita?
Bahasa Madura adalah warisan budaya yang hidup. Ia lahir dari perjuangan, kesenian, sastra, dan nilai-nilai luhur masyarakat Madura. Ia tidak layak dipinggirkan, apalagi dihina. Saatnya kita mengubah cara pandang. Mulailah dari hal-hal kecil: tidak menertawakan orang yang berbicara Bahasa Madura, memberi ruang di media sosial untuk konten berbahasa Madura, atau bahkan belajar dan menggunakannya kembali dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Madura tidak kalah keren, hanya kurang diberi panggung.
Jadi, kalau Bahasa Inggris bisa dihargai, dirayakan, dan diajarkan dengan bangga, kenapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama terhadap Bahasa Madura? Sudah waktunya berhenti malu, dan mulai membanggakan bahasa sendiri.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI