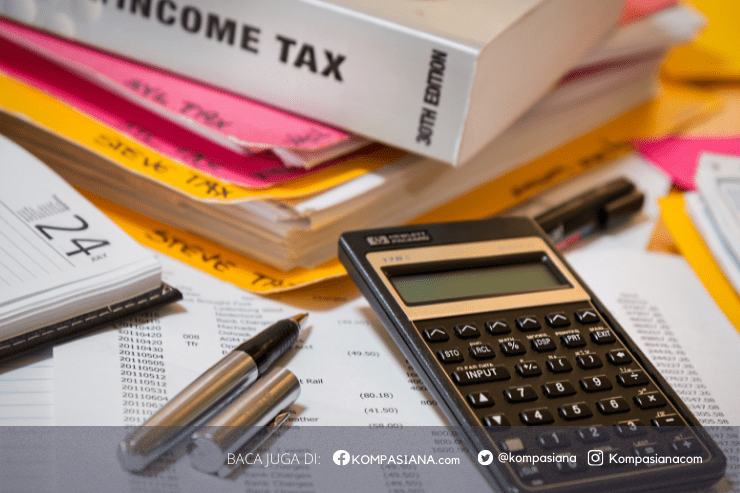Kos-kosan menjadi salah satu penyumbang ekonomi terbesar di Indonesia, terutama di sekitar kampus. Penghuni kos biasanya di tempati oleh mahasiswa dan pekerja yang merantau. Mereka menyewa untuk mendapatkan kenyamanan. Namun dari kacamata pemilik kos, dianggap sebagai bisnis yang stabil, karena pemasukan uang cenderung lancar. Bayangkan jika pemasukan tiba-tiba terhambat. Ada kamar kosong dianggap menimbulkan kerugian karena adanya keresahan untuk membayar tagihan wifi, listrik, air dan lain-lain. Hal ini lah yang menjadi patokan pemilik kos, bagi mereka yang terpenting ada yang menyewa, duit kos lancar. Soal siapa yang akan menempati urusan belakangan.
Penghasilan dari kos bisa menjadi sumber penghasilan utama. Selama penyewa tidak menimbulkan kerugian secara material, pemilik kos tutup mata saja. Tindakan yang mengedapankan uang akhirnya di manfaatkan oleh pelaku LGBT. Kerap kali berita-berita yang disiarkan ke media massa, pelaku LBGT tertangkap basah di area kos-kosan. Menurut pemberitaan mengatakan, hasil dari penelitian “Perhimpunan Konselor VCT dan HIV AIDS Indonesia di Sumatera Barat” menemukan 50 persen aktivitas seksual pelaku LGBT dilakukan di tempat kos (Nugroho, 2018).
Siapa sebenarnya yang lebih pandai menyembunyikan diri: penyewa kos atau pemilik kos yang menutup mata?
Kos adalah ruang aman untuk menjalani kehidupan yang tidak bisa mereka tunjukkan di rumah atau lingkungan sekitar. Pasangan LGBT memilih kos sebagai tempat “living together” karena dianggap lebih aman dari penghakiman sosial. Namun, bagi pemilik kos, kos adalah bisnis. Seperti pemberitaan lainnya, pada tanggal 2 September 2017, polisi melakukan razia terhadap rumah tempat tinggal 12 wanita yang dicurigai lesbian di sebuah kawasan di Jawa Barat. Berdasarkan laporan tersebut, terjadi banyak kasus di mana pasangan LGBT (atau aktivitas LGBT) ditemukan tinggal di rumah kos (kontrakan) atau “kost” (Human Rights Watch, 2020).
Pemberitaan tersebut akhirnya menimbulkan pertanyaan, mengapa pelaku LGBT bisa lolos dari pengawasan pemilik kos ataukah sudah tau namun memilih “diam”. Alih-alih menyelesaikan masalah dengan menegur hingga ancaman mengusir, enggan dilakukan. Alasan-alasan ini bisa didukung oleh faktor ekonomi, penyewa yang sudah membayar merupakan jaminan pemasukan tetap, kemudian alasan sosialnya adalah peyewa merasa diperlakukan tidak adil, bahkan menuduh diskriminasi. Sementara dari kacamata psikologis, merasa tidak nyaman menjadi “penegak moral.” Bagi pemilik kos selama tidak merugikan orang lain, urusan pribadi penyewa sebaiknya tidak dicampuri. Sikap memilih diam menjadi jalan tengah: tidak ikut campur, tapi juga tidak memberi persetujuan secara terbuka.
Keputusan untuk memilih diam ini juga mempetimbangkan kalkulasi untung-rugi. apabila membiarkan penyewa tetap tinggal, uang sewa kos lancar, tidak ada permasalahan konflik antar kedua belah pihak. Akan tetapi, jika pemilik kos memilih untuk menegur ataupun mengusir dapat menjaga norma yang ada di Indonesia, namun dampaknya akan berisiko rugi secara ekonomi dan sosial yang mana bisa saja akan dilabeli “kos penerima LGBT”. Sehingga orang-orang yang ingin menyewa kos kehilangan kepercayaan untuk menyewa di tempat kos seperti itu dan lebih mencari kos aman dan nyaman yang sesuai dengan norma-norma yang belaku di Indonesia.
Apakah pilihan rasional selalu identik dengan pilihan yang benar?
Fenomena ini menunjukkan sisi lain kehidupan kos, tentang bagaimana pemilik kos sering kali berada di posisi serba salah: Keputusan memilih diam dan membiarkan pasangan LGBT tinggal bersama merupakan bentuk negosiasi antara norma sosial dan kepentingan ekonomi. Pemilik kos melihat bahwa manfaat ekonomi memberikan ketenangan lebih besar dibanding risiko sosial, selama kasus tidak menjadi sorotan publik. Berdasarkan beberapa berita menunjukkan bahwa pemilik kos “mengaku tidak tahu” meskipun ada indikasi kuat pasangan LGBT tinggal di tempatnya. Strategi “tidak tahu-menahu” ini sebenarnya bentuk perhitungan rasional, bukan karena pemilik kos buta, tetapi karena mereka memilih risiko yang lebih kecil dibanding kehilangan pemasukan.
Solusi manakah yang paling tepat?
Jika mengubah perilaku pemilik kos agar tidak sekadar diam, maka yang harus diubah adalah pemikiran atas perhitungan rasionalnya. Selama “diam” dianggap lebih aman dan menguntungkan, maka itu yang akan dipilih. Tapi, jika dengan bertindak dibuat lebih menguntungkan, barulah pemilik kos akan memilih jalur itu. Dengan kata lain, solusi terbaik bukan sekadar menyalahkan pemilik kos karena diam, tetapi menciptakan kondisi di mana menegakkan aturan akan terasa lebih masuk akal dibanding membiarkan. Menurut Coleman (1990) yang sesuai dengan logika, pilihan manusia selalu bergantung pada apa yang dianggap paling menguntungkan dan paling sedikit merugikan. Jika perhitungan untung-rugi berubah, maka keputusan pun ikut berubah. Hal ini juga dapat dicegah dengan membuat pamflet berisi larangan bagi pasangan LGBT untuk menyewa di kos.
Salah satu faktor yang berkontribusi pada maraknya razia LGBT di kos-kosan adalah sikap sebagian pemilik kos yang tahu, tetapi memilih diam. Bukan semata karena lalai atau acuh, melainkan karena diam terasa lebih aman, tidak menimbulkan konflik dan pemasukan tetap terjaga. Selama uang sewa kos lancar, pilihan itu akan terus diambil. Namun, ketika ada aturan kontrak yang jelas, dukungan warga, atau sistem pencarian penghuni baru yang lebih cepat, pemilik kos bisa lebih berani bersikap tegas. Pada akhirnya, perubahan tidak cukup bertumpu pada individu, melainkan harus tercipta lingkungan yang membuat pilihan benar terasa lebih menguntungkan.