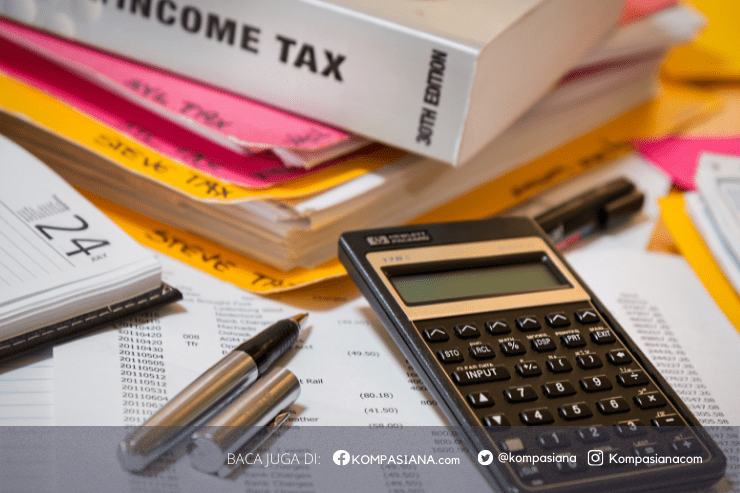Pukul menunjukkan 23.53. Beberapa rekan satu kampus tampak sibuk memeriksa aplikasi perbankan digital, menanti apakah transfer dari orang tua sudah masuk, atau apakah dana beasiswa semester ini telah berhasil dicairkan. Di saat bersamaan, berbagai notifikasi dari platform belanja daring muncul bertubi-tubi: "Segera checkout! Diskon hingga 90%! Hanya sampai tengah malam!" Saya sempat membuka aplikasi tersebut, namun kemudian menutupnya kembali. Malam itu, saya memilih untuk menahan diri, dan menghadapi godaan konsumerisme dengan refleksi: apakah saya benar-benar memerlukan sesuatu, atau hanya terdorong oleh kebiasaan dan tekanan sosial?
Bagi mahasiswa seperti saya, yang hidup di era digital penuh dengan rangsangan visual dan budaya belanja impulsif, No Buy Challenge merupakan bentuk kontemplasi sekaligus perlawanan diam terhadap arus dominan. Sebuah tantangan yang mendorong individu untuk tidak membeli barang atau jasa yang tidak esensial selama periode tertentu. Di media sosial, tagar seperti #NoBuyChallenge, #BuyNothing2025, dan #HidupMinimalis menjadi wadah ekspresi dan solidaritas, memperlihatkan bahwa memilih "cukup" adalah bentuk keberanian di tengah budaya yang mengagungkan kepemilikan.
Merujuk pada data dari GoodStats, gerakan ini mendapatkan popularitas sebagai bentuk resolusi personal masyarakat menghadapi ketidakpastian ekonomi di tahun 2025. Lonjakan harga barang pokok, kenaikan PPN, serta tuntutan gaya hidup yang tinggi membuat banyak individu khususnya mahasiswa mempertimbangkan ulang makna konsumsi. No Buy Challenge, dalam konteks ini, bukan hanya strategi bertahan hidup finansial, namun juga menjadi ajakan untuk mengendapkan kembali kesadaran konsumtif yang selama ini diterima sebagai kenormalan.
Sementara itu, laporan We Are Social 2025 mencatat peningkatan konsumsi digital di Indonesia hingga 17% dibandingkan tahun sebelumnya. Algoritma e-commerce semakin mahir dalam memprofilkan perilaku pengguna: mengetahui kapan waktu belanja terbaik, jenis produk favorit, bahkan emosi yang mungkin memicu pembelian impulsif. Di tengah lanskap ini, menahan diri dari pembelian justru menjadi bentuk kesadaran diri yang tinggi.
Sebagai mahasiswa, saya menyadari bagaimana tekanan untuk "terlihat ideal" memengaruhi banyak keputusan konsumsi. Misalnya, ngopi di kedai kekinian bukan lagi sekadar urusan selera, tetapi telah menjadi simbol gaya hidup produktif. Memiliki gawai model terbaru bukan sebatas kebutuhan akademik, melainkan cara bertahan dalam pergaulan sosial yang serba kompetitif. Dalam konteks ini, No Buy Challenge menjadi ruang untuk bertanya secara jujur kepada diri sendiri: apakah yang saya beli benar-benar saya perlukan, atau hanya ingin saya tampilkan?
Dikutip dari Alinea.id, tantangan ini juga direspons oleh generasi muda sebagai adaptasi atas tekanan struktural: biaya pendidikan yang meningkat, pendapatan tidak tetap dari pekerjaan paruh waktu, serta ketergantungan pada transfer keluarga. Dalam kondisi demikian, menjadi hemat bukan pilihan, melainkan keharusan.
Lebih dari sekadar alasan ekonomi, No Buy Challenge juga memberi dampak psikologis yang signifikan. Saya pribadi mulai mengenali bahwa dorongan untuk membeli sering kali muncul saat saya merasa jenuh, cemas, atau sekadar mencari pelarian. Dengan menunda pembelian, saya belajar memahami emosi, menyusun ulang prioritas, dan menemukan kepuasan dalam hal-hal sederhana: memasak sendiri, memadupadankan pakaian yang sudah ada, atau meminjam buku dari teman.
Namun, tantangan ini tentu tidak dapat diterapkan secara seragam pada semua mahasiswa. Ada yang tetap harus berbelanja demi mendukung kegiatan akademik, kebutuhan medis, atau bahkan untuk keberlanjutan usaha kecilnya. Oleh sebab itu, gerakan ini sebaiknya tidak dipandang sebagai aturan kaku, melainkan sebagai ajakan reflektif untuk lebih sadar dalam mengambil keputusan konsumsi.
Sebagian kritik juga menyebut gerakan ini sebagai bentuk "minimalisme elitis"---bahwa hanya mereka yang telah kenyang berbelanja yang mampu menolak belanja. Kritik ini patut dihargai agar No Buy Challenge tetap relevan bagi berbagai lapisan masyarakat. Alih-alih membanggakan siapa yang paling irit, lebih baik kita rayakan siapa yang paling jujur terhadap dirinya sendiri.
Di lingkungan kampus yang sering kali menekankan capaian-capaian eksternal, keputusan untuk merasa cukup adalah langkah radikal. Di dunia yang menilai kesuksesan dari merek sepatu atau gawai yang digunakan, memilih untuk hidup sederhana adalah bentuk keberanian yang kian langka. Identitas kita sebagai mahasiswa tidak ditentukan oleh isi keranjang belanja, melainkan oleh ide, empati, dan kontribusi nyata yang kita hadirkan di ruang kelas dan masyarakat.
Pada akhirnya, saya tidak menyarankan semua mahasiswa untuk berhenti belanja sepenuhnya. Namun, barangkali ada nilai penting dalam langkah-langkah kecil: menunda checkout, melewatkan diskon impulsif, atau membatasi belanja barang-barang lucu yang tak kita perlukan. Semua itu adalah bagian dari latihan kesadaran---kesadaran untuk mengenali cukup, dan keberanian untuk tidak selalu ingin lebih.