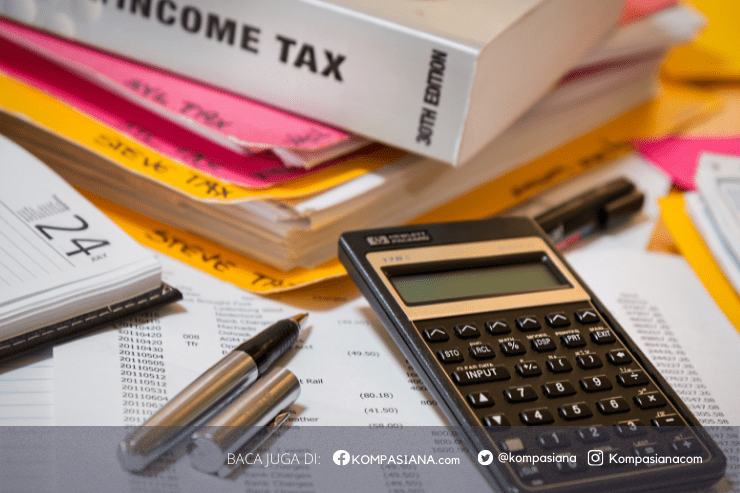Pendahuluan
Banyuwangi dalam satu dekade terakhir dikenal sebagai daerah dengan pertumbuhan pesat. Potensi alam seperti tambang emas Tujuh Bukit, pariwisata kelas dunia Kawah Ijen, hingga hadirnya cabang kampus negeri ternama menjadikannya sorotan nasional. Pemerintah daerah bahkan rutin menggelar event internasional seperti Tour de Banyuwangi Ijen (TdBI), demi memperkuat branding pariwisata.
Namun, di balik gemerlap tersebut, muncul paradoks kesejahteraan. Upah Minimum Kabupaten (UMK) Banyuwangi tahun 2025 hanya Rp2.810.139, padahal biaya hidup di sana kerap lebih tinggi dibanding Kota Malang ataupun Surabaya (Bappeda Jawa Timur, 2025). Tidak sedikit buruh akhirnya bermigrasi ke Bali untuk mencari penghasilan yang lebih layak. Bahkan, menurut data Kementrian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, terdapat sekitar 21.372 pekerja migran asal Banyuwangi yang bekerja di luar negeri (Rimawati, 2025). Ironinya, di tengah keluhan buruh, Pemerintah daerah justru menggelontorkan hingga Rp 40 miliar untuk TdBI, sementara banyak infrastruktur dasar, termasuk jalan kota, masih rusak (Arifin, 2025).
Persoalan UMK rendah tidak bisa dilepaskan dari Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK). Regulasi ini mengubah formula penetapan upah, dari berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menjadi berbasis pertumbuhan ekonomi dan inflasi (Izzati, 2023). Akibatnya, meskipun biaya hidup meningkat, upah tetap stagnan. Esai ini membahas dua hal pokok: (1) politik hukum UUCK dan dampaknya pada UMK Banyuwangi, (2) paradoks pembangunan daerah yang timpang.
Upah Minimum dalam Jeratan Politik Hukum UUCK
Sejak disahkan pada tahun 2020, UUCK mengubah banyak aspek ketenagakerjaan, termasuk mekanisme penetapan upah minimum. Sebelum UUCK, UMK dihitung berdasarkan survei KHL yang mempertimbangkan harga pangan, sandang, perumahan, hingga transportasi (UMKt+1 = KHL + pertimbangan produktivitas + pertumbuhan ekonomi). Dengan demikian, setiap kenaikan harga kebutuhan pokok otomatis berdampak pada penyesuaian upah. Namun setelah UUCK, rumus tersebut diubah menjadi berbasis pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi (UMKt+1 = UMKt + (UMKt x (pertumbuhan ekonomi + inflasi). Konsekuensinya, meskipun biaya hidup meningkat, penetapan upah tidak lagi sepenuhnya mencerminkan realitas kebutuhan buruh (Izzati, 2023).
Dampaknya nyata di Banyuwangi: UMK 2025 hanya Rp2,81 juta, jauh di bawah Surabaya dan Gresik yang mencapai Rp4,72 juta (Kompas.com, 2024). Secara nominal, buruh Banyuwangi berada jauh di bawah standar, padahal kebutuhan sehari-hari di daerah ini tidak kalah mahal.
Secara hukum, kebijakan ini menimbulkan kontradiksi. UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) menegaskan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.", kemudian Pasal 28D ayat (2) juga menjamin hak atas imbalan dan perlakuan adil dalam hubungan kerja (Republik Indonesia, 1945). Selain itu, Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) melalui UU No. 11 Tahun 2005, yang mewajibkan negara menjamin upah yang adil dan penghidupan layak (Republik Indonesia, 2005).
Dengan demikian, politik hukum UUCK telah menciptakan jurang antara norma hukum (konstitusi dan perjanjian internasional) dengan realitas buruh di lapangan.
Citra Global vs Realitas Lokal
Banyuwangi dijuluki The Sunrise of Java dengan kekayaan yang melimpah: tambang emas Tujuh Bukit termasuk salah satu yang terbesar di Indonesia (Merdeka Copper Gold, 2025), pariwisata Kawah Ijen yang dikenal dunia, hingga event tahunan kelas internasional rutin digelar.