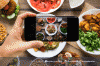Sejak program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mulai digulirkan di sekolahku, suasana jam makan siang jadi punya cerita baru. Kalau dulu anak-anak pulang sekolah langsung mencari gorengan di warung depan gerbang, sekarang mereka bisa duduk rapi di aula atau ruang kelas, menunggu kotak makanan yang sudah disiapkan oleh petugas. Menunya pun beragam: kadang nasi lauk ayam sayur sop, kadang nasi kuning dengan tempe orek, bahkan sesekali buah segar ikut hadir sebagai pelengkap.
Sekilas, program ini memang seperti oase bagi anak-anak. Bagi sebagian siswa yang berasal dari keluarga sederhana, MBG bukan sekadar menu tambahan, tapi jadi penolong yang memastikan mereka tetap bisa makan layak di sekolah. Saya ingat betul, ada teman sekelas yang dulu sering menahan lapar karena bekalnya cuma sepotong ubi. Kini, wajahnya lebih cerah karena ia bisa ikut antre dan menikmati makanan yang sama dengan yang lain. Ada rasa kesetaraan yang tumbuh di situ.
Namun, cerita MBG tidak selalu semulus kulit ayam goreng tepung. Ada kalanya menu yang dibagikan tidak sesuai selera anak-anak. Sayur lodeh misalnya, sering berakhir jadi bahan bercanda: “Yang suka lodeh berarti jodohnya masih jauh,” kata seorang teman sambil mendorong mangkuknya. Ada juga yang hanya mengambil lauk lalu meninggalkan sayur. Di sini lah kita mulai sadar: program MBG tidak cukup hanya menyediakan makanan, tetapi juga harus mendidik soal gizi, kebiasaan makan sehat, dan cara menghargai makanan.
Pertanyaan penting lalu muncul: sejauh mana orangtua bisa dilibatkan? Selama ini, orangtua hanya menerima kabar dari grup WhatsApp kelas, “Hari ini menunya ayam kecap.” Ada rasa lega, tentu saja, karena anak-anak mendapat makanan gratis. Tapi di sisi lain, ada juga yang khawatir: apakah kebersihannya terjamin? Bagaimana kalau anaknya punya alergi tertentu?
Di sekolahku, pernah diadakan pertemuan kecil antara komite sekolah dan orangtua untuk membahas menu MBG. Hasilnya, sekolah mulai memberi formulir pendataan: siapa yang alergi telur, siapa yang tidak bisa makan pedas, siapa yang vegetarian. Meski tidak bisa memuaskan semua pihak, setidaknya ada ruang partisipasi.
Idealnya, orangtua tidak hanya jadi penerima informasi, tapi juga dilibatkan dalam pengawasan dan evaluasi. Bisa dengan cara bergiliran mendampingi distribusi, ikut mencicipi menu, atau memberi masukan soal variasi makanan. Kalau keterlibatan ini terbangun, rasa kepemilikan terhadap program juga akan tumbuh. MBG akhirnya tidak sekadar program pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama antara sekolah, orangtua, dan masyarakat.

Tentu, ada pula cerita yang bikin heboh: kasus keracunan. Di sekolah tetangga, pernah satu rombongan siswa sakit perut setelah makan nasi bungkus MBG yang lauknya telur balado. Mulanya hanya satu anak yang mengeluh mual, lalu menjalar ke beberapa teman lain. Sekolah langsung panik, orangtua datang berbondong-bondong, dan pihak penyedia katering dimintai keterangan.
Yang agak menyedihkan, setelah itu orangtua diminta menandatangani surat pernyataan: “Pihak sekolah tidak bertanggung jawab jika terjadi hal-hal di luar kendali.” Surat semacam ini jelas menimbulkan pro-kontra. Di satu sisi, sekolah ingin melindungi diri dari tuntutan hukum; di sisi lain, orangtua merasa seakan tanggung jawab dilimpahkan begitu saja. Padahal, soal gizi dan keamanan makanan seharusnya jadi tanggung jawab bersama yang serius, bukan sekadar ditutup dengan selembar kertas.
Menurut literatur kesehatan masyarakat, risiko keracunan makanan di sekolah bisa diminimalisir dengan tiga hal utama: pengawasan rantai distribusi, penyimpanan makanan sesuai standar, dan edukasi higienitas bagi petugas. Itu artinya, bukan hanya soal siapa penyedia kateringnya, tetapi juga bagaimana makanan diangkut, dibagi, bahkan sampai bagaimana anak-anak membuang sisa makanan.