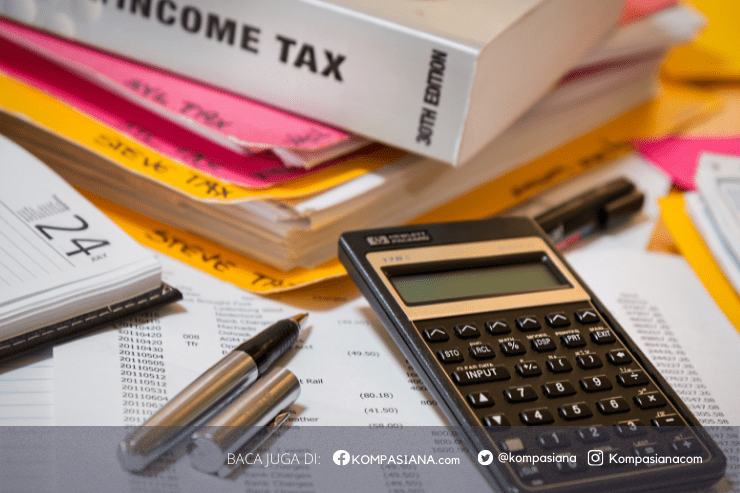Di balik industri dan ekspor nikel Indonesia yang berkembang pesat, terdapat bencana yang mengancam kehidupan masyarakat: air bersih terkontaminasi, sungai-sungai rusak, dan masyarakat kehilangan mata pencaharian.
Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia, dengan cadangan sekitar 72 juta ton atau 52 persen dari total cadangan global. Pemerintah mendorong program hilirisasi mineral dan batubara (minerba) untuk meningkatkan nilai tambah tambang, terutama nikel. Namun, aspirasi ekonomi ini menempatkan masyarakat dan lingkungan dalam risiko yang serius. Masyarakat yang tinggal di dekat lokasi pertambangan harus menghadapi kenyataan pahit berupa bencana ekologis dan kontaminasi air.
Pengujian laboratorium di Maluku Utara menunjukkan bahwa operasi pertambangan nikel telah mencemari empat dari enam sungai yang diteliti. Salah satu daerah yang terkena dampak langsung adalah dusun Kawasi di Pulau Obi, Halmahera Selatan. Pengujian dilakukan oleh tim independen dari Analytika Kalibrasi Laboratorium, yang mengacu pada standar baku mutu air dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021.
Parameter air termasuk DO (7,7 mg/L), daya hantar listrik (DHL 0,947 mS/cm), dan pH (6,8) secara teknis masih dalam kisaran yang dapat diterima untuk mandi dan bersih-bersih. Namun, warga masih perlu memurnikan air lebih lanjut sebelum dapat dikonsumsi. "Kami harus mengolah air terlebih dahulu sebelum diminum," kata salah satu petugas uji laboratorium.
Meski data menunjukkan air relatif aman, warga tetap merasa khawatir. Banyak keluarga kini memilih membeli air galon dengan harga Rp10.000 per galon, yang berasal dari sumur bor swadaya atau mata air Kawasi.
Muhammad Soni Afertiawan, Dosen Rekayasa Air dan Limbah, mengatakan bahwa karena mata air Kawasi terletak di daerah tangkapan air yang terpisah, maka area pertambangan tidak secara langsung merusaknya secara hidrologis. Tambang berada di lempeng B, sementara Kawasi berada di lempeng A. Dengan demikian, keduanya tidak saling mempengaruhi, jelasnya.
Namun, rasa aman warga tidak langsung kembali. Kekhawatiran polusi jangka panjang masih dipicu oleh keberadaan industri besar yang dekat dengan sumber air. Pencemaran air juga telah menyebabkan banjir dan kerusakan ekosistem perairan di tempat lain, seperti Kolaka dan Merawali di Sulawesi Tenggara.
Ironisnya, program hilirisasi yang seharusnya menjadi motor penggerak ekspansi ekonomi justru menimbulkan masalah baru yang membahayakan taraf hidup masyarakat.
Efisiensi sistem pengelolaan air limbah dan air tambang harus dijamin oleh pemerintah dan sektor pertambangan. "Efektivitas pengelolaan air akan berkurang dan pencemaran dapat terjadi jika sedimen tidak dikeluarkan dari kolam sedimen," kata Soni. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya observasi berkelanjutan dan inovasi teknologi dalam pengolahan limbah.
Harus ada implementasi yang mendesak dari langkah-langkah nyata termasuk pungutan lingkungan yang progresif, insentif keuangan untuk bisnis yang mematuhi standar lingkungan, dan penggunaan teknologi hijau.
Apakah kemajuan ekonomi harus selalu mengorbankan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal?