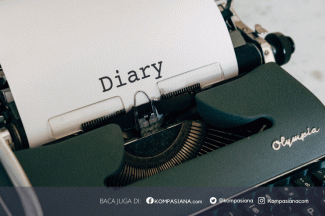Prinsip Dasar Warisan Simbah Ngatirah
Sebuah prinsip akuntansi paling fundamental dalam hidup saya tidak saya dapatkan dari bangku kuliah, melainkan dari sebuah rumah sederhana di kampung. Rumah itu milik almarhumah Simbah Putri saya, Ngatirah. Saya masih bisa mengingat dengan jelas suasana rumahnya: beralaskan tanah yang sejuk, berdinding gebyog kayu yang menyimpan sejuta cerita, dengan aroma khas dari lampu teplok yang menjadi penerang saat senja tiba. Di tengah kesederhanaan itulah, Simbah Ngatirah mewariskan sebuah kaidah abadi yang terus menjadi dasar "Jurnal" hidup saya. Sambil mengunyah sirih dan mengoleskan susur tembakau dimulut, beliau sering berkata dengan nada mantap, "Le, eling-elingen yo. Anak polah, bapak kepradah." (Nak, ingat-ingatlah. Anak bertingkah, bapak yang menanggung akibatnya).
Bagi Simbah, itu adalah Filosofi Jawa yang adiluhung. Namun bagi saya, seorang sarjana Ekonomi Akuntansi, kalimat itu terdengar seperti prinsip dasar akuntansi kehidupan: prinsip pertanggungjawaban penuh (full accountability). Setiap "transaksi" yang dilakukan oleh seorang anak, sekecil apa pun, akan tercatat dalam "buku besar" sang ayah. Ayah tidak bisa lepas tangan; ia adalah penanggung jawab akhir dari neraca keluarga. Filosofi inilah yang menjadi lensa bagi saya dalam mengelola "aset" paling berharga yang saya miliki: ketiga buah hati saya. Satu anak laki-laki yang kini mulai menapaki dunia kreativitas di bangku kuliah jurusan Desain, serta sepasang anak kembar, laki-laki dan perempuan, yang tengah bergejolak di masa SMP. Mereka adalah generasi Z, generasi yang lahir dan tumbuh dengan "laporan keuangan" yang jauh lebih kompleks daripada kehidupan zaman Simbah Ngatirah.
Dalam ilmu akuntansi, kita mengenal aset sebagai sumber daya yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Anak-anak, bagi saya, lebih dari sekedar "aset hidup" atau investasi jangka panjang yang paling utama. Tugas saya sebagai ayah adalah mengelola aset ini agar nilainya terus bertumbuh (apresiasi), bukan menyusut (depresiasi). Proses pengelolaan ini penuh dengan "transaksi" harian yang tak terduga, masing-masing membawa potensi keuntungan dan risiko.
Saya teringat jelas sebuah "transaksi berisiko tinggi" saat putra pertama saya berusia tiga tahun. Ia sangat senang bermain seluncuran di taman, dan suatu hari ia berkeras ingin meluncur bersama mainan-mainan kesayangannya setelah hujan reda. Itulah "polah"-nya, sebuah keputusan investasi dalam kebahagiaan sesaat. Namun, mainan itu membuatnya kehilangan keseimbangan, ia terjatuh, dan wajahnya terluka, babak bunyak kalau dalam bahasa jawa. Saat itu, saya "kepradah". Ada "biaya" yang harus langsung dibayar: biaya ke dokter, biaya obat, namun yang tak ternilai adalah "beban" kekhawatiran seorang ayah. Dari kacamata akuntansi, ini adalah sebuah kerugian. Namun dari kacamata investasi, ini adalah biaya mitigasi risiko. Dari kejadian itu, saya belajar untuk mengaudit "lingkungan bermain" anak, menetapkan aturan-aturan keselamatan, untuk mencegah "kerugian" yang lebih besar di masa depan. Setiap luka kecil yang dikelola dengan baik adalah premi asuransi untuk menghindari bencana yang lebih parah.
Tantangan berbeda datang dari si kembar. Sebagai anak laki-laki dan perempuan, mereka memiliki karakter yang berbeda dan seringkali tidak akur saat bermain atau belajar. Pertengkaran mereka adalah "polah" yang rutin. "Kepradah" bagi saya adalah menjadi penengah, wasit, sekaligus negosiator. Setiap pertengkaran mereka adalah "transaksi friksional" yang dapat menggerus "goodwill" atau hubungan baik di antara mereka. Tugas saya sebagai "manajer aset relasional" adalah mengajarkan mereka cara berkompromi dan bekerja sama. Ini adalah investasi dalam modal sosial keluarga. Jika saya gagal mengelolanya, maka "liabilitas" atau kewajiban saya di masa depan adalah menghadapi dua orang dewasa yang tidak memiliki ikatan persaudaraan yang kuat.
Perbandingan Neraca: Dari Buku Kas Sederhana ke Laporan Konsolidasi Anak Gen Z
Kearifan Simbah Ngatirah lahir dari zaman yang berbeda. Jika kita sederhanakan, "neraca parenting" di zaman beliau ibarat sebuah buku kas tunggal. "Aset" (anak) memiliki peran yang jelas dan diharapkan memberikan "return" yang konkret, seperti membantu di sawah atau mengurus rumah. "Beban" (biaya hidup) juga relatif terukur dan sederhana. "Risiko" yang dihadapi lebih banyak bersifat fisik dan komunal. Prinsip "anak polah, bapak kepradah" di masanya seringkali berarti mengganti rugi ternak tetangga atau memperbaiki pagar yang rusak.
Kini, sebagai ayah dari anak-anak Gen Z, "neraca" yang saya hadapi jauh lebih rumit, ibarat laporan keuangan konsolidasi multinasional company yang ruwet dan njlimet bikin jidat berkerut. Hal ini karena asetnya tidak lagi hanya fisik, tetapi lebih banyak aset tak berwujud (intangible assets). Kreativitas anak sulung saya di jurusan Desain adalah aset. Kemampuan si kembar beradaptasi dengan teknologi adalah aset. Kecerdasan emosional mereka adalah aset yang paling krusial. Nilainya sulit diukur, namun potensinya tak terbatas. Kemudian, bebannya membengkak dan sangat beragam. Bukan lagi sekadar sandang, pangan, papan, tetapi juga biaya kuliah yang tinggi, kuota internet tanpa batas, langganan aplikasi, hingga dukungan untuk kesehatan mental mereka yang lebih rentan terhadap tekanan sosial media. Sedangkan, sisi risikonya menjadi sangat abstrak dan berbahaya. Bukan lagi sekadar jatuh dari seluncuran mainan, tetapi risiko perundungan siber (cyberbullying), kecanduan gawai, krisis identitas akibat paparan konten global, hingga keamanan data pribadi.
Saya merasa bahwa "Kepradah" di era ini memiliki dimensi yang sama sekali baru. Jika anak saya melakukan "polah" yang salah di dunia maya, "kerugian" yang saya tanggung bukanlah materi, melainkan bisa berupa kerusakan reputasi digital yang permanen, atau bahkan jerat hukum. Tugas saya sebagai seorang ayah kini mencakup peran sebagai manajer risiko digital, analis media sosial, dan terkadang, seorang terapis. Filosofi Simbah tetap berlaku, namun "transaksi" dan "liabilitas"-nya telah berevolusi secara drastis.
Pada akhirnya, filosofi "Anak Polah, Bapak Kepradah" adalah tentang akuntabilitas mutlak. Dalam laporan keuangan sebuah perusahaan, direktur utamalah yang menandatangani dan bertanggung jawab atas kebenaran isinya. Dalam keluarga, ayahlah yang memegang pena itu. Saya tidak bisa menyalahkan sekolah, lingkungan, atau teknologi atas "neraca akhir" anak-anak saya. Saya adalah akuntan utamanya. Setiap hari adalah proses audit kecil. Apakah "investasi" waktu saya sudah cukup? Apakah "alokasi sumber daya" perhatian sudah seimbang untuk ketiganya? Apakah "sistem kontrol internal" berupa nasihat dan aturan sudah efektif untuk memitigasi risiko? Inilah audit berkelanjutan seorang ayah.