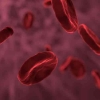"Kenapa hari ini Cindy seperti tidak bernafsu dengan puzzlenya?" tanya Mama.
"Nggak tau, Ma. Sudah beberapa hari dia bersikap begitu," sahut saya.
Kami bertiga sedang berada di rumah sakit. Mbaknya Cindy, kami tinggal supaya rumah tidak dalam keadaan kosong. Anak saya Cindy baru berusia 3 tahun dan mengidap penyakit autis.
Cindy duduk di lantai dengan beberapa puzzle di sekitarnya. Sikapnya terasa aneh. Tidak dipedulikannya semua mainan itu. Melalui jendela, matanya menatap ke arah langit seperti sedang menatap sesuatu. Kami memperhatikan sejak tadi dia terus saja bersikap begitu.
Tiba-tiba Cindy menunjuk-nunjuk ke arah langit, lalu dia berkata dengan suara lirih, "Hari ini Opa meninggal."
"Hihihihi...dasar anak kecil khayalannya luar biasa," kata Mama geli mendengar omongan cucunya.
Saya yang sedang merasa akrab dengan Papa tentu saja tidak mengizinkan dia berbicara seperti itu. Segera saya hampiri dia, "Cindy, kamu nggak boleh ngomong begitu."
Anak itu tidak bereaksi. Matanya masih terus menatap keluar jendela dan kembali menunjuk ke arah langit. Saya ikuti arah telunjuknya tapi tidak terlihat ada sesuatu apapun di luar sana.
"Cindy! Liat Mama. Cindy, liat Mama," kata saya.
Cindy menengok tapi matanya menghindar beradu pandang. Saya pegang dagunya lalu saya paksa untuk menatap ke arah saya, "Cindy, liat mata Mama."
Dengan gerakan perlahan, Cindy mau juga menatap saya. Sebelum saya tanya, dia sudah berkata lagi, "Hari ini Opa meninggal."
"Cindy!" kata saya setengah membentak, "kamu nggak boleh ngomong begitu."
Cindy tidak menyahut. Pandangannya terasa aneh tapi dia tidak berusaha untuk melepaskan pandangannya dari saya.
"Dari siapa kamu tau Opa meninggal? Coba kasih tau Mama. Dari siapa?" kata saya lagi.
"Dari Tuhan," kata Cindy lagi dengan nada sangat serius.
"Hihihihihi..." Mama tertawa lagi. Dia nampak geli melihat kelakuan Cindy. Tapi buat saya hal itu sama sekali tidak lucu. Omongan Cindy malahan membuat saya merinding karena saya betul-betul takut akan kehilangan Papa.
Melihat saya tidak berkata apa-apa lagi, Cindy bangkit dan berjalan ke arah jendela. Seperti tadi jarinya menunjuk-nunjuk ke angkasa, mulutnya berkomat-kamit seakan sedang berbicara dengan seseorang.
"Wah, sudah hampir jam 11! Mama pergi dulu ya, Yo," kata Mama seraya melirik ke arah jam di pergelangan tangannya..
"Okay, Ma," jawab saya.
Mama menggamit lengan Cindy, menariknya dari jendela,"Yuk, Cindy. Jalan-jalan sama Oma, yuk?"
Cindy menurut tapi matanya terus memandang ke arah jendela dan baru berhenti ketika sampai di luar kamar.
Setelah keduanya tidak terlihat lagi, saya berjalan ke arah jendela dan memandang langit yang tadi ditunjuk oleh Cindy. Di sana saya cuma melihat awan putih bergerak ditiup angin ke arah barat. "Apa sih yang tadi dilihat Cindy?' gumam saya. Entah kenapa hati ini rasanya galau sekali.
Hari ini adalah hari Waisak. Hari yang sangat penting bagi Umat Budha. Setiap Waisak biasanya kami sekeluarga pergi ke vihara untuk melakukan peribadatan di sana. Tapi sekarang? Mana mungkin Papa ditinggal? Setelah berunding, akhirnya kami memutuskan untuk membagi diri. Mama dan Cindy pergi ke vihara dan saya tetap menjaga Papa.
Saya duduk di samping Papa lalu membacakan cerita dari buku karya Agatha Christie yang judulnya "And Then There Were None." Seperti novel karangannya yang lain, buku ini merupakan cerita misteri yang ditulis dengan sangat cerdas dan membuat pembacanya turut berpikir.
Kisahnya sebetulnya simple saja, yaitu tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau. Kemudian satu persatu para tamu terbunuh secara misterius. Akibatnya tamu yang tersisa menjadi saling mencurigai satu sama lain. Di setiap kesempatan, Sang penulis juga memaparkan sisi-sisi kelam dari setiap tamu undangan sehingga pembaca dibekali data untuk ikut menerka-nerka, siapa sebetulnya pembunuh berdarah dingin itu.
"Yoyo!" Sekonyong-konyong Suster Aida, Sang Kepala Perawat di area paviliun itu masuk dengan tergopoh-gopoh.
"Ya, kenapa Suster?" tanya saya sambil menurunkan buku yang sedang saya baca.
"Maaf mengganggu, Yo. Sore ini ini Papa kamu kan harus transfusi, tapi ternyata stok darah kami yang golongan AB kosong."
"Waduh! Jadi bagaimana dong, Suster?"
"Bisa nggak kamu ke PMI untuk beli darah di sana?"
"Tapi nanti siapa yang jaga Papa?" tanya saya kebingungan.
"Kalau kamu bisa ke PMI, saya sendiri yang akan menjaga Pak Yo. Kamu nggak usah kuatir."
Walaupun ragu untuk meninggalkan Papa, nampaknya saya tidak punya pilihan lain dan berkata, "Baiklah kalau begitu."
PMI atau Palang Merah Indonesia tidak jauh lokasinya dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Alamatnya di Jalan Kramat Raya no. 47. Kalau kita ke luar dari Rumah Sakit Cipto, kita tinggal belok kiri ke Jalan Salemba lalu lurus saja maka kita akan sampai ke Jalan Kramat Raya. Kedua jalan itu tersambung dan PMI letaknya di sebelah kanan sebelum masuk ke Pasar Senen.
Di koridor menuju ke luar rumah sakit, saya berpapasan dengan Fuad yang baru saja datang untuk menjenguk kakeknya.
"Kamu mau ke mana, Yo?" tanya Fuad.
"Beli darah ke PMI. Stok darah di sini kosong. Bye Fuad," jawab saya tanpa berhenti.
"Hey, Yo! Tunggu. Yuk, saya anter kamu ke sana."
"Nggak usah. Kamu temenin dan bacakan cerita aja buat kakek kamu," kata saya sambil mempercepat langkah.
Fuad berlari menyusul lalu menggamit lengan saya, "Kamu nggak boleh pergi sendirian. Yuk, saya anter."
Dan saya mengalah. Tidak lama kemudian kami berdua sudah berada dalam mobil Fuad. Sayangnya baru saja keluar rumah sakit, mobil kami langsung stuck. Jalan Diponegoro macet bukan main. Seorang tukang parkir mengatakan bahwa jalanan macet karena barusan ada tawuran anak sekolah.
Untuk membunuh waktu, Fuad membuka percakapan, "Mama kamu ke mana, Yo?"
"Mama pergi ke Vihara . Hari ini adalah Hari Raya Waisak."
"Oh iya, betul. Selamat Hari Raya Waisak ya, Yo," kata Fuad sambil menjulurkan tangan mengajak salaman.
Saya menyambut tangannya tapi di luar dugaan Fuad menarik lalu mencium kedua pipi saya. Sebetulnya malu rasanya dicium seperti itu tapi saya tidak protes apa-apa. Dan Fuad juga terlihat biasa saja. Gayanya seakan itu adalah kegiatan yang sangat biasa terjadi di antara kami.
"Sebetulnya Waisak itu hari raya apa sih, Yo?" tanya Fuad lagi.
"Waisak adalah hari suci buat Umat Budha. Di hari ini, kami memperingati 3 peristiwa penting sekaligus. Pertama lahirnya Sang Budha. Kedua, mengenang saat Sang Budha mendapat pencerahan sempurna. Dan ketiga, wafatnya Sang Budha," jawab saya.
"Oh, begitu. Kenapa Mama kamu nggak pergi ke klenteng? Klenteng itu juga untuk Umat Budha, kan?"
"Iya betul."
"Lalu apa bedanya klenteng dan vihara?" Dari nada suaranya, Fuad terdengar serius.
"Vihara adalah tempat peribadatan Umat Budha yang arsitekturnya bergaya India. Kalau masuk ke dalam vihara, kamu hanya akan menemukan patung Sang Budha. Kalaupun ada patung lain, itu biasanya patung dua muridnya yang mengapit di kiri dan kanannya."
"Kalau klenteng?"
"Klenteng mempunyai arsitektur Tiongkok dan biasanya dicat warna-warni dengan dominasi warna merah yang mencolok. Klenteng tidak hanya menjadi tempat peribadatan tapi juga tempat orang-orang Cina menjaga dan memelihara budayanya."
"Oh, begitu. Tapi tempat peribadatannya sama?"
"Beda sedikit."
"Apa bedanya?"
"Di dalam klenteng, kamu akan menemukan beberapa patung. Ada patung Budha, Kong Hu Chu, Kwan Im, patung Lao Tse dari aliran Taois dan masih banyak lagi. Jadi Klenteng dibangun untuk Kaum Cina Perantauan supaya semua aliran agama Budha bisa beribadat di sana."
"Oh, I see," kata Fuad mengangguk-angguk lalu bertanya lagi, " Kata 'Sang Budha" itu sendiri artinya Tuhan, ya?"
"Bukan! Kata 'Budha' maknanya adalah seseorang yang telah sadar."
"Sadar? Maksudnya insyaf karena sebelumnya telah melakukan perbuatan buruk?"
"Hihihi...bukan! Sadar yang saya maksud adalah dalam konteks seseorang telah mencapai pencerahan sempurna. Karena telah mengerti segala makna hidup maka dia berhak menjadi guru sekaligus berkewajiban untuk membagi pencerahan yang diperolehnya pada orang lain. Itu sebabnya banyak aliran Budha yang tumbuh sesuai dengan ajaran guru yang masing-masing mereka percayai."
"Wah! Jangan-jangan di dalam klenteng, saya bisa ngeliat patung Judge Bao dong, ya? Hahahahahaha...." Fuad tertawa terbahak-bahak karena referensi dia tentang Judge Bao hanya diperoleh dari film di televisi.
"Judge Bao memang salah satu guru yang dihormati Umat Budha," kata saya dengan suara dingin.
"Oups...maaf Yo. Saya nggak tau. Maaf ya?"
"Dan di beberapa klenteng tertentu, kamu memang bisa menemukan patung Judge Bao."
"Sekali lagi, maaf, Yo." Fuad terus mengulang maafnya.
"Tapi penampilannya tentu saja tidak sama dengan yang kamu lihat di televisi."
"Sorry, Yo. It's not a good joke. I am so stupid."
Melihat dia salah tingkah seperti itu, saya jadi kasihan padanya. Dan entah karena apa, saya merangkul leher Fuad dan mencium pipinya, "It's okay. Saya nggak marah kok."
Perjalanan yang sangat dekat itu kami tempuh dalam waktu satu setengah jam. Untungnya Suster Aida telah menelpon PMI terlebih dulu sehingga kami tidak perlu menunggu lama. Pegawai PMI telah menunggu dengan 6 kantong darah untuk diserahkan pada saya.
Setelah menyelesaikan pembayaran, kami pun kembali menerjang kemacetan Jakarta untuk kembali ke rumah sakit.
Sesampainya di kamar, Suster Aida dan beberapa orang suster lain tampak sedang merubung di sekeliling ranjang Papa. Selang infus telah dicabut. Ventilator juga sudah dicopot. Salah seorang suster masih memegang nadi dan yang lainnya memeriksa dada Papa dengan steteskopnya.
Hati saya tercekat dan langsung memahami bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi.
Melihat kedatangan kami, semua suster yang berjumlah 6 orang itu menoleh. Suster Aida melangkahkan kakinya menghampiri kami. Dengan gerakan perlahan dia memeluk saya sambil berkata dengan suara lembut tapi tegas, "Maaf, Yo. Papa kamu sudah pergi."
Bulu kuduk saya merinding karena teringat omongan Cindy sebelum berangkat ke vihara tadi. Saya terdiam dengan tangan masih memegang 6 kantong darah yang seharusnya untuk ditransfusikan ke tubuh Papa. Keheningan mendominasi dalam kamar itu. Tak ada suara apapun kecuali yang bersumber dari luar kamar.
Entah karena memang sudah mempersiapkan diri, saya sama sekali tidak menangis. Dengan langkah perlahan, saya berjalan ke arah ranjang. Semua suster seperti dikomando menyingkir untuk memberi jalan. Dengan lembut saya memeluk Papa, meletakkan kepala di dadanya lalu berucap dengan suara lirih, "Selamat jalan, Papa. Semoga Papa bisa berbahagia di sana bersama Tuhan."
Fuad juga berdiri di sisi ranjang seberang. Mulutnya berkomat-kamit entah berdoa atau sedang mengucapkan apa. Saya tidak tau.
Tidak lama kemudian, Mama dan Cindy pun pulang. Seperti saya, beliau juga tidak menangis. Saya selalu mengagumi Mama yang senantiasa tegar menghadapi peristiwa apapun. Mama duduk di bangku yang terletak di samping ranjang. Dia meraih tangan suaminya lalu diusap-usapkan ke pipinya. Tidak ada air mata di sana. Kadang air mata memang tidak cukup untuk mewakili sebuah kesedihan yang melampaui batas.
Tanpa mempedulikan apapun, Cindy mendekat ke arah mainan puzzlenya yang masih berserakan di lantai. Dan kali ini dia bersikap normal dan langsung asyik menyusun kepingan puzzle sesuai dengan petunjuk yang terdapat di tutup kotaknya.
Dalam tradisi Budhis, memperabukan jenazah memang merupakan prioritas tertinggi. Dalam Kitab Suci Tipitaka juga disebutkan bahwa Budha dan murid-murid utamanya memilih perabuan. Akan tetapi hal itu bukanlah peraturan yang wajib. Semua berpulang pada yang bersangkutan atau pihak keluarga apakah hendak dimakamkan atau diperabukan.
Setiap mahluk ingin mempunyai cara matinya sendiri-sendiri. Papa pernah berkata pada Mama bahwa kalau dia mati nanti, dia ingin mati sendirian di suatu tempat tersembunyi. Beliau beralasan, dengan cara itu, anggota keluarga tidak perlu repot-repot mencarikan tanah untuk makamnya. Di samping itu, keluarga juga tidak punya kewajiban untuk pergi berziarah. Menurut Papa, kalau memang ingin mendoakan seseorang, kita bisa melakukannya dari rumah.
Saya pernah membaca bahwa memang ada orang-orang tertentu yang ingin mati tanpa disaksikan oleh orang lain. Dan Papa adalah salah satu di antaranya. Berbulan-bulan Papa mengalami koma. Seluruh keluarga besar menunggui dengan harapan ketika Papa menghembuskan napas terakhir, kita semua berada di dekatnya. Tapi Papa terus bertahan. Begitu lamanya Papa dalam kondisi koma sehingga satu persatu seluruh famili kembali ke tempatnya masing-masing. Bahkan A Koh pun pamit untuk pergi. Kemudian Mama pergi ke Vihara. Di saat yang sama, saya pergi membeli darah ke PMI. Dan akhirnya tak seorang pun dari keluarga yang menjaga Papa.
Dan Papa rupanya benar-benar memanfaatkan waktu tersebut. Dia meninggal dunia di saat tidak ada seorang pun anggota keluarga di kamarnya. Sempat terbersit di kepala saya, kalau Papa masih kuat badannya, pasti dia akan menghilang dan memilih sebuah tempat tersembunyi untuk mati sendirian.
Bersambung...