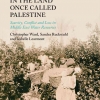Sebuah papan penunjuk arah menjadi penanda masuk ke sebuah makam kuno. “18 kilometer meuju Makam Raja Linge”. Di atasnya tertulis, “bangsa yang besar, bangsa yang menghargai sejarahnya”. Papan petunjuk itu saya jumpai setelah melalui perjalanan di atas aspal mulus jalan negara dari Kota Takengon, Aceh Tengah, sekira 60 kilometer, menuju Kota Blangkejeren, Gayolues.
Perubahan drastis langsung terasa. Kijang Inova yang tadinya meluncur mulus, kini harus membatasi kecepatan kalau tak mau seluruh penumpang terguncang keras. Fauzan, sopir yang setia mengantarkan kami dari Bandaaceh, harus ekstracermat memilih “lubang” yang bakal dilalui, karena memang tak ada ruas jalan yang rata. Tubuhnya mencondong ke depan. Tangannya mencengkram setir. Hampir tak ada senyum di wajahnya membayangkan 18 kilometer perjalanan yang sungguh tak mengenakkan. “Harusnya kita naik double cabin atau jeep,” ujarnya menggerutu dengan suara yang hampir tak terdengar.
Kondisi ruas jalan menuju makam Raja Linge belum teraspal. Para peziarah yang menggunakan kenderaan roda dua dan empat harus berjalan merayap. Debu dan kerikil yang bertebaran di sepanjang jalan membuat Fauzan meminta seluruh penumpang menutup rapat-rapat seluruh kaca jendela. Jarum speedometer tak bergerak dari angka 20 kilometer per jam.
Ini adalah hari kedua perjalanan saya dan teman-teman di Tanah Gayo –dan perjalanan pertama saya ke daerah Aceh Tengah. Kami berangkat dari Bandaaceh Jumat dua pekan lalu, seusai salat Jumat. Adli Abdullah, seorang pemerhati sejarah Aceh, duduk di kursi depan. Dalam perjalanan ini, ia bertugas sebagai “navigator”, menemani Fauzan. Saya dan dua dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Enzus dan Indra duduk di barisan tengah. dan dan di belakang duduk teman saya, Sulaiman Tripa, yang juga mengajar di fakultas tersebut. Dalam perjalanan ini, ia membawa serta istrinya.
Tidak banyak kenderaan yang memasuki kawasan itu. Hanya dua kendaraan berplat merah yang sempat berselisih dengan kendaraan kami. Saya juga tak melihat rumah-rumah penduduk di sepanjang perjalanan. Daerah itu sama sekali tak menunjukkan jejak sebuah kerajaan besar yang pernah berdiri di Aceh. Deretan pinus menambah kesunyian di jalan, beberapa hanya tinggal tunggul karena ditebang. Butuh waktu sekitar satu jam untuk bisa memasuki Dusun Buntul, Kampung Linge, Kecamatan Linge, tempat jenazah Raja Adi Genali, Raja Linge pertama dimakamkan.
“Mungkin kalau hujan, kita bakal tak bisa lewat,” ujar saya yang diiyakan oleh kawan-kawan yang lain. Tak hanya jalan berlubang dan berdebu, untuk sampai di sana, kami juga harus melitasi sungai kecil. Tak ada jembatan. Fauzan hati-hati mengemudikan kendaraan. Ia tak mengurangi kecepatan saat mobil satu gerdang itu melintasi sungai. Ia takut mobil terjebak lubang di sungai itu.
Akhirnya kami tiba juga di Buntul. Pinggang terasa pegal. Perjalanan 18 kilometer ini memang menguras energi dan emosi. Di sana, kami menyingahi sebuah gubuk kecil tempat keluarga Mat Amin. Mat Amin adalah penjaga Istana Linge dan makan Raja Adi Genali. Istana yang dijaga Mat Amin berbentuk rumah Aceh berukuran 50x10 meter. Seluruh tiang dan dinding terbuat dari kayu damar, beratap rumbia. Beberapa bagian dinding terlihat lapuk. Mat Amin mengoleskan oli bekas ke bagian-bagian yang lapuk agar tak terus dimakan rayap. Di bagian depan, tertulis Umah Pintu Ruang.
Di samping rumah itu terdapat sebuah bangunan kecil. Di dalam bangunan ini, terdapat dua kuburan. Salah satunya adalah makam anak Raja Adi Genali dan sebuah sumur, yang konon, kata Mat Amin, airnya tak pernah kering. “Itu kuburan keramat, dulu pernah mengeluarkan cahaya. Kami menyebutnya makam cahaya,” kata Keucik Linge Karimansyah, yang berjanji menemani kami selama menziarahi situs itu.
Menurut Adli Abdullah, Kerajaan Linge merupakan sebuah kerajaan awal dan berpengaruh di Aceh. Kerajaan Linge terbentuk sekitar 1025 Masehi (416 Hijriah) yang dipimpin oleh Adi Genali—Kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam di masa Sultan Iskandar Muda Johan Pahlawan Meukuta Alam berlangsung pada 1590-1636.Bersamaan dengan itu ia diberi gelar Cik Serule (Paman Serule) karena membangun kerajaan di Linge. Serule merupakan sebuah perkampungan di kecamatan itu.
Dalam sebuah litelatur yang memuat perbincangan Tengku Hadji Ilyas Leube (Allahuyarham) disuatu malam pada 26 Oktober 1976, ditulis Raja Genali adalah seorang raja Islam berasal dari Turki. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Tengku Kawe Tepat atau Tengku Kik Betul. Kerajaan ini berlangsung hingga keturunan ke-17.
Kerajaan ini lebih dulu mengenal Islam ketimbang kerajaan lain di Aceh. Bahkan raja-raja yang memerintah di Aceh merupakan keturunan Raja Linge. Seperti Meurah Silu adalah Sultan Malikussaleh. Dia merupakan Orang Gayo yang menyatukan sejumlah kerajaan kecil di daerah Peureulak, yang akhirnya menjadi Sultan Pertama di Kerajaan Pasai yang berada di daerah Samudera Geudong, Aceh Utara. Dan Meurah Johan atau Johansyah yang kemudian menjadi Sultan Aceh Pertama yang memimpin Kesultanan Kute Reje.
Setelah puas memperhatikan istana, kami pun bergerak naik ke bukit, sekira 600 meter dari istana itu. Tujuan berikutnya adalah makam Raja Linge. Kami bersemangat kembali. Dorongan rasa ingin tahu membuat kami menyisihkan sejenak rasa penat. Perjalanan menuju malam tak bisa dilakukan di atas kendaraan beroda empat. Untuk sampai di makam itu, kami melintasi hutan lebat yang dibelah jalan setapak. Lagi, kami harus melewati sebuah alur sungai. Setelah melintasi sungai itu, di hadapan kami, tersusun ratusan anak tangga purba. “Ayo, sikit lagi,” kata Sulaiman setelah melihat saya ngos-ngosan.
Saya seakan tak mempercayai penglihatan saya. Nama besar Raja Linge seolah tak berbekas di makam itu. Kondisinya sangat memprihatinkan. Tak lebih baik dari kandang ayam. Sebagian ornamen, di bagian atas dan bawah, copot. Keramik yang membatasi deretan tujuh kuburan dibuat asal-asal. Di sinilah raja pertama di Aceh di semayamkan. Namun, tak ada kekhasan di makam itu. Hanya deretan nisan yang sebagian sudah miring sebagai petunjuk makam sang raja. Kompleks makam itu sendiri tersuruk di dalam hutan.
Keucik Karimansyah menyayangkan minimnya perhatian pemerintah setempat. Padahal, katanya, di sini, bersemayam jenazah seorang raja yang memiliki peran besar di Aceh. “Banyak orang menziarahi makam raja ini, dari Jakarta, Surabaya, dan Purbalingga. Tapi pemerintah setempat tak peduli. Kami juga tak mempunyai uang untuk memperbaiki kuburan ini,” katanya.
Praktis, untuk biaya perawatan, penjaga kubur dan warga setempat mengandalkan pemberian para peziarah. Seorang peziarah asal Purbalingga, kata Karimansyah, mengaku menyayangkan buruknya kondisi makam Raja Linge dan Istana Tujuh Kamar. “Di sana, makam raja-raja diurus agar orang mau mendatangi dan mengenal asal dan cerita tentang kerajaan itu,” ujar Karimansyah menirukan perkataan peziarah tersebut.
Pikiran saya berbalik ke petunjuk arah ke Istana Raja Linge. Tulisan “bangsa yang besar, bangsa yang menghargai sejarahnya” seolah menohok. “Apakah kami memang tak menghargai sejarah, sehingga kami tak pernah menjadi bangsa yang besar?” Pikiran itu terus berkecamuk sepanjang perjalanan meninggalkan makam Raja Linge dan Istananya yang tak terurus.