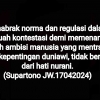Salah satu profesi yang paling aku benci di dunia ini adalah polisi selain politikus dan pengacara. Entah mengapa, aku sangat antipati terhadap sekelompok orang yang memakai seragam cokelat ini. Mungkin, salah satu faktornya karena aku kerap berurusan dengan polisi.
Alasannya bermacam-macam, mulai dari masalah sepele, ditilang akibat melanggar lalu lintas, tawuran sejak masih sekolah, hingga kenakalan remaja lainnya. Dua hal terakhir sudah aku lupakan, kecuali tilang. Ya, mendengar kalimat tersebut membuatku sangat kesal.
Lantaran, tilang merupakan satu kegiatan bodoh yang kerap aku lakukan dengan rutin. Entah itu melanggar lampu merah, tidak pakai helm, tidak mengenakan seat belt, ketinggalan SIM dan STNK, dan lupa memasang kaca spion di sepeda motor. Hingga, yang remeh sekalipun seperti pentil ban tidak sesuai aslinya.
Ya, memang aku lebih sering mengendarai sepeda motor ketimbang mobil dinas. Meski kendaraan yang dipinjami kantor keluaran Eropa dengan logo “Singa Jingkrak” nan prestisius. Namun, aku lebih menikmati memakai sepeda motor keluaran negeri asal Doraemon.
Setidaknya, meski jadul dan harus berpeluh keringat saat mengendarainya, tapi sepeda motor itu merupakan milik pribadi. Dibeli memakai hasil keringat sendiri yang tentu mempunyai kepuasan tak ternilai di atas gengsi. Hanya, karena sepeda motor lebih mudah leluasa membuat aku kerap menerobos lampu merah sampai berurusan dengan polisi.
“Selamat siang Mas. Maaf, bisa dibuka helm dan dikeluarkan kartu identitasnya?” tutur seorang polisi ketika aku melanggar lalu lintas di bilangan Matraman, Jakarta Pusat. Saat itu aku lagi terburu-buru mengejar meeting dengan anggota Direksi lainnya, yang tentu malas berurusan dengan polisi karena takut terlambat.
Jadi, aku langsung mengeluarkan dompet dan dengan sedikit gerakan –secepat kilat- menyelipkan selembar rupiah ke tangan polisi. Petugas yang hendak menilangku itu sempat terdiam. Namun, hanya beberapa saat kemudian, sosok yang memiliki kumis tebal itu langsung paham.
“Silakan jalan Mas. Lain kali, kalau lewat sini jangan melanggar lalu lintas ya,” Polisi tersebut coba memberi nasihat. Aku hanya bisa mengangguk, lega, sekaligus melirik sosok yang mempunyai emblem balok di pundaknya itu meraba selembar rupiah berwarna biru yang kuberikan padanya dengan memasukannya ke saku celana.
“Ah, sebegitu mudah kah hukum dapat dibeli. Jika polisi lalu lintas yang di bawah saja, mudah disuap. Tidak heran, bila atasannya berlaku sama, hingga akhirnya mendekam 10 tahun di penjara akibat kasus korupsi,” kataku setengah bergumam dan tak menghiraukannya kembali karena harus segera ke kantor.
***
“Ga semua pengendara yang melakukan pelanggaran kena tilang,” Wildan, kawanku yang juga personel kepolisian menjelaskan saat kami bertemu di acara reuni sekolah.
“Terus. Aku juga bingung, kadang di depanku ditilang padahal mereka memiliki surat-surat yang lengkap dan ada spion. Sementara, aku yang dibelakang mereka dengan hanya spion di kiri, lenggang kangkung. Tapi, adakalanya terbalik, malah aku yang kena,” ujarku kepada kawan yang delapan tahun terakhir berdinas sebagai reserse di sebuah Polres di Jakarta.
“Nah itu dia. Analoginya begini, kamu kan hobi memancing. Lalu, di antara ribuan hingga jutaan ikan yang ada di laut, apakah kamu bisa tangkap semua? Enggak kan, kecuali satu dua, yang terkena jebakan umpan di kailmu. Begitu juga dengan polisi lalu lintas di jalan raya. Tapi, enggak semuanya seperti itu. Ini bukan karena aku di posisi sebagai polisi, lho.”
“Yupz. Standar ganda. Itu julukan yang tepat bagi mereka yang menerapkan hukum ambigu di jalan raya.”
“Ya begitu. Intinya, kamu jangan sampe melanggar lalu lintas. Lagian, kalo kamu di jalur yang benar, surat-surat lengkap, dan tidak memodifikasi kendaraan dengan aneh. Tentu, polisi yang merazia tidak akan menilang.”
***
Kendati tidak menyukai polisi, bukan berarti enggan menjalin persahabatan dengan mereka. Malah, aku mempunyai banyak teman sekolah dahulu yang sekarang menjadi polisi. Ada yang berdinas di Trunojoyo, Polda, BNN, Polair, Brimob, hingga Reserse. Termasuk Wildan yang kerjanya selalu menangkap individu maupun kelompok yang sering meresahkan masyarakat.
Kadang, saat kumpul dengan sebagian dari mereka dan mendengar bagaimana suka duka menjadi pengayom masyarakat, sangat menyentuh. Sebut saja Nano, yang harus menyamar jadi tukang siomay selama sebulan penuh saat mengintai pabrik ectasy. Atau, bagaimana Pahlevi harus menjadi “orang gila” yang bertelanjang setengah bulat dengan rambut dibiarkan gimbal. Itu demi usahanya menangkap jaringan penyelundup wanita yang akan dijual ke luar negeri.
Ah, memang di dunia ini tiada yang sempurna. Pepatah mengatakan, “air bisa membuat perahu berlayar, tapi juga dapat menenggelamkannya”. Ya, sesuatu yang baik atau buruk berasal dari prilaku seseorang itu sendiri, bukan berdasarkan lingkungan atau orang lain.
***
Senin pagi di perempatan Tomang, Jakarta Barat. Kawasan ini identik dengan kemacetan luar biasa karena menjadi titik temu dari pengendara yang ingin ke luar kota, dari Jakarta menuju Tangerang, atau sebaliknya. Hari ini aku ingin bertemu dengan dua orang investor untuk membicarakan rencana penambahan saham mereka.
Sengaja bangun lebih awal sebelum matahari condong ke timur, nyatanya Jakarta tetap saja macet. Demi memperingkas waktu, aku mencoba membuntuti Bus Transjakarta melalui jalur Busway. Selain mobil yang kutumpangi, di depan dan belakang terdapat beberapa kendaraan lain, termasuk Kopaja, Taksi, dan tak ketinggalan sepeda motor.
Hanya, baru saja hendak berbelok ke arah tol Kebon Jeruk, laju kendaraanku segera dihadang seorang polisi. Tentu, itu membuat kemacetan karena kondisi lalu lintas sedang lampu hijau. Mau tidak mau, aku harus menepikan kendaraan menuju pos polisi.
“Sial. Lagi emergency begini, pake acara tilang lagi. Mana, ini lagi bawa mobil, pasti ga cukup bayar cepe-nope,” ucapku dalam hati. Selain khawatir telat bertemu investor, aku juga risau karena jika ditilang seperti ini tentu kantor tidak akan mengganti. Jadi, aku harus kehilangan uang makan hari ini demi berdamai dengan polisi.
Beruntung, di balik topi dan kaca mata yang dikenakannya, aku mengenal sosok yang memberhentikan barusan. Ya, dari badge di seragamnya terdapat nama Umar yang merupakan teman satu sekolah dulu. Bersama Reza, Pahlevi, Nano, Novel yang kini jadi bankir, Irda (dokter).
Kami, bertujuh bisa disebut sebagai siswa terbadung di sekolah karena tidak pernah mau mengerjakan tugas,sering bolos, hingga tawuran. Bahkan, karena ulah tersebut, kami bangga saat beberapa teman lainnya menjuluki sebagai “The Magnificent Seven” merujuk pada utama pada film Hollywood era 1970.
“Hai Umar. Lama ga ketemu, kata Reza kamu lagi dinas di Bandung,” aku mencoba basa-basi supaya bisa memudahkan negosiasi.
“Sudah selesai dari dua tahun lalu.” Umar berkata dengan ramah.
“Jadi kamu sekarang kembali lagi ke Jakarta ya.”
“Iya Dra. Oh ya, maaf bisa saya lihat kartu identitas kamu Dra?”
“Identitas? SIM sama STNK, maksudnya?”
“Iya.”
“Kalo SIM kan aku memang sudah punya dan kamu tahu. Mengenai STNK, ini punya kantor.”
“Ya sudah, saya boleh lihat?”
“Ini.”
Sosok yang delapan tahun lalu dikenal beringas karena kerap menjadi pemimpin saat tawuran antarsekolah itu tampak mengamati kartu identitas yang kusodorkan. Tak terlihat bayangan masa lalunya yang suram karena sering melinting di toilet sekolah sambil tertawa cengengesan tanpa arti. Meski begitu, Umar sangat setia kawan. Jika ada musuh yang berani menyerang sekolah kami, dia berada pada garda terdepan untuk membela mati-matian.
“Maaf, Dra. Kamu saya tilang karena melewati jalur Busway yang tidak semestinya dilalui kendaraan umum,” ucap Umar dengan datar yang tentu membuatku kaget hingga terhenyak.
“Tilang Mar? Serius?”
“Iya serius. Memang ada yang salah dengan ucapanku ya, Dra.”
“Ya nggak sih. Tapi, kita kan...”
“Tentu saja aku tahu Dra. Kita berdua adalah sahabat sejak masih seragam putih merah hingga pernah sama-sama nginep di Polsek akibat tawuran,” Umar menjawab sambil mengeluarkan buku dan menuliskan sesuatu yang paling aku benci: tilang.
“Terus gimana Mar?” kataku penuh pertanyaan. Sebenarnya tak masalah bagiku kehilangan uang makan seratus-dua ratus ribu agar segera berdamai dengannya demi bertemu investor. Tapi, aku merasa penasaran dengan sikap Umar yang seolah melupakan persahabatan.
“Ya tetap harus ditilang.”
“Beneran Mar, mau tilang aku. Atau kita damai saja deh.”
“Damai? Enggak, kamu tetap saya tilang!”
“Silakan Mar kalo begitu, minggu depan aku urus sendiri di pengadilan. Tapi aku nggak nyangka ya, kamu sekarang telah berubah. Di mana solideritas Umar dahulu yang selalu nomor satu membantu temannya yang sedang kesusahan?”
“Candra... Aku masih waras dan nggak bakal ngelupain persahabatan kita. Tapi, saat ini kita dalam kondisi berbeda. Aku sebagai penegak hukum yang menjalankan tugas negara, dan kamu sang pelanggar. Asal kamu tahu, sebenarnya aku tidak ingin menilangmu karena kita sudah seperti saudara. Namun, ini harus dilakukan, sebab, kalau aku melepasmu, suatu saat aku juga akan melepas Ayah, Ibu, saudara, sahabat, teman, dan lainnya yang melanggar lalu lintas. Lalu, bagaiman kalau 120 ribu anggota polisi lalu lintas berpikiran hal yang sama denganku, yaitu melepas pelanggar orang yang dikenalnya. Bukankah akan membuat hukum menjadi hancur?”
Umar yang mengetahui kekecewaanku segera menepuk pundakku,“Dra, aku harap kamu memahami tugasku di sini. Kita harus ingat, ‘keluarga dan sahabat bagaikan pakaian, hukum dan peraturan yang dibuat negara laksana kaki-tangan’. Pakaian rusak mudah dijahit, tapi jika kaki atau tangan ada yang putus tidak bisa disambung lagi.”
* * *
- Jakarta, 10 September 2013