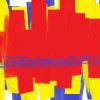Dia yang Malang
-1-
O, alangkah malang nasib anak itu. Sudah berbadan kurus, terhina pula. Bukan oleh sesiapa di luar sana. Melainkan oleh seseorang yang seharusnya melindungi dan mendidiknya. Atau, adakah dunia ini sudah berbalik, Kawan? Atau, inikah yang namanya jaman edan? Seorang ayah tega menghajar anaknya sendiri. Sebaliknya anak tak jarang berbuat serupa. Duhai, di mana lagi peri kemanusiaan? Peri kebinatangan saja tak sampai separah itu. Manusia sudah melebihi binatangkah?
Hari ini seperti yang sudah, entah pasal apa anak itu dihajar lagi oleh ayahnya. Tak hanya dengan sebuah tamparan, juga tendangan yang membuat tubuh kurus itu terjajar ke rusuk rumah. Kupintakan sesiapa saja wajib menolongnya. Kuharapkan adalah seseorang yang berani meredam amarah seorang ayah seibarat gila.
Oalah, lihatlah perempuan yang bergegas itu. Kemarahan juga memancar dari raut wajahnya. Akankah dia menambahi nista anak itu? Kau tahu, Kawan, dia itu istri baru si ayah. Artinya, dia adalah ibu tiri si anak kurus. Lengkaplah pula derita membebatnya.
"Kataku, hentikan semua ini!" geram si perempuan. O, kita salah, Kawan. Aku lupa. Sebelumnya, meski cap ibu tiru itu sangat jelek, konon perempuan satu ini berbeda. Telah berulangkali dia menyelamatkan anak itu dari amukan ayahnya. Dan kali ini, dia ingin berbuat sama. Kau lihat, dia sengaja membawa sapu bergagang rotan, yang pasti sakit bukan kepalang apabila dihantamkan ke tulang punggung.
Kesempatan bagus. Larilah anak kurus. Larilah. Biarkan si ayah yang payah itu menceracau menahan amuk. Larilah sejauh dapat.
Hei, kita sebenarnya belum mengenal kawan yang satu ini; si anak kurus. Siapa namanya. Usianya berapa. Berapa dia bersaudara. Sekarang dia sudah kelas berapa.
Supaya terang bagimu, dengarlah baik-baik. Nama anak itu Kecik. Ya, tepat! Kau menebak bahwa nama itu hanya ujar-ujaran saja. Konon karena dia bertubuh kurus seperti dihimpit dua bukit, maka orang lebih senang memanggilnya demikian. Tak perlulah kuberitahu nama sebenarnya di sini. Karena kau tahu, apalah arti sebuah nama.
Usianya hampir lima belas tahun. Tapi sekarang dia tak lagi sekolah. Setelah ibunya meninggal, praktis ayah yang pengamuk itu tak lagi mau menyekolahkan Kecik. Pun setelah menikah dengan si Lila, itulah nama panggilan istri barunya, bukan amuknya berkurang, malahan bertambah tingkat demi tingkat. Entah setan apa yang bercokol di batok kepalanya.
Tapi usah risau, seperti yang telah diutarakan tadi, tentulah kita tak boleh bersyakwasangka bahwa si Lila itu yang mengobarkan amuk di dada ayah Kecik. Bukan, sama sekali bukan! Lila malahan sering menyelamatkan Kecik agar jangan lagi bernasib lebih naas, misalnya luka parah atau mati. Kasihan dia, ibarat sebatang kara, karena saudara pun tak punya.
Dalam pelariannya, Kecik akhirnya tersungkur di depan sebuah rumah semi permanen. Seorang lelaki dengan dada berbulu, gegas mendekatinya. Dia memapah anak itu masuk ke dalam rumah. Seorang perempuan berkulit terang, keluar membawa segelas air, baskom berisi es dan kain lap. Dia istri lelaki itu.
"Kau dihajar lagi?" Lelaki itu mengusap ujung bibir dan kulit wajah Kecik yang kebiru-biruan. Kecik mengangguk sambil mengaduh.
"Iya, Kyai! Siapa lagi pelakunya kalau bukan Boimin brengsek itu!" Lelaki itu dipanggilnya Kyai. Bukan berarti dia seorang kyai seperti ghalibya. Hanya gelar-gelaran saja. Dia paling senang menasihati orang dan berbincang tentang agama. Tapi menjalankan ibadah dia malas. Maka, orang-orang berseloroh memanggilnya Kyai. Entah kenapa, hingga sekarang nama itu begitu lekat di depan nama aslinya; Kyai Ali.
"Tak baik mengata-ngatai ayah sendiri! Berdosa!"
Kecik meneguk sedikit air di dalam gelas. Dia mengaduh. Perih sekali air mengalir di sela-sela bibirnya. Andai tubuhnya sebesar dan setinggi Boy (nama kerennya, karena nama asli si ayah adalah Boimin), sudah lama dia menghajar lelaki itu. Dia sebenarnya tak mau durhaka. Tapi bagaimana bisa tahan dengan perlakuan demikian?
"Ayah macam apa dia? Sudah kasar, tak pula peduli sekolahku. Aku hanya disekolahkan sampai kelas empat SD. Sekarang Kyai tahu kan kerjaku sehari-hari? Selain mengisi bak mandi dan mencuci piring, hampir setiap malam aku membersihkan lantai karena Boy selalu pulang dalam keadaan mabuk." Hidung Kecik mengembang. Panggilan istri Kyai Ali agar mereka berdua makan siang, seakan panggilan surgawi. Tahu saja kalau orang lagi lapar berat!
Kecik duduk berseberangan dengan Kyai Ali. Istri Kyai tak ikut makan. Dia harus mengurusi bayinya yang tiba-tiba menangis. Sepasang suami-istri itu baru tiga bulan lebih dikarunia anak. Ya, cukup lama juga menunggu kehadirannya. Hampir duabelas tahun. Jadi, selama ini Kecik-lah yang mereka anggap sebagai penghibur lara. Entah setelah mempunyai anak, apakah mereka akan mendepak Kecik. Siapa yang bisa menebak?
"Sedap juga makanan Kyai siang ini. Ada ayam goreng, semur empela, sambal terasi, telor sambal. Boleh nambah ya?"
"Suka-sukamulah! Asal perutmu tak pecah saja. Apa mau diganti dengan pantat kuali?" Mereka tertawa. Sedikit hilang kegundahan Kecik.
"Ada acara apa hingga kita bisa makan besar begini?" Kecik mengekori Kyai. Telah bersinar matanya. Perutnya mengeras karena kenyang.
Kyai duduk di bale-bale teras. Rokok kretek dinyalakannya. Dia menghisap dalam-dalam, dan menghembuskannya sembari mendecak-decak. Mungkin ada serpihan daging menyempil di sela-sela giginya yang jarang.
"Acara karena aku mulai bekerja hari ini, Kecik!"
"Bekerja di mana, Kyai? Menjadi buruh angkut di penggilingan padi Juragan Arman? Nanti Kyai bertengkar pula dengannya pasal gaji kecil."
"Taklah aku mau bekerja lagi dengannya. Aku mau ke Jakarta!"
Kecik menatap Kyai takjub. Dia berhenti memerhatikan anak-anak yang baru pulang sekolah. Dalam benaknya, Jakarta itu sangatlah besarnya. Amat ramai. Ibu tirinya, si Lila itu, pernah berjalan-jalan ke Jakarta. Hanya lima hari saja. Namun menceritakan kebanggaannya pergi ke kota besar itu, seolah dongeng si kancil dan buaya, yang selalu berulang-ulang dia ceritakan kepada Kecik.
"Wah, Kyai pasti akan kaya!"
Kyai Ali memukul pelan bahu Kecik. Katanya, "Kaya bagaimana, Kecik! Aku tetap pekerja kasar. Kau kenal Leman, orang kaya sekampung ini, kan?" Kecik mengangguk. "Nah, dia mengajakku bekerja di truk barangnya. Rencananya nanti malam aku dan kawan-kawan akan berangkat iring-iringan membawa beras milik Juragan Arman ke Jakarta."
Kecik tak sadar menjerit sambil melompat berdiri. Kyai Ali tersentak, dan buru-buru mengelus dadanya.
"Maaf, Kyai. Ini karena pengaruh saking senangnya. Sejak kapan Kyai bisa menyopir? Sopir truk pula! Hahaha tak kusangka Kyai diam-diam bisa menyopir."
"Taklah sampai sehebat itu. Kapan Kyai-mu ini bisa menyopir? Kau ini memang suka bermimpi! Aku hanya membantu-bantu saja. Istilahnya kernet, begitu." Kecik mengangguk-angguk. "Kau kenal Sujak, kan?"
"Yang berjualan kerupuk di pasar kecamatan itu?"
"Bukan! Itu Sujak Gatal! Ini Sujak Pelor. Kau mengenalnya, bukan?"
Kecik bergidik. Dia teringat wajah seorang lelaki yang penuh bekas cakaran. Di bagian lengannya ada ceruk luka yang sudah lama sembuh. Kabarnya ditembak polisi, karena maling ayam di pasar kecamatan. Tapi karena tak ingin malu, dia sering gembar-gembor bahwa itu bekas terserempet peluru yang dilesakkan tentara Belanda. Hahaha, lucu! Dia hanya membual-bual. Jaman penjajahan Belanda, lelaki itu masih orok!
Begitupun, Kecik paling takut bertemu Sujak Pelor. Dulu ketika Boy berkelahi dengannya pasal lahan parkir di pasar, Kecik terkena sasaran. Dia kebetulan ke pasar bersama ayah Boy. Ayahnya itu kalah kuat, kemudian dijerembabkan Sujak Pelor ke selokan. Sebagai penuntasan amarahnya, dia mencekik Kecik, dan menghempaskannya ke lapak ikan.
"Kau takut?" Kecik menggeleng. Kyai Ali terbahak. "Sudahlah! Yang lalu biarlah berlalu. Dia bukanlah Sujak yang dulu. Sejak bekerja dengan Leman, dia berubah lebih baik."
"Oh, begitu. Aku pulang dulu, Kyai. Kapan-kapan ajak aku naik truk, ya?" Kyai Ali menggangguk.
Sekian jam kemudian, di sebuah rumah berdinding triplek, pertengkaran hebat terjadi antara Boy dengan Lila. Mereka memang sudah biasa seperti itu. Kalau tak bertengkar sehari saja, badan mereka pegal-pegal.
"Kau memang selalu membela anak itu. Harusnya kau biarkan saja dia kuhajar sampai mampus."
Lila melipat tangan di depan dada. "Bukankah Kecik anak kandungmu sendiri? Kenapa mesti dimampusi?"
"Anak kandung apaan kalau tingkahnya begitu. Masa' aku suruh beli rokok sebungkus, dianya tak mau."
"Lha, bagaimana pula dia mau! Dia kan tak ada uang untuk membelinya!"
Boy mendecak. Dia menggebrak meja. Lila tersentak. Sebentuk kepala yang bersembunyi di depan pintu rumah, pun ikutan tersentak. Terdengar suara pletuk pertanda kepala itu menghantam pintu.
Boy turun tangan. Pemilik kepala itu diseretnya ke dalam rumah. Lila menjerit. Boy merogoh sesuatu dari saku celana si pemilik kepala. Dia langsung tertawa manakala menemukan beberapa lembar ribuan yang menggumpal di situ.
"Ini apa, sialan!"
Si pemilik kepala meringis sambil memegangi keningnya yang memar. "Jangan, Yah! Itu upahku membantu mengisi bak mandi Mak Latief. Aku mau menabung untuk meneruskan sekolah."
"Sekolah?"
Pletak! Jitakan Boy hinggap di ubun-ubun anak itu. "Umur kau sekarang berapa? Hampir lima belas tahun! Mana cocok lagi duduk di bangku kelas lima SD. Cocoknya uang ini untukku." Boy tertawa. Lila mengedipkan mata ke arah Kecik. Saat Boy masih tertawa, Lila merebut gumpalan uang itu. Lekas dia selipkan ke saku baju Kecik. Ibarat peluru, anak itu segera berlari sekencang-kencangnya.
Kecik menelusuri jalan kampung. Pikirannya tak karuan. Kalau pulang lagi ke rumah, selain uangnya bisa diambil paksa, dia pasti dihajar Boy sampai mampus. Kecik tak mau itu. Lebih baik minggat saja. Tapi minggat ke mana? Ke ibukota kecamatan? Apa yang mau dia kerjakan di sana? Bagaimana kalau dia kelaparan dan tak mempunyai uang? Atau, beranikah dia mengemis seperti anak gelandangan?
Kecik teringat mendiang ibunya. Ibunya pernah berpesan, bahwa pekerjaan yang harus dia hindari adalah mengemis. Hidup tak boleh berpangku tangan. Hidup adalah perjuangan. Hidup adalah kerja keras. Kecik tak mau ibunya sedih di alam sana, bila mengetahui anaknya mengemis.
Tiba-tiba terbetik ide yang cukup cemerlang di benak Kecik. Bagaimana kalau dia ikut Kyai Ali ke Jakarta? Maksudnya bukan jalan-jalan. Melainkan bekerja. Toh dia bisa mengerjakan yang ringan-ringan. Seperti memijiti bahu Kyai Ali atau Sujak Pelor kalau tengah capai. Tenaganya kuat juga mencuci mobil, mengangkat barang-barang yang ringan, membelikan makanan. Aha! Dia melompat kegirangan. Tumpukan ide berkelindan di kepalanya, pecah menjadi tawa yang membuatnya seperti anak gila.
Dia bergegas menuju rumah Kyai Ali. Rumah itu kelihatan sepi. Hanya ada istri Kyai Ali sedang meneteki anaknya di teras rumah.
"Bukannya tadi kau sudah pulang, Kecik?" Istri Kyai Ali berdiri. Dia membawa anaknya ke dalam rumah, kemudian muncul sendirian sekian menit berselang. "Kau tak pulang ke rumah, ya? Minggat?"
"Tidak, Wak! Aku tadi sudah pulang. Tapi langsung dimarahi ayah." Kecik menggaruk-garuk lengannya. Dia menyenderkan punggung di dinding rumah. "Kyai Ali ke mana?"
"Dia sudah pergi ke rumah Bang Leman."
Kecik terbelalak. "Bukankah Kyai baru berangkat nanti malam ke Jakarta?" Dia langsung lemas.
"Dia belum berangkat. Hanya persiapan saja, sekalian membersihkan truk."
"Kalau begitu....." Kecik langsung berlari. Istri Kyai Ali yang mencoba memanggilnya, hanya dihadiahi lambaian. Kecik melintasi pematang sawah. Beberapa ekor bebek yang sedang digembalakan seorang anak seumurannya, berhambur ketakutan. Anak gembala itu mengacung-acungkan galah bambunya. Namun Kecik tak perduli. Meskipun kemudian tubuhnya berulangkali mencium tanah sawah yang becek, dia lekas berdiri dan berlari lagi. Dia sudah membayangkan duduk di jok bagian belakang kabin truk.
Sebenarnya tak bisa disebut jok. Hanya sebentuk dudukan memanjang tempat biasa sopir mengaso. Setiap truk yang melakukan perjalanan jauh, pasti memiliki dua sopir. Begitu sopir yang satu capai dan istirahat di jok bagian belakang itu, tugasnya digantikan oleh sopir pengganti. Yang pasti sopir pengganti itu bukan Kyai Ali. Kyai hanya kernet.
Berarti yang berada di kabin truk ada empat. Sujak Pelor, sopir pengganti, Kyai Ali dan tentu saja dirinya. Apakah tak membuat penuh sesak kabin truk? Ah, hampir saja anak itu mengurungkan niat, lalu berbalik arah. Tapi manakala ingat tinju Boy, tekadnya kembali membara.
"Kyai!" jerit Kecik saat melihat lelaki itu tengah membersihkan ban truk yang berlumpur.
Kyai Ali terkejut bukan kepalang. Dia langsung menghentikan pekerjaannya.
"Kenapa ke mari? Kalau mau ikut jalan-jalan naik truk, nanti saja setelah kami pulang dari Jakarta. Kelak adalah masa mengaso sebelum ada tarikan lain."
Kecik merebut lap basah dari tangan Kyai Ali. Dia mencangkung sambil membersihkan pelak ban yang masih berlumpur. "Aku tetap mau ikut."
"Ikut ke mana? Ini bukan pekerjaan main-main!"
"Ke mana lagi kalau bukan ke Jakarta!" Kecik mencoba bersiul. Tapi dari dulu hingga sekarang, siulannya selalu fals.
"Ke Jakarta? Untuk apa?"
"Bekerja di truk!"
"Kau pikir pekerjaan di sini ringan? Pulang sana! Nanti kalau aku tiba dari Jakarta, aku janji membawakanmu bola kaki. Kau sangat ingin mempunyai bola kaki, kan?"
"Pokoknya aku tetap ikut!"
"Tak bisa!"
"Ikut!"
"Kecik!" Kyai Ali kesal. Dia memegang keras lengan Kecik. Anak itu meringis.
"Tolonglah, Kyai! Aku tak mau dihajar Boy terus-terusan. Aku tak mau dijadikan kuda beban. Apa Kyai ingin ini pertemuan kita yang terakhir?" Mata anak itu berair.
"Maksudmu?" Pegangannya di lengan Kecik, melonggar.
"Bisa saja aku sekarang tak ikut truk ke Jakarta. Aku akan pulang untuk dihajar Boy. Bila aku kemudian pingsan dan tak bisa tertolong...." Kecik dipeluk erat Kyai Ali. Lelaki itu tak bisa memaafkan dirinya bila kelak Kecik mati di tangan ayahnya sendiri. Ya, meskipun hatinya membantah, Boimin belum tentu tega menyiksa Kecik sampai mampus.
Selesai membersihkan truk, Kyai Ali permisi kepada Leman. Dia dan Kecik melangkah pulang. Kyai Ali mewanti-wanti agar Kecik tak banyak omong ikut truk ke Jakarta. Kalau sampai Leman tahu, bisa bahaya. Kyai bisa dipecat. Leman paling tak ingin jumlah awak truk yang diberangkatkan dari kampung akan bertambah di tengah jalan. Kalau yang menumpang memang membayar ongkos, itu lain cerita. Tapi kalau sekadar ikut menumpang dan mengurangi uang jalan, itu menjadi derita. Jelas saja menjadi derita bagi para awak truk, karena jatah makan-minum mereka pasti berkurang. Tepatnya mereka harus berhemat!
Itulah, makanya nanti malam Kecik harus menunggu di perbatasan antara kampung dan jalan lintas provinsi. Leman tak perlu tahu ada penumpang haram. Begitu truk dengan BG 5544 MA melintas, Kecik harus sigap berlari. Truk akan melambat. Pintu kabin terbuka sedikit. Kecik mesti sanggup menelusup ke kabin dengan penuh perhitungan. Salah sedikit, dia bisa terpeleset jatuh, dan tubuhnya dilindas ban truk yang besar itu. Atau kalau gerakannya lambat, awak truk di belakang akan tahu. Bila berniat jahat, mereka akan berbalik arah dan melapor kepada Leman.
"Artinya aku akan dipecat!"
"Tahu!" Kecik mengekori langkah Kyai Ali yang panjang-panjang.
Lelaki itu menambahkan, bila memang sudah puluhan kilometer dari kampung, dan awak truk lain mengetahui ada penyelusup atau penumpang haram, semua saling tahu sama tahu saja. Kebanyakan awak truk sengaja memasukkan penumpang haram untuk senang-senang.
"Penumpang haram untuk senang-senang?" Kecik tak faham cerita Kyai Ali.
"Nanti kau mengerti sendiri."
Istri Kyai Ali menatap heran kedatangan dua lelaki itu. Ketika suaminya mengatakan bahwa Kecik akan ikut truk ke Jakarta, dia mencoba mencegah. Namun penjelasan panjang lebar Kyai Ali tentang Kecik dan perbuatan Boy, akhirnya membuatnya mengalah. Dia buru-buru menyiapkan santapan malam, kemudian masuk ke kamar demi membenahi pakaian yang akan dibawa suaminya.
"Nah, sekarang bagaimana dengan Kecik? Apa selama perjalanan harus memakai pakaian yang itu-itu juga?" tanya Istri Kyai Ali ketika mereka sama-sama mengaso di ruang tamu.
"Siapkan saja baju-baju bekasanku untuk dia. Mungkin bisa muat satu atau dua pasang. Ayo, sana pergi mandi dulu!" Kyai Ali menepuk punggung teman kecilnya. Setelah teman kecilnya mandi dan memakai baju bekasan Kyai, barulah pecah tawa di ruang tamu yang sempit itu.
Bagaimana tak geli melihat tubuh kurus Kecik tenggelam di dalam pakaian bekasan Kyai. Apalagi Kecik kemudian membuat beberapa gaya yang menambah kelucuan. Tawa pun tak urung berderai. Namun semua itu harus berakhir. Tawa harus diputus oleh aroma perpisahan.
Ya, ya. Setiap perpisahan selalu menorehkan sedikit luka di dada. Meskipun itu hanya perpisahan singkat, seminggu, dua minggu, atau malahan berbulan bila angkutan selalu ada dan bertumpuk-tumpuk. Maka akan ada derai air mata. Akan ada kecup perpisahan. Akan ada lambai yang kemudian hilang ditelan gerak laju kendaraan.
Juga bagi Kecik. Meskipun dia selalu dihajar oleh Boy, tapi hatinya terpaut ke rumahnya yang penuh kenangan. Dia sedih meninggalkan tempatnya bernaung sehingga sebesar sekarang. Juga, ibu Lila yang tulus-ikhlas menyayanginya. Membelanya dari sang durjana, Boimin.
Ya, begitupun, perpisahan tetap menimbulkan kesan lain ketika tiba pertemuan. Perpisahan menimbulkan rasa kasih-sayang yang semakin tulus. Seorang Kyai akan bertambah cinta kepada istrinya. Seorang Kecik akan bertambah sayang kepada rumah dan Ibu Lila. Entah kepada Boy.
Ya, ya... Cukup sudah berderai-derai cerita dan air mata. Kecik membuang pandang manakala melihat terbit air mata istri Kyai, saat suaminya itu memeluknya seolah tak ingin dilepas. Lalu lambaian melepaskan kedua calon petualang ke alam bebas dan liar. Semua berkejaran ke belakang. Semua seolah ikut melambai. Kyai Ali mengantarkan Kecik ke perbatasan antara kampung dan jalan lintas provinsi. Selanjutnya dia bergegas menuju rumah Leman.
"Pukul berapa ini?" sungut Sujak Pelor menyambut Kyai Ali yang muncul dari belakang truk. "Kau sempatkan kelonan dengan istri lagi?" Meskipun Sujak sudah berubah lebih baik, bicaranya tetap kasar dan pedas. Tapi Kyai Ali yakin hatinya baik. Dia menanggapi ucapan keras dan pedas itu dengan senyuman.
Seperampat jam berlalu, truk mulai berjalan merayap di jalan kampung yang terbuat dari pasir dan batu. Perlahan pula semua mengantri di halaman penggilingan padi Juragan Arman. Berkarung beras berpindah dari gudang penggilingan ke dalam truk.
Kyai Ali tersenyum sendiri. Dia melihat para buruh angkut tertunduk-tunduk memanggul karung. Begitulah pekerjaan yang dia lakukan beberapa hari lalu. Sekarang tak lagi. Dia menjadi penguasa truk. Pengelana yang menyinggahi tak hanya kampung demi kampung, juga kota demi kota. Lepe, temannya sesama buruh angkut, menyempatkan diri bersalaman dengan Kyai. Dia senang melihat Kyai mulai belajar menjadi orang sukses.
Pukul sebelas lewat barulah semua beras selesai diangkut ke dalam bak masing-masing truk. Iring-iringan itu kembali merayap melintasi jalan pasir dan batu. Kyai Ali berkenalan dengan lelaki gempal yang duduk di antara dirinya dan Sujak. Lelaki gempal itu adalah sopir pengganti saat Sujak capai.
Dia menyebut namanya Lobe. Dia tak banyak omong. Tapi mulutnya tak berhenti mengisap rokok kretek. Jadilah kabin truk dihalimun asap. Kalau saja Sujak tak menegur, mungkin belum dihentikannya pekerjaan yang membuat dada sesak itu.
"Sudah kabut di depan, kau menambahi pula dengan kabut rokokmu!" gerutu Sujak.
"Maaf, soalnya mulutku pahit. Mata rasanya kriyep-kriyep kalau tak merokok."
"Bilang saja mengantuk! Tidur sana! Jangan sampai saat menggantikanku menyetir, kau tabrakan pula truk ini oleh kantukmu." Sujak membanting setir ke kanan karena menghindari lubang menganga di depan. Lobe menanggapinya dengan bernyanyi-nyanyi kecil. Dia berdiri sambil merunduk-runduk menuju jok di belakang. Sekian menit saja hanya dengkurnya yang kedengaran.
"Dasar badak!" gerutu Sujak. Dia menghidupkan tape demi menyaingi dengkur Lobe. Saat itulah Kyai Ali mengatakan rencananya.
"Bang! Nanti di perbatasan antara kampung dan jalan provinsi, Abang melambatkan laju mobil, ya?"
"Kenapa? Ada yang mau ikut?"
"Ada!" Kyai Ali mengucek-ngucek matanya.
"Perempuan?"
"He-eh!"
"Istrimu?" Wajah Sujak berubah masam. "Istri kok diajak-ajak. Bikin susah lagi. Lagian kalian kan baru mempunyai anak!"
"Bukan istriku!"
"Jadi...."
"Adalah!"
Wajah masam Sujak berubah sumringah. "Ah, kau ini. Cepat sekali mengerti selera abangmu." Dia bersiul-siul sambil mengetuk-ngetuk kemudi dengan jari telunjuk.
---
(Bersambung)